Akhir pekan lalu, headline dengan kata kunci “orang Indonesia malas berjalan kaki” trending di mana-mana. Di twitter, ia dipicu keluhan di akun menfess. Sementara di Instagram, beberapa media arus utama langsung mengunggah infografis yang mengutip sebuah studi dari Stanford—studi yang jadi sumber keributan tentang betapa malasnya orang Indonesia berjalan kaki.
Usut punya usut, studi tersebut ternyata kabar lama yang diterbitkan 2017 lalu di jurnal sains Nature. Penelitian yang berjudul Large-scale Physical Activity Data Reveal Worldwide Activity Inequality itu memang membahas temuan menarik. Katanya, rata-rata orang Indonesia berjalan kaki hanya 3.515 langkah setiap hari. Jumlah yang jauh di bawah rata-rata global, yaitu 5.000 langkah per hari.
Penemuan penelitian ini lantas disimpulkan oleh banyak media di Indonesia dengan tajuk utama “Orang Indonesia adalah negara yang paling malas di dunia”. Klaim atas kesimpulan ini pun oleh banyak media Indonesia sengaja dibuat dengan dukungan data perbandingan jumlah langkah negara lain.
Contohnya dengan membandingkan jumlah langkah orang Indonesia dengan Hong Kong. Kota yang diklaim sebagai yang paling aktif di dunia karena warganya berjalan kaki rata-rata 6.880 langkah setiap harinya.
Buat sebagian orang, tajuk berita ini adalah fakta tak terbantahkan yang membuat mereka miris dengan realitas masyarakatnya sendiri. Tapi tak sedikit pula yang malah bertanya ulang tentang kebenarannya. Apalagi setelah tahu bahwa sumber data penelitian ini masih bias kelas dan berorientasi konsep negara maju buatan negara Barat atau negara maju sendiri.
Data penelitian Tim Althoff et al tersebut ternyata diambil dari aplikasi pelacak bernama Argus dan Azumi yang hanya ada di iPhone. Smartphone ini biasanya dimiliki oleh masyarakat kelas menengah-atas yang banyak melakukan mobilisasi sehari-hari dengan kendaraan pribadi. Angka penggunanya dari kelas tersebut lebih tinggi dibandingkan kelas menengah ke bawah.
Jadi, apakah benar orang Indonesia semalas itu atau jangan-jangan ada alasan lain yang gagal diungkap di balik “malasnya” orang Indonesia berjalan kaki?
Baca Juga: Gelap, Rawan Kejahatan, Ringkih: Mengapa Perempuan Takut Berjalan di JPO Jakarta
Tak Ada Trotoar Sejauh Mata Memandang
Orang Indonesia itu tidak malas jalan kaki. Mereka sebenarnya bukan mager atau malas gerak, tapi hanya enggan saja melakukannya. Ini bukan sebuah pembenaran yang asal celetuk, tanpa fakta berbasis realitas.
Buat orang Indonesia, keengganan berjalan kaki itu tak hanya soal cuaca yang makin panas, tetapi ini soal akses pejalan kaki yang tidak diakomodasi dengan baik oleh pemerintah.
Orang Indonesia apalagi yang tinggal di kota-kota besar pasti sudah paham negara ini fakir trotoar. Gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, atau tempat hiburan boleh saja dibangun di sana-sini, tapi kehadiran trotoar layak amat mengkhawatirkan. Jika pun ada, jumlahnya masih terbilang sedikit dan terletak di daerah-daerah tertentu saja—biasanya daerah-daerah yang jadi pusat ekonomi atau bisnis kelas menengah pula.
Fakta ini terlihat dari hasil survei Most Liveable City Index (MLCI) pada 2017 yang dirilis oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Mereka mencatat, hanya sekitar 10 persen trotoar di Jakarta yang layak pakai. Minimnya trotoar layak pakai di Jakarta pun tak berbanding lurus dengan target pemerintah untuk membangun trotoar.
Dilansir dari Media Indonesia, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho hanya menargetkan 118 km trotoar yang akan terbangun pada 2021 dan 2022. Jumlah yang tak sesuai dengan target Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu 289 km trotoar melalui Instruksi Gubernur No 49 tahun 2021.
Bayangkan, jika ibu kota negara saja belum bisa memenuhi kelayakan trotoar bagi para pejalan kaki, apalagi kota-kota satelit?
Lihat saja Depok. Kota yang disebut kota fakir trotoar oleh Koalisi Pejalan Kaki. Jalan Margonda yang begitu besar dan jadi jantung kota Depok dari saya masih SD hingga sudah jadi tante-tante masih tak ramah pejalan kaki. Trotoarnya sangat sedikit dan banyak yang tak layak pakai. Banyak sekali bekas galian atau lubang besar yang dibiarkan begitu saja dan berpotensi membahayakan pejalan kaki.
Dengan kondisi seperti ini, Pemerintah Kota Depok pada 2021 bahkan baru bisa membangun trotoar sepanjang 700 meter. Panjang yang tak seberapa dibandingkan dengan panjangnya Jalan Margonda yang membuat pejalan kaki seperti saya harus siap-siap merapalkan doa tak diserempet kendaraan saat berjalan kaki.
Minimnya trotoar yang layak ini pun jadi refleksi lanjutan tentang bagaimana hampir semua kota di Indonesia tak punya akses transportasi umum yang memadai. Mungkin di Jakarta sekarang sudah mulai ada integrasi halte Transjakarta dan Mass Rapid Transit (MRT) seperti Stasiun Integrasi CSW atau Cakra Selaras Wahana.Namun, di kota-kota lain akses ke stasiun Kereta Rel Listrik atau KRL saja masih sulit dijangkau.
Teman saya yang tinggal di Citra Grand, Bekasi nyerempet Cibubur saja misalnya, tidak bisa pergi ke mana-mana ketika akhir pekan. Pertama, karena Transjakarta di daerah Cibubur tak beroperasi Sabtu-Minggu. Kedua, stasiun KRL terdekat yang ia bisa singgahi adalah stasiun Pondok Cina yang jauhnya lebih dari 13 km.
Realitas inilah yang berbanding terbalik dengan Hong Kong atau Singapura. Hong Kong dan Singapura memiliki transportasi umum yang nyaman, aman, terintegrasi, dan tentunya murah. Hal yang tentu saja mendorong warga-warganya untuk lebih memilih transportasi umum dan berjalan kaki untuk mobilisasi harian dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi atau taksi yang memiliki ongkos yang lebih mahal.
Dengan skema besar seperti ini maka wajarlah jika orang Hong Kong dan Singapura jadi lebih “gemar” berjalan kaki.
Baca Juga: Dilema Jalan Sendirian dan Pulang Malam
Catcalling jadi Makanan Sehari-hari Perempuan Pejalan Kaki
Indonesia tak pernah jadi negara yang ramah pejalan kaki utamanya perempuan pejalan kaki. Sudah aksesnya yang tak memadai, perempuan pejalan kaki juga rentan mengalami pelecehan seksual di jalanan umum. Pelecehan seksual di jalanan umum sudah jadi realitas pahit yang harus ditelan mentah-mentah setiap perempuan yang tinggal dan tumbuh besar di setiap bagian wilayah Indonesia. Baik di desa maupun kota, perempuan pejalan kaki rentan terhadapnya.
Catcalling misalnya jadi bentuk pelecehan seksual (sayangnya dinormalisasi hingga saat ini) yang banyak dialami oleh perempuan pejalan kaki. Tak peduli ketika tengah hari bolong atau malam hari, siulan dan kalimat yang bersifat seksual kerap kali terlontar dari bibir pelaku kepada perempuan pejalan kaki.
Tak peduli juga kamu pakai baju apa. Toh, saya sendiri yang suka bolak-balik ke sekolah berjalan kaki beberapa kali mengalami catcalling saat saya masih memakai seragam sekolah. Lengkap dengan kerudung panjang menutupi dada, rok lebar, dan baju kurung tak membentuk lekuk tubuh.
Realitas tentang kerentanan perempuan mengalami pelecehan seksual di jalanan umum pernah dipotret dalam dalam survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dan difasilitasi oleh Change.org Indonesia pada 2019. Dengan melibatkan total responden sebanyak 62.224 orang Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik (2019) mencatat 3 dari 5 Perempuan pernah mengalami pelecehan di ruang publik (64 persen dari 38.776 Perempuan) dengan lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan adalah jalanan umum, yaitu sebanyak 33 persen.
Baca Juga: 'Catcall' Tak Bisa Ditoleransi
Data survei ini pun tak jauh berbeda dengan survei terbaru KRPA pada 2021. Dengan total responden 4.236 di seluruh Indonesia, KRPA mencatat kendati diberlakukan pembatasan sosial akibat COVID 19, lebih dari 2.000 responden melaporkan pelecehan seksual di ruang publik umum, seperti jalanan umum dan taman. Hal ini membuat pelecehan seksual di jalanan umum masih jadi lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan dibandingkan di transportasi umum, kawasan pemukiman, dan toko/mall/pusat perbelanjaan.
Jadi kalau dilihat-lihat dari data yang ada, orang Indonesia itu sebenarnya enggak malas jalan kaki. Mereka dan termasuk saya di dalamnya hanya enggak saja. Enggan menerima dampak materi yang bisa ditimbulkan dari minimnya akses trotoar yang tak memadai. Dan enggan menerima dampak non-materi seperti trauma yang ditimbulkan dari kerentanan perempuan pejalan kaki mengalami pelecehan seksual di jalanan umum.
Ilustras oleh: Karina Tungari





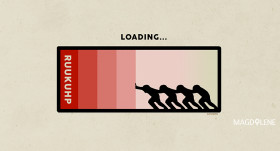
-thumb.png)

Comments