Sebagai anak rantau yang tidak punya sanak saudara di Jakarta, kecemasan segera muncul ketika kasus corona (COVID-19) pertama kali diumumkan awal Maret lalu. Tinggal seorang diri di rumah kos daerah Jakarta Selatan, yang sekarang ini sudah menjadi zona merah, membuat bingung bukan kepalang. Membayangkan harus swa-karantina tanpa dapur dan kulkas untuk memenuhi kebutuhan perut setiap hari rasa-rasanya mimpi buruk yang sebaiknya dihindari.
Beruntung keluarga pasangan saya dengan sukarela menawarkan agar tinggal di tempat mereka untuk sementara waktu. Dengan penuh pertimbangan saya pun mengiyakan tawaran mereka. Poin “penuh pertimbangan” perlu digarisbawahi di sini untuk menggambarkan relasi kami yang terbilang cukup rumit karena kami berbeda agama.
Pasangan saya, “Budi”, lahir dari ibu Cina Indonesia dan ayahnya dari wilayah timur Indonesia. Kakak perempuannya beberapa tahun lalu berpindah kewarganegaraan setelah menikah dengan pria Amerika Serikat, yang kini bekerja di Kedutaan Amerika Serikat di Beijing. Sang kakak dan anak laki-laki mereka saat ini harus menetap di rumah orang tuanya di Jakarta.
Mengingat kondisi Cina-Amerika yang sedang bersitegang, saling tuduh menuduh, apalagi sejak pandemi, berada di tengah-tengah keluarga Budi ternyata cukup tricky. Mengapa? Pertama saya harus bisa berdialog senetral mungkin jika mereka sedang bersitegang. Kedua, sebagai perempuan Sunda dengan wajah “pribumi”, isu rasialisme yang keduanya alami tidak pernah benar-benar saya hadapi.
Meningkatnya xenofobia
Selain COVID-19 yang terus menyebar ke berbagai negara dan mematikan perekonomian, sentimen xenofobia juga kembali menyebar setelah sempat cooling down setelah pemilihan umum tahun lalu. Xenofobia sendiri dapat diartikan sebagai ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, atau yang dianggap asing. Dalam kasus ini etnis Tionghoa menjadi sasaran xenofobia karena COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi secara global ini.
Beberapa waktu lalu, salah seorang teman saya membagikan unggahan di Facebook yang menggambarkan para korban berjatuhan di area publik kota Wuhan. Namun alih-alih kata-kata empati, ia malah menulis bahwa virus itu merupakan azab bagi Cina komunis yang zalim kepada muslim Uighur. Narasi provokatif yang merupakan misinformasi semacam itu mencerminkan xenofobia dengan balutan agama yang acap kali dipelintir oleh kelompok tertentu. Saya bingung betul dengan mereka yang mati-matian membela minoritas muslim di negara lain tapi abai pada hak minoritas di negara sendiri.
Belakangan juga muncul berbagai pesan berantai tentang teori konspirasi yang berisi narasi bahwa COVID-19 merupakan virus yang sengaja dikembangkan oleh Cina, lalu laboratorium tempat virus itu dikembangkan tidak sengaja membocorkan virus itu sehingga akhirnya menyebar. Meski sudah dibantah berbagai lembaga, namun teori konspirasi tersebut kadung dipercaya banyak orang.
Baca juga: Hoaks dan Misinformasi Soal Virus Corona yang Bikin Geleng Kepala
Sebuah hasil penelitian yang dimuat di The Conversation tentang bahayanya teori konspirasi di tengah pandemi menunjukkan, fenomena teori konspirasi yang banyak dipercaya masyarakat ini memiliki dampak yang tidak kalah membahayakan dibanding virus itu sendiri.
Teori-teori ini tidak hanya dapat memengaruhi pilihan kesehatan orang karena kehilangan kepercayaan pada pelayan publik, teori konspirasi juga dapat mengganggu cara berbagai kelompok yang berbeda saling berhubungan serta meningkatkan permusuhan dan kekerasan terhadap mereka yang dianggap "bersekongkol”.
Tendensi sentimen anti-Cina memang bukan perkara baru di Indonesia. Hal tersebut berhubungan dengan sejarah panjang politik rezim Orde Baru (1965-1998). Pada masa ini Presiden Soeharto melarang para pengikut Konghucu untuk beribadah di depan publik, dan sentimen anti-Cina pun terus dilanggengkan, bahkan sampai sekarang. Dari kecil ibu saya, misalnya, selalu bilang bahwa orang Cina itu pelit bin kikir.
Puncaknya terjadi pada kerusuhan 1998 di mana warga Tionghoa menjadi sasaran penjarahan, pemukulan, dan bahkan pemerkosaan yang terjadi secara massal.
Tidak hanya di Indonesia, media-media di Eropa, Australia, Kanada, Italia, hingga Ukraina memberitakan bahwa tindakan rasialis meningkat sejak COVID-19 merebak. Orang-orang keturunan Asia dan mereka yang berwajah oriental menjadi bulan-bulanan. Perlakuan rasialis tersebut bahkan sudah mengarah pada kekerasan fisik seperti yang terjadi pada Jonathan Mok, 23, mahasiswa asal Singapura yang mengalami pemukulan di Oxford Street, London (24/2).
Membangkitkan kembali trauma
Di hari kedua karantina, pasokan makanan sampai obat-obatan sudah menggunung di rumah Budi, cukup untuk persediaan beberapa bulan. Ibu Budi, Tante “Gaby” mengatakan ia merasakan ketakutan dan trauma saat COVID-19 ini muncul dan diikuti sentimen anti-Cina.
“Sebagai peranakan Cina dan korban kerusuhan 1998, ya jujur aja takut. Takut jadi sasaran penjarahan, kan krisis terjadi hampir di semua bidang,” ujarnya sambil menjahit pakaian cucunya.
“Tante udah pengalaman dulu pas 1998. Kami nyetok banyak makanan karena kalau keluar rumah itu bahaya. Secara fisik sudah kelihatan sipit, orang dijarah dan diperkosa itu di depan orang tuanya loh waktu 1998,” katanya dengan emosional.
Obrolan kami malam itu membuat saya kembali tersadar betapa terlahir sebagai orang Sunda dan dianggap “pribumi” itu merupakan privilese. Di tengah wabah corona dan xenofobia terhadap Cina Indonesia, kelompok ini menjadi lebih rentan.
Sementara itu, ada teori konspirasi yang beredar menyebut bahwa virus corona adalah senjata biologis yang direkayasa oleh Badan Intelijen Pusat (CIA) Amerika Serikat sebagai cara untuk berperang di Cina.
Ketegangan kedua negara diperparah oleh Presiden Amerika Donald Trump yang kerap kali melontarkan pernyataan rasialis saat berpidato, atau nge-tuit. Ia sering menyebut COVID-19 sebagai virus Cina. Akibatnya, ketika Cina sekarang ini sudah berangsur pulih, kasus rasialisme justru terjadi pada orang-orang berkulit putih yang menetap di negara tirai bambu tersebut.
Baca juga: Dari Lucinta Luna sampai Virus Corona: Tips Jadi Pembaca Berita yang Kritis
Menurut “Riana”, kakak Budi, suaminya menghadapi penolakan, seperti ditolak tukang cukur atau penjual makanan, karena takut ditulari virus oleh orang kulit putih. Teman-temanya yang berasal dari Inggris dan Ukraina pun menghadapi tindakan rasialis yang sama. Mereka kesulitan memperpanjang sewa apartemen di Beijing, karena pemilik sewa yang tidak mau ada orang asing tinggal di wilayahnya. Sementara untuk kembali ke negaranya saat ini sulit karena pandemi.
“Di Cina kalau sudah enggak mau nyewain, tanpa aba-aba barang-barang langsung dikeluarin, digeletakin begitu aja di luar apartemen,” ujar Riana.
Suasana biasanya menjadi keruh ketika Tante Gaby dan Riana berargumen. Sebagai Cina Indonesia, Tante Gaby biasanya menjawab dengan nada agak sinis terhadap orang kulit putih.
“Ya tapi orang kulit putih yang rasialis duluan sampai main fisik sama orang-orang Cina yang tinggal di negara mereka. Kakak harus ingat Mama juga secara historis orang Cina,” ujarnya.
Layaknya Soekarno yang kebingungan memilih antara bersekutu dengan Uni Soviet atau Amerika pada masa perang dingin dulu, saya pun berusaha menjadi pihak nonblok ketika kami bertiga sedang berkumpul dan mengobrol. Tidak ingin memvalidasi keduanya, saya biasanya hanya berargumen bahwa mau dari negara mana pun dan siapa pun pelakunya, xenofobia tetap merupakan sesuatu yang salah dan membahayakan.
“Yang salah bukan lagi antara Cina dan Amerika tapi lebih kepada para pelaku yang melanggengkan tindak rasialisme itu sendiri”, ujar saya.
Dalam keluarga saya, perdebatan paling sengit di antara kami paling tentang logat Sunda mana yang paling kental (atau tentang hubungan saya dan Budi). Sejak mengungsi karena pandemi, saya mendadak merasa jadi pengamat politik luar negeri yang menangani perang dagang dan sentimen Cina-Amerika. Sungguh persoalan xenofobia ini membuat saya yang sudah cemas karena wabah semakin pusing.
Mungkin sudah saatnya kita mulai memutus rantai narasi-narasi rasialis yang kerap kali berseliweran di lini masa sosial media, atau pesan berantai yang dibagikan lewat WhatsApp. Kita harus mengingatkan si pembaginya tentang bahaya melanggengkan dan mempercayai narasi semacam itu. Ada kelompok yang rentan jadi korban di kehidupan nyata hanya karena kita yang turut membagikan narasi provokatif itu.
Kita semua sedih, cemas, takut, dan merasa kehilangan. Jangan sampai kepedihan kita menghadapi pandemi ini bertambah lagi dengan gesekan konflik rasial. Seperti yang dikatakan Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhamom, “Stigma to be honest, is more dangerous than the virus itself.”



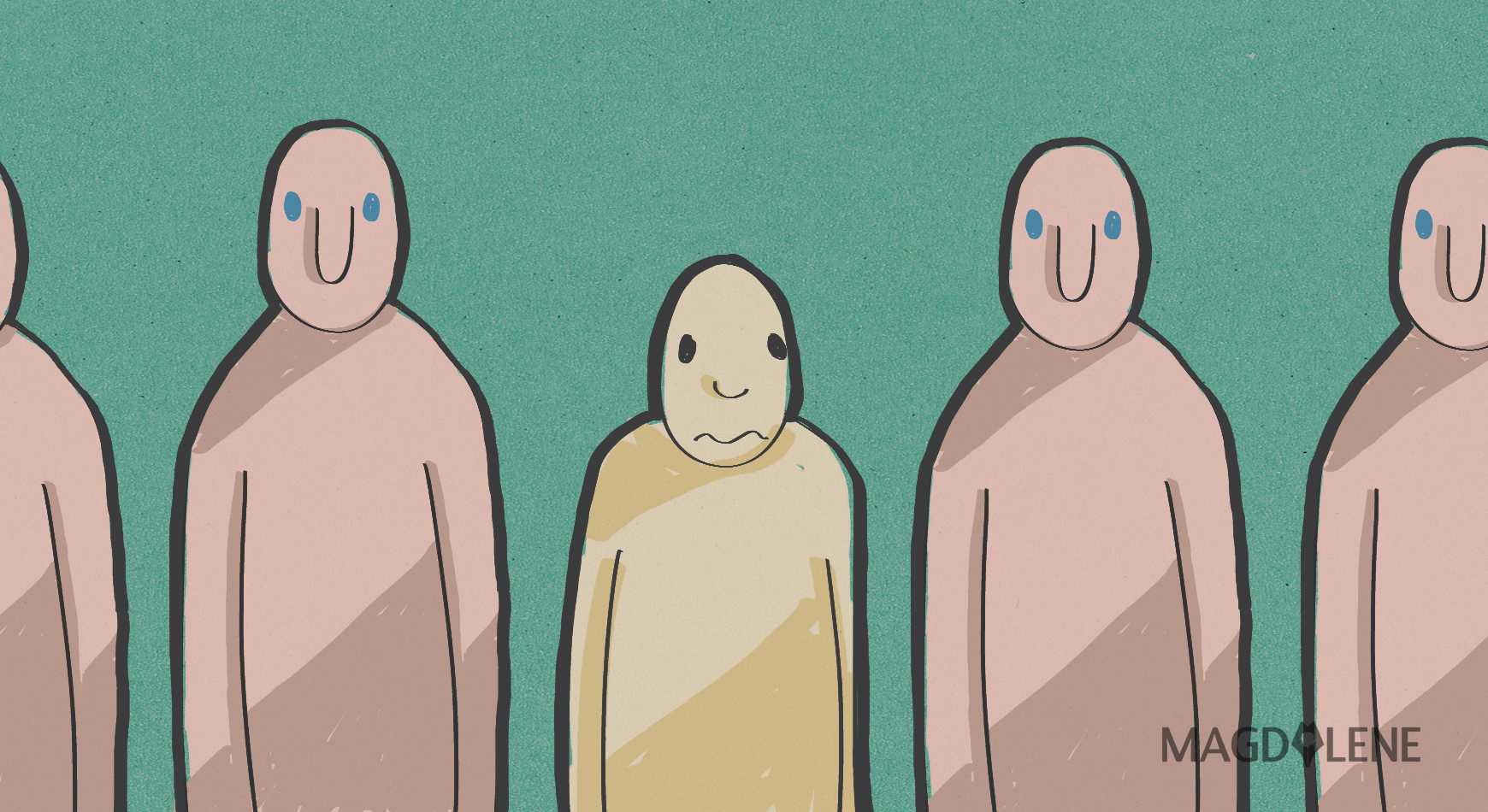
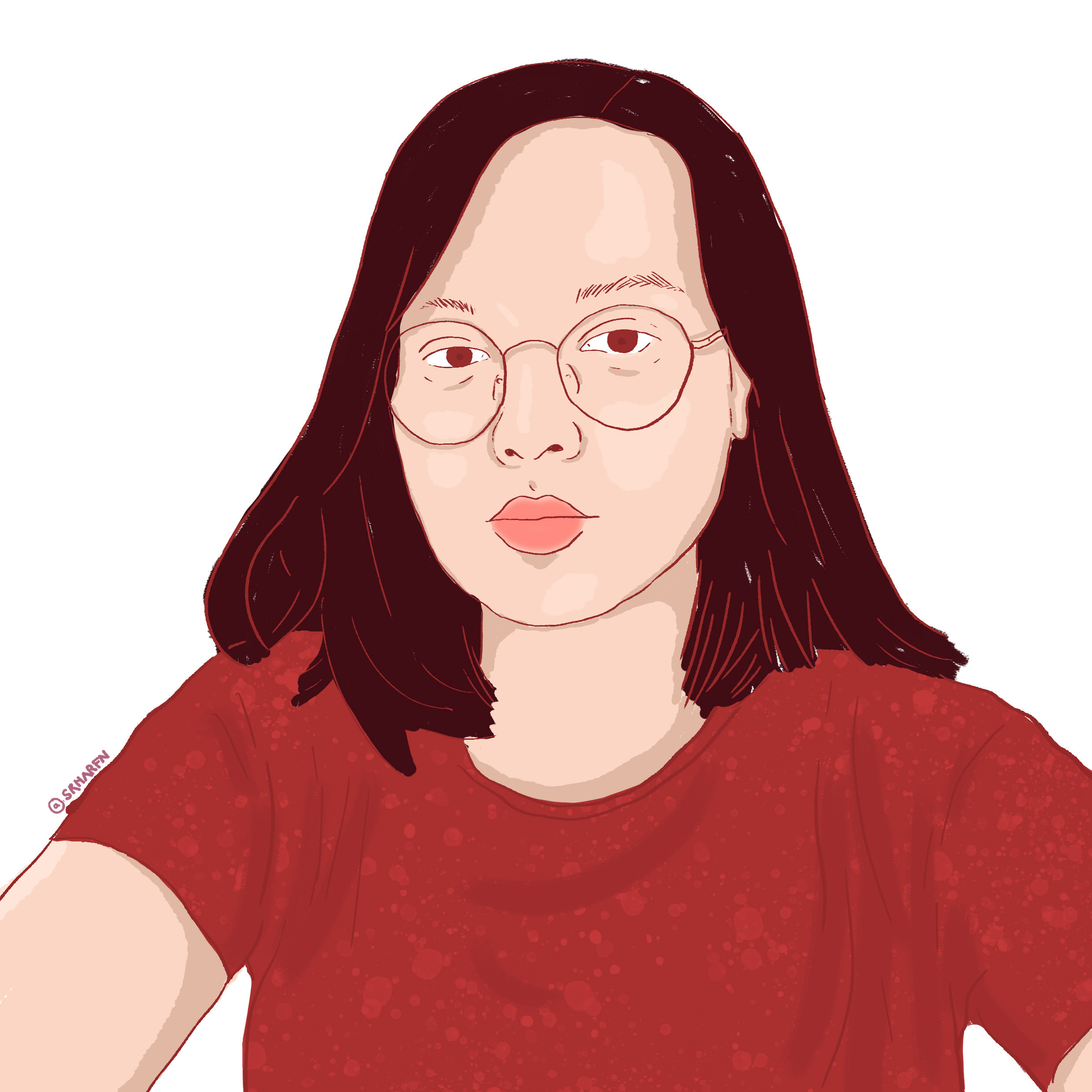



Comments