Video-video dari kanal YouTube The Lawalatas—aktris Reggy Lawalata dan kedua anaknya Oscar dan Mario—menjadi viral belakangan ini, terutama karena pengakuan Oscar soal identitas gendernya sebagai transpuan. Oscar mengatakan sekarang memilih menggunakan nama Asha Smara Darra, ia mengisahkan perjalanannya yang cukup panjang hingga akhirnya memutuskan untuk melela dan menjalankan transisinya.
Bagi saya yang seorang transpria, kemunculan kisah The Lawalatas merupakan langkah penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, terutama keluarga, terhadap transgender. Sebagai desainer mode dengan reputasi bagus, kisah Asha menjadi semacam validasi bagi kelompok transgender.
Meski demikian, ternyata masih saja ada miskonsepsi mengenai transgender, bahkan dalam komunitas LGBTIQ sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Asha belum sepenuhnya transgender dan “masih gay” karena berambut pendek. Lalu ada juga yang menyebut identitas transgender Asha adalah produk dari broken home dan orang tua yang tidak becus mendidik anak.
Baca juga: 5 Hal yang Bisa Dipelajari dari Hubungan Oscar dan Reggy Lawalata
Pernyataan-pernyataan ini mengingatkan saya pada miskonsepsi yang dilekatkan pada saya saat saya melela. Untuk itu saya ingin membahasnya berikut ini.
- Belum perempuan kalau belum feminin
Masyarakat masih menanamkan stereotip bahwa perempuan harus berpenampilan feminin, berambut panjang, berdada besar, dan berdandan. Sementara laki-laki harus maskulin, berambut pendek, berperut bak roti sobek, dan acuh tak acuh. Sayangnya, stereotip ini juga diberlakukan pada kelompok transgender sebagai syarat untuk lebih diterima, baik oleh masyarakat maupun komunitas LGBTIQ sendiri. Itulah mengapa, masih ada yang meragukan “keabsahan” Asha sebagai transpuan karena berambut cepak dan bahkan menyebut bahwa dia “masih cowok” karena ekspresinya tersebut.
Padahal, bagaimana kamu bertingkah laku dan berpenampilan (ekspresi gender), dan bagaimana kamu memaknai dirimu (identitas gender) bukanlah sesuatu yang selalu berkaitan satu sama lain. Namun akibat adanya konstruksi sosial yang biner, ekspresi dan identitas gender selalu dianggap satu paket (perempuan feminin dan laki-laki maskulin). Sehingga yang di luar konstruksi biner tersebut selalu dianggap aneh.
Sah-sah saja ‘kan kalau ada laki-laki yang suka berdandan feminin seperti para anggota BTS, atau perempuan yang tomboi berambut pixie cut, atau bahkan berotot seperti Madonna dan Vicky Burky? Begitu pula dengan kelompok transgender. Transpuan tidak melulu harus menjadi sosok perempuan yang feminin, berambut panjang, dan memakai sepatu hak tinggi untuk diakui sebagai perempuan.
- Belum sepenuhnya transgender kalau belum operasi
Lagi-lagi karena konstruksi yang biner tadi, masyarakat seperti menerapkan standar tertentu untuk diakui sebagai laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan harus bervagina dan laki-laki harus berpenis. Akibatnya, identitas-identitas yang di luar standar tersebut, seperti kelompok transgender, selalu menjadi liyan.
Masih banyak yang menganggap bahwa transgender belum seutuhnya gender yang mereka hayati jika belum menempuh prosedur medis atau operasi. Hal ini juga sering terjadi terhadap transpria. Banyak transpria tidak dianggap sebagai laki-laki atau transpria karena belum atau tidak menjalankan tindakan medis apa pun. Anggapan ini pada akhirnya berdampak pada tingkat kepercayaan diri para transpria, yang beberapa mereka merasa tidak pantas menyebut diri laki-laki atau transpria karena belum melakukan terapi hormon.
Padahal, lagi-lagi, identitas gender seseorang tidak ada hubungannya dengan bentuk fisik, karakteristik seks, serta status transisi medis orang tersebut. Tidak semua transgender tidak nyaman dengan tubuhnya. Tidak semua transgender ingin untuk melakukan prosedur medis. Ada transpuan yang nyaman dengan penisnya dan tidak ingin menghilangkannya; ada juga transpria yang nyaman dengan genitalnya.
Selama seseorang yang terlahir dengan penis menghayati dirinya sebagai perempuan, tetaplah ia perempuan. Begitu pula seseorang yang terlahir dengan vagina, selama ia menghayati dirinya sebagai laki-laki, ia tetaplah laki-laki. identitas gender seseorang hanya bisa ditetapkan oleh orang itu sendiri, bukan kemauan orang lain.
Baca juga: Lucinta Luna dan Obsesi Kita dengan Selangkangan Orang Lain
- Transgender adalah ‘produk gagal’ dari keluarga yang berantakan
Saya masih ingat pada episode saat Reggy Lawalata bercerita mengenai proses dirinya berdamai dengan Asha. Reggy mengatakan bagaimana ia mendapat banyak penghakiman bahwa kondisi Ahsa adalah akibat perceraian orang tuanya. Asha disebut kehilangan sosok ayah sehingga ingin menjadi transgender, dan Reggy dianggap gagal mendidik Asha.
Cerita Reggy ini sangat dekat dengan beberapa bagian dari perjalanan saya sebagai transpria. Saya sudah menghayati diri sebagai laki-laki sejak kecil, walaupun sejak itu saya masih menerka-nerka identitas dan jati diri saya karena minimnya informasi dan panutan bagi saya. Sayangnya, saat saya mulai firm dengan jati diri saya, waktunya bersamaan dengan perceraian orang tua saya. Alhasil, omongan dan penghakiman seperti yang diterima Asha dan Reggy juga terjadi saya terima dari keluarga besar. Perbedaannya, saya sudah patah arang dengan situasi keluarga yang sangat konservatif sangat, dan memilih memutuskan hubungan.
Identitas gender seseorang tidak ada hubungannya dengan bentuk fisik, karakteristik seks, serta status transisi medis orang tersebut. Tidak semua transgender tidak nyaman dengan tubuhnya. Tidak semua transgender ingin untuk melakukan prosedur medis.
Karena itu, saya salut dengan bagaimana Reggy mendukung Asha dan prosesnya sebagai transgender. Meskipun orang tua yang menerima dan mendukung anaknya yang transgender dicap sebagai orang tua yang buruk, Reggy adalah sosok orang tua yang diidamkan oleh sebagian besar individu transgender, dan merupakan sosok yang bisa menjadi pembelajaran bagi orang tua dengan anak transgender.
Benarkah keluarga broken home adalah penyebab seorang anak memiliki gender dan seksualitas berbeda? Bagi saya, jawabannya sederhana. Jika broken home menjadi penyebab, pasti akan lebih banyak LGBTIQ di luar sana. Nyatanya, banyak juga keluarga-keluarga yang masuk kategori “samara” alias sakinah mawaddah warahmah yang memiliki anggota keluarga yang transgender.
Reggy juga bercerita dalam episode The Lawalatas bahwa ia sudah menyadari Asha berbeda sejak ia kecil. Ia sempat menyuruh Asha untuk ikut dengan Mario, anak keduanya, untuk bermain basket dan bergaul dengan teman-teman Mario yang dinilai lebih macho dan “laki”. Namun, Asha tetap menjadi Asha. Hingga akhirnya Reggy sudah berdamai, menerima, bahkan memberi dukungan tak terhingga kepada Asha sebagai transgender.
Namun ternyata tidak sampai situ. Penerimaan dan dukungan Reggy justru dianggap sebagai langkah yang salah dan akan membuat anak semakin buruk dan “kebablasan”. Padahal studi oleh Trans Student Educational Resources (TSER) pada 2012 menunjukkan, 72 persen remaja transgender dengan orang tua yang menerima identitas mereka memiliki tingkat harapan dan kebahagiaan hidup lebih tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Trans Student Educational Resources (TSER) pada 2012, mengenai pentingnya peran sistem dukungan pada transgender remaja.
Mereka yang diterima dan mendapat dukungan dari orang tua atau keluarga juga memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan kondisi kesehatan mental yang baik atau sangat baik. Sementara remaja transgender yang mendapat penolakan dari keluarga cenderung menderita depresi, mengalami permasalahan dalam keluarga, serta memiliki keinginan untuk bunuh diri yang lebih tinggi.
Terlepas dari keistimewaan atau privilese yang dimiliki oleh keluarga Lawalata, dukungan dan penerimaan Reggy sejak awal perjalanan anaknya telah membuat Asha tumbuh menjadi individu yang dapat menerima dirinya dengan baik, dekat dengan keluarga, dan berprestasi. Bagaimana Reggy menerima identitas anaknya yang transgender tidak hanya berdampak pada Asha sendiri, tapi juga pada Mario, adik laki-laki Asha yang sangat maskulin, namun dapat menerima dan mendukung kakaknya. Bahkan hubungan keduanya sangat akrab. Sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh laki-laki yang memiliki maskulinitas toksik dan rapuh di luar sana jika mereka berhadapan dengan transpuan.
- Transgender karena ketularan saudara
Mitos ini sering menimpa transgender yang memiliki banyak saudara kandung dengan gender yang sama. Saya salah satu yang dihakimi dengan mitos tersebut. Ketika orang tahu bahwa saya memiliki dua adik laki-laki, tidak jarang yang berkata bahwa saya “terbawa” karena terlalu banyak main dengan mereka. Padahal, secara logika, saya adalah anak pertama dan lahir lebih dulu dan dari orang tua yang cis-gender. Kalau tular-menular itu benar, seharusnya saya tertular dari orang tua dan menjadi seorang cis-gender, atau adik-adik saya yang lahir setelah sayalah yang seharusnya tertular menjadi transgender. Nyatanya kan tidak.
Mitos ini juga dipatahkan oleh kakak beradik Lawalata, yang tidak “saling menulari” menjadi transgender atau menjadi macho. Jadi lupakanlah soal cocoklogi, apalagi alasan mistis seperti guna-guna dan kutukan.
Baca juga: Transgender Dambakan Toilet Umum Uniseks
- Transgender adalah homoseksual kebablasan
Soal ini justru banyak saya dengar dari komunitas LGBTIQ sendiri. Banyak yang berpikir bahwa “menjadi” transgender adalah usaha seorang homoseksual agar dapat menikah dengan pasangannya, misalnya ketika pasangan gay dengan salah satu lebih feminin dari pada salah satunya, maka yang feminin ini kalau dibiarkan lama-lama ingin berubah menjadi perempuan atau transpuan. Sama juga dengan pandangan bahwa transpria adalah lesbian maskulin yang ingin menikahi pasangan perempuannya. Atau sebaliknya, lesbian maskulin adalah transpria yang tertunda.
Tentu saja ini adalah kesalahpahaman besar. Pertama, tidak semua transgender mengubah karakteristik seks mereka untuk menikah dengan pasangan. Bahkan, sebagian besar transgender melakukannya sebagai upaya berdamai dan mencintai diri sendiri.
Kedua, tidak semua transgender adalah heteroseksual, dalam artian transpuan memiliki ketertarikan pada laki-laki cis dan transpria memiliki ketertarikan kepada perempuan cis. Banyak juga transgender yang memiliki ragam orientasi seksual lainnya. Seperti transpria yang memiliki ketertarikan kepada laki-laki, transpuan yang memiliki ketertarikan kepada perempuan, transgender yang berelasi dengan transgender lainnya, dan ada juga transgender yang tidak memiliki ketertarikan seksual sama sekali.

Laith Ashley merupakan seorang transpria yang berprofesi sebagai model dan penyanyi. Laith melela sebagai aseksual.
Bagaimana seseorang menghayati dirinya, dalam hal ini identitas gender, dan kepada siapa seseorang tertarik secara romantis dan emosional (orientasi seksual) adalah dua hal yang berbeda. Seksualitas setiap individu bisa berbeda dan sangat cair, sesuai perjalanan hidup masing-masing dalam berdamai dengan diri.

Jake Graf dan istrinya, Hannah Winterbourne, seorang transpuan yang merupakan prajurit militer di Inggris, serta anak mereka.
Mengutip kata Jake Graff, seorang aktivis transgender yang juga pembuat film, “I’ve come out three times. I came out as a lesbian, I came out as trans, and then I came out as a gay man so I’ve been around the block. For me, as my experiences have grown and my hormones have leveled out, I’m attracted to people and not a particular gender.”
Ketiga, informasi yang minim mengenai transgender di Indonesia membuat sebagian transgender mengidentifikasi diri sebagai homoseksual ketika mencari dukungan sebaya di masa awal pencarian jati diri mereka. Doktrin “melawan kodrat itu dosa” juga sering menjadi alasan dan ketakutan para transgender untuk melela sebagai transgender. Namun, sebagian besar teman-teman transgender tidak nyaman jika disebut dan disamakan dengan kelompok homoseksual.
Masih banyak lagi miskonsepsi soal transgender yang beredar di masyarakat maupun komunitas LGBTIQ sendiri yang mungkin butuh tulisan jilid 2. Namun, apa yang ditampilkan oleh keluarga Lawalata dengan cerita penerimaan Reggy, cerita melela dan proses dari Asha, dan bagaimana Mario sebagai laki-laki menerima saudaranya yang transpuan, patut kita jadikan contoh bahwa saling berdamai, mendengar, dan menerima satu sama lain adalah hal yang berarti bagi kelompok transgender.





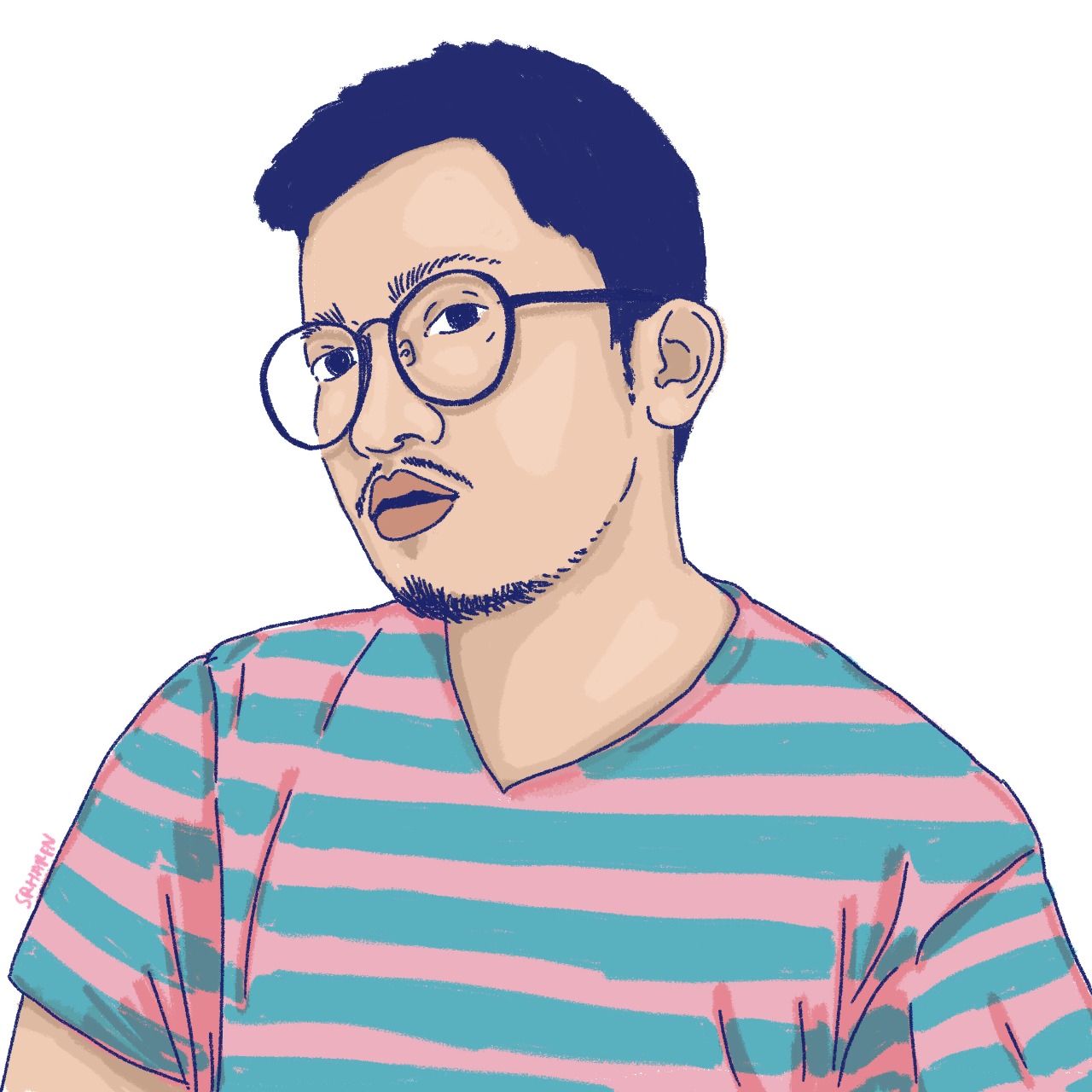



Comments