Bercerai seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan prosesnya mudah dan terjangkau oleh semua orang tanpa terkecuali. Namun di tengah-tengah nilai sosial masyarakat yang mengglorifikasi ikatan pernikahan, bercerai di Indonesia menjadi urusan yang pelik dan sering kali membawa stigma negatif. Tidak mudah bagi warga negara Indonesia, terutama perempuan, untuk menggugat cerai pasangannya. Hal ini diperumit dengan adanya aturan cerai khusus bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang sejak 1990 belum ditinjau kembali relevansinya.
Hal ini dialami oleh “Dessy”, yang bekerja sebagai ASN di Kantor Dinas Pemerintah Daerah di salah satu provinsi. Sebagaimana dituturkan oleh Dessy, pernikahan yang dijalaninya bersama suami semakin tidak harmonis. Dessy merasakan konflik rumah tangganya kian hari kian meruncing yang berujung pada perselisihan dan kekerasan bertubi-tubi.
Tidak hanya kekerasan fisik, Dessy juga mengalami kekerasan verbal dan psikologis serta penelantaran ekonomi dari laki-laki yang dinikahinya sepuluh tahun lalu itu. Dengan melalui berbagai macam pertimbangan, ia akhirnya mantap memutuskan bercerai.
Namun, ternyata tidak semudah itu bagi Dessy untuk memulai proses perceraian secara hukum. Sebagai seorang ASN, ada prosedur berlapis yang harus Ia jalani sebelum gugatan cerainya bisa diproses di Pengadilan Agama.
Baca juga: Reggy Lawalata dan Ketabuan Seputar Perceraian
Rumitnya Saat ASN Bercerai
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan aturan perubahannya PP No. 45/1990, seorang ASN wajib mengantongi surat izin bercerai dari pejabat negara terkait. Dalam kasus Dessy, pejabat ini diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di provinsi tempat Dessy bertugas.
Tidak hanya itu, untuk mendapatkan surat izin tersebut, Dessy harus melalui proses mediasi yang panjang mediasi dan berliku di internal kedinasannya, kantor Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Kantor Urusan Agama (KUA) di lokasi ia menikah, dan di BKD sendiri.
Menurut pengakuan Dessy, ia telah menjalani tujuh sesi mediasi di tiga instansi tersebut dalam rentang lima bulan. Proses ini mengharuskan Dessy menceritakan kekerasan dan permasalahan rumah tangganya secara berulang-ulang kepada staf terkait dan atasan langsungnya. Dessy Ia diwajibkan untuk mengurus surat keterangan bercerai dari Kantor Kelurahan melalui RT dan RW tempatnya tinggal yang kembali membuatnya harus menceritakan persoalan pribadi rumah tangganya kepada orang lain.
Proses mediasinya sendiri pun bukan perkara mudah. Sebagai seorang perempuan, Dessy merasa pihak mediator, yang didominasi oleh laki-laki, gagal memahami persoalan dengan menggunakan perspektif perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berulang kali mediator memiliki persepsi yang salah mengenai definisi kekerasan yang dianggap hanya meliputi fisik yang mengancam jiwa (misalnya, bonyok, memar dan berdarah).
Baca juga: Mimpi Buruk Baru: Mengurus Perceraian di Tengah Pandemi
Kegagalan memahami apa yang disebut kekerasan membuat mediator memberikan saran yang bias dan membahayakan. Dessy diminta untuk mengizinkan suaminya pulang ke rumah dan mencabut laporan kepolisian atas kekerasan fisik yang dialaminya dengan alasan mereka masih suami istri, dan tidak elok seorang ASN terlibat urusan dengan polisi. Pihak mediator seakan tidak peduli bahwa kekerasan bisa terjadi lagi jika pelaku dibiarkan berkumpul lagi dengan korban.
Bias Gender bagi ASN Perempuan yang Menggugat Cerai
Latar belakang Dessy yang berpendidikan tinggi (pascasarjana) juga kerap dijadikan amunisi untuk memojokkan posisi Dessy sebagai perempuan. Seorang perempuan dianggap menjadi “liar” dan “pemberontak” jika sekolah tinggi sehingga menuntut suami macam-macam. Belum lagi pendekatan-pendekatan agamis sarat bias gender yang dilancarkan oleh mediator, sehingga perempuan seakan bersalah karena dianggap memancing emosi pasangannya dan tidak sabar dalam menghadapi kekurangan suami.
Dessy kerap tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membela diri, sehingga informasi yang dikumpulkan menjadi timpang. Mediator laki-laki yang ia temui selama proses mediasi dinilainya tidak netral dan tidak mampu melihat persoalan secara objektif. Gugatan cerai dari Dessy dianggap tidak memiliki basis yang kuat padahal perselisihan terus menerus dan penganiayaan lahir batin adalah alasan valid bagi seseorang untuk bercerai menurut UU Perkawinan No. 1/1974.
Baca juga: Risiko Mediasi dan Rekonsiliasi Antara Penyintas dan Pelaku KDRT
Keseluruhan proses mediasi di BKD membuat Dessy tertekan. Jika “berulah” atau terlalu banyak menyanggah, ia merasa pekerjaannya sebagai ASN akan terancam. Berulang kali mediator mengatakan jika Dessy tetap mempertahankan perilaku emosionalnya di dalam rumah tangga maka Ia bisa terkena tindakan disipliner dari negara, tanpa melihat apa yang menjadi latar belakang persoalan dan kekerasan yang sudah dialami Dessy selama bertahun-tahun.
Pengalaman Dessy cukuplah menjadi bukti carut marutnya prosedur perceraian di Indonesia. Seorang ASN di negara ini harus rela persoalan pribadi rumah tangganya digali sedemikian dalamnya dan dijadikan bagian dari penilaian profesionalitas bekerja, oleh orang-orang yang tidak kompeten yang bahkan tidak mengenalnya dekat.
Jika Anda perempuan, maka ketidakadilan yang Anda alami bisa berlipat-lipat. Sebagaimana tertulis di PP No. 10/1983, tujuan intervensi negara dalam perceraian adalah rujuknya kembali suami dan istri yang berselisih. Tanpa SOP yang jelas, berbagai cara bisa dilakukan oleh mediator dan instansi terkait untuk mencapai tujuan ini tanpa mempertimbangkan faktor perlindungan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan, terutama korban KDRT.
Sambil menunggu surat dari BKD keluar yang kabarnya bisa memakan waktu tiga bulan, Dessy hanya bisa berharap cemas apakah proses berbelit yang sama akan dihadapinya lagi nanti di Pengadilan Agama. Pada akhirnya, apakah memang segala yang seharusnya mudah dan menjadi hak warga negara harus dipersulit di negara ini?



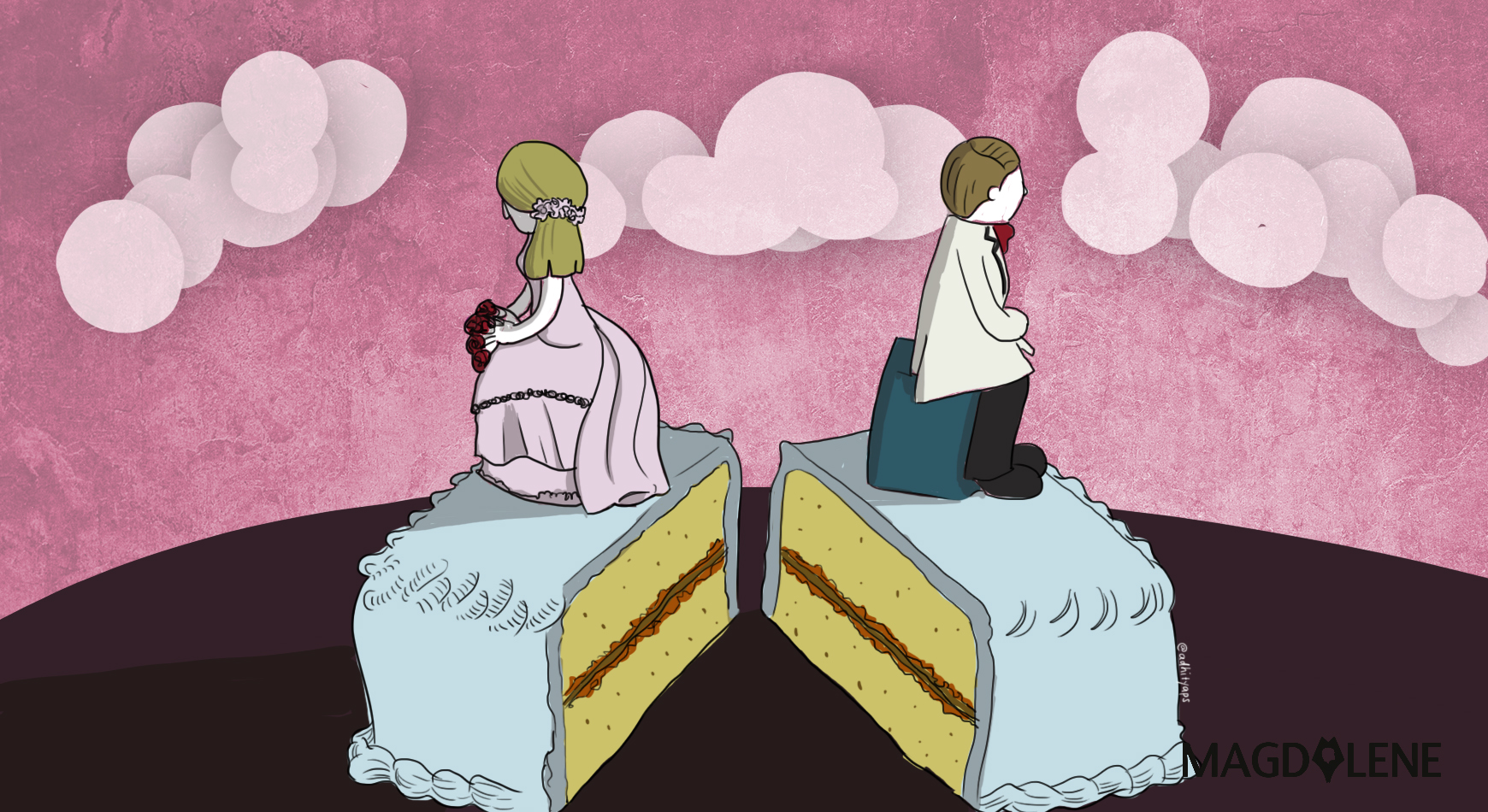



Comments