Tahun lalu, penganiayaan terhadap “Rina” oleh suaminya mencapai puncaknya saat ia dihajar sampai tangannya terkilir. Tak sanggup lagi menghadapi kekerasan dalam rumah tangga tersebut, Rina keluar dari rumah dan menggugat cerai, sebelum kemudian memberanikan diri melapor ke polisi untuk meminta perlindungan.
Polisi memang merespons laporan Rina dan menjaga rumahnya, namun perlindungan ini tidak dilakukan dengan cuma-cuma. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) telah mewajibkan hal itu. Pasal 16 Ayat 1 UU tersebut menyatakan bahwa polisi wajib untuk segera memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam, terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT.
“Saat melapor ke polisi, Rina belum menjadi mitra LBH APIK Jakarta. Dia meminta perlindungan kepada polisi, yang kemudian menjaga rumahnya. Yang jadi masalah, polisi minta uang,” ujar Husna Amin, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).
Menurutnya, perlindungan yang diwajibkan oleh UU sering kali tidak dilakukan sehingga LBH APIK pun tidak pernah mengajukan permohonan perlindungan sementara kepada polisi.
“Polisi justru sering melakukan mediasi. Selain itu, laporan baru diterima kalau korban sudah mengalami luka berat. Jadi, kalau mengadu dan tidak ada bekas luka berat, tidak akan diterima,” ujar Husna.
Pratiwi Febry, pengacara publik yang pernah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengatakan bahwa sepanjang pengalamannya, polisi tidak pernah berinisiatif memberikan perlindungan sementara. Justru dialah yang pernah mengajukan permohonan perlindungan kepada polisi meskipun tak direspons dengan baik, ujarnya.
“Apabila korban kembali ke rumah, dia akan berpotensi kembali mengalami KDRT. Kami selalu minta perlindungan ke polisi untuk menempatkannya di rumah aman. Proses agar laporan KDRT diterima juga sangat sulit, misalnya polisi meminta buku nikah atau mereka berkata ‘nanti kami proses dulu’. Padahal korban berada dalam bahaya,” ujarnya.
Baca juga: Kasus KDRT Meningkat Namun Rumah Aman Terbatas
Rumah aman sebagai solusi cepat
Sudah hampir 16 tahun berlalu sejak UUPKDRT disahkan. Berbagai pembaharuan hukum pidana dan acara pidana, yang tak pernah diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dicantumkan dalam UU ini, salah satunya adalah pasal-pasal mengenai perlindungan. Namun kenyataannya, sulit bagi korban mendapatkan perlindungan.
Sebagai solusi cepat, jika sangat dibutuhkan, lembaga-lembaga pemberi layanan bagi korban kekerasan biasanya menyewa rumah aman.
“Kalau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bisa merespons dengan cepat, kami mengontak mereka. Atau kami mencari organisasi non pemerintah yang menyediakan rumah aman bagi perempuan,” ujar Pratiwi.
Arnita Ernauli Marbun, konselor hukum Rifka Annisa Women’s Crisis Center di Yogyakarta mengatakan, argumen kepolisian untuk tak memberikan perlindungan sementara, meskipun korban sudah melapor, adalah minimnya sumber daya manusia, banyaknya laporan yang masuk, dan ketiadaan tempat untuk mengamankan korban di kantor polisi. Namun, jika sangat dibutuhkan, polisi akan mengontak lembaganya. Pasal 17 UU PKDRT menyebutkan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan relawan pendamping.
“Kami memiliki layanan hotline 24 jam. Kami bisa melakukan penilaian lewat telepon untuk mengetahui seberapa pentingnya kebutuhan rumah aman bagi klien. Kalau dirasa sangat penting, kami mendatangi kantor polisi saat itu juga dan mengamankannya,” kata Arnita.
Sejumlah korban yang enggan melapor sehingga Arnita pernah mengusahakan perlindungan untuknya, tetapi tidak melalui prosedur yang tercantum dalam UU PKDRT, yakni harus melapor polisi terlebih dulu.
Baca juga: Perlindungan Saksi dan Korban KDRT Terhambat Aturan PSBB dan WFH
“Kami meminta korban meninggalkan rumahnya, tetapi dia tidak berani lapor ke polisi karena ada risiko diminta damai dan dianggap bahwa kasusnya adalah urusan privat. Karenanya kami arahkan dia untuk menuju ke kantor kami,” katanya.
“Klien berada di shelter kami selama dua minggu dan setelah melakukan konseling secara intensif, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Otomatis kami mengupayakan pengamanan dengan cara lain,” ujarnya.
“Cara lain” yang dimaksud adalah melakukan pendekatan kepada kepolisian sektor (polsek) terdekat. Polsek dapat mengontak Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas, polisi yang bertugas di tingkat desa/kelurahan yang mengemban fungsi preemptive dengan cara bermitra dengan masyarakat) agar berpatroli untuk memonitor rumah korban. Pendamping korban juga melakukan pendekatan terhadap RT/RW setempat dan tetangganya.
Ketentuan perlindungan lainnya dalam UU PKDRT adalah “menetapkan suatu kondisi khusus” (pasal 31 ayat 1 huruf a). Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “kondisi khusus” adalah “pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban”. Penetapan kondisi khusus dilakukan oleh pengadilan setelah menerima permohonan korban atau kuasanya.
Selama bekerja di LBH Jakarta, Pratiwi mengatakan bahwa kasus yang dia tangani tidak pernah sampai ke tahap persidangan karena banyak yang terhenti di kepolisian, setelah korban berdamai dengan pelaku. Dengan demikian, otomatis dia tak pernah mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan suatu kondisi khusus.
Arnita dari Rifka Annisa juga tak pernah mengajukannya karena “kami fokus kepada korban. Daripada kami mengurusi pergerakan pelaku, lebih baik kami mengamankan korban. Pengamanan korban kan juga bagian dari usaha menjauhkan korban dari pelaku.”
Baca juga: KDRT dan Buruh Perempuan: Rantai Kekerasan yang Sulit Diputus
Ketiadaan SOP dan kesenjangan pengetahuan
Pratiwi mengatakan tidak mengetahui secara pasti kendala polisi dalam menerapkan pasal perlindungan. Namun, untuk mengilustrasikannya, dia merujuk pada peraturan mengenai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian.
“Tidak ada sebuah hal yang pakem mengenai bagaimana seharusnya unit PPA. Aturannya sih ada tapi bagaimana infrastrukturnya, itu tidak ada. Dari situ saya berasumsi, ketika ada peraturan perlindungan dalam UU KDRT, yang harus kita pertanyakan apakah tersedia infrastrukturnya,” katanya.
“Saya mengasumsikan polisi kesulitan memikirkan infrastrukturnya. Lalu bagaimana biaya hidup korban selama diproteksi? Secara birokrasi, semua hal itu harus diatur sehingga penggunaan anggarannya jelas. Kalau tidak ada (pengaturan), maka penerapannya akan semrawut di lapangan,” tambahnya.
Dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun LBH APIK 2017, lembaga ini mendorong adanya standardisasi penerapan Standard Operating Procedure (SOP) di aparat penegak hukum untuk penanganan kasus KDRT. Namun, hingga saat ini, hal itu belum ada tindak lanjutnya.
LBH APIK mendorong adanya SOP adalah karena polisi sering kali memediasi kasus. Meskipun UU PKDRT sudah disahkan pada tahun 2004, hal itu tak menjamin bahwa polisi mengetahui mengenai peraturan ini.
“Di polsek-polsek yang tidak memiliki unit PPA, jarang sekali yang mengetahui bahwa ada UU PKDRT. Mereka hanya mengetahui KUHP saja,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah lembaga-lembaga layanan pernah mendorong adanya Peraturan Pelaksanaan (PP) UU PKDRT, Husna menjelaskan, mereka lebih memilih melakukan hal yang paling memungkinkan.
“Bagaimanapun juga untuk melaporkan kasus ke kepolisian dibutuhkan alat bukti dulu, misalnya visum. Kami mendorong adanya visum gratis bagi korban kekerasan. Apabila ada visum, berarti ada alat bukti dan polisi tidak punya alasan untuk menolak laporan,” katanya.
Artikel ini didukung oleh hibah Splice Lights On Fund dari Splice Media.
Jika memerlukan bantuan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan hubungi Komnas Perempuan (021-3903963, [email protected]); Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan/LBH APIK (021-87797289, WA: 0813-8882-2669, [email protected]). Klik daftar lengkap lembaga penyedia layanan di sini.



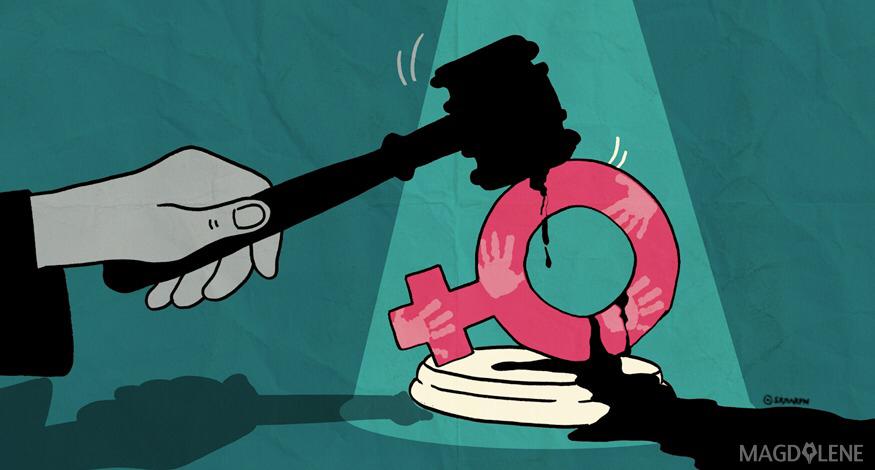




Comments