Peringatan Pemicu
20 Mei 2021, sekitar jam 11 siang
“Mbak, ke sini mau berobat apa?” tanya ibu berkerudung biru nan asing itu pada saya, sebutlah “Bu Indah”.
“Poli jiwa, Bu,” saya bilang sambil menunjuk ruangan psikiater saya. “Kalau ibu?”
“Oh, saya nemenin anak saya. Capek pikiran. Ini udah ketiga kali ke psikiater ini,” kata Bu Indah.
Ia kemudian curhat soal anaknya, yang sudah semester 8 dan belum kunjung kelar skripsi. Anak itu punya dua kakak yang menurut Bu Indah sudah “sukses”, punya kerja di tempat bonafid, bahkan ada yang sudah punya rumah, jadi ia suka membandingkan dengan dalih ingin memotivasi anaknya ini.
“Setiap saya tanya soal skripsi, dia pasti marah, murung. Tapi kalau teman-temannya datang nyamperin, dia baru kelihatan senang,” ujarnya.
Terkadang, si anak suka menjerit-jerit merasa badannya sakit dan demam, tapi saat beberapa kali dia dibawa ke rumah sakit berbeda, dia selalu didiagnosis tidak sakit apa pun. Paling mentok dehidrasi sehingga butuh diinfus beberapa hari.
Bu Indah merasa semua kebutuhan anaknya sudah dia cukupi, tapi si anak masih saja terganggu mentalnya. Dia tak paham. Sempat dia bilang, “Buat apa sih, minum obat segala?” Saya cuma meresponsnya dengan tetap berusaha agar tidak menghakimi dan menggurui.
“Yang Ibu kira niat baik atau sesuatu yang netral, normal dilakukan banyak orang tua, bisa diterima menyakitkan waktu anak lagi ‘sakit’, Bu. Dan itu mungkin baru kelihatan akhir-akhir ini di anak Ibu karena sudah menumpuk, terus meledak.”
Baca juga: Saat Adik Remaja Jatuh dalam Depresi, Kita Bisa Bantu Apa?
Sekitar jam 2.30 siang
Setelah konsultasi dengan psikiater, saya bertemu Bu Indah lagi. Air menggenang di matanya sembari dia berjalan ke bagian sepi lorong rumah sakit, tak jauh dari poli jiwa.
Saya bingung, tapi akhirnya saya memutuskan menghampirinya.
“Kenapa, Bu?”
“Anak saya mau bunuh diri, saya dengar dia bilang ke dokter begitu,” seketika tangisnya pecah. Saya memeluknya meski agak canggung dan ragu mengingat protokol kesehatan yang harus saya ikuti. Ia goyah dan terduduk di lantai, saya mengusap-usap punggungnya dan mengatakan wajar ibu sedih dan menangis. Hal itu saya lakukan setelah suaminya yang tak lama kemudian menghampiri kami meminta Bu Indah bangkit dan jangan menangis lagi. Barangkali dia malu kalau dilihat orang-orang sekitar.
“Enggak papa, Pak, wajar Ibu sedih. Keluarin aja emosinya, Bu. Kasih Ibu waktu sebentar, ya, Pak,” kata saya kepada suami Bu Indah.
Bu Indah terus menyalahkan diri. Ia tak pernah sekali pun membayangkan anaknya mau bunuh diri. Sebagai orang tua, ia sudah memberi segala yang ia bisa untuk anaknya. “Salah saya apa, ya Allah? Apa dia enggak inget orang tuanya susah payah buat dia?”
Di belakang kami, anak Bu Indah yang diceritakannya tadi sudah berdiri menanti, mungkin heran juga ada orang asing seperti saya yang menenangkan ibunya.
“Bu, saat ini bukan salah siapa-siapa yang jadi perkara. Bukan salah Ibu, Bapak, atau anak Ibu. Saya pernah di posisi anak Ibu tahun 2016, dan saya masih hidup sampai sekarang. Harapan masih ada, Bu. Ibu percaya Allah, Ibu berdoa saja yang terbaik,” saya terdengar seperti konselor dadakan meski sebenarnya status saya hari itu pasien.
“Sekarang anak Ibu lagi sakit, dan proses pemulihannya panjang. Ibu harus kuat untuk bisa nemenin dan nguatin anak Ibu, ya,” ujar saya ke Bu Indah sebelum ia menanyakan nomor telepon dan nama saya. Mungkin dia perlu teman cerita.
Saya berjalan ke arah anak Bu Indah, mengatakan hal serupa. Bahwa saya pernah mau bunuh diri dan bertahan sampai sekarang. Banyak hal akan terjadi, dan proses pemulihan itu panjang dan sering sulit.
“Jangan capek, ya, ngejalanin prosesnya. Kalau kamu butuh cerita, ibu kamu punya nomor saya. Saya pernah ada di posisi kamu,” kata saya sambil menepuk pundaknya, dan sedetik kemudian ia turut menangis.
Baca juga: Bunuh Diri pada Anak Muda dan Bagaimana Menghadapinya
Sekitar jam 1 siang
“Bagaimana keadaannya hari ini?” psikiater atau psikolog pasti menanyakan hal ini, dan sebenarnya ini adalah hal yang saya benci.
“Makin buruk, Dok,” jawab saya singkat.
Kemudian sekitar 10 menit saya bercerita, dengan urutan acak-acakan, berdasarkan catatan yang saya tulis di ponsel. Psikolog saya dulu bilang journaling atau menulis adalah bagian terapi, dan membantu melihat jejak-jejak kapan kita up, down, atau terpicu sesuatu.
“Saya kelepasan minum alkohol suatu malam, cukup banyak, dan reaksi dengan obat dari Dokter yang saya minum ternyata memicu sekali keinginan bunuh diri,” kata saya terbata-bata.
Lanjut cerita, disisipi derai air mata sesekali, saya bilang saya sudah sampai mencari “formula” yang efektif untuk mengakhiri hidup. Mulai dari berpikir menyimpan tambang di rumah sampai mencari obat ilegal yang bisa bereaksi mematikan bila bercampur satu dua botol alkohol berkadar tinggi. Saya bahkan sampai mencari tahu berapa kadar alkohol dalam darah yang membahayakan, membuat koma, atau sampai menyebabkan kematian.
Saya cari tahu sedetail mungkin karena saya tahu, kalau bunuh diri gagal, rasa sakitnya jauh lebih berlapis dibanding sakit yang dirasakan sebelumnya.
Buat saya sendiri, dorongan untuk itu bukan hanya rasa sakit, capek, atau suatu hal traumatis yang terus menghantui, tapi juga kebosanan dan merasa hidup tak mesti punya tujuan.
Saya merasa sudah cukup, dalam artian saya tak punya keinginan, ambisi, atau mimpi apa pun lagi. Pasalnya, saya sudah pernah merasa meraih banyak hal yang menurut orang membanggakan, tapi jiwa saya masih kosong. Bak ember bolong yang terus dikucuri air. Bahkan kalaupun saya dapat “uang kaget”, berkesempatan sekolah lagi atau memenangkan beragam hal, saya tak yakin saya akan senang, apalagi bahagia.
Psikiater telah menyatakan saya punya gangguan depresi dan kecemasan, menyarankan saya dirawat inap mendengar keinginan saya bunuh diri yang sering muncul dan bisa kapan saja saya eksekusi. Saya menolak dengan dalih masih harus mengurus anak. Ia menghargai keputusan saya dan mengambil opsi menambah satu jenis obat lagi untuk mengendalikan pikiran berulang soal hal-hal jelek lain dan bunuh diri itu.
Mengingat pengalaman hari ini, rasanya ironis bagaimana saya mencoba menguatkan si anak yang mau bunuh diri dan ibunya, sementara saya sendiri suicidal.
Bertahan. Untuk sekarang, pikirkan hanya bertahan. Berkali-kali saya dengar kata ini dari psikolog dan psikiater saya. Saya masih belum mendapat jawabannya untuk apa sekarang ini, tapi toh tiap pagi saya kembali bangun, dengan segala beban terpendam yang hampir tidak pernah saya bagikan ke suami atau teman, dan menjalankan tugas saya sebagai ibu dan karyawan.
Sehari demi sehari saja. Bertahan, dengan terus mencoba memulihkan diri, entah lewat konseling, psikotropika, atau outlet apa pun saat emosi menjadi-jadi. Tak mesti kita tahu jawabannya untuk apa saat ini juga.



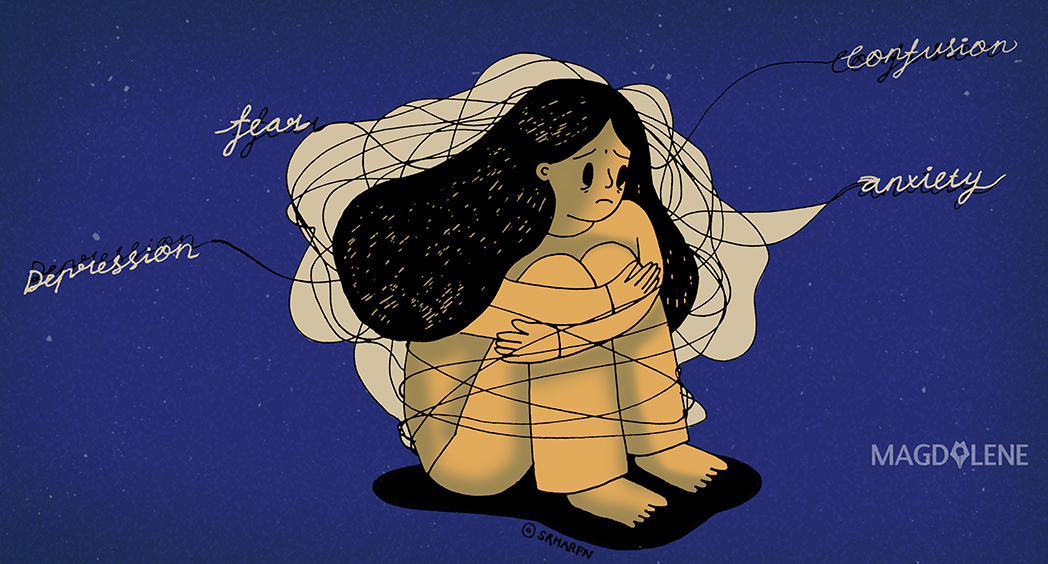



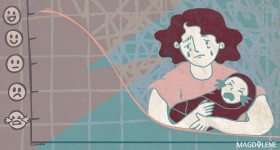

Comments