Sebagian besar dari kita mungkin sudah akrab dengan istilah "call-out". Secara teori, call-out sebenarnya sangat sederhana: ada yang melakukan kesalahan, ada yang memberitahu, lalu kesalahan tersebut enggak dilakukan lagi. Tapi sekarang ini, tidak perlu seaktif itu di internet dan media sosial untuk tahu bahwa budaya call-out ini sangat memecah belah sebab sering menjadi debat kusir super ngegas dan merendahkan orang lain.
Banyak yang mulai gerah dengan budaya ini, salah satunya mantan presiden AS Barack Obama yang mengatakan ada kecenderungan di kalangan anak muda bahwa untuk membuat perubahan adalah cukup dengan menjadi sangat menghakimi terhadap orang lain.
Lalu di mana sebetulnya batasan call-out yang efektif? Apakah itu memang ada? Kapan call-out jadi cara yang tepat atau malah “kebablasan” dan berlebihan?
Magdalene membahasnya pada 20 Desember 2019 bersama Intan Paramaditha (@sihirperempuan), penulis dan dosen Kajian Film dan Media di Macquarie University, Sydney, dalam diskusi interaktif twitter #MadgeTalk. Berikut adalah hasilnya.
Pertama-tama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan call-out culture?
Call-out culture adalah budaya menunjukkan secara publik, khususnya di media sosial, kesalahan individu atau kelompok. Kesalahan mungkin terkait dengan eksploitasi relasi kuasa yang timpang, pengabaian isu privilese kelas, maupun tindakan atau pernyataan yang seksis, rasialis, atau homofobik.
Bagaimana sampai budaya call-out ini terbentuk?
Call-out culture berhubungan erat dengan potensi demokratisasi media yang dimungkinkan teknologi digital. Budaya ini lahir dari konteks kesadaran bahwa bersuara adalah resistensi. Jika dulu bagaimana kita terlihat bergantung pada akses ke media mainstream, kini kita mendengar suara dan narasi yang jamak.
Beberapa momen dalam sejarah media kontemporer turut membentuk call-out culture. Pertama, ada perubahan perspektif terhadap siapa yang bisa bercerita; orang-orang yang tadinya hanya menonton kini bisa memproduksi narasi. Bisa dilihat manifesto Jay Rosen dari New York University pada 2006 mengenai perubahan audiens.
Kedua, ada kesadaran bahwa platform baru dapat digunakan sebagai sarana melawan dominasi. Arab Spring menjadi momen penting pembahasan potensi politik media sosial sebagai alat mobilisasi (melalui tagar) dan perlawanan. Setelah itu, aktivisme digital kian disadari sebagai kekuatan.
Sebagaimana kita lihat dari gerakan #MeToo, bersuara di media sosial dilihat sebagai cara menolak pengabaian dan pembungkaman. Call-out culture bisa menjadi kendaraan politik yang efektif, tapi bisa juga tak ke mana-mana bila ia dilihat sebagai ujung dari aktivisme itu sendiri.
Baca juga: Bongkar: Siasat Feminis dalam Seni dan Budaya di Indonesia
Bagaimana agar call-out ini menjadi efektif?
Call-out adalah salah satu strategi aktivisme, tapi aktivisme tidak dapat direduksi sebatas call-out. Tidak semua upaya membuat perubahan ada, atau harus ditampilkan, di media sosial.
Penting melihat konteks munculnya call-out culture sebagai respons terhadap dominasi. Soal etika dan politik call-out mesti terus diperdebatkan, tapi fenomena ini tidak sesederhana “SJW kebablasan”. (Ingat juga istilah SJW atau Social Justice Warrior ini muncul di kalangan konservatif yang privilesenya terusik)
Aktivisme tidak tunggal. Ada bentuk protes dan negosiasi dengan publik terbatas (forum tatap muka atau surat-menyurat). Kritik disampaikan dengan cara call-in ketimbang call-out. Sebagian aktivis memilih fokus menciptakan narasi tandingan, sebagian lagi bekerja dengan komunitas.
Keputusan untuk call-out harus dibuat dengan kesadaran bahwa ada dampak dari tindakan yang dipilih. Apa benar call-out cara yang paling tepat untuk kasus tertentu? Kapan aktivisme berubah menjadi witch hunting?
Call-out adalah salah satu strategi aktivisme, tapi aktivisme tidak dapat direduksi sebatas call-out. Tidak semua upaya membuat perubahan ada, atau harus ditampilkan, di media sosial.
Kapan atau dalam konteks apa sebaiknya call-out dilakukan?
Call-out bisa menunjang apa yang disebut Melani Budianta (Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia) "emergency activism"-- aktivisme yang merespons keadaan darurat, semisal munculnya kebijakan dengan logika kriminalisasi ketimbang perlindungan, atau kekerasan kelompok dominan maupun aparatus negara.
Tapi kita mesti mempertanyakan tujuan dan keberlanjutannya. Apakah call-out buat kita hanyalah “low-risk, feel-good activism” yang memberi validasi atas betapa benar dan pintarnya kita? Jika tidak, seberapa banyak waktu dan energi yang dapat kita luangkan untuk isu ini sesudahnya?
Kesadaran sosial di media sosial dihasilkan oleh kerja murah atau tak dibayar orang-orang yang menyoal penindasan. “Cheap female labour is the engine that powers the internet,” kata Lisa Nakamura. Aktivisme digital menguras tenaga, padahal ia tak bisa berhenti di sana.
Sebagaimana aktivisme darurat, call-out culture bisa intens dan menggerakkan, namun secara emosional sangat melelahkan. Sementara ada energi besar yang dibutuhkan untuk berjejaring, membuat aliansi, bersama-sama memikirkan strategi jangka panjang.
Sampai kapan call-out ini berlaku untuk pihak yang di call-out? Apakah berlaku selamanya?
Tak ada yang abadi di dunia ini, apalagi di media sosial. Tantangan aktivisme digital adalah lini masa yang berubah cepat. Umur suatu wacana bisa sangat singkat, dan kita semakin mudah lupa.
Skenario terbaik adalah keterbukaan: permintaan maaf di publik dan tawaran solusi masalah. Tapi bisa juga, pihak yang ditunjuk hanya menunggu perhatian reda, lalu tak ada apa-apa selain status quo. Karena itu call-out tak ke mana-mana tanpa strategi jangka panjang menuju perubahan.
Baca juga: Feminisme untuk Keadilan, Bukan Feminisme Pengakuan
Apakah tepat jika kita melakukan call-out kepada terduga pelaku atau pelaku kekerasan seksual?
Menunjuk terduga pelaku atau pelaku kekerasan seksual di media sosial membangkitkan kesadaran publik tentang normalisasi kekerasan berbasis gender. Tapi kita harus lihat perspektif penyintas: bicara atau berada di publik berisiko mengalami kekerasan dua kali karena disalahkan atau tak dipercaya.
Dampak dari terungkapnya kasus terhadap mereka yang mengalami kekerasan seksual harus jadi fokus utama kita. Tindakan call-out tidak bisa dilakukan tanpa menyiapkan infrastruktur keamanan dan kesehatan mental buat si penyintas.
Apakah tepat jika melakukan call-out kepada sesama kelompok feminis dengan pandangan yang berbeda?
Call-out bisa dilakukan terhadap kelompok mana pun. Tapi kita perlu bertanya, saat tak sepakat dengan orang-orang yang memperjuangkan hal yang sama atau bersinggungan, apakah kita bicara dengan cara yang sama seperti menghadapi lawan lain yang jelas tidak duduk di satu meja?
Apakah kritik terhadap feminis, perusahaan kapitalis, atau kelompok intoleran kita sampaikan secara sama rata, sama rasa? Apakah kita ingin titik temu atau membakar jembatan? Kita perlu memikirkan komunikasi mana yang kita pilih, dan untuk bicara dengan siapa. Apa yang diharapkan muncul dari komunikasi itu? Dialog? Kesadaran publik? Shock therapy? Masing-masing punya konsekuensi berbeda.
Jadi bagaimana cara melakukan call-out yang tepat?
Di era media sosial kita perlu ingat dua hal. Pertama, banyak ragam strategi dalam aktivisme. Call-out di media sosial adalah bentuk aktivisme digital, tapi ia bukan satu-satunya medium transformatif, juga bukan tujuan akhir. Kedua, perlawanan terhadap opresi tak dapat dilakukan tanpa otokritik.
Ajukan pertanyaan kritis pada diri sendiri: Apa implikasi dari tindakan call-out yang kita lakukan? Mana yang menjadi prioritas tujuan--mempertunjukkan pengetahuan atau posisi politik, atau perubahan sosial?
Saat mengidentifikasi kesalahan orang/ kelompok lain secara publik, di mana posisi kita? Apakah kita benar-benar terlepas dari struktur yang melahirkan persoalan? Penting untuk keluar dari dikotomi dan melihat keterkaitan.
Terakhir, apakah perlawanan baru valid jika ia bisa didengar dan dilihat oleh publik? Mari telusuri banyak cara untuk bicara, tidak hanya satu, demi mengupayakan perubahan.



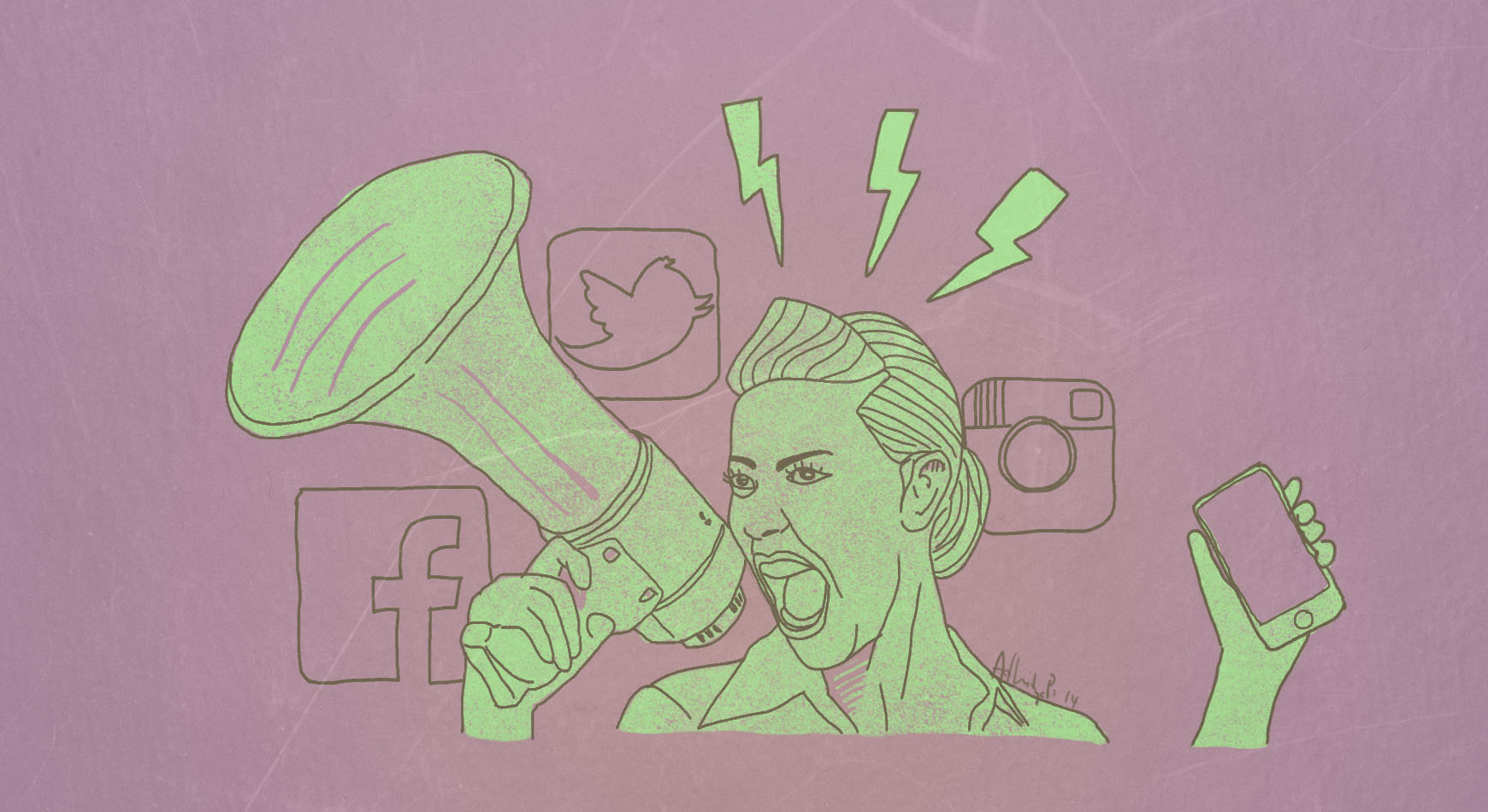
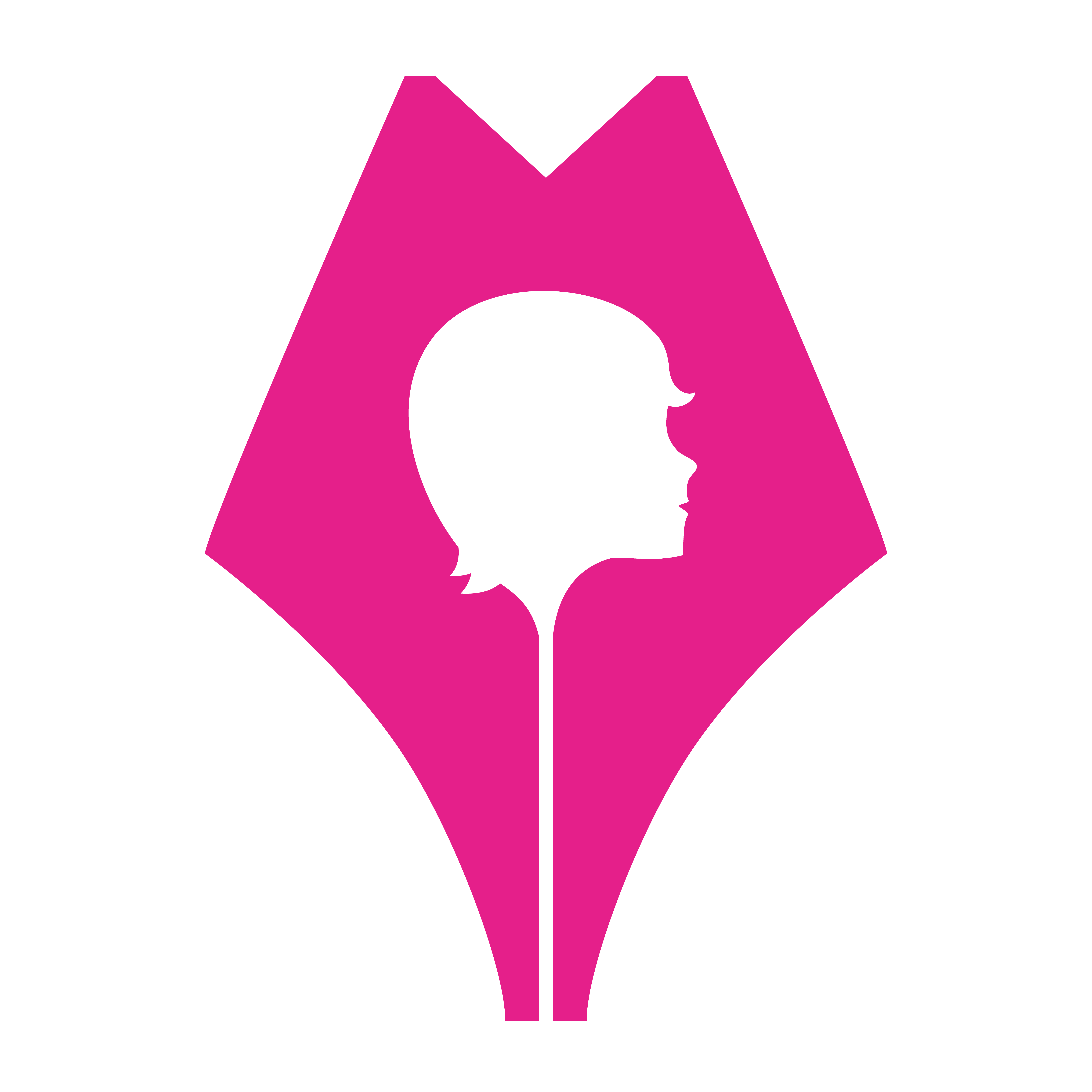



Comments