Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya rutin melakukan ritual akhir tahun: Merefleksikan suka, duka, dan pencapaian diri sebagai refleksi pribadi. Meski 2021 ini saya relatif babak belur tapi saya tetap menulis refleksi tersebut. Buat saya menulis juga membantu bersiap menghadapi 2022 yang bisa jadi tak jauh-jauh dari masalah dan kepahitan.
Kenapa saya terdengar pesimis? Ceritanya begini. Tahun lalu adalah momen yang penuh dengan catatan buruk, setidaknya buat saya. Pandemi COVID-19 yang belum enyah, karier yang terjun bebas, urusan beasiswa yang ditolak melulu, hingga persoalan asmara yang bikin hati ambyar.
Namun ternyata, melewati momen-momen buruk itu membuat kekuatan saya bertambah berlipat-lipat. Memang, apa lagi yang harus ditakuti? Perasaan diremehkan? Sudah jadi santapan sehari-hari. Ditolak gebetan? Ah, saya cenderung sudah mati rasa sekarang. Gonjang-ganjing isi dompet? Sudah biasa. Apa lagi?
Baca juga: Aku Pamer, Maka Aku Ada: Koar-koar Dahulu, Prestasi Kapan-kapan
Pengalaman buruk ini juga membuat saya belajar satu hal: Tak usah mengumbar usaha ketika semua serba belum pasti. Misalnya, saat saya koar-koar soal mendaftar beasiswa kuliah, hal itu pula yang membuat saya harus menelan pil pahit. Ceritanya, saat teman-teman sesama pelamar beasiswa ternyata lolos, mereka mencemooh saya dengan bilang, “Eh, kamu kok masih di sini aja? Kirain dah udi luar negeri.”
Pengalaman itulah yang mendorong saya untuk menahan diri tak mengekspos apapun usaha saya di media sosial. Pun bercerita pada kolega di luar sana. Sudah lelah karena meladeni wawancara tanpa ujung, ini masih harus direpotkan dengan drama rekan pemburu beasiswa yang sinis.
Saya pun bertekad untuk working under the radar. Artinya, saya tak akan mengunggah apapun proses pekerjaan saya, menyampaikan cita-cita dan mimpi saya, hingga mendapatkan hasil yang pasti. Ini berbeda jauh dengan saya dulu yang gemar oversharing di media sosial, pamer mimpi, pencapaian, cita-cita, segala hal. Tujuannya agar orang-orang tahu, saya adalah orang aktif, ambisius, punya kehidupan yang menarik, dan enggak suka bengong di rumah. Terkadang saya mengunggah apapun di story sebagai wujud self-reward ketika rampung mengerjakan sesuatu.
Namun ujung-ujungnya, hasilnya nyaris selalu sama: Zonk. Semua cita-cita saya kandas. usut punya usut, ada penjelasan psikologis kenapa kebiasaan mengumbar di media sosial justru kerap menjegal mimpi-mimpi si empunya pembuat cerita di media sosial. Psikolog Peter Gollwitzer dalam jurnalnya “When Intentions Go Public” (2009) misalnya menyebutkan, dalam tubuh kita ada zat dopamin. Ketika kita sibuk mengunggah proses tertentu dalam hidup, sekonyong-konyong tubuh bakal memproduksi zat dopamine reward sekaligus, yang bikin bahagia.
Baca juga: Kita Harus Berhenti ‘Flexing’ Soal Kekayaan
Semakin kagum dengan motivasi dan gol kita di Instastory, semakin banyak dopamin yang diproduksi dan membuat kita jadi mager untuk mengeksekusi mimpi tersebut. Lagi-lagi, karena kita sudah lebih dulu puas dengan reaksi orang yang memuji megahnya cita-cita atau mimpi kita.
Menurut sejumlah penelitian, ada istilah “Prematur Sense of Completeness” yang membuat otak kita berpikir sudah meraih gol tersebut, padahal faktanya enggak. Ini sekaligus mengamini pernyataan penulis AS Derek Sivers yang menyebutkan, otak kita terjebak realitas sosial dan menganggap gol itu sudah diraih. Ujungnya, semangat untuk mengeksekusi mimpi itu pudar di tengah jalan.
Meski orang boleh tidak sepakat soal ini lantaran ada yang bilang, pamer mimpi bisa meningkatkan motivasi. Nyatanya, saya tak cocok dengan metode semacam itu. Alasannya personal, dan kamu boleh tak sepakat: Saya akan kecewa berat jika tak tercapai dan cenderung membuat mental saya jadi korban. Alasan kedua, biasanya orang-orang memasang ekspektasi tinggi saat kita sedang mengejar mimpi. Sementara saat kita sudah gagal, mereka pula yang sibuk menertawai pertama kali.
Alasan terakhir yang membuat saya selalu sentimentil adalah karena malu harus melaporkan kegagalan di hadapan orang tua. Seperti kegagalan beasiswa tahun lalu ketika membuka pengumuman dan kata “MOHON MAAF” seolah meledek semua ikhtiar saya. Air mata sontak keluar, saya takut sekali membuat ibu terluka dan kecewa. Alasan ini pula yang sebenarnya membuat saya lebih memilih diam ketika tengah berusaha. Biar hasil yang berbicara. Kalau pun hasilnya diam alias gagal, ya sudah itu manusiawi, kan? Tak salah kok menjadi manusia, seperti mantra yang selalu saya rapal tiap harinya.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.



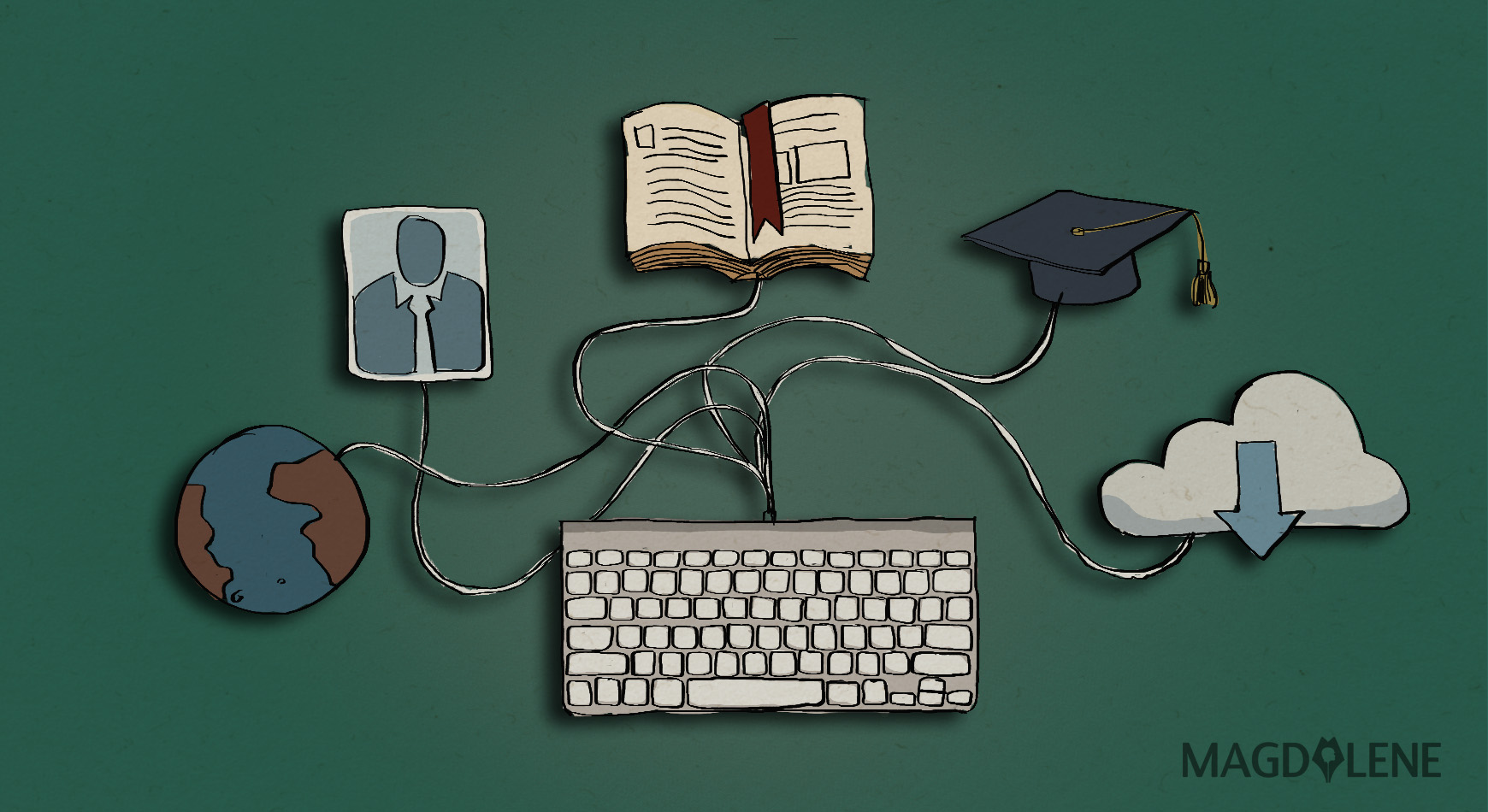



Comments