Pada artikelnya yang membahas mengenai 7 pandangan saklek soal menjadi feminis, Patresia Kirnandita menyatakan bahwa terdapat sebagian kelompok feminis kiri yang memandang miring perjuangan feminis liberal. Sebagaimana dinyatakan oleh Patresia, “terlepas dari di mana pun para feminis liberal berkarier, selama mereka bukan pemilik modal, mereka adalah buruh juga. Karenanya, sentimen sebagian feminis kiri terhadap feminis liberal sebenarnya tidak perlu. Hanya karena fokus perjuangan berbeda, tidak berarti satu kelompok feminis tidak sevisi dengan kelompok feminis lainnya.”
Perbedaan antara feminis liberal dan “sebagian kelompok feminis kiri” tentunya bukan hanya berada pada perbedaan fokus perjuangan, namun perbedaan visi yang ingin dicapai pula. Sebagaimana dinyatakan oleh bell hooks, ekspektasi feminis liberal atas persamaan hak antara perempuan dan laki-laki berhenti pada kelas sosial mereka. Lebih lanjut, visi feminis liberal tidak serta merta menantang dan mengubah basis kultural dari praktik opresi. Hal ini tentu menjadi penting untuk didiskusikan lebih lanjut. Mengingat bahwa kekuatan feminisme berakar pada kritik atas relasi dan struktur kekuasaan, kita harus berhati-hati pada jargon-jargon yang kerap kali digunakan oleh feminis liberal, khususnya yang terkait dengan isu representasi, gagasan bahwa setiap perempuan sama tertindasnya oleh patriarki, dan “sisterhood.”
Bahaya paradigma “sisterhood” terletak pada kapasitasnya untuk menghapuskan suara-suara marginal yang seharusnya menjadi fokus utama feminisme. Layaknya sejumlah aspek liberalisme lainnya, “sisterhood” ialah persoalan representasi dan siapa yang punya sumber daya, termasuk untuk menggaungkan gagasan dan suara.
Kita telah cukup lama menyaksikan feminis-feminis imperialis kulit putih mengangkat diri mereka sebagai suara yang mewakilkan suara perempuan-perempuan marginal lainnya melalui legitimasi narasi “sisterhood.” Sejumlah feminis kulit berwarna telah mengkritik paradigma “sisterhood” semacam ini, mulai dari Gayatri Spivak, Nima Naghibi, Akwugo Emejulu, Lila Abu-Lughod, Saba Mahmood, dan Asma Barlas.
Paradigma “sisterhood” yang bermasalah ini, misalnya, tampak pada pidato Laura Bush yang menjustifikasi serangan Amerika Serikat ke Afganistan pada tahun 2001. Dalam pidatonya, Laura Bush berkata, “Because of our recent military gains in much of Aghanistan, women are no longer imprisoned in their homes. They can listen to music and teach their daughters without fear of punishment. The fight against terrorism is also a fight for the rights and dignity of women.”
Apakah Laura Bush merupakan seorang feminis karena ia telah “menyelamatkan” perempuan-perempuan Afghan dari opresi Taliban? Kami pikir tidak.
Baca juga: Siapakah yang Pantas Disebut Feminis?
Layaknya kritik Lila Abu-Lughod, pidato Laura Bush memiliki nafas yang sama dengan sejumlah upaya “penyelamatan” yang terjadi sepanjang sejarah kolonial. Alih-alih membangun ruang dialog, paradigma “sisterhood” yang dimaknai secara sumir dan berangkat dari gagasan bahwa setiap perempuan mengalami pengalaman ketertindasan yang sama justru mereproduksi tindakan kekerasan dan penghapusan agensi pada perempuan-perempuan yang berada pada kategori marginal.
Pada konteks Indonesia, “sisterhood” yang dapat diterjemahkan sebagai “persatuan gerakan feminis” ini menjelma dalam dominasi suara-suara feminis kelas menengah atas, terdidik, dan urban. Kita masih belum benar-benar mempertanyakan siapa saja yang ada dalam lingkaran “persatuan” tersebut, dan siapa yang berada di luarnya. Hal ini tentu harus disikapi dengan kritis, terlebih mengingat bahwa kita kerap kali memperjuangkan isu gender dan seksualitas di bawah panji feminisme dan.
Spivak telah memperingatkan kita bahwa kita (sebagai aktivis dan akademisi yang memiliki kuasa dan kapital untuk menggaungkan suara dan gagasan) untuk berbicara dengan subjek yang selama ini diredam narasi dan pengalamannya oleh struktur kuasa. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Spivak, praktik gerakan yang seyogianya kita lakukan ialah membangun dialog dua arah dengan orang-orang yang selama ini dibungkam oleh kuasa dan sejarah, alih-alih naik ke atas panggung dan berbicara untuk mereka yang selama ini dijadikan liyan.
Persoalan kedua tampak pada ketidakhadiran elemen agama. Pada artikel Patresia Kirnandita, terdapat dua poin yang menyertakan elemen agama, yakni: (1) menyoal feminis yang tetap memegang ajaran agama; dan (2) feminis yang menjunjung kredo pro-life. Kedua poin tersebut, sayangnya, khas dengan perspektif feminisme liberal terhadap feminisme agama-agama: superfisial dan hanya berhenti di narasi “inklusivitas.” Inklusivitas ini sekadar terpaku pada kekaguman terhadap feminis-feminis religius yang mengonseptualisasi keadilan gender dalam diskursus keimanan mereka.
Fokus pembebasan pribadi yang menjadi inti pemikiran feminisme liberal pun tampak tak bergeser dalam narasi “inklusivitas” tersebut. Dengan kata lain, feminisme agama-agama memperoleh “kehormatan” untuk masuk ke dalam payung “persatuan” feminisme liberal dalam artikel Patresia hanya karena para feminis religius, dalam kacamata sempit feminisme liberal, juga terlihat ingin “bebas.” Hal serupa tampak pada isu feminis pro-life, khususnya karena artikel Patresia gagal membaca kompleksitas kaitan antara pergerakan pro-life dengan rasialisme dan diskriminasi kelas di negara-negara serupa Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa.
Baca juga: Benarkah Feminisme Anti-Agama Bukan Feminisme Sama Sekali?
Pada akhirnya, patut diingat pula bahwa pandangan “sebagian kelompok feminis kiri” mengenai kelas tidak hanya berfokus pada persoalan perburuhan (meski isu perburuhan itu sendiri tentu isu yang penting untuk diperjuangkan!). Sebagaimana dinyatakan oleh The Combahee River Collective dalam pernyataan mereka pada tahun 1977, “We believe that sexual politics under patriarchy is as pervasive in Black women’s lives as are the politics of class and race. We also often find it difficult to separate race from class from sex oppression because in our lives they are most often experienced simultaneously.”
Dengan demikian, perkara kelas tidak hanya menjadi sorotan dalam gerakan perempuan, namun sepatutnya dipahami sebagai bagian yang tidak terpisah dalam pembentukan pengalaman opresi yang dialami perempuan dan minoritas seksual.
Kelindan kelas, ras, identitas gender, seksualitas, dan identitas sosial lainnya hadir dan membentuk pengalaman ketertindasan yang dialami oleh perempuan. Jika kita benar-benar serius dalam menerapkan ide interseksionalitas dalam praktik dan politik feminisme yang kita lakukan, kita harus senantiasa mengingat bahwa kehadiran ide interseksionalitas tidak menegasikan pentingnya analisis kelas.
Alih-alih meniadakan kelas dalam kritik feminis, interseksionalitas justru dikembangkan dalam pemikiran feminisme kulit hitam (dengan berangkat dari teorisasi Kimberle Crenshaw, tepatnya) yang bertumpu pada irisan sistem opresi (termasuk kapitalisme dan ketimpangan struktur kelas) yang menghadirkan pengalaman ketertindasan yang kompleks. Hal inilah yang menjadikan perbedaan antara feminisme liberal dan “sebagian kelompok feminis kiri” bukan hanya terejawantah pada perbedaan fokus perjuangan, namun kedua aras feminisme ini telah memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam memahami dan memaknai akar penindasan terhadap perempuan.
Pada akhirnya, kita harus senantiasa mengingat bahwa kritik tidak serupa dengan memecah belah gerakan. Salah satu prinsip utama ideologi-ideologi kritis, termasuk feminisme, ialah adanya kritik internal yang dilakukan dengan terus menerus. Dengan adanya kritik internal, feminisme sebagai ideologi kritis dapat terus menemukan nafas berikutnya. Dengan kata lain, ketika kritik internal terhenti dalam suatu gerakan ideologis kritis, ideologi tersebut berarak menuju kematiannya.
Layaknya Audre Lorde mengingatkan kita, kita tidak dipisahkan karena perbedaan identitas yang menubuh pada diri kita. Akan tetapi, kita dipisahkan pada penolakan kita pada pengakuan atas perbedaan identitas yang, pada praktiknya, menumpulkan praktik, politik, dan gerakan feminis yang kita lakukan.



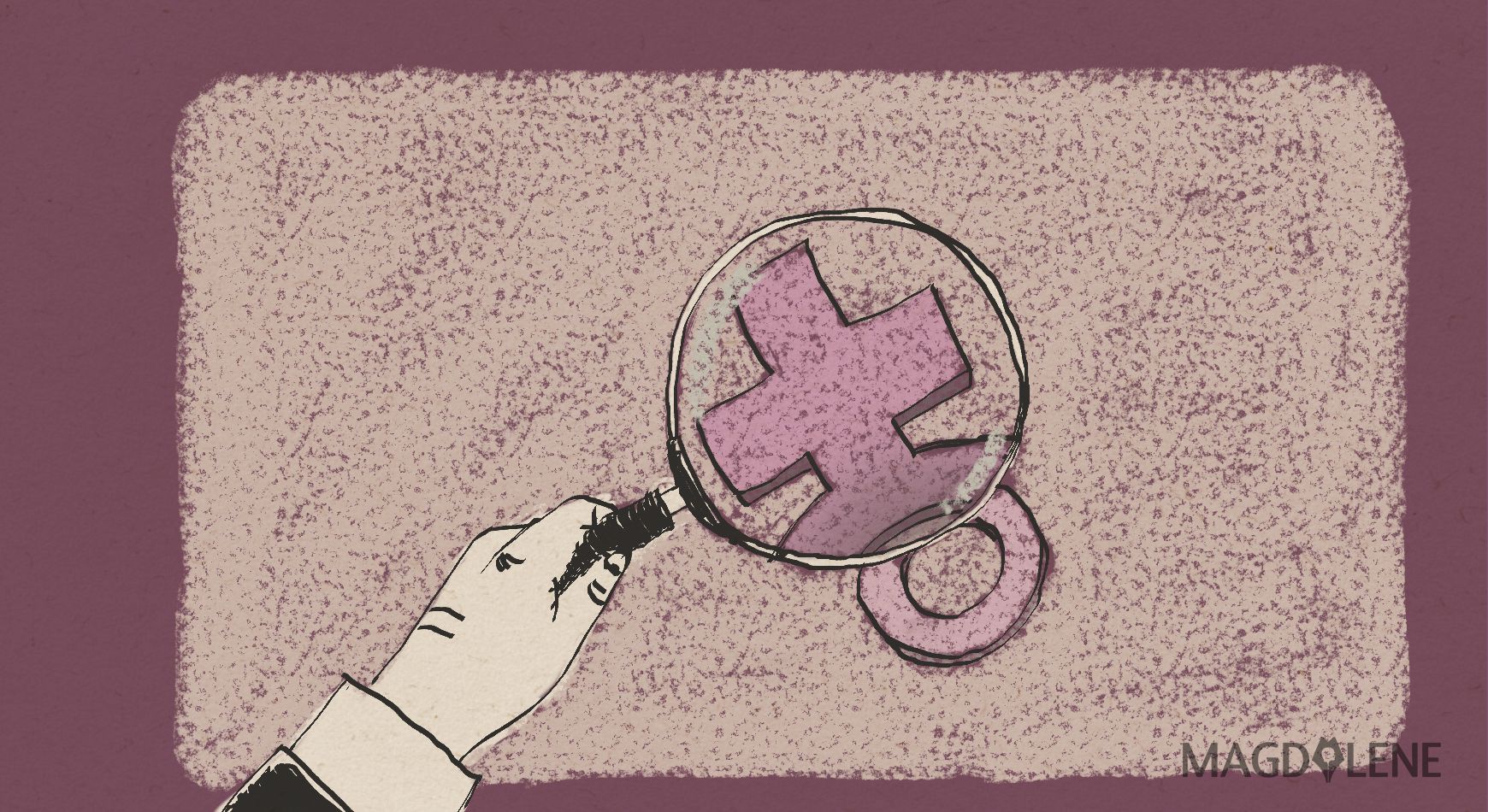



Comments