Masih tertanam dalam ingatan Sukemi yang kuat, bahwa di antara 31 siswa kelas enam SD Sejahtera Abadi Desa Suka Maju, dia adalah yang paling tua di antara teman-temannya.
Sebagai gadis desa yang lahir dari pasangan buruh tani dan pencari kayu di hutan yang tak jauh dari rumahnya, baginya, bisa duduk di bangku kelas 6 SD di usia yang menginjak 15 tahun adalah pengalaman yang langka dan berharga. Bukan karena tidak disangka-sangka, tapi memang itulah yang selalu dia bayangkan dan cita-citakan sejak empat tahun yang lalu, saat dia selalu merawat ayahnya di rumah karena lumpuh akibat jatuh dari pohon kelapa.
Sukemi harus menggantikan sang ayah yang sakit untuk membantu ibu bekerja di hutan. Dia berhenti sekolah karena harus bekerja setiap harinya. Pekerja full-time, part-time, whole time? Itu hanya istilah-istilah rumit baginya. Dia bahkan belum sempat berpikir soal kebiasaan lulusan sekolah formal yang umumnya mengirim surat lamaran dan melewati prosedur wawancara yang terstruktur, dengan posisi pekerjaan dan kesepakatan gaji yang stabil dan itu-itu saja. Dia juga masih buta dengan istilah-istilah rumit lain seperti entrepreneur, freelance marketer, freelance writer, freelance editor dan jenis-jenis pekerja kreatif lainnya. yang dia tahu, “Saya bekerja, berhenti sekolah, dan membantu Ibu dan Bapak”.
Tidak ada kontrak dan gaji tetap, juga tidak ada libur di akhir pekan, karena setiap hari Sukemi pergi ke hutan untuk sekedar mengumpulkan ranting pohon kering yang sudah jatuh untuk dibawa ke rumah. Kadang untuk dijual, kadang untuk dimanfaatkan sendiri untuk keperluan memasak atau membuat api unggun di malam hari yang sering dilakukannya bersama Ibu untuk sekedar membakar ketela pohon yang ditanam di belakang rumah, kadang sekedar untuk mengurangi udara dingin saja.
Masih tertanam dalam ingatannya yang kuat, sekuat keinginan dan usahanya untuk melanjutkan sekolah agar bisa lulus SD yang sering diungkapkannya ke sang ibu. Dia masih mengingatnya, udara dingin malam hari di musim kemarau waktu itu, sore sebelum malam, dia dan Ibu membuat api unggun. Satu-satunya kakak perempuan sekaligus satu-satunya saudari kandung yang dimiliki Sukemi, berkunjung ke rumah dan mengabarkan berita bahagia bahwa ekonomi keluarga kecilnya mulai membaik, sejak dia menikah enam tahun lalu dengan seorang ustaz dari desa sebelah dan memiliki dua anak perempuan.
“Kamu gimana, nduk? Alhamdulillah, Bapak keadaannya sudah membaik. Soal nasihat kakak kamu tadi, kamu lanjut saja di pesantren tempat kakakmu mondok dulu. Kalau Ibu jelas setuju. Selain biaya murah, kamu juga bisa mendalami agama seperti kakakmu,’’ kata Ibu kepada Sukemi.
“Ndak, Bu. Aku di sini saja nemenin Bapak. Aku mau lanjutin sekolah SD-ku di sini,” jawab Sukemi.
“Apa enggak papa, nduk? Kamu kan sudah dua tahun lebih enggak sekolah.”
“Seminggu yang lalu aku habis dari sekolah, Bu, dan kata Bu Sulastri enggak papa. Enggak ada biaya tambahan, tinggal masuk saja, kata beliau.”
Mendengar keinginan kuat Sukemi yang ingin melanjutkan sekolah, sang ibu hanya bisa mendukung dengan izin dan doa. “Njeh mpun, nduk. Ibu doakan bisa lulus sekolah sesuai apa yang kamu inginkan”.
Sukemi senang, sangat senang, karena dia kembali ke jalur yang dia pikir akan membawanya ke arah kehidupan yang lebih baik, lulus sekolah di SD Sejahtera Abadi adalah cita-citanya dulu.
***
Sudah 23 tahun berlalu, entah cerita masa lalu seperti itu masih perlu diingat atau tidak, yang jelas Sukemi masih sangat kuat untuk mengingatnya. Bagi sebagian orang, cerita seperti itu adalah kebanggaan untuk diceritakan sebagai episode titik balik dalam hidup, seperti kebanyakan orang yang gemar menjadikan dirinya sendiri sebagai tokoh pahlawan super dalam setiap cerita kesuksesan dan perjuangan mereka. Persis seperti cara para pelatih dan motivator yang mengobarkan semangat dan nasihat hidupnya. Tapi bagi sebagian orang, cerita seperti itu adalah titik terendah yang menyisakan trauma dan keengganan untuk mengingatnya lagi. Tapi bahkan jika kondisinya seperti itu pun, Sukemi masih sangat sudi untuk mengingatnya.
Sudah 23 tahun berlalu, entah kenapa Sukemi masih saja mengingat masa-masa SD-nya dulu. Hari ini, di Jakarta, dia menyaksikan seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi menemui Profesor Psikologi Dewi Siskandhini dan ahli biomedis bernama Adinia Geraldine, untuk melakukan wawancara demi memenuhi tugas liputan jurnal komunikasi di kampusnya.
Ada juga beberapa jurnalis dari beberapa media yang meliput untuk membicarakan soal feminisme sebagai ideologi dan bagaimana peran perempuan Indonesia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk keberlanjutan energi ramah lingkungan. Terutama soal posisi Indonesia sebagai negara terburuk dan paling labil di antara lima negara terbesar penyumbang gas emisi rumah kaca lainnya. Ditambah lagi, di kursi dewan perwakilan kita, jangankan perempuan bisa menyuarakan lingkungan dan energi keberlanjutan, untuk menyuarakan hak politik dan kemerdekaan mereka sendiri saja masih terbelenggu politik dinasti dan patriarki yang mendominasi atas nama instruksi dan kepentingan bersama.
Dari jarak 25 meter, Sukemi memerhatikan mereka, sambil mengingat masa SD-nya. Dia memerhatikan wawancara yang dilakukan mahasiswi dan para jurnalis itu. Mengamati para perempuan dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan, yang dengan bersemangat bersama-sama menyuarakan hak-hak perempuan untuk lebih merdeka dalam memutuskan jalan hidupnya sendiri.
Kuliah atau menikah, lanjut kuliah atau bekerja, memilih menjadi profesor atau kader partai, bahkan menjadi penjual nasi goreng di malam hari pun, dalam benak Sukemi, biarkan perempuan sendiri yang menentukan selagi upaya soal pendidikan dan literasi terus ditingkatkan dan diupayakan dengan setara dan merata. Dia juga sedang berpikir sejenak, mungkin tidak akan melihat langsung acara wawancara penuh semangat itu, jika bukan karena statusnya sekarang sebagai dosen pengajar di program magister psikologi profesi di kampus tempat sekarang dia bekerja.
Hari ini, sambil terus memperhatikan wawancara itu, sudah tak ada lagi api unggun dan ketela pohon bakar, hanya ada segelas lemon tea dan sebotol vodka. Sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu, dia sadar, tak akan ada lagi obrolan hangat api unggun di malam hari yang dingin, hanya ada obrolan-obrolan ringan bersama seorang teman yang sekarang sedang menemaninya duduk di satu meja sambil menyaksikan program wawancara itu berlangsung.
“Natania,” begitu Sukemi memanggilnya. Bagi hidupnya, Natania adalah sosok setelah sang ibu yang benar-benar tahu makna dan perjuangan hidupnya. Tak banyak bahasa apa lagi keluh kesah sejak lulus dari Madrasah Tsanawiyah dekat kampungnya. Dengan segenap semangat hidup dan perjuangan, Sukemi memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMA Negeri favorit di kotanya. Bagi Sukemi waktu itu, sekolah di SMA Negeri favorit adalah upayanya untuk melihat dunia yang lebih luas dan pandangan hidup yang lebih beragam. Hingga akhirnya dia meraih beasiswa di sekolah tersebut dan bertemu dengan Natania sebagai teman sekelas di tahun pertama.
Wawancara penuh semangat itu masih berlangsung. Sambil menikmati vodka di gelas kecilnya, Natania memerhatikan Sukemi dengan hati-hati. Sebagai teman dekat sejak SMA hingga mereka berdua sama-sama menempuh program Master di Jerman meskipun berbeda Universitas dan konsentrasi jurusan, Natania masih ingat bagaimana hubungan mereka berdua lebih dari sekedar dekat.
Natania terus memandangi Sukemi karena dia tahu bahwa teman dekatnya sedang memikirkan sesuatu yang sangat menguras energi, Natania pun mengingat kejadian waktu kuliah di Jerman dulu, bahwa dari Bremen tempat dia menempuh studi Computer Science dengan konsentrasi Data Engineering, dengan suka rela dia izin tidak masuk kuliah demi menemui Sukemi di Erfut tempat teman dekatnya tersebut menempuh studi Psikologi.
Natania menemui Sukemi di Irish Pub, tempat Sukemi biasanya menenangkan diri untuk menuliskan ide-ide dan gagasan segar. Sebotol whisky dan tiga gelas air putih dihadapi oleh Sukemi seorang diri. Bagi Natania, sebagai seorang Kristiani yang memutuskan menjadi sekularis sejak kelas tiga SMA, menemui perempuan berkerudung yang menghabiskan banyak takaran whisky adalah hal yang biasa, apalagi perempuan tersebut adalah teman dekatnya. Tapi Natania tahu, bahwa waktu itu Sukemi tidak sedang menuliskan gagasan apa pun, tapi terjebak di antara dua perasaan yang sama-sama kuat. Ia berduka karena mendapat kabar ibunya meninggal dan tak bisa pulang karena terkendala biaya, tapi di saat yang bersamaan Sukemi bangga, percaya, dan merasa merdeka, bahwa dia yakin ibunya masih tetap tersenyum dan selalu mendukungnya, meskipun para tetangganya dan bahkan ustaz yang mengajarinya agama semasa SD dulu telah menganggapnya murtad, kafir, produk barat, dan musuh Tuhan.
Natania tahu bahwa tatapan tajam Sukemi hari ini menandakan dia sedang mengingat masa-masa itu, masa di mana mereka berdua sama-sama memutuskan menjadi feminis liberal sebelum berangkat ke Jerman. Karena tindakan dan gagasan mereka, khususnya Sukemi, ia bukan hanya menjadi makhluk lain di desanya, tetapi juga sebagai perempuan sesat yang harus diusir dari lingkungan desanya karena dianggap merusak agama.
Desa Suka Maju memang terkenal religius dari dulu, tapi dia tahu, ibunya selalu menutupi kecenderungan dirinya yang suka kebebasan, haus ilmu pengetahuan, membenci perjodohan dan pernikahan dini dan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan orang-orang beragama yang dinilainya merampas hak perempuan. Sukemi sadar, di balik perilaku ibunya yang religius dan taat agama, bahkan tidak pernah meninggalkan salat dan puasa wajib kecuali memang datang bulan, ibunya selalu mendukung pilihannya. Bahkan bertahun-tahun ibunya menutupi kebiasaan Sukemi dari para tetangganya, bukan karena tidak mau terbuka, tapi ibunya tahu kalau dia menceritakan kegiatan anaknya yang sering berkumpul dengan komunitas lesbian sejak dia kelas tiga SMA, hal itu akan membahayakan dirinya.
Wawancara penuh semangat itu masih terus berlangsung.
“Apakah menjadi feminis itu harus lesbi? Atau sebaliknya? Menjadi lesbi harus feminis?” tanya mahasiswi Ilmu Komunikasi itu pada Profesor Dewi Siskandhini.
“Tidak, tidak harus, feminis juga tidak harus perempuan. tapi feminisme membolehkan dan mendukung lesbi, tapi tidak semua kaum lesbi tahu apa itu feminisme. Di Indonesia, orang-orang feminis nasibnya hampir sama dengan para ateis dalam konteks keagamaan, di mana hukum negara tidak membolehkan, tapi tak memungkiri. Masyarakat kita ada yang memegang kepercayaan itu. Hanya saja feminsme lebih cenderung sebagai ideologi dan gerakan sosial, bahwa tak ada lagi penindasan dan subordinasi perempuan di mana pun, kapan pun dan dalam bentuk apa pun,” jawab profesor dengan tegas penuh semangat.
Wawancara penuh semangat itu masih terus berlangsung. Jawaban profesor tersebut semakin menguatkan ingatan Sukemi tentang ibunya. Natania terus memandangi Sukemi. Dia tahu teman dekatnya itu sedang berjuang mengontrol emosi, semangat, dan kenangan tentang ibunya yang meledak-ledak. Mata Sukemi mulai memerah, meski tak banyak tetes air mata yang diiringi senyum tipis jatuh dari matanya, Natania tahu bahwa akan ada ledakan emosio dari teman dekatnya. Natania tersenyum sangat tipis.
Dia menatap Sukemi dan begitu sebaliknya. Sekitar lima detik mereka berdua saling menatap. “Me too, with them all activists, do you feel we are in ‘six degrees of separation’ now?” tanya Natania. Sejenak Sukemi menghela nafas, tersenyum lepas dan menghabiskan sisa lemon tea di gelasnya, lalu menjawab pertanyaan Natania dengan penuh keramahan, seramah almarhum sang ibu setiap kali memanggil namanya. “Injih nduk, Rahayu.. Feminismus und Die Phänomenologie des Geistes.”
Keesokan harinya, Sukemi mengajak Natania mengunjungi kuburan ibunya di desa, mereka berdua ditemani oleh kakak kandung Sukemi. Baik Sukemi maupun Natania, keduanya sama-sama memakai kerudung. Itu cara mereka berdua menghormati budaya setempat, dan satu-satunya alasan Sukemi selalu memakai kerudungnya di tempat publik adalah cara dia untuk selalu mengenang sosok ibunya yang tangguh.
Suasana mendadak hening. Sukemi memeluk batu nisan ibunya, tersenyum, menangis, tersenyum kembali, lalu menangis lagi. Keheningan pecah, Sukemi tertawa lepas, kemudian menangis deras, terisak lalu menangis lagi dengan deras, meledak-ledak, dengan haru dan bahagia dia tertawa lepas, menangis lagi dengan deras... lalu kembali tertawa lepas, dengan sedikit teriakan menangis lagi, tertawa lagi. Dia tidak gila, tapi untuk merayakan kemerdekaan dan kebebasannya lagi sebagai Sukemi.



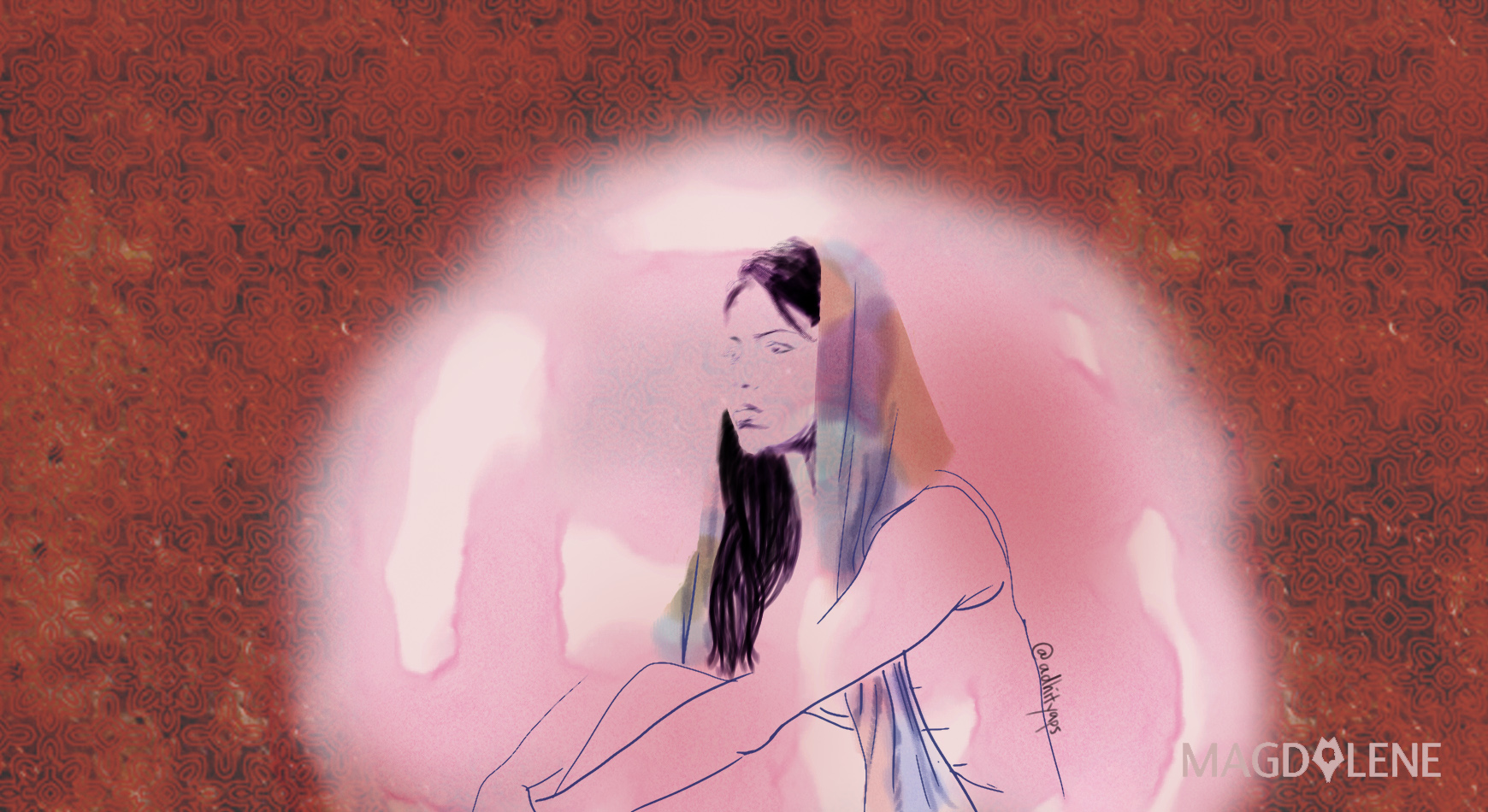



Comments