26 Desember 2004. Pagi datang dan membawa damai diantaranya. Kicauan burung membangunkan akan hari yang baru. Rumput pun masih basah disirami embun.
Tak ada yang kupikirkan setelah bangun tidur, selain menghidupkan TV. Waktu saat itu masih menunjukkan pukul 07:00 WIB. Mataku menatap layar TV.
Tiba-tiba kurasakan getaran dahsyat dari lantai rumahku, semakin lama semakin kencang, seakan dunia ini ikut bergoyang. Kulihat Ibuku berlari dan mematikan TV. Ibu merasakan kakinya gemetar dan ia duduk secara perlahan. Matanya terpejam erat dengan mulutnya komat-kamit mengucapkan Asma Allah tanpa henti.
Di sekelilingku, perabotan rumah yang sebelumnya tersusun rapi, kini jatuh hingga menciptakan suara nyaring. Abangku berlari berusaha menggenggam dari sisi kanan akuarium berukuran besar agar tak jatuh. Walaupun begitu, air yang ada di dalamnya aquarium tumpah seiring getaran kuat yang muncul dari bawah tanah.
Kurasakan gempa sedikit mulai mereda, tetapi keluargaku mulai melangkahkan kaki keluar rumah. Semua bunga kesayangan Ibu tampak jatuh berantakan.
Kemudian, satu persatu tetangga kami datang dan berkumpul di jamboe yang ada di samping rumah kami. Jamboe itu adalah tempat bersantai yang mirip seperti balai tapi berukuran kecil. Jamboe itu sudah ada semenjak bapakku masih hidup.
Tak berapa lama, terdengar suara ledakan tiga kali berturut-turut. Suara itu terdengar mengerikan. Kami saling memandang kebingungan dan tak ada yang berani berkata-kata. Tetangga kami yang rumahnya paling pojok, muncul tiba-tiba untuk berkumpul dengan tetangga lainnya, tetapi sambil berteriak histeris.
Kulihat dari arah utara banyak orang berlarian. Mereka menunjukkan sesuatu sambil berkata “air laut naik“ dengan raut wajah yang terlihat ketakutan. Tak lama, aku tercengang melihat ombak raksasa berwarna hitam pekat menuju ke arah kami.
Aku mengayunkan kaki, makin lama makin cepat untuk menghindari ombak raksasa yang sangat mengerikan itu. Aku bertanya dalam hati tanpa henti, “Apakah dunia ini akan berakhir? Apakah ini kiamat?”
Aku berlari secepat mungkin, sampai sadar keluargaku tak lagi bersamaku. Aku melihat ke kiri kananku. Kurasakan nafasku begitu berat. Semua yang ada di sekitarku terasa sangat lambat. Kemudian ada yang memegang tanganku dan kepalaku refleks berpaling ke belakang. Kulihat kakakku menggenggam tanganku dengan erat.
Kami berlari tanpa henti sampai-sampai sandalku terlepas dan aku berlari tanpa alas kaki. Sesampainya di mushalla Lamseunoeng, aku menoleh ke belakang, kulihat air hanya beberapa langkah dariku. Akupun menyadari bahwa Ibu, Abang dan Cekta (adik ibu) masih berada jauh di belakangku, dan pasti mereka sudah diterjang ombak besar.
Aku berpikir, sekarang aku menjadi anak yatim piatu. Aku dan Kakakku pasrah dengan keadaan. Kami hanya berdiri melihat ombak yang hampir mengenai kami. Air mataku menetes memikirkan nasibku sendiri.
Ombak yang kedua muncul dan akhirnya menghantam kami berdua. Aku terperangah sejenak melihat apa yang ada di dalam air yang hitam pekat itu. Selain menyapu bersih semua orang, ombak itu juga menghancurkan rumah yang dilewatinya. Seng rumah yang lepas dan terbawa air itu mengenai kepala orang yang tak berdaya hingga putus.
Kami berdua berpegangan tangan dengan erat seakan tak mau kehilangan satu sama lain. Tetapi ombak itu sanggup melepaskan tangan kami berdua. Aku terpisah jauh dari Kakak. Aku tersangkut di tumpukan mayat. Ada ratusan mayat di sekitarku, tapi aku tidak mempedulikannya.
Aku tidak bisa berenang sehingga seringkali timbul tenggelam dalam gelombang ombak tersebut. Aku meminta tolong pada orang-orang, tapi tidak satupun yang memperhatikan. Saat itu, aku menemukan sesuatu yang mengapung di depanku, kemudian aku memegangnya erat-erat agar aku tidak tenggelam. Rupanya yang aku pegang adalah kepala mayat. Matanya melotot, sedangkan mata kirinya keluar.
Gelombang ketiga kembali datang dan tanganku terlepas dari kepala mayat itu. Aku terbawa jauh sampai aku tersangkut di tumpukan mayat lainnya. Kayu besar menghimpit kakiku sedangkan tanganku memegang kayu besar lainnya agar tidak tenggelam.
Aku hanya bisa berteriak minta tolong tapi tak seorang pun mendengar. Aku melihat ke kiri dan kanan, yang kulihat hanya air bercampur bangkai rumah, juga mayat-mayat yang mengerikan. Tak ada lagi rasa takut melihat mayat-mayat itu, yang kupikirkan hanyalah bagaimana menyelamatkan diriku sendiri.
Saat itu, aku sangat kelaparan namun aku berada di hamparan air yang luas. Kemudian ada kulkas yang menyangkut di depanku. Aku berusaha menggapai kulkas itu. Aku mengayunkan tanganku agar sampai di kulkas itu. Akhirnya aku dapat menyentuh kulkas tersebut. Ketika aku membukanya, di dalam kulkas itu banyak sekali makanan. Aku mengambil seadanya saja dari kulkas tersebut dan memakannya.
Saat mulai merasa kenyang, aku putuskan untuk tidak memakannya lagi. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada seorang pun yang masih hidup.
Diselamatkan
Tiba-tiba aku mendengar suara, “Adek“. Aku terdiam sejenak dengan raut wajah kebingungan. Aku sangat yakin bahwa tidak ada lagi orang hidup di sini. Suara siapa itu dan dia memanggil siapa?
Rupanya ada seorang laki-laki yang mau menolongku. Dari mukanya, aku tahu dia seumuran Abangku. Aku dibawanya ke tempat tinggi dan kering.
Sepanjang perjalanan, kami menemukan mayat-mayat yang tergeletak dan ada yang tidak mengenakan sehelai benang pun. Keadaan mereka sangat mengerikan. Ada yang tersangkut di pagar, ada yang kepalanya hilang, dan yang lebih tragis lagi, ada mayat seorang Ibu dan juga bayi dengan tubuhnya yang hancur.
Akhirnya kami sampai di sebuah lapangan, tempat banyak sekali orang yang mengungsi. Kami beristirahat sejenak. Kemudian datang seorang Ibu yang mengajak kami ke rumahnya. Ibu itu menyuruhku mandi dan memberikan aku baju bersih untuk dikenakan, kemudian ia mempersilakan kami makan.
Selesai makan, kami mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kami diberhentikan oleh seseorang untuk beristirahat di pos. Mereka memberikan kami makanan untuk mengganjal perut kami yang kosong. Aku sangat bersyukur karena masih ada orang baik di dunia ini.
Sesampai di Cot Keueueng, dekat Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, seorang bapak mengajak kami tinggal bersamanya dan membawa kami ke rumahnya. Dia memiliki seorang istri dan tiga orang anak, dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Mereka menganggapku sebagai keluarganya sendiri.
Aku dirawatnya, dan setiap sore bapak tersebut mengajakku jalan-jalan. Nama bapak itu Kasim. Sepuluh hari aku di rumahnya, dan selama itupun aku tidak memiliki selera makan, karena bukan Ibuku yang masak. Mereka menjadi bingung dengan tingkah lakuku. Pak Kasim terus membawaku jalan-jalan, dengan maksud untuk mencari keluargaku.
Tapi kemudian ia membawaku ke kampung halamannya, tempat aku disembunyikan seperti tahanan. Setiap hari aku hanya diberi makan mie instan. Banyak warga kampung bertanya-tanya tentangku, tetapi laki-laki itu hanya berkata, “Dia anak musibah tsunami dan kubawa kemari, dia anak yatim piatu, sehingga aku memeliharanya di sini “.
Berita itu menyebar sampai ke Tapak Tuan. Rupanya ada satu keluarga yang mengenalku dan mereka langsung pergi menemuiku dan mengajukan beberapa pertanyaan padaku. “Siapa nama Ibu dan Ayahmu? Siapa nama kakek dan nenekmu? Di mana kamu tinggal? Di mana kampungmu berada, Nak?”
Aku menjawab semua pertanyaan mereka. Merekapun tersadar bahwa aku saudara dari suami keponakan mereka.
Mereka memohon pada Pak Kasim untuk mengembalikan aku pada mereka, tetapi pria itu menolak. Kerabatku tidak menyerah. Setiap minggu mereka memberi uang jajan untukku Rp 200 ribu. Tapi uang tersebut tidak pernah sampai ke tanganku.
Berkumpul kembali
Ternyata Ibu, Kakak, dan Cekta selamat dari bencana tsunami, kecuali Abangku yang tidak pernah ditemukan lagi. Kabarnya, setiap hari keluargaku mengadakan tahlilan untuk mendoakan aku dan Abangku. Setiap mayat yang ditemukan dan diungsikan ke masjid, keluargaku pasti selalu memeriksanya, untuk memastikan apakah ada mayat aku atau Abangku di sana.
Hingga suatu saat, Ibuku pasrah dan membuat tahlilan untukku. Pada hari ke-30 tahlilan, datang seorang tetangga kami memberi tahu bahwa dia melihat aku dibawa pergi laki-laki tak dikenal ke Aceh Selatan. Ibuku hanya diam. Tapi tetangga kami itu tetap meyakinkan Ibu bahwa dia melihatku saat itu. Ibuku tetap saja tidak percaya dan memilih diam dan masuk ke kamar.
Pada saat yang sama, keluargaku mengetahui bahwa UNICEF dan beberapa lembaga membuka layanan untuk mencari anak atau keluarga yang hilang untuk dipertemukan. Mendengar hal ini, keluarga besarku dan tetanggaku melaporkan informasi keberadaanku dan meminta tolong kepada UNICEF untuk mencari diriku.
UNICEF bersama rekan kerja dan staf Departemen Sosial akhirnya menemukan titik terang, bahkan bisa mendapatkan nomor telepon saudara dari laki-laki yang menolongku.
Suatu hari, aku mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang ternyata adalah salah satu warga kampung asalku. Ketika aku mengangkat telepon, terdengar suara yang tak asing lagi bagiku, “Halo, Assalamu’alaikum.”
Tanpa terasa air mataku menetes dengan sendirinya. Ini suara Ibuku, tapi aku tak sanggup menjawabnya karena takut akan menangis sekencang-kencangnya. Kemudian laki-laki itu mengambil paksa telepon yang ada di tanganku. Dia berbicara panjang lebar di telepon tapi aku tidak tidak tahu apa yang dibicarakan karena perasaan yang berkecamuk.
Keesokan harinya, aku melihatnya berkemas dengan sangat terburu-buru. Ketika kutanya, dia mengatakan akan pergi ke Sigli menemui keluargaku. Aku ingin sekali ikut, tapi dia tidak mengizinkan.
Sesampainya di Sigli, laki-laki yang menolongku berbicara panjang lebar dengan keluargaku dan kemudian ia bersiap untuk kembali pergi. Tapi keluargaku tidak membiarkan dia lolos begitu saja. Sebagian keluargaku termasuk Ibuku juga beberapa anggota UNICEF ikut dengan laki-laki itu.
Sesampainya di Aceh Selatan, Ibuku terkejut dan marah karena aku tidak ada di rumah yang ditunjuk. Orang UNICEF menyuruh laki-laki itu untuk membawaku ke hadapan mereka dengan suara keras. Laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menjemputku dan membawaku ke hadapan Ibuku. Pada saat itu, aku ditempatkan di toko tetangga.
Kembali ke rumah laki-laki itu, aku begitu terkejut melihat sosok perempuan yang paling kusayangi, kuhargai, kucintai. Aku memeluknya dengan erat. Aku menangis histeris seperti orang yang sedang kesurupan. Lalu aku membisikkan pertanyaan pada Ibuku, “ Mak, Abang mana? Kakak mana?”.
Ibuku terdiam seakan kehabisan kata-kata. Kemudian ibu mengatakan, “Mereka ada di kampung, Intan tenang aja.“ Aku sedikit lega, walaupun merasa kecewa karena tidak dijemput Abang.
Sesampainya di kampung, orang yang pertama kulihat adalah Kakak. Aku langsung memeluknya cukup lama, tak ingin terpisah lagi. Aku bertanya, di mana Abang, tapi tak ada yang memberikan jawaban. Saat akhirnya aku tahu, aku merasa tak ada lagi yang menyayangiku seperti Abangku. Abangku satu-satunya pergi selamanya tanpa kulihat wajahnya, mayatnya, kuburannya pun tak ada.
Selang seminggu aku berada di kampung, aku harus kembali ke tanah kelahiranku di Aceh Besar untuk bertemu dengan Menteri Sosial yang sedang mengunjungi Aceh saat itu. Di sana aku ditanya habis-habisan tentang kejadian diculik oleh laki-laki itu.
Aku kelelahan menjawabnya. Tapi, setiap jawabanku, diberi muka simpati olehnya. Bukan itu saja, aku diberinya amplop yang berisikan uang. Aku terkejut ketika aku menghitung uang tersebut karena jumlahnya cukup besar, Rp 2.500.000.
Setelah pertemuan dengan pak Menteri yang berkesan itu, aku dan Kakak pun pulang ke kampung. Di sana aku mulai bersekolah kembali di SD 1 Lampoh Saka, tempat nenekku mengajar. Selama di kampung, aku merasa getir dan pahit karena Ibuku tidak ada di sampingku. Ia tinggal di tenda pengungsian di wilayah taman Masjid Ulee Kareng, Banda Aceh.
Setahun kemudian, setelah Kakakku tamat SMA 1 Sigli, ia menyusul Ibuku ke Banda Aceh untuk tinggal di sana sementara aku tetap bersama nenek di kampung. Tidak lama kemudian, Ibu, Kakakku dan para pengungsi yang ada di tenda Ulee Kareng pindah ke barak Neuheun. Di kampung, aku merasa sendirian, hanya nenek yang memahamiku.
Yang paling kuingat adalah suatu kali nenek mencuci bajuku. Namun adik ipar ibuku, yang kupanggil Bapak, menyalahkan aku karena menyebabkan nenek mencuci bajuku. Aku dimarahi habis-habisan, namun tidak ada yang membelaku.
Masalah baru
Tanpa sepengetahuanku, ternyata Ibuku menikah lagi dan tidak ada yang memberitahuku soal itu. Saat itu aku pergi ke Aceh Besar karena ingin lebih dekat dengan Ibu. Tapi Ibuku tetap saja bersikeras menutupi semuanya. Aku tidak diizinkan tidur bersamanya dan disuruh tidur di barak tetangga.
Akhirnya tetanggaku memberitahukan tentang pernikahan Ibuku. Aku marah sekali dan darahku mendidih. Ibu ketakutan, tapi aku tidak memarahinya. Aku hanya mendiamkannya selama sebulan. Ayah tiriku berusaha baik terhadapku dengan membelikan barang untukku. Tapi tetap saja aku merasa marah.
Akhirnya aku pulang kembali ke kampung untuk mengurus surat kepindahan ke Aceh Besar. Dijemput kembali oleh Ibu dan Ayah tiriku ke Banda Aceh, aku melanjutkan sekolah di SD 2 Klieng Cot Aron, tempatku bersekolah sebelum terjadinya musibah tsunami.
Sejak berkumpul lagi bersama Ibu dan Kakak, aku berharap hidupku akan bahagia. Ternyata lebih menyedihkan. Ayah tiriku dan anaknya selalu membuat kekacauan di barak. Anaknya sangat dimanja dan tidak pernah bekerja sedikitpun, sehingga yang melakukan pekerjaan rumah hanya aku dan Kakakku. Kakak kemudian menikah dengan seorang anggota BRIMOB. Kakak tiriku juga kemudian pindah ke rumah bibinya yang juga tinggal di Lamseunoeng.
Empat tahun tinggal di barak, kami pindah pada 2008 ke rumah baru kami, hasil bantuan dari Kanada. Kakak tiriku memilih tinggal di rumah lain seorang diri, tetapi ia tetap mengandalkan Ayahnya, yang selalu membelikannya makanan. Sementara untukku dan ibuku, uang jajan atau keperluan lain seperti uang Lebaran dan uang bulanan juga tak pernah diberikan. Ayah tiriku juga suka menuduh Ibu yang tidak-tidak.
Pada 2013, aku sudah mulai kuliah dan mencurahkan perhatian pada belajar dan belajar di FKIP Matematika, Universitas Syah Kuala. Masalah datang lagi karena Ibuku tidak sanggup membayar uang kuliah dan akhirnya menjual kambing peliharaan kami.
Aku harus bekerja keras banting tulang untuk membayar uang sekolahku sendiri. Namun tak peduli seberapa banyak air mata yang keluar dariku, tak peduli seberapa banyak usaha yang kulakukan, aku akan memperjuangkan kebahagiaanku sendiri. Ini hidupku, dan hanya aku yang berhak atas hidupku.
Aku menganggap hidup ini seperti piano, berwarna putih dan hitam. Namun, ketika Tuhan yang memainkannya, semuanya menjadi indah.
Intan Afriaty, 19, adalah seorang mahasiswi yang tinggal di Banda Aceh dengan ibunya. Ia senang menulis dan menggambar sketsa. Ia ingin menjadi guru.







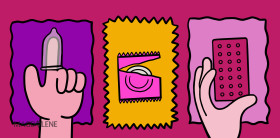
Comments