Maria Gunawan, 55, mengenang bagaimana orang tuanya menolak dengan keras keinginannya menikahi seorang laki-laki Kristen asal Halmahera, Maluku Utara. Sang orang tua tidak ingin anaknya, yang Cina Katolik, menikahi “pribumi”, apalagi dari daerah timur Indonesia. Sentimen rasial memang masih sangat kental masa itu. Belum lagi perbedaan agama dengan sang calon suami, yang makin memupus harapan mereka berdua untuk menjalani hidup bersama.
“Jarang ada orang Chinese yang disetujui ketika menikah sama orang ‘pribumi’ apalagi dia dari timur. Orang timur itu dianggapnya keras, kalau ngomong itu suka pakai urat, emosian, pemalas dan budayanya masih menganggap laki-laki itu di atas,” ujar perempuan dua anak itu kepada Magdalene.
“Kami akhirnya menikah tanpa dukungan keluarga besar. Saya akhirnya milih keluar dari rumah dengan barang seadanya. Selama lima tahun di awal pernikahan tidak dianggap keluarga. Setelah punya anak, baru perlahan mereka luluh dan menerima pernikahan kami,” ujar Maria.
Selain penolakan dari keluarga besarnya, tantangan lain muncul dari keluarga pihak suaminya yang Protestan. Maria pernah diminta pindah agama, tapi ia menolak.
“Waktu itu kami akhirnya menikah secara adat. Sempat disuruh pindah tapi saya tegaskan bahwa sampai mati saya tetap Katolik. Kalau masih disuruh pindah saya mending cerai aja. Lama kelamaan mereka menerima juga,” tambahnya.
Tidak kalah ruwet dari Maria, risiko terusir dari keluarga besar karena pilihan menikah dengan suku yang dianggap “berlawanan” juga dialami oleh “Gloria”, 52, perempuan Batak Toba yang dulunya beragama Kristen.
Gloria, yang dibesarkan di lingkungan bertradisi kuat, berani mengambil risiko menikahi laki-laki Minang muslim yang juga berasal dari keluarga yang tak kalah konservatif. Bagai air dan api, kedua keluarga sudah tentu menolak keras pilihan keduanya untuk menikah.
“Dari segi sejarah aja Batak sama Minang itu pernah perang, bayangin. Waktu pertama kali ngenalin, ditolak habis-habisan,” ujar Gloria kepada Magdalene.
Dengan banyaknya pertimbangan ketika hendak menikah, Gloria pun secara sadar dan tanpa paksaan akhirnya memilih menjadi muslim. Kendati demikian, kehadiran Gloria masih sulit diterima oleh keluarga suaminya. Belum lagi keluarganya yang murka saat mengetahui ia pindah agama.
“Jadi pas nikah dulu cuman diwakilkan sama paman dari pihak suami yang jadi saksi. Dari pihak keluarga saya enggak ada yang datang sama sekali,” ujar Gloria.
Menahun putus relasi dengan kedua pihak keluarga, konflik antara keluarganya dan keluarga suami sedikit reda kala Gloria melahirkan anak pertamanya. Tiga tahun kemudian, keduanya memutuskan hijrah ke tempat orang tua Gloria di Medan. Sebagai suku minoritas dan agama di sana, perlakuan diskriminatif kerap kali diterima mereka, baik oleh keluarga besarnya maupun masyarakat sekitar.
“Kata-kata bernada menghina seperti ‘Si Padang’ itu sering terucap dari orang-orang di sana. Belum lagi kesulitan kami secara ekonomi sering disangkutpautkan dengan hukuman Tuhan karena saya pindah agama,” ujar Gloria.
Budaya kolektif dan nilai-nilai feodalistis
Dilema yang dialami Maria dan Gloria jamak ditemui ketika berbicara perkawinan campur. Meski Indonesia adalah negara plural dengan keragaman ras, suku, dan agama, nyatanya perkawinan campur masih sulit dilakukan sampai sekarang.
“Widyawati”, 21, belum-belum sudah mendapat penolakan keras dari keluarganya yang menjunjung tinggi tradisi Jawa, karena ia berpacaran dengan laki-laki Hindu asal Bali. Neneknya mengatakan, sejahat-jahatnya orang Jawa, mereka masih ulet dan mau membantu keluarga, sedangkan orang dari suku lain itu belum tentu.
“Katanya, kalau aku sampai nikah beda suku dan beda agama, enggak akan dianggap sebagai cucunya lagi,” ujar Widyawati.
Data dari Sensus Penduduk 2010 menunjukkan hanya satu dari sembilan perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan antarsuku. Di Jakarta, misalnya, sebagai wilayah dengan migrasi tertinggi di Indonesia, sekitar satu dari tiga pasangan menikah di Jakarta terdiri dari pasangan beda suku, sedangkan di wilayah lain seperti di Jawa Tengah hanya 2 persen dari jumlah total pasangan.
Peneliti dari Universitas Melbourne, Australia, Ariane Utomo, dalam artikelnya di The Conversation menyebutkan, selain faktor campur tangan pihak ketiga seperti orang tua dan keluarga, pilihan individu untuk memilih jalan “aman” dengan menikahi pasangan dari suku yang sama bisa menjelaskan rendahnya angka perkawinan antarsuku. Di samping itu, Ariane menemukan adanya indikasi bahwa tingkat perkawinan antarsuku semakin tinggi di antara pasangan yang usianya lebih muda.
Antropolog sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Wening Udasmoro mengatakan, kecenderungan suatu ras dan suku yang menginginkan keluarganya menikah dengan suku dan ras yang sama, tidak terlepas dari generasi ayah-ibu kita yang masih mempunyai pemikiran feodalistis. Istilah ini mengacu pada strategi yang kerap kali dipakai oleh para bangsawan atau monarki untuk mengendalikan kekuasaannya di ranah sosial politik.
Baca juga: Ruang (Ny)Aman: Dilema Pernikahan Beda Agama
“Ada semacam strata sosial yang harus dipertahankan di masyarakat. Selain itu, budaya kolektif yang kuat dan masih dipraktikkan oleh generasi sebelumnya, membuat adanya kesenjangan atau perbedaan dengan generasi sekarang yang cenderung lebih individual dan toleran,” ujar Wening kepada Magdalene.
Wening sendiri mengalami penolakan dari keluarga besar karena menikahi orang Papua Nugini.
“Keluarga inginnya saya menikah dengan orang Jawa lagi dan mempertahankan kejawaan saya. Secara teori sederhananya bisa digambarkan begini, jika seseorang yang hidup dalam habitusnya, maka kalangan ini akan selalu memilih yang sama untuk mempertahankan kuasanya,” ujarnya.
Selain soal kuasa, ada pengalaman lain yang membuat pernikahan lintas ras, suku, dan agama masih menjadi isu di Indonesia.
“Ada juga pengalaman traumatis yang dialami suku tertentu. Contohnya orang-orang Cina terhadap ‘pribumi’ misalnya. Kita tahu orang-orang Cina punya sejarah kelam diskriminasi di Indonesia. Bisa jadi munculnya stigma antarsuku itu berasal dari sana,” ujarnya.
Menurut Wening, meski generasi sekarang ini jauh lebih toleran terhadap perbedaan dan latar belakang pasangan, namun relasi dengan keluarga besar masih dianggap pertimbangan paling utama dalam memutuskan perkawinan.
Hal tersebut, ujarnya, tidak lepas budaya kolektif masyarakat kita yang masih sangat kuat, sehingga pernikahan selalu melibatkan dua keluarga besar. Benturan aturan dari masing-masing keluarga besar inilah yang kadang membuat pernikahan campur cukup dihindari, padahal inti dari pernikahan yang paling utama adalah relasi kedua pasangan.
“Masing-masing keluarga besar punya aturan yang berbeda satu sama lain, jadinya rebutan sana-sini. Merasa ras dan suku mereka yang paling baik. Itu sebetulnya yang menghalangi pernikahan lintas suku, ras dan agama terjadi di Indonesia,” kata Wening.
Agama jadi batu sandungan utama
Selain kecenderungan memilih suku yang sama, dalam penelitiannya, Ariane Utomo juga menggarisbawahi bahwa sikap keluarga dan masyarakat yang menentang perkawinan antarsuku sebagian besar berkaitan dengan agama. Di Indonesia, jika sudah bersinggungan dengan agama, bukan hanya keluarga yang menolak, tapi juga negara.
Deputi Direktur Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, misalnya, memilih menandatangani surat pernyataan pindah agama dari Katolik menjadi Buddha karena negara hanya akan mengakui pernikahan yang telah disetujui oleh lembaga agama.
“Orang berbeda-beda dalam melihat agama maupun kepercayaan. Saya sendiri berpikir cinta itu kepada siapa aja dan tidak bisa dibatasi. Tapi UU membatasi, tidak toleran, dan tidak bisa mengelola keberagaman. Jadinya saya enggak menganggap pindah agama untuk kebutuhan administrasi itu jadi suatu masalah. Istilahnya, lu jual gue beli,” ujar Daniel kepada Magdalene.
“Ada semacam strata sosial yang harus dipertahankan di masyarakat. Selain itu, budaya kolektif yang kuat masih dipraktikkan oleh generasi sebelumnya, sehingga pernikahan campur masih ditolak.”
Ia menambahkan, sepucuk surat yang menyatakan perpindahan dirinya ke agama tidak memengaruhi keyakinannya pada agama yang ia anut. Daniel percaya, agama itu urusan dan hak personal yang patut dilindungi negara. Namun kenyataannya, alih-alih melindungi hak tersebut, negara malah membuat aturan yang menjadikan orang-orang secara terpaksa pindah keyakinan.
Aturan yang ia maksud adalah UU Perkawinan No. 1/1974. Sebelum UU ini berlaku, peraturan perkawinan masih mengikuti aturan pemerintah kolonial yang rasialis, yang membedakan aturan untuk pernikahan orang Cina, Arab, dan Eropa. Pernikahan beda ras dan suku kemudian diatur dalam pernikahan campuran yang bernama Regeling op de gemengde Huwelijken (RGH), yang tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, tapi lebih kepada ikatan keperdataan.
Setelah UU Perkawinan disahkan di masa Orde Baru, perkawinan tidak lagi dianggap sekadar ikatan keperdataan antara perempuan dan laki-laki, namun dilihat sebagai ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk rumah tangga yang berdasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya, UU Perkawinan ini sering disebut melarang pernikahan beda agama.
Namun perangkat hukum ini sebetulnya tidak pernah secara eksplisit melarang pernikahan beda agama, yang menimbulkan perbedaan tafsir dan polemik. Banyak pihak protes karena UU Perkawinan dianggap tidak mendukung kebebasan beragama. Hal ini mendorong dikeluarkannya Keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 yang menyatakan tidak melarang adanya perkawinan antar agama.
Ahli hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Febi Yonesta mengatakan, sebetulnya memang tidak ada larangan menikah beda agama, baik secara eksplisit atau harfiah. Pasal 2 UU No. 1/1974 hanya menyebut “Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.
“UU Perkawinan itu tidak bicara tentang siapa yang menikah atau subjeknya. Tapi bicara tentang mekanisme atau prosedur pelaksanaan pernikahan. Jadi sebetulnya jika ditafsirkan secara meluas, sepanjang seseorang melakukan pernikahan menurut tata cara agama, dan dia menundukkan diri pada tata cara agama itu, maka seharusnya bisa dicatatkan secara hukum,” ujar Febi kepada Magdalene.
Permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan pernikahan beda agama datang dari lembaga pencatatan sipil yang ogah mencatatkan jika agamanya tidak sama, meski secara prosedur, pernikahan itu sudah dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan. Mereka biasanya tetap tidak mau mencatat kecuali ada surat pindah agama, seperti yang dilakukan Daniel.
Baca juga: Banyak Jalan Menuju Roma: Siasati Aturan Nikah Beda Agama
Febi menjelaskan masih banyak petugas pencatatan yang masih gagap melihat peraturannya secara meluas. Ia pernah mendampingi pasangan menikah beda agama antara Katolik dengan Islam yang dilaksanakan dengan dispensasi pemimpin gereja Katolik. Karena lembaga keagamaan membolehkan dan menganggap sah pernikahan tersebut, seharusnya negara berkewajiban mencatat itu, ujarnya.
“Jadi menurut saya, masalahnya bukan hanya urusan normatif. Tapi masalahnya itu di praktik diskriminatif, yaitu ketidakmauan pihak pencatat pernikahan untuk mencatat,” ujarnya.
“Hukum perkawinan itu ada dua hal. Pertama, perkawinannya itu sendiri secara aktivitas ritual keagamaan maupun adat. Kedua, pernikahan yang tercatat secara hukum. Yang banyak bermasalah kan bukan di lembaga keagamaannya, tapi di pencatatannya,” ujar Febi.
Ahmad Nurcholish, mediator pernikahan beda agama dari organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), mengatakan bahwa tantangan tersulitnya masih berasal dari Catatan Sipil yang tidak paham akan hukum perkawinan secara utuh.
“Di level agamawan atau lembaga agama sudah lebih maju dalam menilai pernikahan beda agama. Tapi di level lembaga negara, baik di tingkat kelurahan maupun Dukcapil (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) masih sangat sulit,” ujar Nurcholish yang telah memediasi 800 pernikahan campur.
Petugas pencatatan gagal pahami UU Perkawinan
Menurut Ahmad, kurangnya pemahaman terhadap konstitusi dan bias ideologi agama yang dipeluk para petugas membuat mereka meyakini bahwa pernikahan beda agama seharusnya tidak diakomodasi.
Ia menambahkan, dirinya sering mengacu pada Ketetapan Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986, yang dalam putusannya menyebutkan bahwa pernikahan agama tidak dilarang. Lalu ada juga UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap manusia bebas memilih keyakinannya masing-masing, dan UU Administrasi Kependudukan No. 16/2019 yang mengatur tugas pencatatan sipil sebagai lembaga negara.
“Semuanya kita keluarkan saat berargumen dengan pihak pencatatan sipil,” ujar Nurcholish.
Kepala Pencatatan Sipil Tangerang Selatan Dedi Budiawan mengatakan, aturan hukum di Indonesia memang tidak diperbolehkan menikah beda agama, kecuali salah satu pihak mengalah dengan melampirkan surat berpindah agama atau lewat jalur pengadilan, baru bisa dicatatkan.
Ketika ditanya tentang dispensasi gereja Katolik yang memperbolehkan umatnya menikah dengan beda agama dan disahkan oleh gereja, Dedi bersikukuh bahwa pihak pencatatan sipil tetap tidak bisa mencatatkan selama tidak ada surat keterangan pembaptisan.
Baca juga: Sampai Keyakinan Pisahkan Kita? Tumbuh Besar dengan Orang Tua Beda Agama
“Selama agamanya sama, itu kewajiban kami untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Kalau tidak sama berarti balik ke UU Perkawinan tadi yang tidak bisa. Memang ada lembaga agama, tapi di atasnya ada juga aturan hukum yang harus ditaati,” ujar Dedi kepada Magdalene.
Ia mengatakan, selama ini memang ada beberapa pasangan yang datang ke Dukcapil Tangerang Selatan dengan menyertakan bukti pernikahan di gereja. Setelah dilihat kolom agamanya berbeda, maka otomatis petugas pencatatan sipil tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka, kata Dedi. Biasanya bila sudah begitu, ia akan menyuruh pasangan tersebut untuk meminta surat baptis terlebih dahulu kepada Gereja, agar bisa dicatatkan. Hal itu berlaku pula untuk agama-agama lainnya.
Selain di Dukcapil, pernikahan beda agama juga ditentang keras oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Meski ada sebagian ulama yang membolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen, pihak KUA umumnya tetap menolak pernikahan beda agama.
Kepala KUA Serpong Utara Ahmad Phudoli mengatakan, selain harus menyertakan surat sudah mengucapkan syahadat dan masuk Islam, pihak KUA juga akan bertanya tentang pengetahuan Islam dan pengamalannya kepada pihak yang menyertakan surat mualaf.
“Kalau misal sudah ada sertifikat di KUA, nanti ada pembinaan kembali, apakah syahadatnya sudah mantap atau belum, pengamalan ibadahnya sudah dilaksanakan atau belum. Sudah mulai salat atau belum. Pembinaan langsung dengan tatap muka,” ujar Ahmad.
Praktik birokrasi diskriminatif dan melampaui ketentuan hukum
Febi Yonesta dari YLBHI mengatakan, jamaknya penolakan untuk mencatat pernikahan beda agama serta adanya aturan melampirkan bukti pindah agama merupakan praktik birokrasi yang melampaui ketentuan hukum dan mengada-ada. UU Perkawinan tidak pernah menyebutkan persyaratan surat pindah agama, sehingga praktik birokrasi ini lahir dari diskresi, atau aturan yang keluar dari pejabat pemerintah.
“Diskresi itu berbeda dengan regulasi. Kalau regulasi itu berlaku umum, maka diskresi itu berlaku sesuai dengan aturan instansi yang bersangkutan. Dalam konteks diskresi juga kita harus melihat jauh ke belakang. Itu kan pernah santer pernikahan beda agama di kalangan artis di tahun 80-an. Nah bisa jadi itu mendorong Kementerian Agama melakukan surat edaran yang melarang menikah beda agama, itu namanya diskresi,” ujar Febi.
Di level agamawan atau lembaga agama sudah lebih maju dalam menilai pernikahan beda agama. Tapi di level lembaga negara, baik di tingkat kelurahan maupun Dukcapil masih sangat sulit.
Menurut Febi, unsur pemaksaan pindah agama untuk bisa dicatat secara hukum, bisa mengindikasikan tidak hadirnya lembaga negara dalam menjamin kebebasan beragama masyarakatnya yang juga telah diatur dalam Kovenan Internasional atau perjanjian hukum internasional.
“Pencatatan pernikahan secara hukum itu kan berhubungan dengan ahli waris, harta gono-gini, administrasi anak pokoknya hal-hal yang fundamental. Ketika kita tidak bisa menikah karena tidak mau dicatatkan, ada potensi selama hidup kita didiskriminasi,” ujarnya.
“Adanya diskriminasi dan stigmatisasi mendorong pasangan-pasangan untuk terpaksa mengubah agamanya. Itu bentuk pemaksaan keagamaan yang sangat dilarang oleh kovenan hak sipil dan politik,” kata Febi.
Alternatif lain untuk mencatatkan pernikahan beda agama adalah lewat jalur pengadilan, namun sangat jarang yang menempuhnya karena dianggap rumit. Dalam catatan Direktori Putusan Mahkamah Agung, sejak 2012 sampai sekarang hanya ada 32 putusan terkait dengan pernikahan beda agama. Itu pun tidak semua putusan perkara pernikahan beda agama langsung dikabulkan oleh hakim. Sepanjang 2020, satu dari dua gugatan pernikahan beda agama ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan UU Perkawinan yang berlaku. Menariknya, putusan yang lebih toleran justru muncul di pengadilan-pengadilan daerah seperti Purwokerto, Jawa Tengah, dibandingkan pengadilan-pengadilan di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.
Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Arief Rahman mengatakan, Indonesia memang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama.
“Sejauh ini, kami hakim yang bertugas sejak 2019 belum pernah menangani pemohon terkait dengan pernikahan beda agama. Tapi setahu saya memang di Indonesia ini tidak boleh menikah beda agama, makanya banyak yang memilih ke luar negeri saja,” ujar Arief.
Sebagai aktivis hak asasi manusia, Daniel dari HRWG mengatakan, aturan hukum itu selalu sarat nuansa politik.
“Selama politik kita hanya membenarkan satu agama, maka agama yang merasa paling benar tidak akan pernah memberi ruang untuk perbedaan. Sikap tidak toleran terhadap perbedaan itu yang kemudian diteruskan dalam satu produk hukum,” ujarnya.
“Harusnya Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini persilangan budaya itu sangat beragam, tapi perangkat hukum tidak bisa mengelola keberagaman, khususnya untuk soal perkawinan. Bagi saya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak diturunkan pada produk hukum yang berlaku,” kata Daniel.
Liputan ini didukung oleh hibah Story Grant dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).



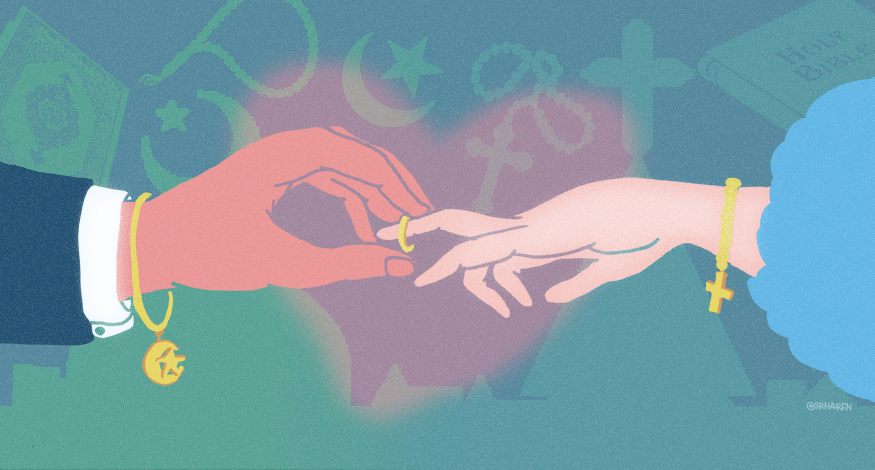
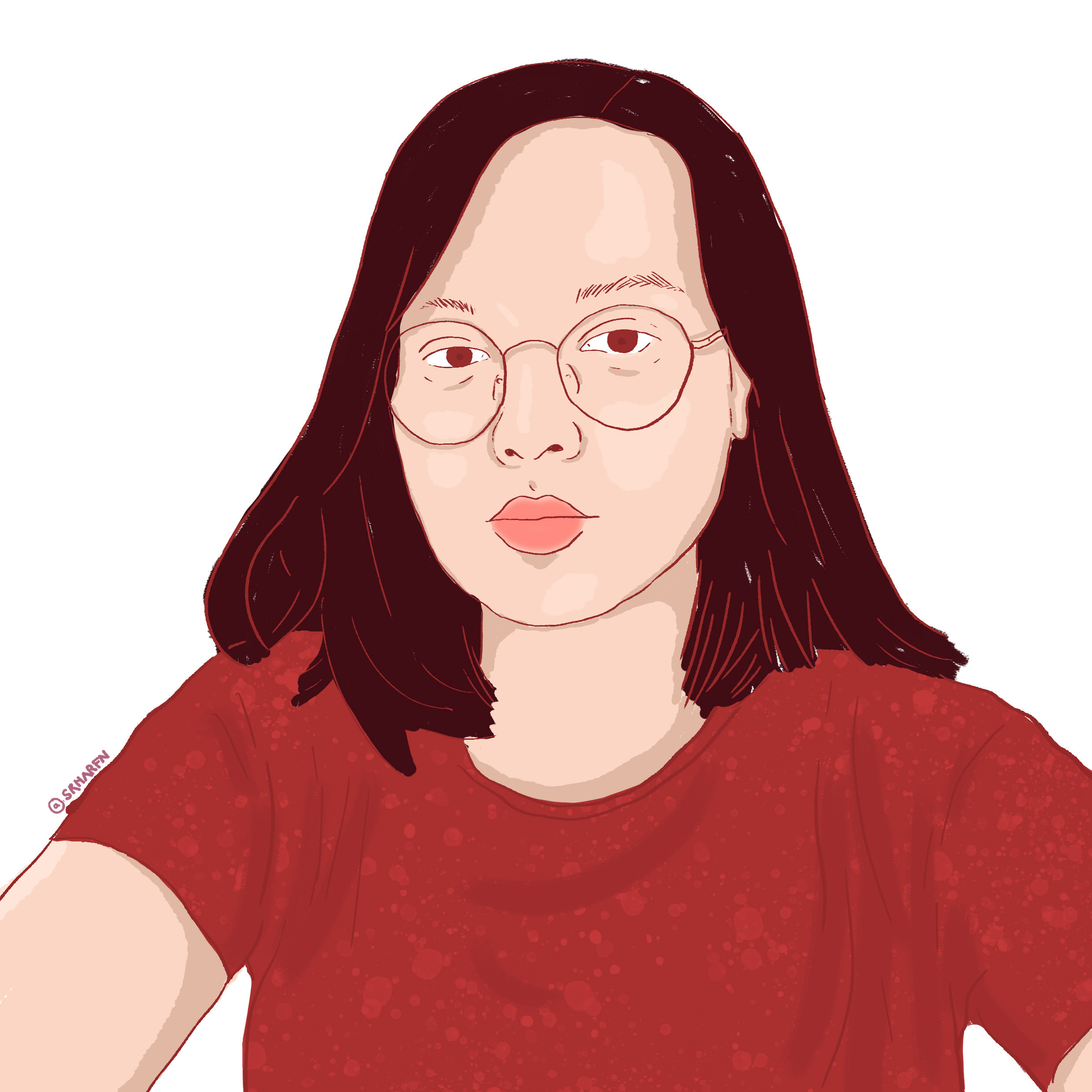



Comments