“Alasan sesungguhnya saya bisa menjadi model karena saya punya keberuntungan genetik. Saya mewarisi wajah dan tubuh yang sesuai dengan standar kecantikan, yaitu berwajah simetris, muda, feminin, dan berkulit putih.”
Kata-kata itu diucapkan oleh model Victoria’s Secret Cameron Russel saat jadi pembicara dalam TEDtalk x MidAtlatis pada 2013 silam. Pernyataan tersebut sempat membuat ramai jagat hiburan Amerika Serikat, bahkan videonya di Youtube TEDTalk sudah ditonton lebih dari 27 juta kali. Russel semakin populer karena dianggap membongkar konstruksi kecantikan di dunia model dan membuat orang semakin sadar dengan beauty privilege.
Selain Russel, aktris Hollywood legendaris Charlotte Rampling dalam wawancaranya dengan Huffington Post juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa terlahir cantik itu merupakan sebuah privilese yang besar. Di masyarakat yang normatif, menjadi rupawan adalah kekuatan dan berpotensi digunakan tak hanya di dunia hiburan, tapi juga dalam banyak hal.
“Kalau kamu cantik, pintu akan selalu terbuka untukmu; orang tersenyum padamu; kamu diterima di tempat yang orang lain belum tentu bisa,” ujar Rampling.
Keberuntungan mempunyai wajah rupawan atau dikenal dengan istilah beauty privilege adalah isu yang sebetulnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun jarang sekali dibicarakan secara mendalam. Isu ini sering kali hanya dilihat sebatas masalah takdir Tuhan yang punya hak otoritatif menciptakan manusia, ketimbang digali dari kaca mata bagaimana hal itu bisa menciptakan ketidakadilan sosial.
Padahal, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kalsey P. Yonce dari Universitas Smith, Amerika Serikat, bertajuk Attractiveness Privilege: The Unearned Advantages of Physical Attractiveness, disebutkan bahwa beauty privilege merupakan isu interseksional yang erat kaitannya dengan masalah ketidakadilan lainnya, seperti rasialisme, ableism, ageism, fatphobia, dan classism.
Baca juga: Novel ‘Breasts and Eggs’ Gugat Standar Kecantikan, Stigma Inseminasi Buatan
Standar Kecantikan dan Manfaat Beauty Privilege
Adanya standar kecantikan normatif yang berlaku secara global seperti bentuk wajah simetris, bertubuh langsing, tinggi serta berkulit putih, membuat ras tertentu yang memenuhi standar tersebut dianggap lebih unggul. Sedangkan, mereka yang memiliki kulit gelap dianggap jelek atau kurang atraktif. Hal ini yang menjadikan beauty privilege tidak bisa dilepaskan dengan isu rasialisme yang berhubungan dengan warna kulit dan fatphobia yang berkaitan dengan bentuk tubuh.
Selain itu, Yonce juga menggarisbawahi bahwa mereka yang punya wajah rupawan umumnya lebih sering dikategorikan atraktif. Namun standar atraktif biasanya dihubungkan dengan umur yang muda (ageism) dan bentuk tubuh yang sempurna atau tidak memiliki disabilitas (ableism).
“Standar kecantikan juga biasanya dibarengi kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan atau barang-barang tertentu, di mana itu berkaitan dengan masalah kelas (classism), karena tidak semua orang punya akses untuk pelayanan kesehatan atau pembelian produk untuk alasan mempercantik diri,” tulis Yonce.
Menurutnya, banyak orang yang hanya melihat isu ini dari dimensi yang sederhana, misalnya, menganggap bahwa mereka yang jelek atau tidak atraktif pun bisa saja berubah menjadi cantik kalau merawat dan merias diri, padahal tidak semua orang punya akses untuk melakukan itu. Hal tersebut, yang kemudian Yonce bilang, menjadi alasan kenapa isu penting ini untuk dilihat dari beragam dimensi.
Ia menambahkan, isu ini masih sering dianggap tabu untuk dibahas karena sebagian besar mereka yang memiliki beauty privilege tidak menyadari hak istimewa yang mereka punya dan cenderung menganggap ini sebagai suatu hal yang normal. Padahal kenyataannya, mereka adalah pihak yang punya kekuatan (power) karena diuntungkan dengan sistem atau standar masyarakat yang masih timpang.
Baca juga: Stop Pandang Kulit Putih Lebih Superior
Di dunia kerja, misalnya, banyak perusahaan yang mencantumkan kriteria “berpenampilan menarik” untuk mengisi bidang-bidang tertentu dan terutama menyasar perempuan. Dari hasil penelitian Markus M. Mobius, dkk, dari Universitas Harvard, berjudul Why Beauty Matters, menemukan bahwa orang yang dianggap atraktif secara fisik sering kali diasumsikan memiliki hidup lebih baik, kompeten dan pintar, dibanding mereka yang dianggap tidak atraktif. Hal itu membuat orang-orang yang berpenampilan menarik cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
Di bidang hukum, ketidakadilan karena masalah penampilan juga terlihat dari hasil penelitian lembaga riset hukum Australia bernama The Law Project pada 2017, yang menemukan bahwa 120-305 persen terpidana yang berpenampilan tidak atraktif menerima dakwaan lebih lama dibanding terpidana yang memiliki penampilan atraktif.
Temuan serupa juga terlihat dari laporan US Sentencing Commission yang mengambil data dari 2012-2016. Laporannya tersebut menunjukkan bahwa 19 persen terpidana kulit hitam menerima dakwaan lebih lama daripada terpidana kulit putih. Contoh kasus tersebut mengukuhkan kembali hasil penelitian Yonce bahwa beauty privilege berhubungan dengan isu rasialisme.
Beauty Privilege di Era Digital dan Kemunculan Influencers
Sebelum adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, media melalui iklan, film dan sinetron sebetulnya sudah menjadi pihak yang melanggengkan standar kecantikan normatif. Sekarang, di mana semua orang bisa punya platform sendiri untuk mengekspresikan dirinya, standar kecantikan ternyata tidak jauh berbeda alias masih sama saja. Ini terlihat dari banyaknya para influencer di media sosial yang punya pengikut jutaan karena cantik, muda, berbadan langsing, dan yang paling penting heteroseksual.

Cameron Russell, model dari Victoria's Secret Fashion Show.
Meski sekarang ini sebetulnya sudah banyak juga bermunculan influencer yang berasal dari kelompok minoritas dan tidak sesuai dengan standar kecantikan normatif, namun biasanya mereka mengalami fase penghakiman terlebih dahulu baru diterima. Selain itu, jumlah pengikut mereka pun jarang yang sampai ke angka jutaan.
Ian Hugen yang merupakan model transpuan, misalnya, beberapa kali dalam unggahan di akun Instagramnya bercerita tentang pengalamannya melawan rasa takut dan penghakiman warganet karena identitas seksualnya.
Hal serupa juga dialami oleh Vindy, beauty vlogger asal Malang, Jawa Timur, yang memiliki kulit sawo matang. Dalam Instagram Live bersama Magdalene, Vindy bercerita bahwa perlu waktu bagi dirinya untuk berani tampil karena takut dicemooh. Ia merasa dirinya tidak akan diterima karena wajah dan tubuhnya tidak sesuai dengan standar kecantikan normatif, belum lagi cara berbicaranya yang medok.
“Kalau yang gelap kayak aku ini seringnya dikatain dekil dan kucel. Ya sempat berpikir kayaknya kalau punya kulit putih itu segalanya akan lebih mudah,” katanya.
Kolumnis New York Times, Vanessa Friedman pernah mengkritik tentang masalah influencer ini. Dalam artikelnya berjudul The Rise and (Maybe) Fall of Influencers, Friedman mengatakan bahwa para pengikut influencer ini sering kali memosisikan mereka sebagai teman sehingga pendapatnya lebih didengarkan. Hal itu yang membuat banyak perusahaan komersial menyasar influencer untuk mendorong kampanye mereka.
Baca juga: Mau Lebih ‘PD’ Sama Tubuhmu? Pilih-pilih Ikuti Akun di Medsos
Namun, menurut Friedman, banyak influencer yang hanya mementingkan keuntungan materi dengan memanfaatkan beauty privilege yang dia punya, tapi sebetulnya tidak paham dengan isu sosial. Kasus Kendall Jenner dengan iklan Pepsi pada 2017 lalu, misalnya, sempat jadi sorotan karena iklan itu mengangkat isu sosial tentang minoritas yang sedang demo. Namun justru berujung backlash karena dianggap tidak sensitif.
Selain itu, di tahun yang sama, Jenner juga mendapat kecaman karena tampil di sampul Vogue India. Publik pun menyebut Kendal tidak sensitif dan mempertanyakan Vogue yang lebih memilih model kulit putih dibandingkan perempuan India berkulit cokelat.
Di Indonesia, kasus influencer yang bias dan tidak sensitif juga sudah sering terjadi. Beberapa waktu lalu bahkan sempat ramai influencer yang dikecam karena dibayar pemerintah untuk mempromosikan Omnisbus Law, yang jelas merugikan rakyat. Pemerintah disebut-sebut menggelontorkan hampir 90 Milyar untuk membayar para influencer itu.
Juli tahun lalu juga sempat viral tagar #InfluencersAreGross setelah banyak brand dan penjual makanan yang berbicara tentang kejengkelan terhadap influencer yang selalu meminta fasilitas dan makanan gratis. Tak sedikit pula ahli media yang memprediksi bahwa influencer di masa depan bisa jadi tidak begitu lagi punya “influence” karena harga selangit dan blunder yang sering mereka lakukan. Seperti yang Friedman katakan:
Since being what used to be called a “tastemaker” became a job, and word-of-mouth tips became known as “influencer marketing,” attention has been focused largely on the risks to brands in linking up with individuals.
Ilustrasi oleh Karina Tungari.




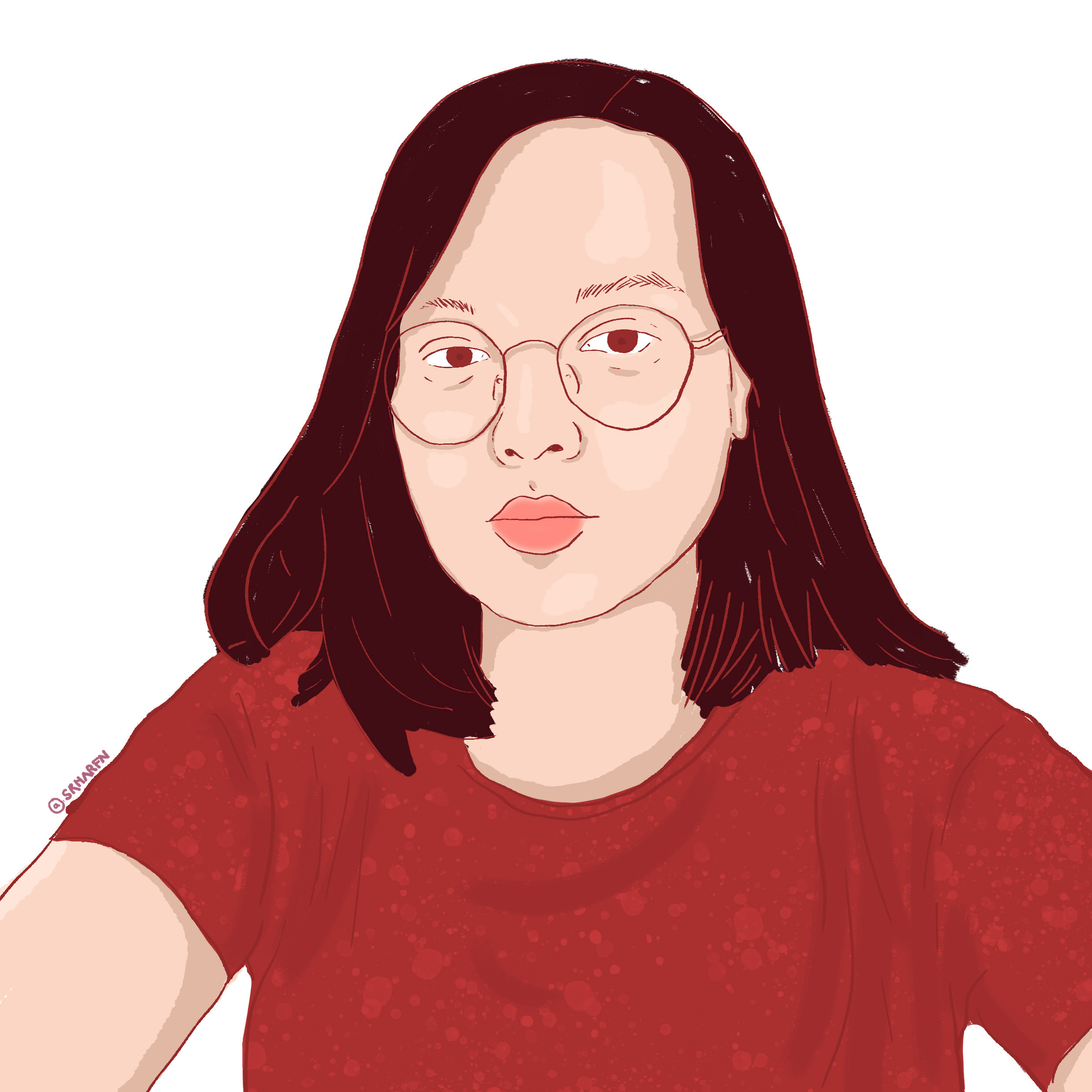

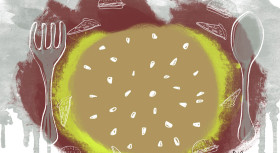

Comments