Dua minggu belakangan ini ramai diperbincangkan kasus Aprilia Santini Manganang yang mendapatkan "legal gender recognition" atau pengakuan hukum atas pergantian identitas gender. Ia kemudian resmi menjadi Aprilio Perkasa Manganang dengan keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano (Sulawesi Utara), Nova Laura Sasube, yang menetapkan “memberi izin kepada pemohon (Aprilia) untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berstatus jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki.”
Keputusan ini mendapatkan beragam reaksi masyarakat di media sosial, menurut Retno Daru Dewi G.S. Putri, dalam artikel di Magdalene, menunjukkan buruknya wawasan gender dan seksualitas di Indonesia.
Kasus Aprilio Manganang Bukan Hal Baru
Terlepas dari hebohnya pemberitaan, kasus Aprilio bukanlah yang pertama yang terjadi di Indonesia. Dapat dipastikan juga, bukan yang terakhir. Perubahan status hukum penggantian nama dan, di Indonesia masih disebut penggantian jenis kelamin, sudah ada jauh sebelumnya. Setidaknya pada 1973 dengan adanya kasus Vivian Rubiyanti yang kala itu didampingi pengacara HAM ternama, (alm.) Adnan Buyung Nasution.
Kita bisa punya daftar panjang mereka yang memperoleh pengakuan hukum atas penggantian gender. Selama lima tahun terakhir ini saja (sejak 2015), tercatat setidaknya 30 kasus yang tersebar dari berbagai pengadilan di Indonesia, dari Banda Aceh hingga Mataram, dari Jakarta hingga Singkawang.
Perubahan status jenis kelamin akibat kondisi genetik atau organ (seperti hipospadia) juga bukan hal yang baru bagi dunia meja hijau kita. Sudah ada sejumlah kasus serupa sebelumnya, seperti kasus B di Mungkid, Jawa Tengah (2015), dan kasus F di Mataram, Nusa Tenggara Barat (2019).
Baca juga: Magdalene Primer: Memahami Gender dan Seksualitas
Kebanyakan kasus memang tidak ramai diberitakan media karena pertama, kasus tersebut menyangkut orang biasa sehingga mereka perlu menjaga privasinya. Terlebih untuk kasus yang melibatkan anak-anak, permohonan perubahan nama dan gender diajukan oleh orang tuanya, seperti dalam hal kasus di Purworejo (2015) dan Temanggung (2018), Jawa Tengah, dan di Banda Aceh (2018).
Kedua, kasus-kasus ini sudah menjadi perkara yang lumrah dalam sistem hukum kita, dan bukan lagi keanehan seperti 40 tahun lalu. Memang, sampai hari ini masih belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai pergantian jenis kelamin atau gender, selain UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (dan UU no. 24/ 2014 tentang Perubahan UU no. 23/2006). Selain itu, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.
Ini artinya bahwa sistem hukum kita menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan. Karena itu pula, di masa kini pengacara yang mendampingi tidak perlu sampai harus mengutip piagam hak asasi manusia untuk meyakinkan hakim.
Umumnya, sering dikatakan bahwa hukum kita tertinggal dari perubahan sosial yang ada. Namun, dalam kasus-kasus ini boleh dibilang tidak demikian adanya. Malah, hukum kita sudah cukup akomodatif, tapi justru penerimaan masyarakat yang belum sepenuhnya terjadi.
Hukum di Indonesia sering dikatakan tertinggal dari perubahan sosial yang ada. Namun, dalam kasus-kasus pergantian status gender, hukum kita sudah cukup akomodatif, tapi justru penerimaan masyarakat yang belum sepenuhnya terjadi.
Baca juga: Asha bukan Oscar: Membongkar Miskonsepsi Soal Transgender
Kasus-kasus Pengakuan Gender Secara Legal
Dari kasus-kasus yang ada, setidaknya ada dua hal yang menjadi prasyarat substantif kasus permohonan perubahan status dapat dikabulkan oleh hakim.
Pertama, ada setidaknya dua saksi yang dapat memberikan kesaksian di muka pengadilan bahwa saksi mengenal baik pemohon dalam kehidupannya. Di dalam satu kasus (kasus D di Sumedang, Jawa Barat, 2015), salah satu saksi malah menyatakan bahwa “sejak usia balita pemohon berperilaku menyimpang dan bertingkah laku seperti perempuan.”

Aprilio Manganang (credit:Instagram/manganang92)
Bagi kita, pernyataan tersebut tentu saja terdengar membingungkan (dan mungkin kontroversial) sebab menggunakan ukuran heteronormatif. Meski begitu, pernyataan tersebut, terdengar lebih meyakinkan karena perubahan status tersebut adalah hal yang “normal” dan perlu dilakukan agar pemohon tidak lagi “menyimpang.”
Kedua, adanya bukti-bukti medis yang mendukung permohonan tersebut. Hal ini terutama berupa surat keterangan dari dokter yang memeriksa kondisi fisik dan psikis pemohon. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, surat tersebut dapat dilengkapi pula dengan bukti pendukung seperti: hasil pemeriksaan hormon (kasus S di Klaten, Jawa Tengah, pada 2015 dan kasus N di Bangkinang, Riau, 2019), dan hasil pemeriksaan kromosom (kasus T di Purworejo 2015 dan kasus S di Tasikmalaya, Jawa Barat, 2021).
Selain itu, hakim perlu memastikan bahwa permohonan penggantian tidak digunakan untuk maksud yang lain dan tidak terkait permasalahan perdata atau pidana. Hal ini untuk meniadakan kemungkinan “error in persona”, yaitu kesalahan dakwaan/gugatan hukum karena ditujukan kepada orang yang salah (akibat identitas yang keliru), sehingga ia dapat terhindar dari tuntutan hukum yang ada. Jika demikian adanya, maka hakim mesti menolak permohonan tersebut.
Kasus-kasus Lain Berujung Diskriminasi
Penting dicatat pula, ada sejumlah permohonan yang ditolak oleh hakim seperti dalam kasus T di Cirebon (2019), kasus R di Mungkid (2019), dan kasus N di Palangka Raya (2020). Mengapa kasus-kasus ini ditolak?
T di Cirebon lahir sebagai perempuan, dan sudah memeriksakan diri ke psikiater di Jakarta dan Thailand. Ia menyatakan sudah melakukan operasi perubahan kelamin dan payudara di Thailand pada 2016. Namun, hakim tidak dapat menerima surat bukti medis yang tertera dalam bahasa Inggris (tidak tersedia terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia).
Selain itu juga, anehnya, hakim mendasarkan pertimbangannya bahwa “perubahan kelamin itu adalah hal yang dilarang dalam ajaran agama yang dianut oleh pemohon (yaitu Katolik).” Lebih jauh, hakim malah berpendapat bahwa “pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Tuhan takdirkan atas diri pemohon yang terlahir sebagai perempuan normal.”
R di Mungkid lahir sebagai pria dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ia sudah memeriksakan diri ke psikiater di Jakarta pada 2018. Ia menyatakan telah menjalani serangkaian operasi guna kepentingan penyesuaian fisik sebagai perempuan. Sayangnya, hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh R kurang meyakinkan. Selain, hakim mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin no. 03/Munas-VIII/MUI/2010 (27 Juli 2010) yang menyatakan bahwa mengubah alat kelamin adalah haram hukumnya.
N di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, lahir sebagai perempuan dan bekerja wiraswasta. Di dalam kehidupan sosialnya, ia telah menggunakan nama pria yang sesuai dengan ekspresi gendernya. N ingin pengadilan mengabulkan permohonan ganti nama. Di dalam persidangan juga hadir dua orang saksi yang mendukung permohonan N tersebut. Pergantian nama itu juga sudah seizin kedua orang tuanya. Sayangnya, hakim berpendapat bahwa hal tersebut “sangat bertentangan dengan norma kepatutan dan norma sopan santun dan adat istiadat di tengah masyarakat.”
Dari kasus-kasus ini, terlihat persoalan apakah hakim perlu merujuk ajaran/hukum agama dan “norma kepatutan,” terutama tafsir secara sempit. Karena permohonannya ditolak, orang-orang ini tidak dapat menjalani kehidupan sosial mereka sesuai ekspresi gendernya, dan juga tidak dapat melangsungkan perkawinan. Ini mengakibatkan diskriminasi. Jadi, perlu ada acuan yang jelas bagi hakim agar penetapan/putusannya tidak berujung diskriminasi seperti yang sudah terjadi.
Baca juga: Pengalaman Transgender Laki-laki Pasca-Operasi
Menjadi Negara Maju?
Di banyak negara lain, seperti di Eropa Barat, kasus penggantian nama dan status identitas adalah masalah privat. Negara tidak bisa ikut campur (intrusif), apalagi menghalangi. Peran negara terbatas menyediakan perangkat aturan yang menjamin kebebasan individu untuk mengekspresikan identitas gendernya.
Di Perancis, individu transgender dapat mengganti nama dan statusnya tanpa perlu pemeriksaan psikiater dan melakukan operasi ganti kelamin terlebih dulu. Jadi, surat keterangan dari psikiater dan operasi ganti kelamin tidak menjadi prasyarat dalam penggantian nama dan status. Terlebih, sudah sejak 2016, istilah “identitas jenis kelamin” diganti dengan istilah “identitas gender.”
Agar tidak hanya menjadi buih-buih sensasi sesaat, kasus Aprilio justru bisa menjadi momentum yang penting guna mengembangkan wawasan masyarakat (termasuk para hakim dan pemuka agama) yang lebih inklusif akan keberagaman gender dan seksualitas di tanah air.
Agar tidak hanya menjadi buih-buih sensasi sesaat, kasus Aprilio bisa menjadi momentum untuk mengembangkan wawasan masyarakat (termasuk para hakim dan pemuka agama) yang lebih inklusif akan keberagaman gender dan seksualitas di tanah air.
Pemuka agama yang menjadi saksi ahli di dalam kasus Vivian Rubiyanti (1973) justru lebih terbuka dan mendukung kebebasan individu. Apakah ini karena ada peningkatan konservatisme beragama selama tahun-tahun belakangan ini?
Selain itu, kita perlu mengembangkan kerangka acuan hukum nasional yang lebih humanis bagi semua orang Indonesia. Sebab, kasus-kasus hukum yang ada di negara kita hanya berupa puncak gunung es. Kebanyakan kasus justru berada di luar hukum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki backing dan berasal dari kelas ekonomi bawah karena tidak mampu membiayai pemeriksaan medis dan mengurus penggantian status secara resmi ke pengadilan.
Kita ingin hukum nasional dapat menjamin kebebasan individu, tidak diskriminatif, dan menyediakan akses yang adil bagi semua, tanpa pengecualian. Tentunya, ini adalah bagian dari upaya kita bersama membangun perangkat kebijakan sosial yang lebih mumpuni sebagai prasyarat menuju Indonesia yang maju.
Ilustrasi oleh Jemima Holmes



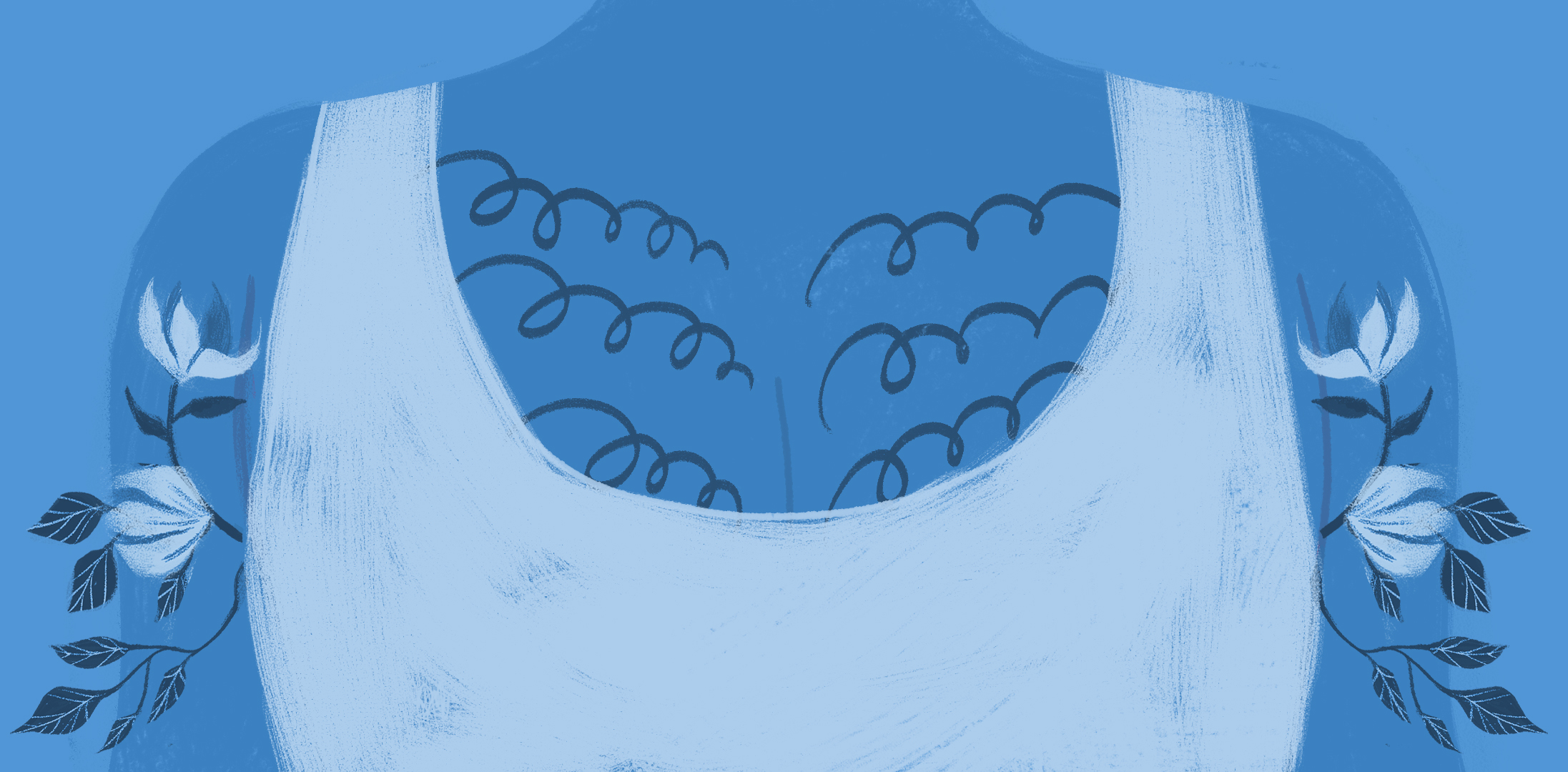



Comments