Kasus pemerkosaan tiga orang anak oleh ayah kandung mereka di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang diangkat Project Multatuli baru-baru ini menyita perhatian banyak orang. Pasalnya, ketiga korban adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun dan mendapatkan penanganan yang mengecewakan dari Polres Luwu Timur. Selain itu, sang ibu, “Lydia”, juga mengalami perundungan oleh pihak kepolisian. Dia difitnah dengan vonis kesehatan mental yang dianggap tidak stabil.
Dalam penangangan kasus kekerasan seksual di Indonesia, memang jarang sekali penegak hukum yang mau dengan senang hati membela korban. Seolah-olah mereka, yang didominasi laki-laki, merasa maskulinitasnya terancam melihat ada korban perempuan yang dengan lantang menuntut keadilan. Atau mungkin mereka masih mewajarkan tindakan mesum laki-laki selama tidak ada bukti masuknya penis ke dalam vagina secara paksa.
Apa terjadi dengan Lydia dan anak-anaknya hanya seperti kisah lama yang berulang kembali. Buruknya empati para penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual masih sering ditemukan. Hal ini diperburuk dengan minimnya dukungan dari masyarakat sesama perempuan, pemahaman akan kesehatan mental, dan minimnya aturan hukum yang berpihak pada korban.
Baca juga: Mengenal Definisi Pencabulan, Pelecehan Seksual, dan Pemerkosaan
Perempuan Dukung Perempuan adalah Hak Istimewa
Perilaku primitif yang membuat perempuan saling berkompetisi masih sering terjadi di sekeliling kita. Mulai dari bersikap sinis terhadap perempuan yang memiliki penampilan berbeda dan unik hingga menyalahkan perempuan lain jika pasangan laki-lakinya selingkuh. Akan tetapi, harapan saya tentu berbeda apabila seorang perempuan menghadapi perempuan lain yang mengalami kekerasan seksual. Sayangnya, hal ini tidak terjadi dengan Lydia.
Ketika Lydia pertama kali melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Luwu Timur, dia diterima oleh Firawati yang menjabat sebagai Kepala Bidang organisasi tersebut. Alih-alih memberikan ruang aman, Firawati justru bersikap simpati ke pelaku pemerkosaan dan menghubunginya dengan alasan mengonfirmasi ke sesama Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman perempuan mendukung perempuan adalah hak istimewa bagi mereka yang paham saja. Mungkin di Luwu Timur, pola pikir mayoritas masyarakatnya tidak semaju di kota besar lainnya. Karena itu, perempuan belum memahami pentingnya membela perempuan lain, apalagi yang menjadi korban kekerasan seksual.
Baca juga: #MeTooInceste: Pelajaran dari Skandal Inses di Perancis
Vonis Kesehatan Mental yang Buruk untuk Membungkam Korban
Sebelum memberanikan diri pergi ke Makassar demi mencari keadilan, bersama ketiga anaknya, Lydia diarahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Di situ lah Lydia harus merespon pertanyaan-pertanyaan yang tidak merepresentasikan proses pemeriksaan kesehatan jiwa yang baik dan benar.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Lydia kemudian disebut gila sehingga kasus tidak diteruskan oleh Polres Luwu Timur. Laporan dianggap tidak sah karena Lydia dengan seenaknya divonis memiliki gangguan jiwa dan memiliki motif tertentu untuk menghukum suaminya. Ditambah lagi dengan bukti fisik pada ketiga anak Lydia dalam laporan pemeriksaan medis yang tidak diakui.
Hal ini menunjukkan bahwa Polres Luwu Timur seolah-olah tidak ingin bekerja lebih giat lagi untuk membela korban kekerasan seksual. Dengan mudahnya mereka menggunakan vonis yang salah untuk menegasikan kondisi kesehatan mental korban. Akibatnya, tidak hanya kehilangan pembelaan dari aparat penegak hukum, Lydia juga mendapatkan stigma masyarakat setempat akibat vonis psikologis yang keliru tersebut.
Apabila banyak pihak kepolisian yang bersikap seperti ini, maka korban-korban kekerasan seksual di luar sana akan semakin terpuruk. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental akan semakin buruk.
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebaiknya Berbenah Diri
Sebagai warga negara, saya cukup sering berinteraksi dengan petugas kepolisian. Sayangnya tidak semua interaksi tersebut menyenangkan.Mulai dari pemaksaan ‘bayar di tempat’ ketika saya ditilang, harus menunggu lama di Polda Metro Jaya karena lemari di mana mereka menyimpan SIM saya kuncinya tidak ada, dimarahi petugas SAMSAT karena saya memberikan dokumen menggunakan tangan kiri, hingga dihentikan ketika sedang berkendara dan dilepaskan kembali tanpa alasan.
Akan tetapi, apa yang saya alami tidak menyebabkan trauma yang luar biasa seperti yang dialami Lydia dan ketiga orang anaknya. Trauma tersebut diperburuk dengan pembelaan Polres Luwu Timur menggunakan akun Instagram mereka @humasreslutim pada hari Rabu, 6 Oktober 2021. Melalui Instagram Story, pihak kepolisian Luwu Timur bersikeras bahwa kisah Lydia adalah berita palsu atau hoax. Selain itu, mereka turut bercerita melalui Instagram bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan ketiga anak Lydia mengalami pemerkosaan oleh ayah mereka. Bahkan, identitas Lydia yang sebenarnya dibeberkan begitu saja lewat story tersebut.
Tidak hanya terkesan arogan, pembelaan institusi resmi negara seperti Polres Luwu Timur melalui Instagram Story terlihat sangat remeh. Seolah-olah trauma yang dialami oleh korban tidak berarti sehingga ditepis melalui cerita di media sosial yang akan menghilang dalam jangka waktu 24 jam saja. Sebagai pekerja profesional, saya paham bahwa penanganan krisis ada kalanya butuh disebarluaskan melalui konferensi pers atau surat resmi. Sayangnya, Polres Luwu Timur tidak memiliki pola pikir yang sama seriusnya.
Daripada melanggengkan citra menggoda perempuan muda dengan berkata ‘pacarmu bisa gini gak?’ sembari mengangkat senjata atau menyebutkan nominal penghasilan tetap yang tidak seberapa, mungkin ada baiknya pihak kepolisian mulai berpihak pada korban kekerasan seksual yang melapor dan menuntut keadilan, agar yang dapat mereka sombongkan bisa lebih berarti daripada pamer bedil dan gaji.
Darurat Kekerasan Seksual, Sahkan RUU PKS!
Hal pertama yang terlintas di pikiran saya ketika membaca kisah tragis Lydia dan ketiga anaknya adalah kebutuhan negara akan aturan hukum yang berpihak pada korban. Apabila Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disahkan, tentu aparat penegak hukum harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan tidak menyenangkan yang dialami Lydia dan ketiga anaknya selama melapor dapat dihindari.
Jika masih ada yang tidak paham dan menuduh RUU PKS menyosialisasikan hubungan sesama jenis, seharusnya mereka paham bahwa undang-undang ini melindungi korban dari berbagai jenis kekerasan seksual. Salah satunya adalah penetrasi penis ke anus seperti yang terjadi dan melukai anak-anak Lydia. Pemerkosaan tidak sebatas penetrasi penis ke vagina saja. Buktinya, pada 2016, ada perempuan yang diperkosa menggunakan gagang pacul hingga meregang nyawa. Ini adalah bukti bahwa kekerasan seksual adalah legitimasi kekuasaan si pelaku dan tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual.
Indonesia mungkin masih butuh waktu untuk membenahi sikap dalam membela korban kekerasan seksual. Mungkin masih banyak Lydia-Lydia lain di luar sana yang menunggu adanya sikap adil dari aparat penegak hukum negara dalam membantu mereka. Dengan tersebar luasnya kasus ini, semoga negara segera berbenah dan sadar bahwa sudah saatnya mereka bersikap manusiawi kepada warganya sendiri.




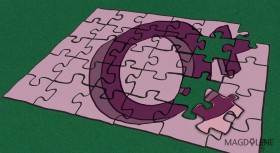


Comments