Sebagai medium interaksi antara sesama pengguna, media sosial dimanfaatkan warganet untuk menyampaikan informasi dari mulut ke mulut, atau word of mouth, termasuk keluh kesahnya saat berkunjung ke kafe maupun restoran yang tak jarang berujung viral. Apalagi warganet punya kebiasaan minta spill cerita kurang mengesankan, dan “didiskusikan” di akun-akun confess.
Misalnya, beberapa waktu lalu saat seorang pengguna TikTok mengunggah video wajah seorang staf di tempat makan karena pelayanannya dianggap buruk. Melalui kolom komentar, ia menegaskan tindakan tersebut sah-sah saja lantaran sekarang “zamannya media sosial” dan sudah selayaknya yang melakukan kesalahan dirundung banyak orang.
Ada alasan mengapa orang senang berkoar-koar soal buruknya layanan restoran di media sosial. Sebuah penelitian berjudul “An Exploration of Consumers’ Online Complaining Behaviour on Facebook” (2013) oleh Doga Istanbulluoglu dari University of Birmingham menjelaskan, alasan pertama warganet lebih suka komplain di salah satu platform media sosial dibandingkan secara tatap muka ke manajer restoran adalah adanya keyakinan si konsumen bahwa perusahaan tidak akan merespons keluhannya. Ini membuat responden penelitian Istanbulluoglu memanfaatkan Facebook sebagai platform berkomunikasi dengan pengguna lain soal restoran yang dikeluhkannya, bukan perusahaan. Kedua, jika perusahaan responsif terhadap keluhan mereka di Facebook, mereka menggunakannya untuk menyampaikannya secara langsung.
Perbedaan di antara keduanya terletak pada tingkat ketidakpuasan konsumen, apakah keluhannya terkait permasalahan yang tergolong berat atau tidak. Namun, sekecil apa pun persoalannya, konsumen tetap memilih komplain di media sosial karena tidak membutuhkan usaha lebih.
Baca Juga: Kekeyi dan Tajamnya Lidah Warganet di Media Sosial
Berpotensi Mematikan Bisnis
Sambatan di media sosial itu bisa mematikan bisnis, terlebih jika mendapatkan perhatian warganet yang berbondong-bondong melakukan cancel culture pada tempat makan tersebut.
Peristiwa itu pernah dialami Rumah Sekara, sebuah kafe di Bandung yang viral usai baristanya mengunggah konten TikTok tentang reaksi mereka setiap konsumen mengucapkan “espresso” menjadi “expresso”. Tentu warganet tidak tinggal diam, mereka memberikan ulasan buruk berupa bintang satu dan komentar penuh kritikan.
Dilansir Eater, tindakan seperti itu adalah sebuah kesalahan karena dapat menghambat restoran dalam memperbaiki kesalahannya. Maka itu enggak heran, ulasan Google beberapa waktu lalu menunjukkan kafe tersebut tutup permanen.
Michael Luca, seorang akademisi di Harvard Business School, AS dalam penelitiannya berjudul “Reviews, Reputation, and Revenue: The Case of Yelp.com” (2011) menuturkan, peningkatan satu bintang pada Yelp—situs ulasan berbagai fasilitas seperti restoran, salon, hingga kelab malam—dapat meningkatkan penghasilan sebesar lima sampai sembilan persen.
Ini menunjukkan ulasan konsumen yang disampaikan lewat daring, berkontribusi dalam pembentukan reputasi sebuah bisnis. Terlebih sebagai warganet, kita sering merujuk pada ulasan di media sosial atau aplikasi aggregator restoran sebelum berkunjung.
Baca Juga: Zara dan Keributan Warganet yang Tidak Perlu
Konsekuensi Kriminalisasi Jika Sebarkan Komplain di Media Sosial
Sebetulnya enggak ada salahnya konsumen mengeluhkan pengalaman makan di sebuah restoran lewat media sosial, toh sekaligus menginformasikan ke calon pengunjung lain kalau tempat itu worth it dicoba. Dengan catatan, komplain dilakukan secara etis.
Dalam hal ini, media sosial terbukti mampu “memperbaiki hubungan” antara pihak restoran dan konsumen. Contohnya kehadiran akun @_sadfood di Instagram yang menampung kekecewaan warganet, terhadap makanan yang mereka pesan, dari segi harga, rasa, porsi, maupun presentasinya.
Lewat akun tersebut, banyak keluhan konsumen yang direspons pihak restoran. Misalnya memberikan kompensasi berupa produk gratis, mengirimkan video cara memasak agar konsumen mengetahui penyebab bentuk makanannya yang kurang layak, hingga menambahkan porsi untuk pesanan berikutnya.
Selain itu, sebagai konsumen, kita memang punya berbagai hak. Beberapa di antaranya ialah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Hal ini sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya di pasal 4.
Kendati demikian, dalam realitas saat hendak memperjuangkan hak ini, konsumen di Indonesia mesti berhadapan dengan risiko dikriminalisasi lewat UU yang lebih anyar, yakni UU ITE saat mereka komplain di media sosial.
Kejadian ini pernah dialami oleh Prita Mulyasari pada 2008. Usai memeriksakan kesehatannya, ia mengeluhkan pelayanan RS Omni Internasional lewat email yang tersebar. Akibatnya, ia dinyatakan melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pasal tersebut berbunyi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, dan memiliki muatan pemerasan/pengancaman.”
Selain Prita, ada juga Stella Monica Hendrawan, seorang konsumen klinik kecantikan asal Surabaya yang curhat di media sosial, karena kondisi wajahnya semakin buruk setelah perawatan. Ia dikriminalisasi dengan pasal yang sama yang dikenakan ke Prita.
Di samping itu, dalam kasus pengguna TikTok yang memublikasikan wajah staf restoran tadi, ada isu pelanggaran lain yang sering kali luput dari perhatian. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi, karena gambar diambil tanpa izin yang bersangkutan. Hal ini dapat menciptakan rasa tidak aman dan sudah ada aturan mengenai itu, salah satunya tercatat dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut.
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Alternatif Komplain Selain di Media Sosial
Dalam situsnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memublikasikan panduan menyampaikan pengaduan bagi konsumen. Terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi, yaitu konsumen harus merumuskan terlebih dahulu hasil yang diharapkan dari pengaduan, dan memahami kelebihan kekurangan masing-masing lembaga pengaduan konsumen.
YLKI pun menyarankan konsumen langsung melakukan komplain ke pelaku usaha. Ini merupakan hal penting karena banyak pertikaian timbul akibat komunikasi yang buruk antara keduanya.
Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan kepada Kompas.com, komplain yang disampaikan konsumen di media sosial itu bisa ditangkap berbeda oleh pelaku usaha. Ia pun menyetujui konsumen bisa menunjukkan bukti dari ulasan, tetapi pelaku usaha punya alasannya sendiri dalam menginterpretasikan komplain tersebut, dan membawanya ke UU ITE.
Tulus juga menyampaikan konsumen dapat melakukan pengaduan ke YLKI, dengan syarat sudah ditanggapi pelaku usaha, tetapi direspons kurang baik. Ia pun menilai mengomunikasikan permasalahan ke pelaku usaha lebih ideal daripada mengkritik di media sosial.
Namun, ia dapat memahami alasan konsumen menyampaikannya di media sosial, yakni karena komplain tidak ditanggapi dengan layak oleh pelaku usaha. “Yang penting konsumen menyampaikan sesuai fakta hukum yang jelas, bukan fiktif yang berpotensi fitnah,” tuturnya kepada Okezone.
Walau tak bisa dimungkiri kita dibuat kesal dan kecewa oleh layanan suatu restoran, kita tetap perlu memperhatikan etika saat menyampaikan keluhan. Mengutip Senior Planet, keluhan yang disampaikan dengan tidak sopan cenderung diabaikan karena pelayanan konsumen—dalam hal ini penanggung jawab media sosial, memiliki banyak hal yang harus ditangani. Jika konsumen ingin keluhannya ditanggapi, ia mesti menyampaikannya baik-baik dan secara terus terang.
Kalau seperti itu kan kedua pihak diuntungkan. Permasalahan konsumen ditindaklanjuti dan kemungkinan memperoleh kompensasi, sementara restoran menerima saran membangun untuk memperbaiki kualitas makanan dan pelayanannya, tanpa menerima citra buruk di media sosial.



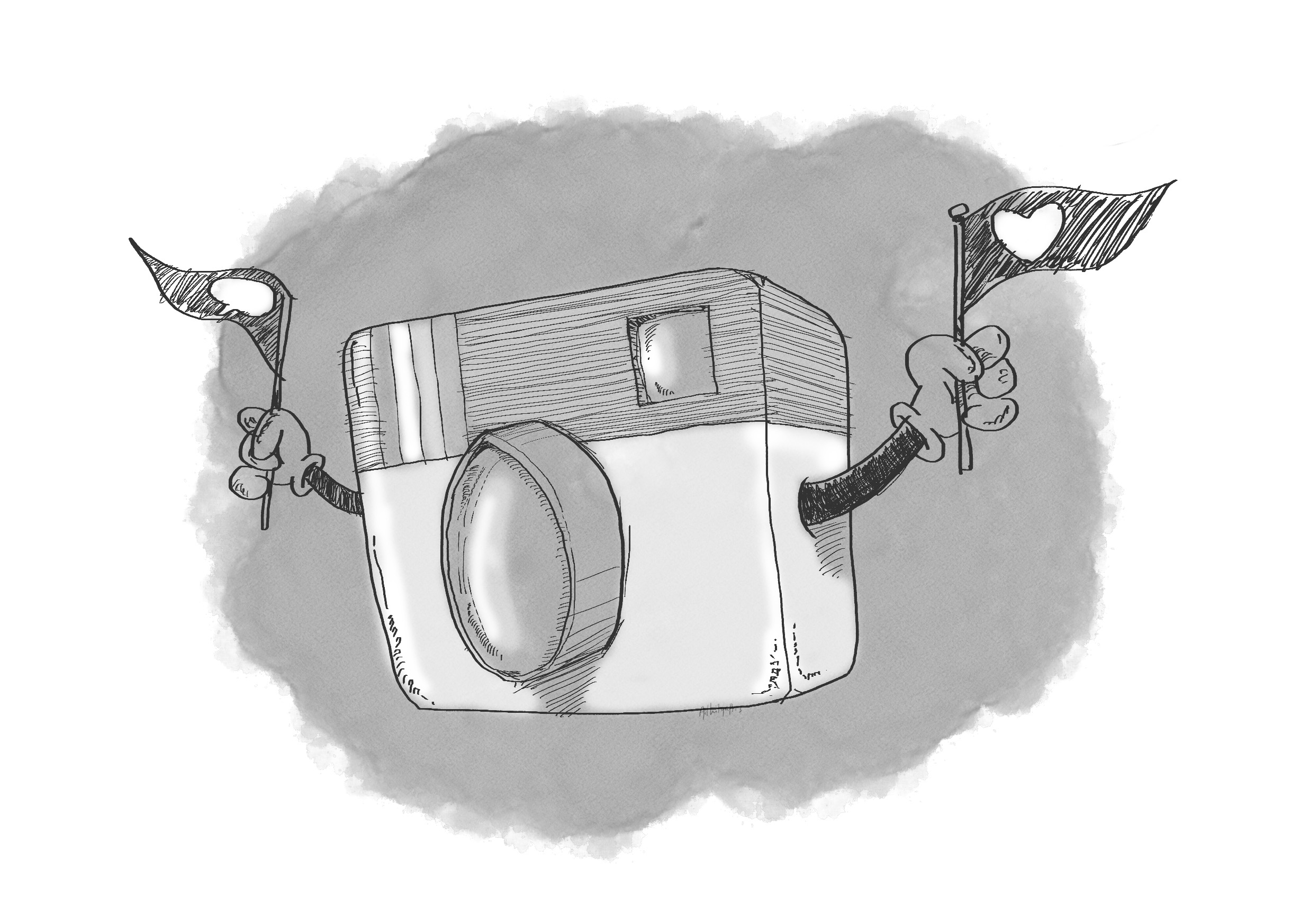




Comments