Sudah beberapa tahun belakangan ini, saya menghabiskan Lebaran hanya berdua dengan ibu saya. Kadang ada beberapa keluarga yang datang, tapi lebih sering tidak. Kami tidak punya tradisi khusus untuk merayakan Lebaran, termasuk foto keluarga. Hal itu pernah membuat saya merasa begitu sedih dan kesepian setiap kali Lebaran tiba.
Bagaimana tidak. Sejak kecil, saya selalu dicekoki potret kalau Lebaran yang menyenangkan hanya bisa dimiliki oleh keluarga yang besar dan utuh. Beranjak remaja, paparan media sosial dan media lainnya membuat anggapan itu terasa semakin nyata. Sedangkan konsep keluarga ideal itu sendiri sangat bermasalah karena kita tumbuh besar di lingkungan normatif yang mendoktrin kalau keluarga itu harus punya kuantitas yang lengkap, besar, dan seragam.
Media sosial yang selalu dibanjiri foto keluarga teman-teman dan kenalan dengan format yang seragam—keluarga besar lengkap dengan kakek, nenek, om, tante dan para anaknya berderet rapi tersenyum ke arah kamera sampai memenuhi satu frame foto—kemudian jadi pemandangan tak asing setiap Idul Fitri tiba.
Baca juga: Kenapa Orang Lebih Mudah Saling Memaafkan Saat Lebaran Dibanding Waktu Lainnya?
Bukan cuma itu. Dari mulai iklan sereal di televisi sampai ucapan mohon maaf lahir batin dari berbagai instansi pemerintah, Lebaran selalu menampilkan jargon bahwa kehangatan hari raya hanya bisa didapatkan kalau kita punya keluarga besar yang bisa kita kunjungi. Hal ini turut melanggengkan anggapan semu soal keluarga ideal yang mengecilkan keluarga-keluarga lain dengan kondisi berbeda.
Sialnya, paparan dari semua itu bertepatan dengan masa ketika orang tua saya baru bercerai. Berbagai tuntutan dan glorifikasi soal Lebaran membuat saya semakin merasa sedih dan terasingkan dari definisi lebaran yang “normal”.
Saya sempat kesal pada ibu saya karena tidak bisa “memberikan” kemeriahan hari rayaLseperti lebarannya teman-teman saya. Alhasil, pada satu lebaran beberapa tahun lalu, saya memaksa ibu saya foto berdua dengan mengenakan gamis. Bahkan saya sudah menyiapkan tongsis (tongkat narsis) alias tongkat panjang yang bisa membantu kita mengambil foto dari jarak yang lumayan jauh, karena kami hanya berdua dan tak ada yang bisa mengambil foto kami.
Foto itu masih saya simpan. Lumayan bagus untuk diposting di Instagram Story pada waktu itu. Tapi belakangan saya menyadari, niat saya sungguh tidak mulia. Saya ingin punya foto keluarga waktu Lebaran hanya agar saya dipandang normal dan seperti teman-teman saya kebanyakan. Padahal, siapa yang membuat aturan kalau Lebaran belum sah tanpa foto keluarga? Seharusnya, Lebaran jadi momen kita bisa saling mengasihi dan berempati, baik terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita.
Baca juga: Jangan Berbasa-basi dengan 6 Pertanyaan Ini
Momen Lebaran untuk Merefleksikan Ragam Bentuk Keluarga
Buat kebanyakan muslim di Indonesia, Lebaran adalah momen yang lekat dan diidentikkan dengan makna kekeluargaan, berkumpul, dan bersilaturahmi. Sayangnya, karena reproduksi pengetahuan soal keluarga ideal yang sudah terlanjur salah kaprah, ditambah dengan kenyataan kalau pada umumnya apa yang kita tampilkan di media sosial itu hanya yang bagus-bagusnya saja, lebaran jadi momen yang diglorifikasi, dengan foto keluarga sebagai salah satu alatnya.
Bukannya memaknai lebaran sebagai hari kemenangan setelah berhasil melawan hawa nafsu selama 30 hari, kita malah cenderung terobsesi untuk menunjukkan kalau kondisi keluarga kita baik atau bahkan lebih baik dari keluarga orang lain. Pose senyum ke arah kamera pakai baju muslim seragam itu bukan jaminan kalau keluarga besar kita sebahagia apa yang kita tampilkan di media sosial, bukan?
Saya sama sekali tidak merasa iri karena orang lain punya keluarga yang lengkap dan harmonis. Saya benar-benar bahagia untuk mereka. Silaturahmi dan kedekatan antar keluarga seperti itu pada kenyataannya adalah hal yang sangat baik dan membahagiakan bila bisa dirasakan. Tapi, kebiasaan ini yang juga mungkin disebabkan oleh Fear of Missing Out (FOMO) sehingga kita terus mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa benar-benar memahami dan mengambil esensinya, justru berkebalikan dengan makna lebaran itu sendiri yang seharusnya penuh kasih pada sesama.
Baca juga: Warisan, Kekuatan Sedekah, dan Kita
Ada beberapa hal penting yang luput kita perhatikan saat Lebaran tiba. Lebaran seharusnya menjadi momentum kita untuk menerima, merefleksikan, dan memaafkan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah momentum untuk mulai membuka mata kita dan menghargai ragam bentuk keluarga. Bisa berkumpul dalam keadaan lengkap dan sehat, serta bisa mempunyai foto keluarga, adalah sebuah privilese yang tidak dimiliki semua orang. Itu adalah hal yang patut disyukuri. Tapi itu tidak lantas membuat orang-orang yang merayakan lebaran dengan cara yang berbeda, atau dengan komposisi yang berbeda, jadi lebih kurang atau lebih buruk dari mereka yang bisa merayakan bersama keluarga.
Lebaran seharusnya menjadi momentum kita untuk menerima, merefleksikan, dan memaafkan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah momentum untuk mulai membuka mata kita dan menghargai ragam bentuk keluarga.
Apalagi, pada situasi pandemi seperti sekarang, mobilisasi kita terpaksa harus terbatas dan dibatasi agar tidak memperburuk keadaan. Hal ini tentu saja membuat banyak orang tidak bisa pulang dan mengunjungi keluarga dan orang-orang terdekat.
Lebaran seharusnya jadi milik semua orang yang merayakannya. Sebagaimana Tuhan yang selalu mengajarkan kebaikan universal dan inklusivitas, saya yakin itu juga adalah hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang di sekitar kita.
Kalau Lebaranmu sunyi dan sepi seperti saya, jangan berkecil hati. Selama kebaikan untuk diri sendiri dan sesama selalu kamu simpan di dalam hati, maka kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri.






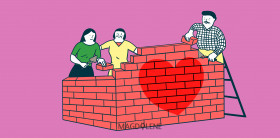
Comments