Mammi sangat melarangku menikah cepat-cepat. Katanya, sebelum memiliki pekerjaan tetap, aku tidak boleh menikah. Mammi wajar berpandangan demikian, ia seorang hakim pengadilan agama yang sering memutus perkara cerai. Mammi menyaksikan bahwa tidak bekerja membuat para istri mempertahankan pernikahannya yang tidak sehat. Mereka memohon pada Mammi untuk menolak permohonan cerai sang suami yang nyatanya telah berselingkuh, atau para istri yang akhirnya menarik gugatan seakan buta dengan lebam-lebam di tubuh mereka yang masih biru. Belum lagi soal gono gini. Harta membuat para istri tak punya harga. Dan betapa tragisnya ketika para istri yang ditinggal pergi tanpa warisan yang berarti.
Mammi sendiri merasa berhasil dengan bekerja. Mammi berhasil lepas dari Pappi yang berselingkuh, membelanjai perempuan lain dengan uang Mammi. Keberhasilannya lepas dari bayang-bayang suami dan menjadi mandiri dijadikannya sebagai pengalaman berharga untuk anak perempuan semata wayangnya ini.
Kalau mengingat nasib burukku, aku sudah tiga kali bermasalah dengan pernikahan. Dua kali gagal nikah, satu kalinya lagi hampir nikah. Pertama dengan Uci saat aku baru selesai wisuda. Kata Mammi aku harus bekerja dulu, dan itu dengan tekanan. Padahal aku sudah memilih-milih warna pakaian seragam dengan teman-temanku. Masih kuingat warna navy blue. Sejak itu Uci merasa ditolak dan selalu mengungkit-ungkitnya saat kami bertengkar. Akhirnya kami putus juga tiga bulan setelah ia melamarku.
Dengan prosesi pernikahan yang tertutup, dia menikahi perempuan yang ia.. ah sudahlah. Kata Mammi, “lo makkebu ana’ tu, de’ na elo ma’bene” (Itu mau buat anak, bukan mau nikah).
Dua tahun setelahnya, kusampaikan niat baik Kak Fauz, yang nama aslinya Fauzi dan biasa dipanggil Uci. Sengaja kuubah panggilannya, karena mengingatkan masa lalu saja. Tak ada lagi temanku yang tahu, takutnya tidak jadi lagi dan memang tidak jadi. Mammi bilang, “Cari kerja mi dulu!”. Namanya bukan jodoh, aku masih menganggur sampai Kak Fauz menawarkan proposal pernikahan pada perempuan lain. Mammi bilang “laki-laki begitu mau ji saja menikah, nda mau berjuang.”
Teman-temanku yang gagal jadi bridesmaid akhirnya tahu juga. Katanya aku banyak rezeki karena membuka pintu jodoh mantan-mantanku. Padahal kalau banyak rezeki seharusnya aku yang nikah, bukan mereka. “Tunggu tanggal mainnya,” mereka menghibur.
Mendengar sudah dua orang yang ditolak lamarannya, keluarga Pappi mengambil inisiatif. Aku dijodohkan dengan anak dari kakak ipar sepupunya anaknya sepupunya adik iparnya indo, mamanya Pappi. Katanya keluarga, yah keluarga dari mana, orang hubungannya eksternal semua.
Baca juga: Aku Bohong pada Ibu
Dijodohkan tidak masalah, kalau ada waktu untuk berkenalan. Aku ikut alur saja. Tapi sejak awal aku sudah tahu kalau perjodohan ini tidak mudah, meski aku sudah bekerja. Sebenarnya Mammi masih membangun silaturahmi dengan Pappi sekeluarga. Ia masih bisa tersenyum. Tapi senyumnya tidak mengisyaratkan apa pun yang berarti. Termasuk ketika keluarga Pappi mencoba melunakkan hati Mammi untuk setuju. Tapi Mammi sangat jelas menolak, tidak tanggung-tanggung, ia minta uang panaik untuk pesta Rp250 juta, ditambah sompa (mahar) berbentuk tanah. Mundurlah anak orang.
Keluarga Pappi berang. “Pettu peru pa Mammimu, sampai hatinya ibumu.” Aku ikut alur saja, walaupun sedikit waswas karena ini sudah tiga kali. Mammi ikut menyindir, “Elo ande de’ na elo eco, mau makan tidak mau berusaha.”
***
Saat aku telah bekerja dan Mas Farid membicarakan pernikahan, kuteruskan lagi itikad baik seorang lelaki pada Mammi. Tapi Mammi tidak langsung memberi jawaban. Seminggu kemudian kutanyai lagi, tapi beliau bilang, nanti.
“Mungkin Mammi ta’ tidak suka sama saya!” kata Mas Farid.
“Tidak, memangnya Mas itu Pappi.”
“Atau mungkin karena saya orang Jawa?”
“Tidak, Mammi nda rasialis.”
Aku mulai memikirkan omongan Mas Farid. Bisa saja Mammi rasialis, merasa suku Bugis lebih terhormat. Kutanyai lagi Mammi soal Mas Farid, dan beliau bilang, “Cari kerja yang tetap dulu!”. Ternyata Mammi bukan hanya ingin aku bekerja, tapi ia ingin aku menjadi abdi negara. Mammi bilang bahwa keberhasilannya ketika aku telah mendapatkan pekerjaan yang pasti, yaitu menjadi PNS sepertinya. PNS memang selalu menang di wilayah ini.
“Mammi, jaman sekarang orang nda harus ji jadi PNS.”
“Jadi apa pade?”
“Ya, bisa jadi pegawai swasta toh. Sekarang gajiku lebih besar dari temanku yang tahun lalu jadi PNS, ada tunjangannya, ditanggung ji juga BPJS-nya.”
“Ada dana pensiunnya?”
“Yah, nnddaa ada.”
Mammi terdiam tampak merasa menang.
“Tapi siapa juga yang mau pensiun dini, Mammi? Masih muda jeka’. Jenjang karierku masih panjang, soal pensiun itu urusan belakangan.”
“Pacarmu PNS atau bukan?” Mammi menanyakan hal yang sudah dia tahu.
“Bukan, tapi gajinya lebih besar dari kakaknya yang sudah sepuluh tahun jadi PNS.”
“Nda ada jaminannya, Nak. Perusahaanmu itu tidak bisa na jamin kehidupan keluargamu setelah kau mati”.
Mammi pergi meninggalkanku menuju dapur.
Baca juga: Antara BH, Drakor, dan Jemuran Kos
***
Permintaan Mammi itu kuteruskan pada Mas Farid. Umur kami berdua belum melewati batas maksimum untuk menjadi PNS, tapi Mas Farid tidak tertarik. Dia sangat nyaman menjadi programmer perusahaan startup, pekerjaan yang tidak dimengerti Mammi.
Aku sendiri sebenarnya menyerah. Sudah tiga kali aku mendaftar PNS, tapi selalu gagal. Mungkin memang karena aku tidak sungguh-sungguh. Sulit membayangkan menjadi pegawai dari pukul tujuh sampai tiga sore dengan lingkungan yang lesu dan kaku, seperti yang kusaksikan di kantor Mammi.
Lagipula aku telah lama memusuhi pemerintah, dan menjadi bagian kecil darinya tentu tidak akan berpengaruh apa-apa pada negeri ini. Malah bisa jadi gaji dari uang rakyat itu kuhabiskan dengan bermalas-malasan di kantor.
Minggu berikutnya kusampaikan hasil diskusiku dengan Mas Farid. Aku bilang pada Mammi, kalau jadi, sampai pada pernikahan kami, Mas Farid masih harus menyelesaikan pekerjaannya dan belum bisa melamar menjadi PNS. Aku sendiri akan ikut tes CPNS. Yang jelasnya kami siap untuk membangun rumah tangga.
“Jadi bagaimana, Mi?”
“Kamu saja, kalau begitu.”
Ternyata alasan-alasanku belum juga meyakinkan Mammi. Kemarin kumaklumi ketakutan-ketakutannya. Tapi itu hanyalah kemungkinan.
“Kenapa ki’ selalu pikir perpisahan kah? Tidak semua orang bercerai Mammi. Tidak semua laki-laki selingkuh, na tinggal anak-istrinya. Kalau begitu ki’, tidak menikah meka’ itu sama laki-laki!”
Aku jengkel dan mulai menangis.
“Kamu saja, kukasih tahu jeko ini.” Suara Mammi meninggi dan kesal.
“Jangan ki’ bilang begitu, tidak direstui ka’ kalau begitu ki’. Kalau nda kita’ suka Mas Farid, bilang ki’.”
“Kusuka ji.”
“Jangan meki’ pade’ persulit ki, orang mau semua anaknya menikah, ini ada lamar anak ta’ tidak mau ki’.”
“Tapi kau anakku, bukan anaknya orang lain! Dan ini tentang kau, bukan tentang calon suamimu! Aro bawang eloku, Itu saja pintaku.”



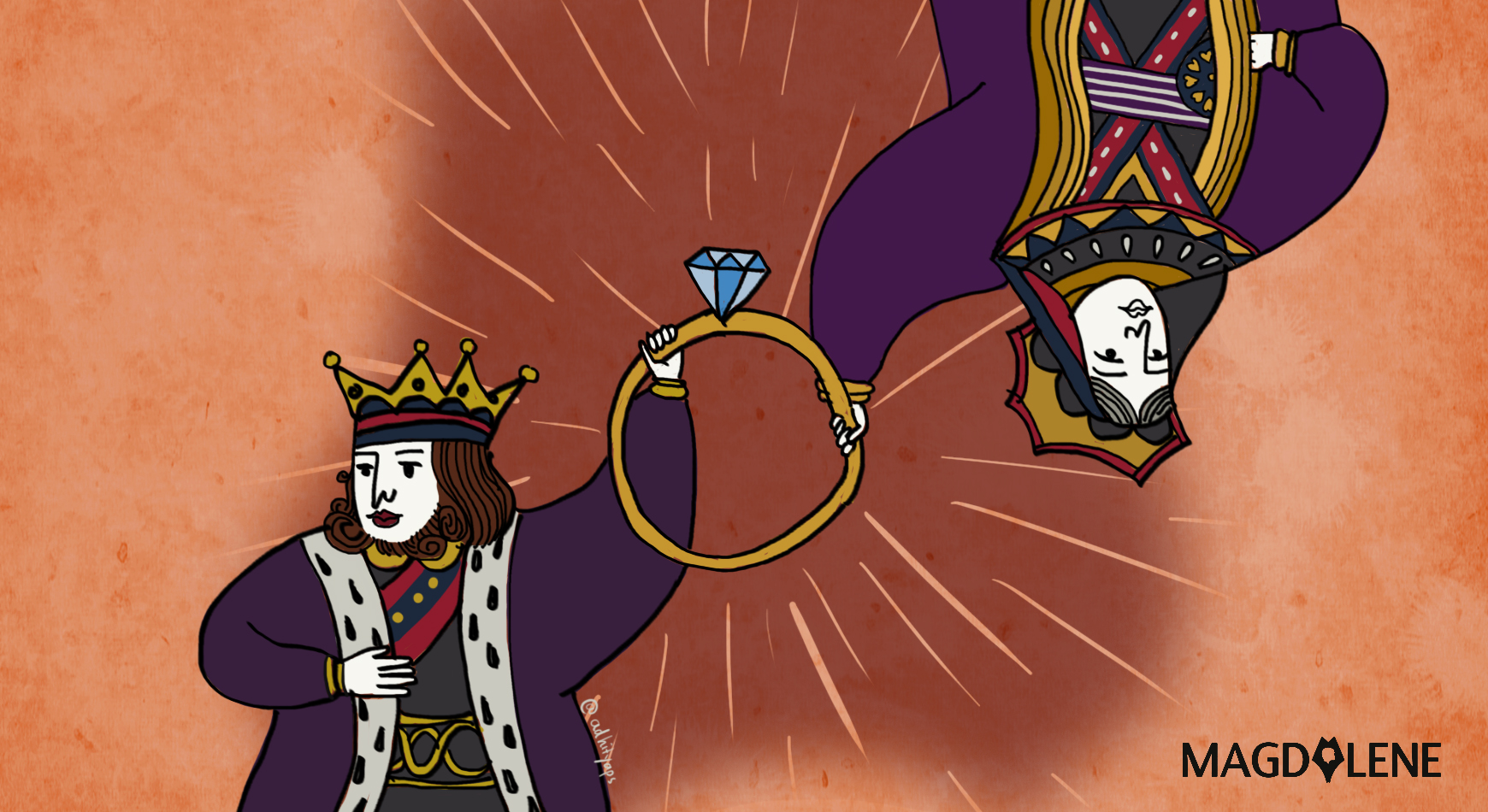



Comments