Sore itu, kami sedang bersantai di dalam ruang tamu yang kecil, di salah satu rumah penduduk yang telah berbaik hati membolehkan saya menumpang selama beberapa hari. Ruang tamu terasa semakin kecil karena banyak warga yang datang untuk sekedar bercengkerama.
Remang cahaya pelita minyak tidak mengurangi kegembiraan kami sore itu. Dari para warga, saya tahu bahwa saat itu bukan musim melaut: perahu tradisional yang tak bermesin terlalu berbahaya untuk digunakan menghadapi ombak besar dan angin kencang. Musim panen singkong, makanan pokok kampung, masih beberapa minggu lagi, sehingga waktu sering dilewati dengan canda gurau seperti sore itu.
Ari mengucapkan salam dari ambang pintu dan para warga pun langsung mempersilakannya masuk. Penampilannya terlihat sangat rapi dan bersih, dengan kaos putih yang dikenakan masuk ke celana jeans agak ketat, berikat pinggang kulit hitam. Kontras, mencolok di antara para warga kampung yang pakaiannya kotor, berdebu tanah kebun atau abu kayu bakar yang digunakan masak sehari-hari. Salah seorang Ibu beranjak ke dapur, agar Ari bisa bergabung bersama kami di ruang tamu.
Kontras semakin kuat terkesan ketika Ari duduk melantai tepat di depan saya. Rambutnya panjang lurus, terawat, diikat ke belakang. Bedak putih tipis membuat wajahnya terlihat lebih cerah dari pada warna kulit tangannya. Bibirnya bergincu merah. Dengan senyum dan suara ramah, Ari menanyakan beberapa pertanyaan umum, seperti dari mana asal, apa tujuan dan berapa lama saya akan tinggal di kampung.
Pembicaraan kami ringan mengalir, walau tidak ada topik khusus. Dia menanyakan apa saja makanan yang telah saya coba dan apakah saya menyukai makanan tersebut. Singkong dan ikan sangat enak, jawab saya dalam bahasa lokal, diikuti gelak tawa mereka. Ari bercerita bahwa dia belum pernah ke Jakarta dan menanyakan seperti apa kehidupan di ibu kota, apa benar seperti yang terlihat di televisi? Saya menyampaikan kekaguman terhadap keindahan pulau, dan terutama pada keramahan warga kampung. Ari bilang belum pernah ada orang dari Jakarta yang datang ke kampung ini, dan mengeluhkan sulitnya transportasi bahkan untuk ke kota terdekat. Jalan masih banyak yang rusak, orang-orang lebih suka pakai perahu kecil dari pada lewat jalan darat.
Tiba-tiba salah satu warga menyela. "Ari ini beda loh. Cantik. Sukanya sama laki-laki", yang kemudian disambut tawa oleh yang lain. Dalam diam, saya mencoba memerhatikan bagaimana Ari akan bereaksi. Terlihat sedikit terusik, ia membalas dengan santai, "Apaan sih?" dan kami pun melanjutkan pembicaraan seolah tidak terjadi apa-apa.
Kira-kira setelah satu setengah jam, Ari permisi pulang. Warga lain mempersilakan dengan sopan, dan Ari mengundang saya untuk berkunjung ke rumahnya. Sayangnya hal itu tidak kesampaian – kami hanya sempat berpapasan lagi satu kali setelah pertemuan sore itu, di tengah jalan di tengah kampung. Masih dengan penampilan yang sama, Ari dengan nyaman menceritakan kegiatannya hari itu.
Pengalaman tersebut cukup membekas, dan juga menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana bisa, Ari tampil begitu mencolok dengan begitu bebasnya? Di daerah terpencil seperti ini, Ari harusnya sembunyi di balik norma dan nilai yang dipegang kuat oleh para penduduk.
Bukannya malah berani berdandan, lalu berinteraksi dengan warga kampung, seolah tidak takut pada tuduhan ‘mengganggu ketenteraman umum’ atau ‘memberi pengaruh buruk’ bagi anak-anak.
Mengapa juga tidak ada yang mencemooh, baik di depan atau setelah Ari pulang? Hanya satu kalimat yang membahas mengenai kontras
pribadi Ari. Selain itu, Ari diperlakukan dengan begitu sopan dan hormat oleh para penduduk, seolah telah menjadi bagian kehidupan normal kampung terpencil tersebut.
Pertanyaan tersebut, sedikit banyak terpengaruh oleh pemberitaan dan pengalaman orang-orang LGBT lain seperti Ari yang terjadi di kampung-kampung lain dan di Jakarta, cerita-cerita yang lebih banyak bernuansa negatif dan diskriminatif. Atau ini mungkin karena asumsi bahwa keterbukaan, kebebasan dan perbedaan seperti Ari merupakan suatu pengaruh budaya dan produk ideologi Barat.
Mungkin baru bisa paham sepenuhnya, jika saya kembali dan menghabiskan waktu lebih lama di kampung itu, bersama Ari dan para warga.
Tapi setidaknya sekarang saya tahu, walau sering luput dari perhatian, akar rumput dapat memberi ruang bagi perbedaan.
Denny Firmanto Halim adalah penulis dan penerjemah lepas, serta peneliti bagi Reality Check Approach, suatu metode yang fokus pada pemahaman realita masyarakat umum dalam konteks mereka sendiri. Info lebih lanjut, lihat: http://www.reality-check-approach.com






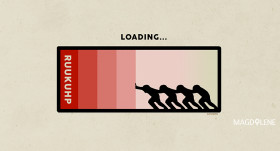

Comments