Yang helainya kini tak tujuh ribu lagi
Belasan, hingga puluhan ribu membentang negeri
Entah jiwa mana lagi yang dicabik
Entah raga siapa lagi yang diusik
(“Di Negeri Tujuh Ribu Rok, Aku Terhenti” oleh Zubaidah Djohar)
Hari ibu adalah hari yang tepat bagi kita mengenang pahlawan perempuan yang sedikit sekali disebut dan diabadikan dalam sejarah. Rupa-rupa penyebabnya mulai dari penulisan sejarah yang terlalu maskulin, syarat pahlawan yang juga maskulin (maju perang dan agresi), atau memang sengaja dilupakan seperti Hari Ibu yang direduksi jadi Mother’s Day.
Hari Ibu pada 22 Desember adalah hari feminis. Feminis yang berarti membela hak asasi manusia dan melawan penindasan. Ibu adalah retorika yang digunakan oleh kelompok perempuan politis pada zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1920 supaya tidak dicurigai oleh pemerintah kolonial yang semakin represif terhadap gerakan anti kolonialisme. Dengan semangat melawan penindasan dan memperjuangkan hak asasi manusia, pada Hari Ibu kali ini saya ingin berkisah tentang seorang perempuan feminis dari Aceh yang telah memimpin gerakan global World Clean-Up Day 2018 dan berhasil menggerakkan tujuh juta orang di seluruh Indonesia. Banyak pemimpin seperti Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo berada dalam arahannya yang sederhana: membersihkan bumi dengan landasan cinta kasih.
Rumahku dihancurkan dengan pekik takbir
Perempuan itu bernama Agustina Iskandar. Di balik semangatnya dalam mengelola gerakan global tersebut dia masih menyimpan luka yang belum sembuh dari kampungnya—sebuah kejahatan kemanusiaan yang belum selesai. Ia tumbuh besar dengan menyaksikan kekerasan di sekelilingnya. Pada 2011, ia menghadapi persekusi dari sekelompok orang di kampungnya dengan tuduhan penyebaran ideologi Barat dan ilmu sesat, dan keluarganya dituduh kafir. Hingga saat ini kasusnya masih menggantung dan tidak kunjung selesai. Agustina berkali-kali berusaha bangkit dari rentetan kekerasan yang dialami selama tinggal di Aceh dan itu bukan perkara mudah. Percobaan bunuh diri pernah dilakukan, trauma itu di sana. Ada dan berkepanjangan. Dan untuk bisa sanggup bercerita kepada orang lain adalah sebuah upaya yang berat.
Agustina, 29, lahir dan besar di Aceh. Ia mengalami masa darurat operasi militer (DOM), tragedi tsunami, dan pembangunan ulang hingga transformasi Aceh menjadi provinsi syariat dengan puluhan perda diskriminatif terhadap perempuan.
Tumbuh di tengah konflik militer sungguh tidak mudah. Saat kecil, Agustina terpaksa berpisah dengan orang tuanya demi alasan keamanan. Dia dan beberapa sepupunya tinggal bersama nenek dan kakeknya di sebuah kampung di kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Pada masa darurat militer, kekerasan sudah jadi makanan sehari-hari di Aceh, apalagi untuk perempuan. Pemerkosaan oleh tentara atau keluarga dekat, pemaksaan jilbab melalui razia “botak” oleh aparat, bahkan menyaksikan mayat kerabat atau kepala teman dekat yang dipenggal adalah pengalaman yang dekat dengan Agustina dan anak-anak lain di daerah ini. Anak-anak tumbuh dengan kekerasan dan bukan berarti mereka jadi banal dan terbiasa. Mereka hanya merepresi luka-luka dan trauma jauh ke dalam dan tidak pernah sanggup untuk dibicarakan.
Sejak kecil Agustina suka membaca. Neneknya sempat khawatir dengan kegemaran cucunya itu sehingga Agustina harus membaca secara diam-diam. Dalam wawancara dengannya baru-baru ini, dia menuturkan bahwa dia membaca saat sedang menggembala kambing. Nenek berkata buku yang wajib dibaca hanya kitab suci Alquran dan buku-buku agama. Demi menghindari konflik dengan neneknya akhirnya Agustina mengundang anak-anak lain di kampungnya ikut membaca dan mengaji di rumah. Supaya dia tidak seorang diri dimarahi.
Satu, dua, dan beberapa anak tetangga yang singgah diajarkan membaca dan mengaji sehingga rumah tersebut menjadi sanggar baca. Tempat seperti itu menjadi sebuah hiburan untuk anak-anak yang telah melalui hidup penuh kekerasan. Membaca adalah rehat dan pelarian. Membaca menanamkan harapan supaya konflik itu berakhir. Selain membaca, mereka juga menghibur diri dengan menyanyi dan menari.
Namun kegiatan budaya tersebut tidak disukai oleh petinggi di kampung itu. Menurut mereka, apa yang Agustina lakukan adalah mengajarkan anak-anak kampung itu menjadi kebarat-baratan. Para petinggi kampungnya tidak suka Agustina membuat taman baca hingga hari itu tiba.
Hingga saat ini, Agustina mengatakan bahwa dia sangat trauma dengan kata Allahu akbar yang diucapkan keras-keras. Karena kata tersebut diteriakkan oleh sekelompok massa yang menghancurkan rumah dan sanggar bacanya hingga cuma tersisa puing-puing, dan hampir menewaskan nenek yang sedang salat Isya di dalam rumah. Peristiwa itu terjadi pada Kamis malam, 13 Januari 2011. Dimulai dengan melemparkan batu ke kaca-kaca jendela sambil memekikkan takbir, kemudian massa membakar rumah hingga tinggal tersisa puing-puing. Kandang sapi berikut isinya dan hewan ternak lain ikut dibakar. Mereka bilang merampas tempat tinggal dan tempat taman baca anak-anak adalah jihad.
Seluruh kampung dan orang tua anak asuh yang tinggal sebagai tetangga dipaksa ikut menandatangani lembar pengusiran atau rumah-rumah mereka pun akan ikut dibakar. Mereka mencari Agustina, “Mana itu cucunya biar ikut dibakar sekalian!” dan beruntung dia sedang tidak berada di kampung. Salah seorang sepupu meneleponnya untuk tidak pulang.
“Dari belakang telepon aku mendengar suara teriakan Allahu akbar bersahut-sahutan, aku enggak tau gimana nasib aku kalau aku ada di sana,” ujar Agustina pada saya.
Cut Nyak yang tidak bisa pulang
Esok harinya, ketika situasi sudah mulai tenang, Agustina datang ke rumah dan sanggar yang sudah hancur. Anak-anak didiknya hadir menatapnya dengan tatapan nanar. Mereka merasa bersalah karena orang tua mereka tidak mampu membela. Agustina menenangkan mereka dan mengucapkan, “Jangan menyerah”, di atas fondasi rumah yang sudah hancur. Seseorang yang menemukan Agustina dan kisah persekusinya kemudian mengajak Agustina untuk pindah ke Jakarta. Pada tahun 2012 Agustina pergi ke Jakarta dan bergabung dalam organisasi Gerakan Mari Berbagi (GMB). Dia berusaha bangkit dan itu dilakukan dengan susah payah. Banyak malam-malam di mana dia tidak bisa tidur. Suara azan mengingatkan pada kaca pecah akibat lemparan batu, dan pria berbaju putih terlihat mengancam buatnya.
Di GMB, menurut Agustina, dia belajar menyembuhkan luka-luka dan trauma melalui meditasi dan aktif dalam organisasi yang mengutamakan kecintaan terhadap bumi. Agustina juga melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan di Aceh: menggunakan pakaian yang dia inginkan tanpa ada tekanan dari penguasa, dan bercengkerama dengan anjing, makhluk ciptaan Tuhan yang juga dinistakan di Aceh. Tapi dia terus mendapat tuduhan “kafir” dan ancaman pembunuhan dari sejumlah pihak di Aceh. Semua akibat kepemimpinannya dan kritiknya terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan di Aceh. Banyak kalangan di Aceh yang tidak bisa menerima Agustina karena dia berbeda dan seorang perempuan untuk jadi pemimpin. Ia mendapat ancaman secara langsung maupun lewat media sosial. Agustina sebetulnya ingin pulang dalam waktu yang lama tapi itu bukanlah pilihan. Dia ingin tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa. Dia ingin ganti KTP tapi dia tahu akan sulit mengurus banyak hal administratif karena bagi sejumlah tokoh di Aceh, ujarnya, darah Agustina hukumnya “halal”.
Persekusi yang dialaminya menunjukkan bahwa masih ada yang tidak bisa menerima jika warganya punya kesadaran untuk membaca dan sanggar baca itu diinisiasi seorang perempuan. Membaca memberikan imajinasi tentang kebebasan. Kebebasan dan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Cut Nyak Dien pada abad ke-18 supaya rakyatnya bisa melawan penindasan kolonial dan mengakhiri kekerasan di tanah rencong. Hari ini, kekerasan tidak dilakukan oleh kolonial berkulit putih tapi oleh petinggi Aceh dengan pola yang sama, yakni kekerasan kepada rakyat. Setelah ratusan tahun berselang, penguasa masih takut pada pemimpin perempuan.
Terkait dengan kepemimpinannya sebagai perempuan, Agustina mengajarkan saya tentang gerakan pembersihan lingkungan hidup yang dia inisiasi.
“Dengan kegiatan World Cleanup ini kamu enggak akan ditanya agamamu apa saat lagi mungut sampah oleh orang sebelahmu kan?” katanya.
Kebencian memang mudah menggerakkan manusia untuk saling membunuh, tapi gerakan sosial bersih-bersih lingkungan dilandasi oleh cinta, ujar Agustina.
“Cinta memberikan alasan perjuangan. Kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, meminum air yang sama dan memiliki cinta yang sama untuk bumi ini, makanya kita berjuang,” tambahnya.
Agustina mengatakan ada banyak perempuan Aceh yang saat ini masih dihantui oleh kekerasan tapi masih belum bisa bercerita. Butuh waktu untuk merasakan kembali semua perasaan perih yang bertahun-tahun direpresi. Agustina adalah pahlawan perempuan yang negeri Aceh tidak punya karena Aceh belum pantas mendapatkannya.
Selamat Hari Ibu, Agustina.
Baca tentang feminisme dalam gerakan emak-emak militan.



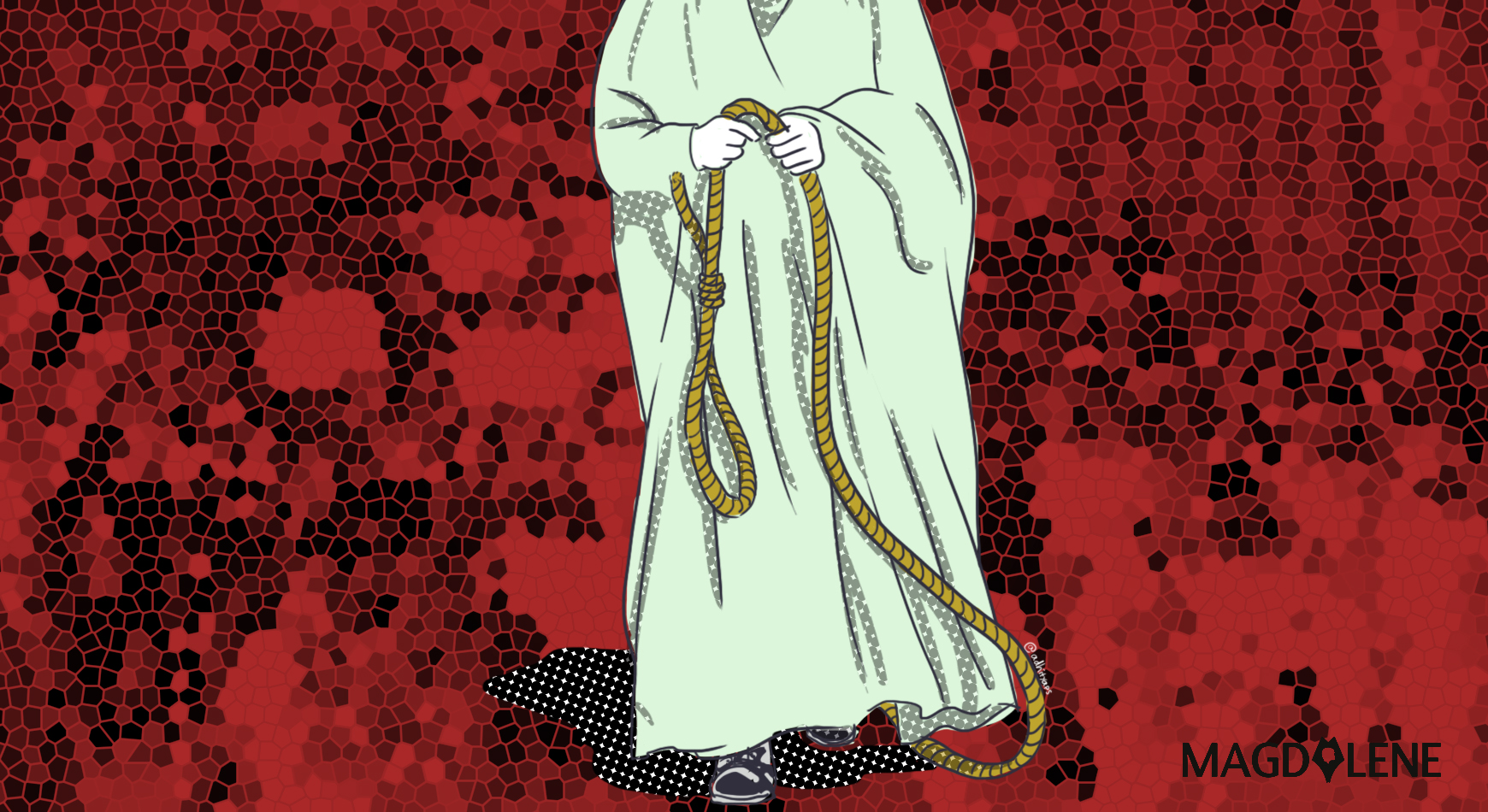

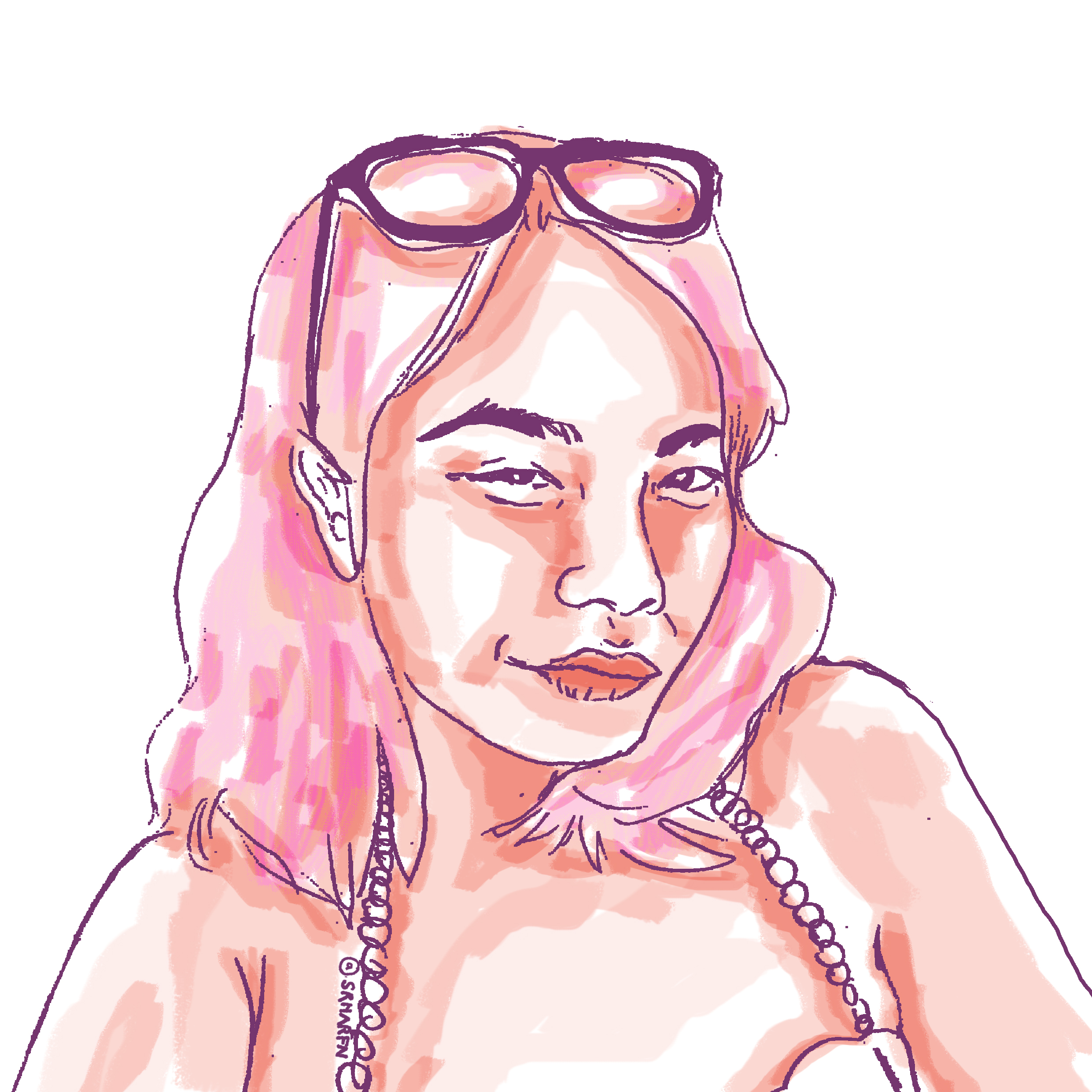



Comments