Tanggal 21 April saban tahun, media daring kita dijejali berita yang berisi puja dan puji soal Kartini. Sosok yang oleh Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja (1962) disebut sebagai peletak dasar pemikiran modern pertama sekaligus pejuang emansipasi perempuan, direpetisi oleh berita hari-hari ini.
Kartini dielu-elukan karena jasanya memperjuangkan kesetaraan gender. Anak bangsawan Jepara yang mati muda ini kerap berbicara tajam lewat surat-suratnya pada Stella dan Nyonya Abendanon, sahabat penanya. Ia mengkritik feodalisme yang melanggengkan penindasan atas akar rumput dan perempuan. Ia juga mengecam kolonialisme Belanda dengan kerja-kerja paksa dan melucuti rakyat lewat pajak tinggi, sehingga mereka tak berdaya.
Ia juga menyoroti praktik poligami dan perjodohan yang menurutnya sangat merendahkan martabat perempuan. Urusan pendidikan pun ia kuliti, lantaran alpa memberi ruang bagi kelompok marginal, seperti rakyat miskin dan perempuan, untuk mengaksesnya.
Ya, Kartini adalah pahlawan, setidaknya versi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964. Meskipun biasanya penunjukan pahlawan dalam tiap rezim selalu tendensius. Seperti Soekarno yang membangun pemahaman bahwa pahlawan nasional adalah mereka berlatar ideologi Nasakom (Nasionalis, Agamam dan Komunisme), juga yang vokal saat pergerakan nasional dari abad ke-19 hingga abad ke-20. Kartini dalam hal ini adalah salah satunya, dan rasa-rasanya saya harus sepakat dengan penunjukannya itu.
Namun saya sendiri lebih senang menganggap Kartini sebagai manusia biasa, alih-alih pahlawan bangsa, panteon bagi gerakan perempuan, atau pemikir yang melampaui zamannya. Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat Kartini jadi karakter yang lebih manusiawi di mata saya.
Pertama, ia menanggung beban patriarki karena terpaksa menelan pil pahit poligami dari Bupati Rembang. Padahal, dalam surat-suratnya, yang pertama kali diterbitkan jadi buku bertajuk Door Duisternis tot Licht (DDTL) pada 1911 atas prakarsa Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, Mr. J.H. Abendanon, sudah ada uraian terperinci soal betapa besar penolakan Kartini terhadap praktik poligami.
Baca juga: 5 Alasan Mengapa Pola Pikir Kartini Masih Relevan Hingga Kini
Kepada Stella, ia menyebut:
"Saya tidak akan, sekali-kali tidak akan jatuh cinta. Karena mencintai seseorang, menurut hemat saya, pertama-tama harus ada rasa hormat. Dan saya tidak bisa menghormati seorang pemuda Jawa. Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah, yang apabila sudah bosan kepada istri dan anak-anaknya, dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah ..."
Dengan nada yang sama, ia juga bercerita kepada sahabatnya yang lain, Nyonya Abendanon-Mandri, seperti yang dilansir dari gubahan kedua “DDTL” versi Armijn Pane yang diberi judul “Habis Gelap Terbitlah Terang” (1922). Ia menyebut di suratnya:
“Bukankah hal ihwal itu merupakan perkosaan terhadap kodrat alam, apabila perempuan harus tinggal secara damai dengan madunya? Sesungguhnyalah, anak bangsa itu sendiri, kaum perempuan harus memperdengarkan suaranya. Masih akan adakah orang dengan tenang mengatakan bahwa "keadaan mereka baik-baik saja", kalau mereka melihat dan mengetahui semuanya yang telah kami lihat dan ketahui sendiri? Saya pernah mengutip sesuatu dari pidato Prof. Max Muller, seorang ahli bahasa-bahasa timur yang ulung dari Jerman, yang juga ahli sejarah dan lain-lain. Bunyinya kurang lebih: Poligami seperti yang dijalankan bangsa-bangsa Timur adalah suatu kebijakan bagi kaum perempuan dan gadis-gadis, yang di dalam negerinya tidak dapat hidup tanpa suami atau pelindung. Marx Muller sudah memperlihatkan kebajikan adat itu kepadanya. Orang berusaha membohongi kami, bahwa tidak kawin itu bukan hanya aib, melainkan juga dosa yang besar ...”
Poligami dalam tradisi priayi Jawa saat itu dipandang sebagai kewajaran. Bahkan, dalam tiap suratnya, Kartini melukiskan betapa pemisahan laki-laki dan perempuan didesain sedemikian curam, hingga perempuan harus merangkak-rangkak demi sekadar memenuhi panggilan bapak atau suami. Citra perempuan yang berhasil adalah mereka yang menikah usai rampung menjalani masa pingitan. Perempuan dianggap sempurna jika melahirkan, berbakti kepada suami, dan terampil mengerjakan hal-hal domestik.
Sayangnya, sebagai manusia, Kartini harus menerima kegagalan (menurut dia dalam suratnya. Red) sejak ia dikawini oleh Raden Adipati Joyodiningrat dan diboyong ke Rembang. Suratnya tak lagi segalak saat ia masih percaya bahwa nasib baik akan berpihak padanya. Ia tak sadar, yang tengah ia lawan adalah raksasa besar bernama sistem patriarki dan feodalisme yang memang lebih digdaya dan berakar lama.
Kita sendiri adalah Kartini yang menetapi jalan masing-masing untuk bertahan dan melawan patriarki, feodalisme, dan stereotip, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.
Kartini, perempuan 24 tahun yang tergila-gila dengan buku itu ter(di)paksa mengamini, “ibuisme”, yang merupakan gabungan nilai borjuis kecil Belanda dengan nilai tradisional priayi, adalah keniscayaan yang tak bisa ditolak lagi. Ibuisme di era kolonial, seperti halnya yang berkembang zaman Orde Baru, mendukung tindakan yang diambil oleh ibu untuk mengurus keluarga, kelompok, kelas, perusahaan, atau negara, tanpa menuntut kekuasaan atau prestise sebagai imbalan, seperti yang ditulis Madelon Djajaningrat.
Pada 2011, Julia Suryakusuma melanjutkan uraian Djajaningrat, bahwa “ibuisme” kemudian dipahami sebagai ideologi yang tak hanya mendukung, tapi juga mendefinisikan kaum perempuan dalam kapasitas itu. Jadi kaum perempuan tidak bisa eksis terhadap dirinya sendiri, tetapi selalu berada dalam hubungan dengan sesuatu (keluarga, komunitas, negara) atau seseorang (anak, suami, bapak) yang lain. Kartini dalam hal ini adalah contoh paling konkret, betapa perempuan dikepung oleh kekuatan-kekuatan itu.
Penyebab kedua, yang membuat Kartini tampak manusiawi adalah kenyataan bahwa pendidikan kakak laki-lakinya, Kartono, hingga ke Universitas Leiden, Belanda, ternyata tak mampu membantu Kartini untuk bisa setara. Ya betul, selama dipingit, Kartini banyak memperoleh asupan buku-buku bergizi dari sang kakak. Tapi kendati pikirannya mengembara ke ujung cakrawala, fisiknya tetap disekap di balik tembok Jepara.
Kartini sendiri hanya bisa bersekolah hingga ELS (Europese Lagere School) atau setara sekolah dasar. Namun menginjak 12 tahun, ia “dikerangkeng” dalam pingitan. Sempat terbersit niatan untuk hijrah demi belajar di Belanda seperti kakak laki-lakinya, tapi kandas karena Abendanon menolak permohonan itu dengan alasan ayahnya tengah sakit.
Sebagai gantinya, Kartini diizinkan untuk membuka sekolah bagi perempuan pribumi. Ia memulai kegiatan sekolah sederhananya di beranda belakang rumah dinas Bupati Jepara pada Juni 1903. Murid-murid Kartini belajar membaca, menulis, memasak, kerajinan tangan, menjahit, dan budi pekerti.
Saat akhirnya izin dan beasiswa ke Belanda sudah dikantongi, impian Kartini kembali ambyar karena harus menikah dengan Bupati Rembang yang memiliki tiga selir dan ditinggal mati dua istrinya. Dalam pernikahan itu, sang suami membebaskan Kartini untuk membuka sekolah perempuan di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang.
Baca juga: Kartini Sebagai Kakak Perempuan Panutan
Hal ketiga yang membuat Kartini tampak lebih manusiawi adalah, suaranya nyaring tapi sebenarnya terkungkung. Ia tak bisa mengekspresikan gagasan dan kritiknya secara terang-terangan karena posisinya sebagai perempuan, yang relatif dianggap sebagai subordinat atau klien dalam relasi patronasi. Sebaliknya, ia hanya mencurahkan seluruh pandangannya lewat surat-surat yang tulis pada sahabatnya di Belanda.
Surat-surat inilah yang menurut Soekarno saat memutuskan Kartini sebagai pahlawan nasional pada 1964, sangat revolusioner, kental nasionalisme, dan mengarusutamakan kesetaraan perempuan.
Berangkat dari tiga sebab itu, saya ingin bilang, tak apa memandang Kartini sebagai orang biasa, bukan idola apalagi pahlawan. Pasalnya, yang dialami Kartini di masa itu bukanlah kekhususan karena di zaman sekarang pun, praktik poligami dengan dalih nilai agama atau adat masih jamak dijumpai. Demikian pula dengan terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok marginal termasuk perempuan, ditambah stereotip dan domestifikasi perempuan yang turut menambah panjang umur sistem patriarki. Buruh-buruh masih digebuki, perempuan dilecehkan di jalan, rancangan undang-undang yang pro-perempuan dipinggirkan, dan perempuan dianggap berharga karena selaput dara keberhasilannya membahagiakan suami.
Jika dunia yang kita hadapi masih begini-begini saja, maka saya kira Kartini pun tak akan keberatan jika ia cukup dibingkai sebagai sosok yang lebih manusiawi. Sebab kita sendiri adalah Kartini yang menetapi jalan masing-masing untuk bertahan dan melawan patriarki, feodalisme, dan stereotip, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.





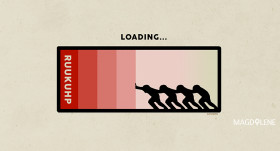

Comments