Kematian Mahsa Amini, 22, akibat penyiksaan yang dilakukan Polisi Moralitas Iran telah memicu aksi massa besar-besaran di seluruh dunia belakangan. Di negara asalnya, aksi protes itu terjadi merata di semua kota dan telah memakan 83 jiwa.
Di beberapa kota besar di dunia seperti Athena, Berlin, Brussels, Istanbul, Madrid, New York, Paris, London, dan Melbourne, para perempuan dari berbagai kelompok turun ke jalan sebagai aksi solidaritas kepada perempuan di Iran.
Kasus Amini berangkat dari aturan ketat kewajiban berhijab bagi perempuan di Iran yang sudah diberlakukan sejak Revolusi Iran 1979. Aturan ini memberlakukan hukuman berat kepada perempuan yang tidak menutup tubuh mereka sesuai dengan Hukum Syariah saat berada di ruang publik dan di dunia maya. Pemaksaan hijab telah menjadi gambaran suram terhadap semua perempuan.
Saya sempat berdiskusi intens tentang insiden ini dengan seorang sahabat dari Iran. Dia mengatakan, demonstrasi besar-besaran di seluruh Iran menunjukkan akumulasi dari segala kesalahan yang dilakukan negara itu selama empat dekade terakhir. Rezim penguasa menggunakan nilai-nilai agama untuk mengontrol tubuh perempuan dan melanggengkan praktik korupsi yang masif.
Pada akhirnya, perempuan di Iran lebih memilih untuk memperjuangkan hak-hak dan kebebasan mereka melalui aksi demonstrasi ini daripada dipermalukan dan dipukuli sampai mati oleh Polisi Moralitas Iran.
Yang membuat saya terhenyak adalah kalimat terakhir yang ia katakan, “Mungkin bagi Iran, sudah terlambat (karena sudah banyak korban jiwa), tapi masih belum terlambat bagi Indonesia”.
Baca juga: Kematian Mahsa Amini: Perempuan Iran Makin Solid Tuntut Perubahan Transformatif
Pemaksaan Hijab di Indonesia
Kematian Amini mengingatkan kita pada rentetan isu terkait aturan penggunaan hijab di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Penggunaan hijab di Indonesia telah lama menjadi simbol identitas politik dan aturan-aturan terkaitnya juga dipengaruhi oleh iklim politik negeri dari waktu ke waktu.
Pada Maret 2021, Human Rights Watch menerbitkan laporan tentang berbagai aturan pemaksaan hijab di sekolah-sekolah negeri dan di kantor pemerintahan. Laporan tersebut merangkum pengalaman korban pemaksaan hijab dalam bentuk penghakiman publik, intimidasi, perundungan dan teror psikologis, yang pada akhirnya membuat para korban trauma.
Upaya pemerintah untuk memitigasi isu pemaksaan hijab di institusi pendidikan pun dipatahkan oleh pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur seragam siswa oleh Mahkamah Agung pada Mei 2021. Sejak saat itu, insiden pemaksaan penggunaan hijab oleh figur otoritas, seperti guru atau senior di tempat kerja, terus menghantui perempuan.
Selain menyebabkan trauma bagi korban, pemaksaan hijab sebenarnya bisa menyebabkan berkurangnya kehadiran di ruang publik, yang pada jangka panjang dapat memarjinalisasi partisipasi perempuan di berbagai bidang.
Kenapa Harus Paksa Orang Lain Berhijab?
Dalam penelitian saya tentang perempuan dan ekstremisme kekerasan di kalangan mahasiswi di tiga kampus di Indonesia, saya menemukan beberapa fakta terkait penggunaan hijab di kalangan perempuan dalam jaringan ekstremisme.
Pertama, di kalangan kelompok ekstremis, berhijab menjadi alat ukur totalitas kepatuhan para perempuan yang ingin bergabung ke dalam kelompok mereka.
Salah satu partisipan penelitian menyampaikan, untuk bisa diterima masuk ke level yang lebih tinggi di kelompok tersebut, ia harus mengenakan hijab yang sesuai dengan “standar” kelompok. Dengan kata lain, kepatuhan dan penerimaan di dalam kelompok ini hanya dapat diukur apabila perempuan menyerahkan kontrol atas tubuhnya kepada kelompok tersebut.
Kedua, secara lebih luas di luar konteks kelompok ekstremisme, hijab ternyata menjadi penanda relasi kuasa. Seperti yang diberitakan di media-media massa, ‘pelaku’ pemaksaan hijab biasanya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, teman-teman sekelas yang didukung oleh guru, serta senior di tempat kerja.
Partisipan lainnya dalam penelitian saya mengatakan, yang memaksa mereka mengenakan hijab sebagian besar adalah orang tua dan keluarga terdekat.
Melalui pemaksaan hijab, figur yang memiliki otoritas tersebut memanfaatkan relasi kuasa dalam masyarakat patriarki, demi mencapai keinginan mereka meraih status sosial di masyarakat melalui glorifikasi kesalehan di ruang publik. Hijab menjadi salah satu ukuran utama dari perilaku religius.
Hijab sebagai bentuk konkret dari perilaku religius bahkan diterapkan menjadi salah satu syarat akreditasi sekolah, sebagaimana yang terjadi pada kasus pemaksaan jilbab di Yogyakarta pada Agustus 2022.
Perilaku religius yang ditunjukkan dengan berhijab ini juga menjadi upaya pihak sekolah untuk mendongkrak “branding image” lembaga mereka agar dapat menarik perhatian para calon murid di masa depan. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya bersekolah di sekolah yang semua muridnya berperilaku religius?
Dengan demikian, terlihat jelas kontrol atas tubuh perempuan pun menjadi instrumen yang digunakan oleh para figur otoritas di sekolah untuk memenuhi kepentingan mereka. Ambisi mereka untuk menampilkan kesalehan di ruang publik itu didapat dari mengontrol tubuh perempuan atas nama nilai-nilai agama.
Kematian Amini di Iran, serta deret aturan pemaksaan hijab di Indonesia ini, adalah alarm tanda bahaya bagi kebebasan berekspresi masyarakat dan telah mengancam menurunnya kemajemukan di kehidupan bermasyarakat.
Baca juga: Kenapa Aturan Memakai Jilbab di Sekolah Makin Marak dan Masih Terjadi?
Pelajaran bagi Indonesia
Satu persamaan antara Iran dengan Indonesia, selain besarnya jumlah populasi Muslim, adalah keduanya sama-sama telah menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai isu moral.
Sepanjang sejarah, tubuh perempuan memang telah menjadi arena pertarungan berbagai ideologi dan politik identitas, terutama di Indonesia. Penerapan kode berpakaian pada perempuan menjadi strategi untuk menegakkan identitas politik ini.
Pemahaman nilai-nilai agama yang tidak tepat oleh mereka yang berkuasa acap kali menempatkan beban “kesucian dan kesopanan” pada perempuan yang berujung pada penyangkalan terhadap hak atas otoritas tubuh perempuan. Akibatnya, aturan-aturan yang dibuat pun cenderung memperkuat subordinasi perempuan di ranah publik.
Kebebasan dan martabat adalah nilai utama dalam setiap agama. Ironisnya, kematian Amini menunjukkan bahwa martabat dan kebebasan perempuan tidak dimasukkan sebagai bagian dari nilai agama yang paling utama.
Kasus Amini seharusnya menjadi tanda peringatan bagi Indonesia, sudah saatnya masalah pemaksaan hijab yang terjadi di berbagai daerah di tanah air mendapat perhatian serius dari semua pihak.![]()
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.





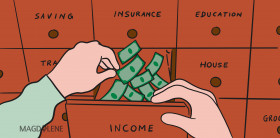

Comments