"So what would happen if suddenly, magically, men could menstruate and women could not?
Clearly, menstruation would become an enviable, worthy, masculine event: Men would brag about how long and how much. Young boys would talk about it as the envied beginning of manhood. Gifts, religious ceremonies, family dinners, and stag parties would mark the day."
- Gloria Steinem
Salah satu bukti bahwa pengetahuan dan kebijakan publik di sebuah negara dibuat dan dipikirkan oleh gerombolan lelaki adalah tidak dianggapnya menstruasi sebagai bagian dari hak dasar manusia. Padahal kita tahu bahwa setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan, dan hampir semua perempuan mengalami menstruasi setiap bulannya.
Namun pengalaman menstruasi perempuan terus dianggap tabu dan menjijikkan dalam banyak budaya. Berbeda dengan laki-laki yang ketika disunat dirayakan oleh seluruh keluarga, anak perempuan tidak mendapatkan perayaan saat mendapatkan menstruasi. Justru banyak keluarga waswas bila anak perempuan menginjak pubertas karena “salah sedikit” bisa hamil dan mempermalukan keluarga.
Ketika saya mendapatkan menstruasi pertama di bangku sekolah, saya minta bantuan teman untuk mencarikan pembalut. Dia memberikannya secara sembunyi-sembunyi dan menyebutnya dengan kata sandi "roti jepang". Ada dua alasan yang membuat menstruasi menjadi hal yang tabu dan menjijikkan. Pertama, sebagian besar sekolah pada masa tersebut tidak menyediakan pembalut sebagai bagian dari pertolongan pertama. Pendidikan seksual tidak ada sehingga pengetahuan tentang kesehatan reproduksi termasuk menstruasi pun absen.
Sementara itu, anak perempuan merasa menstruasi adalah hal yang memalukan. Mereka akan malu setengah mati kalau darah menstruasi “tembus” dan menodai rok sekolah. Di sini, kita bisa melihat bahwa secara struktural, menstruasi dianggap sesuatu yang asing dan menjijikkan.
Baca juga: Kisah Menstruasi Pertama: Siklus Ketidaktahuan Menahun
Baru setelah saya belajar feminisme, saya paham bahwa menstruasi adalah kondisi terberi, tidak bisa ditolak, dan merupakan bagian dari hak asasi perempuan yang selama ini dipinggirkan karena dominasi ilmu pengetahuan yang maskulin dan bias gender. Epistemologi feminis mengkritik keras ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan politik yang sangat maskulin dan menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang juga maskulin. Maskulin karena tidak menyertakan pengalaman perempuan sebagai bagian dari pertimbangan kebijakan.
Pada 1979, berlangsung konvensi global terkait penerapan hak asasi manusia perempuan bernama Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini adalah tindak lanjut untuk membuat pengalaman dan pengetahuan perempuan tertuang dalam kebijakan publik seluruh negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konvensi ini, dijabarkan bahwa ternyata identitas gender berpengaruh dan hak asasi manusia perempuan terpinggirkan. Perempuan dengan pengalaman ketubuhan dan identitas gender yang berbeda memberikan kondisi yang tidak sama dengan laki-laki. Misalnya dengan tabu menstruasi, hak cuti hamil dan melahirkan, akses pendidikan dan kesehatan, dsb.
Konvensi CEDAW dan epistemologi feminisme menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan kebijakan publik yang “netral” terbukti bias gender. Misalnya dengan tidak menjadikan pembalut sebagai salah satu barang bersubsidi. Pembalut dan beras seharusnya menjadi barang yang sama-sama diperhatikan regulasi dan aksesnya oleh pemerintah. Karena sebagaimana lapar yang tidak bisa ditunda, begitu pula menstruasi.
Menstruasi adalah kondisi terberi yang harus menjadi hal yang politis dan dibicarakan serius oleh pembuat kebijakan. Berbagai hal terkait menstruasi harus dijadikan bahan diskusi politik serius seperti hak cuti menstruasi, penyediaan WC yang higienis untuk pekerja, dan subsidi pembalut. Negara harus turut campur dalam menyediakan kebutuhan pembalut dan mengawasi kualitas teknologi menstruasi dan akses bagi seluruh perempuan warga negara.
Baca juga: Memikirkan Kembali Menstruasi: Darah dalam Iklan Pembalut
Evolusi pembalut: dilema lingkungan dan kesenjangan Sosial
Adalah twit dari Kalis Mardiasih, penulis buku Muslimah yang Diperbedatkan yang membuat saya menulis artikel ini. Kalis mengetik bagaimana ia berempati dengan perempuan miskin di desa yang hingga hari ini masih tidak bisa membeli pembalut. Ketika banyak feminis kelas menengah perkotaan seperti saya mempromosikan penggantian pembalut dengan cawan menstruasi untuk melestarikan lingkungan, masih banyak anak perempuan di pedesaan yang mungkin tidak bisa membeli pembalut setiap menstruasi.
Kesenjangan ekonomi antara perempuan di Indonesia dibuktikan dengan akses terhadap teknologi menstruasi. Sejarah membuktikan bahwa kelas sosial sangat menentukan akses tersebut. Cawan menstruasi yang diklaim paling ramah lingkungan harganya tidak murah, berkisar di atas Rp400.000 per buah dan masih harus diimpor. Sementara itu, tampon hanya tersedia di mal-mal besar di Jakarta dengan harga per paket mencapai lebih dari Rp50.000 dengan isi 30. Pembalut sekali pakai menjadi teknologi menstruasi yang paling populer dan banyak variannya di seluruh Indonesia. Semakin canggih daya serap, kenyamanan dan jaminan tidak bocor, akan semakin mahal harganya.
Dilema kedua muncul ketika inovasi pembalut sekali pakai disertai dengan peningkatan penggunaan plastik dalam bahan pembuatannya yang memunculkan alergi pada kulit serta perasaan bersalah bagi perempuan. Penelitian Alejandra Borundra dari National Geographic 2019 berjudul "How tampons and pads became so unsustainable" membandingkan evolusi tampon dan pembalut hari ini dengan pada tahun 1970. Tampon dan pembalut sekali pakai hari ini menggunakan lebih banyak bahan baku lebih plastik demi inovasi produk yang semakin nyaman dan sekaligus menekan biaya produksi. Sebab plastik jauh lebih murah daripada bahan mentah lainnya.
Di sini, feminisme dan tubuh perempuan lagi-lagi menjadi bahan pertarungan. Di satu, sisi menstruasi adalah pengalaman dan hak dasar perempuan, dan teknologi terkait itu harus bisa diakses semua orang termasuk kelompok miskin. Di sisi lain, keekonomian dan kemudahan akses dari pembalut sekali pakai memunculkan masalah lingkungan. Peran negara yang kuat dan berperspektif gender diperlukan untuk memberikan akses dan subsidi pembalut yang memenuhi prinsip-prinsip kebersihan dan keamanan produk sekaligus ramah lingkungan.
Kita tidak mau menjadi seperti Inggris dan eks negara jajahannya, India dan Australia, yang justru memberikan pajak untuk pembalut dan tampon. Baru tahun 2019 ini Australia mencabut pajak tampon atas desakan kelompok feminis kepada pembuat kebijakan.
Menurut saya, kelompok feminis di Indonesia juga bisa untuk terus galak dan marah-marah supaya pemerintah mulai mengevaluasi program/slogan pengarusutamaan gender dengan benar-benar memberikan perspektif gender pada kebijakannya. Hal ini dapat dimulai lewat pemberian pelayanan kesehatan reproduksi, dan subsidi pembalut di sekolah serta posyandu.




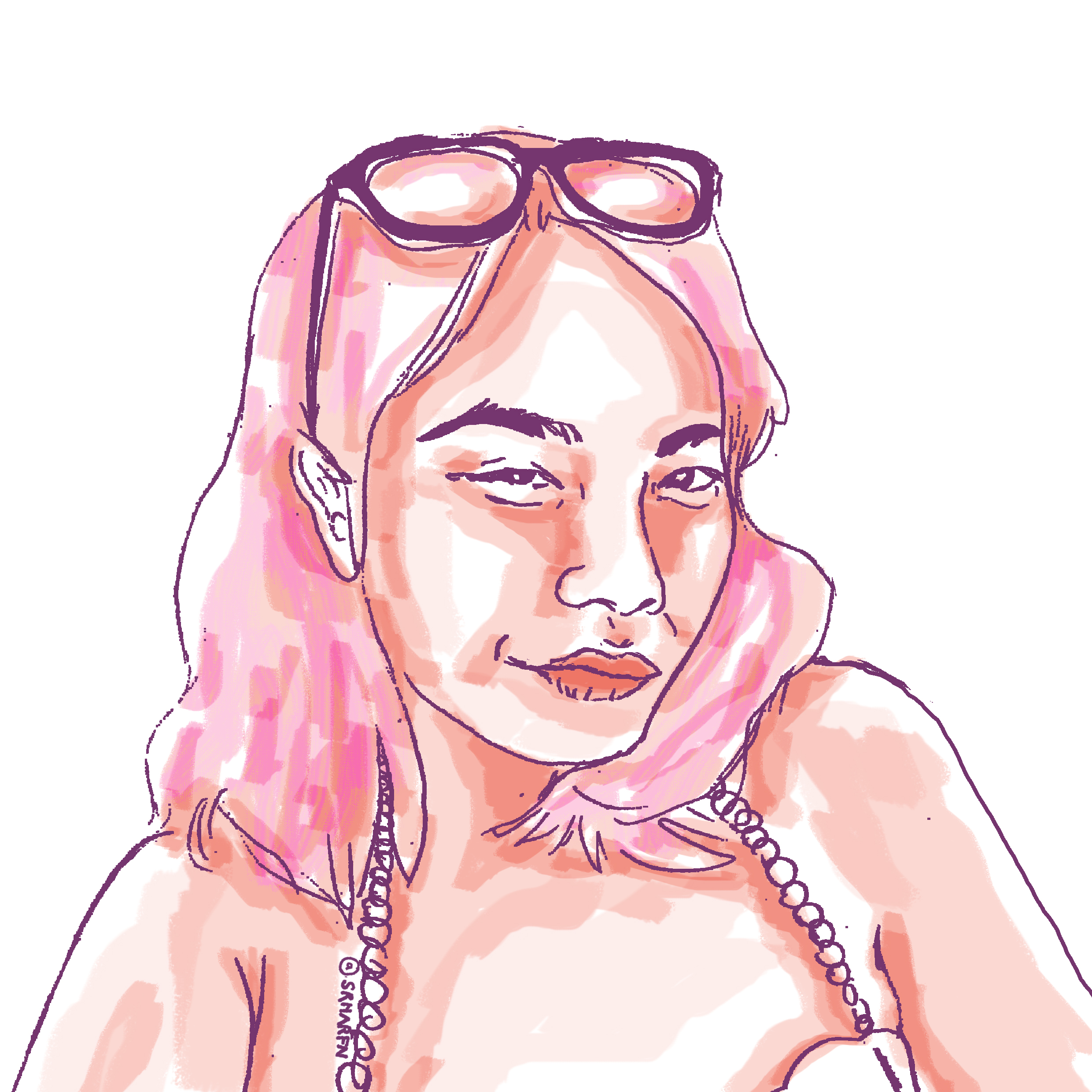



Comments