Perempuan muda dengan baju terusan putih selutut itu tampak tegang ketika namanya dipanggil ke atas panggung. Suaranya sedikit bergetar saat ia mengenalkan namanya: Nabila Tabita, usia 21 tahun.
“Saya sudah beberapa kali mengikuti acara open mic, tapi baru kali ini berbagi cerita di House of Unsilenced (HOU). Maaf ya kalau agak terbata-bata membacakan prosa saya,” ujarnya Sabtu malam itu (30/11) di IFI Thamrin.
Begitu membacakan tulisannya, suaranya berubah tegas dan menggelegar. Ia mengisahkan kesedihan atas traumanya, juga kemarahannya karena Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) gagal disahkan tahun ini. Nabila juga mengatakan sudah saatnya penyintas beraksi.
Sebagai seorang penyintas kekerasan seksual, Nabilla mengatakan ia mengerti terbatasnya ruang untuk para penyintas bersuara.
“Cerita ini sudah aku bacakan di beberapa acara open mic, tapi vibe dari House of the Unsilenced beda. Bukan hanya sekadar tampil, tapi saya juga merasa kita pulih bersama,” katanya kepada Magdalene sesudah tampil.
House of Unsilenced adalah sebuah inisiatif untuk mendukung para penyintas kekerasan seksual lewat seni. Kolektif ini mengumpulkan seniman, penulis, dan penyintas kekerasan seksual untuk menciptakan karya mengenai kehidupan para penyintas dan apa artinya berbicara.
Terbatasnya ruang ekspresi bagi para penyintas kekerasan seksual membuat acara HOU menjadi salah satu oase bagi para penyintas. Tahun ini merupakan kali kedua dari penyelenggaraan acara ini, yang bertepatan dengan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP). Selain open mic, HOU juga mengadakan lokakarya kesenian, termasuk menulis.
Sama seperti Nabila, Dewi Nova juga menemukan kekuatan untuk berbicara dalam acara tersebut. Penulis berusia 45 tahun itu mengatakan, untuk pertama kalinya ia dapat menceritakan kekerasan seksual yang ia alami dalam sebuah gerakan aktivisme kemanusiaan.
Baca juga: Film Sebagai Katarsis Bagi Penyintas Kekerasan Seksual
“Aku enggak pernah testimoni seperti yang di HOU, karena aku berada di lingkungan dengan orang-orang yang masih menyalahkan aku atas kejadian tersebut. Apalagi orang-orang ini dari lingkaran sesama aktivis juga,” ujar Dewi kepada Magdalene.
Sepanjang penampilan dari peserta lain, Dewi terus menerus menitikkan air mata. Ia merasa momen itu adalah sebuah titik balik dalam hidupnya.
“Yang aku rasakan bukan hanya sedih, tetapi ada semacam perasaan dikuatkan oleh teman-teman penampil lainnya. Itu jadi polesan besar dalam hidup aku,” kata Dewi.
Penulis Eliza Vitri selaku penggagas dari acara House of the Unsilenced mengatakab ia menemukan pola yang sama dalam acara-acara lokakarya yang diadakan oleh kolektifnya, yakni bagaimana penyintas merasa mendapatkan ruang untuk berekspresi dengan aman.
“Dari memecah kebungkaman ini, para penyintas merasa lebih lega atau lebih kuat. Suara-suara mereka pun membuat para penyintas lain merasa mereka tidak sendiri banyak orang yang berjuang bersama kita,” ujar Eliza.
Open mic tersebut menampilkan 15 penampil dengan latar belakang dan cerita yang beragam. Ada lima orang laki-laki yang juga berbagi cerita, termasuk Sebastian Partogi, 30 tahun, seorang wartawan yang menceritakan tentang standar ganda dalam masyarakat terhadap lelaki feminin.
“Karena ekspresi gender saya yang feminin, sejak sekolah saya harus bekerja dua kali lebih keras untuk membuktikan diri saya juga bisa berprestasi. Namun tetap saja stigmanya masih ada. Dan itu memiliki efek pada kesehatan mental saya. Setelah berbagi cerita lewat tulisan, ternyata lega banget rasanya,” kata Sebastian.
Baca juga: Rayya Makarim dan Tema Kekerasan Seksual dalam Film Indonesia
Riset menunjukkan bahwa literasi memiliki dampak positif dalam proses penyembuhan trauma. Penelitian Limor Pinhasi-Vittorio, yang hasilnya diterbitkan oleh Journal of Poetry Therapy pada 2018, mengeksplorasi peran literasi terhadap kehidupan perempuan yang sedang dalam pemulihan dari penyalahgunaan zat adiktif. Penelitian ini berfokus pada karya-karya dari sebuah lokakarya menulis dan membaca prosa, puisi.
Dari pengamatan Pinhasi dan Vittorio, lokakarya tersebut membuat para peserta menemukan suara mereka dalam tulisan; mengalami perubahan persepsi terhadap diri mereka dan mengapresiasi satu sama lain; mendapatkan sarana ekspresi dan berbagi trauma-trauma masa lalu, serta membicarakan tentang kecanduan mereka.
Menurut Eliza, medium seni membantu para penyintas untuk lebih memahami pengalaman itu, apa ihwal ketidakadilan yang dialami. Karena sifatnya yang sangat personal, seni pun juga dapat diartikan sebagai penanda dari korban menjadi penyintas atau pejuang, ujarnya.
“Dengan seni dan kisah kita bisa membangun empati orang lain yang tidak bisa terjalin dengan sekadar fakta atau statistik. Kisah penyintas pun penting untuk mematahkan asumsi keliru yang banyak dimiliki masyarakat yang mungkin belum pernah mendengar langsung dari para penyintas,” kata Eliza.
Sebagai penulis, Dewi Nov mengatakan ia tahu betul bagaimana seni membantunya dalam memulihkan trauma yang sudah 19 tahun ia pendam.
“Ketika dituangkan dalam sebuah karya seni, ada semacam jarak antara aku dan karya itu. Hal ini membuat aku memiliki ruang untuk berefleksi terhadap apa yang terjadi padaku. Sudah sejauh mana aku pulih, dan bagaimana lagi yang perlu aku pulihkan,” ujarnya.



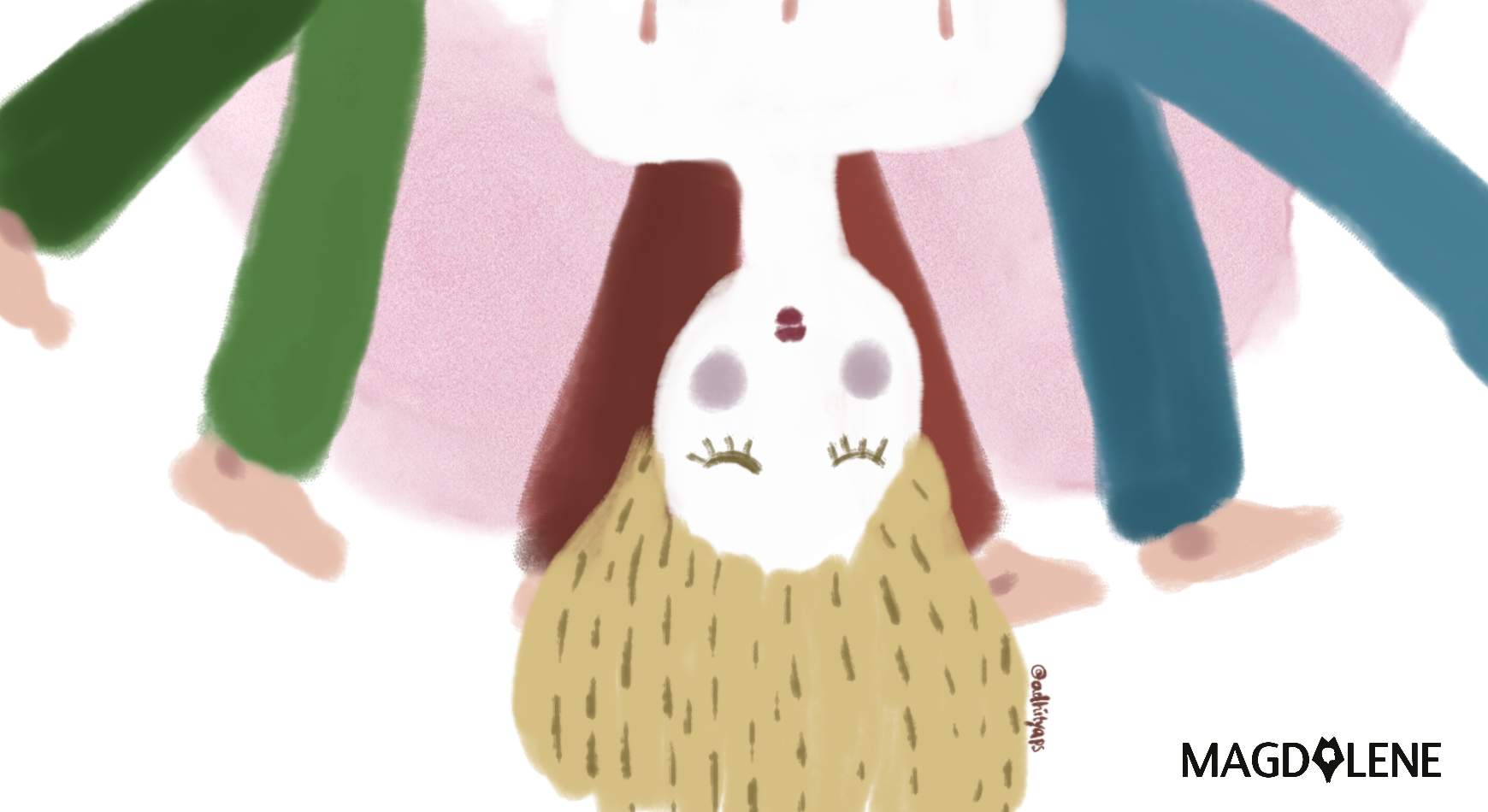




Comments