Kepala Ningrum tertunduk, air muka gusar jelas tergambar. Meski sakit, ia harus legowo dikawinkan paksa dengan lelaki itu. Ningrum juga lebih banyak menelan lukanya sendirian, bahkan saat berkali-kali ia mencoba menggugurkan kandungan. Di akhir cerita, Ningrum tetap pasrah pada keadaannya dan memutuskan untuk bunuh diri, ketimbang melawan suami.
Kepahitan Ningrum ini bisa kita lihat dalam film Rahim Puan besutan dua sutradara laki-laki, Syahiddan Abdillah dan Bayu S. Yusi. Film yang diputar pada (28/5) ini dikemas dalam tone warna yang gelap, seolah mengafirmasi bahwa menjadi perempuan memang sangat menderita. Ini kontras dengan dua film lain yang diputar dalam momen bersamaan bertajuk “Jalan Terjal Perempuan” tersebut. Dua film lainnya, yakni My Clouded Mind dan Yuki, disutradarai oleh perempuan, Annisa Adjam dan Citra Melati.
Baca Juga: ‘City of Joy’: Ubah Luka Korban Pemerkosaan Jadi Kekuatan
The Female Victim adalah Narasi Usang
Saya masih ingat dengan jelas rasa jengkel para feminis ketika menonton film Rahim Puan malam itu. Saya tahu, para sutradara Rahim Puan bermaksud memotret realitas perempuan pekerja pabrik yang kerap mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual. Namun, bukannya memberikan gambaran konkret tentang pengalaman perempuan, mereka justru mengomodifikasi kesedihan dan penderitaan.
Mirisnya, apa yang dilakukan Syahiddan dan Bayu adalah hal jamak dalam dunia sinema kita. Banyak sineas yang berusaha mengangkat cerita perempuan, memiliki tujuan mulia untuk memaparkan realitas, tapi pada akhirnya justru tetap me-liyan-kan perempuan lagi.
Claire Johnston, ahli teori film feminis dalam esainya Women's cinema as counter-cinema (1973) mengungkapkan bagaimana laki-laki berada di pusat alam semesta dalam teks yang berfokus pada citra perempuan. Karena itulah produk-produk seperti film, mengemas jalan cerita, dialog, dan musik agar sejalan dengan pesan ”perempuan tak setara dan berbeda dengan lelaki”.
Cara laki-laki me-liyan-kan perempuan dalam film tergambar dari bagaimana mereka menggambarkan kelompok ini sebagai pihak yang tak berdaya. Mereka selamanya adalah korban yang tak punya suara. Dalam artikel media Redefy dijelaskan, perempuan hampir selalu digambarkan sebagai korban kekerasan dengan penderitaan dan kesedihan yang penuh dramatisasi. Sementara, narasi perempuan yang lebih penting hanya dimasukkan sebagai lelucon atau "catatan kaki" dalam plot utama.
Enggak percaya? Coba lihat film Welcome to Dongmakgol (2005). Di film tersebut, kematian karakter perempuan Yeo-Il didramatisasi dan dipenuhi narasi bahwa ia adalah korban yang menderita. Di film genre horor macam Halloween (1978), karakter perempuan Jamie Lee Curtis juga digambarkan sebagai korban yang cuma bisa teriak minta tolong. Karena itulah pada 2015, muncul istilah “Scream Queen” dalam genre horor atau sub genre slasher, yakni istilah untuk menggambarkan ketidakberdayaan lewat teriakan dan jeritan. Masih belum cukup? Coba tengok di hampir semua sinetron atau FTV di Indonesia yang mayoritas masih menciptakan karakter perempuan protagonis yang tersakiti, nestapa, dan tak punya daya.
Kendati beberapa film yang telah berusaha mendobrak bias dan stereotip gender, tapi perempuan pada akhirnya akan tetap jadi korban.
Baca Juga: Superhero Perempuan dan Problematika Representasinya
Harapan dan Perlawanan lewat Perspektif Perempuan
Berbeda dengan Rahim Puan, My Clouded Mind dan Yuki membuat karakter perempuan sebagai sosok yang lebih berdaya. Dengan segala trauma dan rintangan hidup, korban perempuan memilih untuk memaafkan diri mereka sendiri dan bangkit secara perlahan.
Di saat bersamaan, karakter perempuannya tidak dibiarkan bungkam tapi justru diberikan sorotan khusus melalui dialog yang mendominasi cerita. Inilah yang jadi kekuatan mereka. Karena mereka berdua tak hanya menampilkan realita, tapi mereka juga mampu memberikan harapan kepada penontonnya, kepada sesama korban atau penyintas.
Memotret ketertindasan khas dari perempuan memang penting untuk meningkatkan kesadaran. Apalagi di tengah gejolak konflik, ketidakadilan, dan angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat, perempuan nampaknya sudah cukup muak melihat dunia tanpa cahaya. Perempuan butuh harapan. Perempuan butuh alternatif untuk melawan ketertindasan. Perempuan butuh ceritanya diangkat, alih-alih dijadikan hiburan semata.
Untuk itu Isabella Eklöf, sutradara dan penulis skenario asal Swedia dalam wawancaranya bersama The Guardian mengatakan, kita butuh berpihak pada perempuan. Tujuannya agar kita memiliki pandangan bahwa ternyata perempuan punya pilihan dan jadi sosok aktif.
Baca Juga: Film Sebagai Katarsis Bagi Penyintas Kekerasan Seksual
Terkait itu, riset J. Walter Thompson Company yang melibatkan 4.300 perempuan di sembilan negara (Brasil, Cina, India Arab Saudi, Afrika Selatan, Rusia, Australia, Inggris, dan Amerika) pada 2016 menemukan, sebanyak 61 persen responden bilang, karakter perempuan berdaya dalam film dan TV telah berpengaruh dalam kehidupan mereka. Sementara, 58 persen mengatakan, perempuan telah terinspirasi untuk menjadi lebih ambisius atau asertif. Bahkan 1 dari 9 perempuan berkomentar, karakter perempuan yang berdaya dan positif telah memberi mereka keberanian untuk keluar dari hubungan abusif.
Dengan demikian, memang kini sudah saatnya kita berhenti mengglorifikasi kesedihan dan penderitaan perempuan. Berhenti membuat mereka menjadi korban tak berdaya. Sebaliknya, ceritakan kisah mereka dalam sudut pandang berbeda. Sudut pandang yang lebih memberdayakan, sehingga perempuan di luar saya bisa menerima harapan dan pilihan.



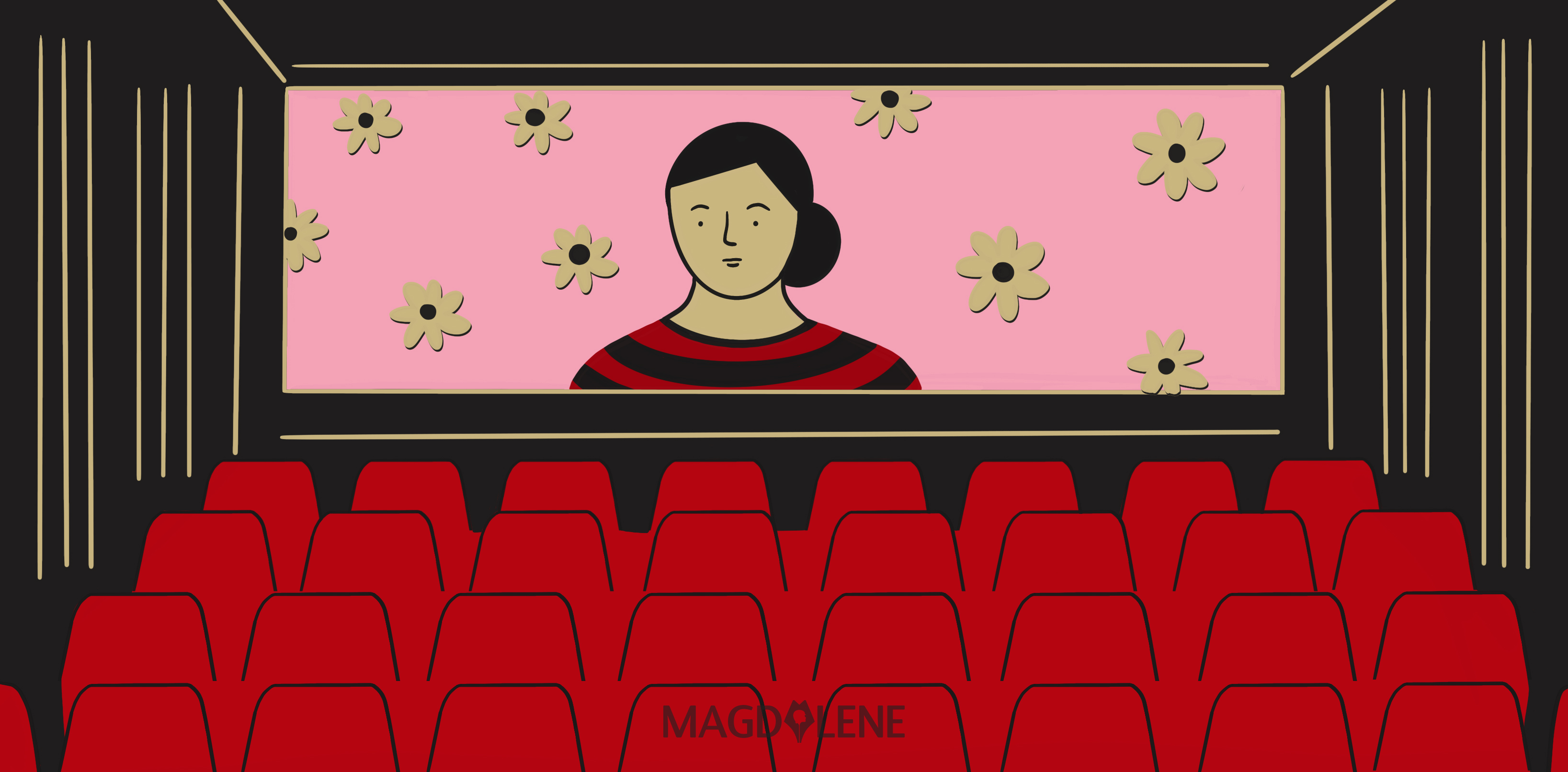




Comments