Pelaku bom bunuh diri di tiga gereja Surabaya minggu lalu (13/5) adalah satu keluarga yang terdiri dari enam orang, yakni ibu, ayah, dua anak laki-laki berusia 18 dan 16 tahun, serta dua anak perempuan berusia 12 dan 9 tahun.
Meskipun terdengar mengejutkan, fenomena keluarga teroris ternyata bukanlah hal baru, menurut para pembicara dalam diskusi bulanan ‘Reading in Social Science’ yang diadakan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jumat (18/5).
Diskusi tersebut merujuk pada penelitian Donatella della Porta, profesor ilmu politik dan sosiologi politik dari European University Institute di Firenze, Italia, pada 1995, mengenai organisasi teroris sayap kiri di negara itu, Brigade Merah (BM). Penelitian itu menunjukkan 298 dari 1.214 anggota BM memiliki hubungan darah atau satu keluarga, baik itu sebagai orang tua, ayah, ibu, anak, atau saudara.
Riset komisi PBB untuk peristiwa pembajakan pesawat 11 September 2001 (9/11) di Amerika Serikat juga mengonfirmasi fenomena keluarga teroris, karena enam dari 19 pembajak pesawat itu bersaudara. Tak hanya itu, pelaku bom Boston Marathon pada 2012 juga dilakukan oleh Tsarnaev bersaudara. Di Indonesia sendiri, tiga pelaku Bom Bali I pada 2002 -- Ali Ghufron, Amrozi, dan Ali Imron -- merupakan kakak beradik.
“Dulu, proses radikalisasi membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya panjang. Keluarga menjadi semacam jalan pintas atau short cut dalam proses radikalisasi,” kata Ihsan Ali Fauzi, Direktur PUSAD Paramadina. Ia merujuk pada riset Mohammad M. Hafez, ahli gerakan Islamis dan kekerasan politik dari Naval Postgraduate School di Monterey, California, yang berjudul The Ties that Bind: How Terrorists Exploit Family Bonds (2016).
Ihsan menjelaskan, dulu aksi terorisme tergerak karena pertimbangan politik atau pencarian makna hidup (ideologi) seseorang. Menurutnya, saat ini teroris cenderung tidak lagi melihat pencarian makna hidup sebagai motivasi bergabung ke dalam gerakan terorisme. Selain itu, karena pengawasan dari aparat keamanan yang cenderung meningkat, teroris mulai menggunakan cara perekrutan lain, yaitu di dalam kelompok yang tertutup dan tidak mudah dicurigai, seperti di dalam keluarga.
“Dengan adanya unsur-unsur yang ada dalam ikatan keluarga seperti cinta kasih, rasa percaya dan ikatan seumur hidup, memudahkan pelaku teroris dalam perekrutan. Karena proses radikalisasi-terorisme lebih cepat dan radikalisasi tidak perlu terlalu dalam,” ujarnya.
Proses perekrutan ini biasa disebut bloc recruitment, di mana merekrut kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya akan jauh lebih mudah karena adanya tekanan sosial, kekhawatiran ditinggalkan, dan keinginan untuk terus menjaga relasi. Tak hanya itu, bloc recruitment juga dapat meminimalisasi resistensi dan pengkhianatan.
Cara lain yang biasa digunakan adalah menikahkan saudara atau anak perempuan dengan teman sesama teroris. Mukhlas atau Ali Gufron, salah satu tersangka bom Bali, menikah dengan Paridah Abas, saudara perempuan Nasir Abas, yang merupakan sesama alumni pelatihan militer di Afghanistan. Terdakwa tindak pidana terorisme Baridin atau Bahrudin Latif adalah mertua gembong teroris Noordin M. Top, dan ia dihukum karena mendukung dan menyembunyikan menantunya itu sehingga terjadi peledakan bom di JW Marriot dan Ritz Carlton pada Juli 2009.
“Kedekatan persaudaraan dan pernikahan lebih efektif digunakan oleh pelaku teroris untuk membentuk jaringan karena adanya pengaruh psikolog yang mengikat dan saling menguatkan satu sama lain,” ujar Dyah Ayu Kartika, peneliti PUSAD Paramadina.
“Adanya ikatan keluarga juga menghindari perbedaan pandangan satu sama lain, serta memperkokoh hubungan yang sudah terjalin.”
Dengan kata lain, tambah Dyah, saat seseorang telah menjadi keluarga maka akan lebih mudah membangun kepercayaan dibanding dengan orang lain. Selain itu, dengan kondisi para teroris yang dalam pengawasan aparat dan terbatasnya pergerakan mereka, maka mereka harus lebih berhati-hati ketika ingin menambah anggota.
“Ditinjau dari kondisi saat ini, pengawasan [aparat] sudah semakin meningkat, sehingga proses perekrutan melalui media sosial, seperti Telegram misalnya, akan lebih berbahaya,” ujar Dyah.
“Sementara jika proses perekrutan dilakukan di dalam keluarga, akan lebih sulit untuk mendeteksi proses perekrutannya. Selain itu, adanya ikatan (bonding) antar keluarga juga akan mempersulit terjadinya pengkhianatan di dalam kelompok.”
Baca juga soal rendahnya tingkat sosialisasi dan informasi soal layanan kesehatan reproduksi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ilustrasi oleh Sarah Arifin.




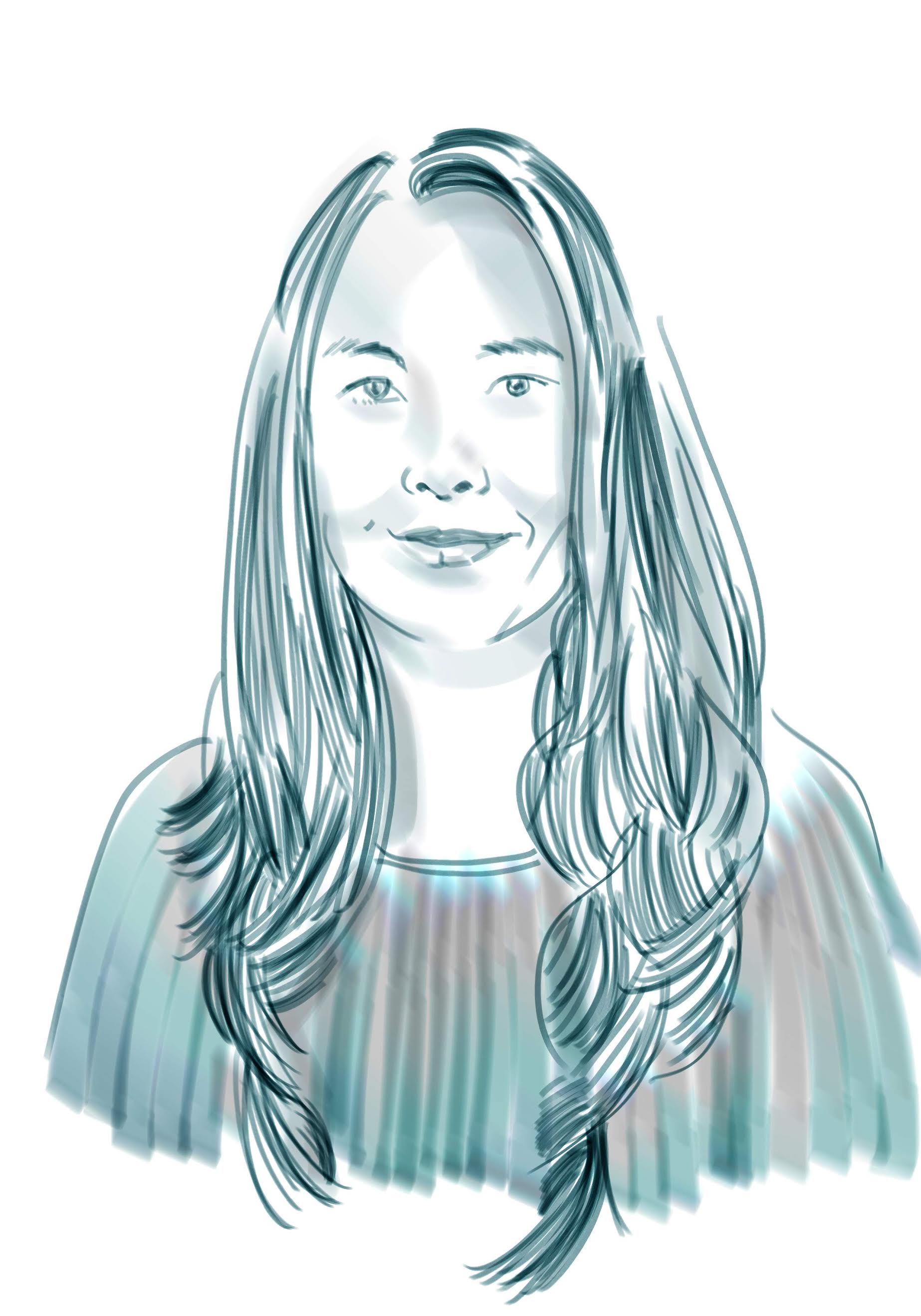



Comments