Gerakan feminisme terus berkembang dari dekade ke dekade, melalui berbagai saluran, dan mengusung perjuangan beragam. Pada awal abad ke-21, gerakan feminisme memanfaatkan keberadaan internet, termasuk media sosial mulai 2010-an.
Britannica.com mencatat, sekitar periode ini muncul gelombang keempat feminisme yang berfokus pada pelecehan seksual, body shaming, dan budaya pemerkosaan. Yang membedakannya dengan lainnya adalah pemakaian media sosial untuk menyuarakan isu-isu tersebut. Biasanya, kesadaran akan isu feminisme yang digaungkan lewat media baru ini berangkat dari insiden-insiden dengan perempuan atau kaum marjinal sebagai korbannya.
Media sosial yang menjadi sumber informasi pertama bagi generasi muda bukanlah hal yang mengagetkan sekarang. Ini mencakup pula pengetahuan tentang feminisme atau isu kesetaraan gender. Sebuah riset yang baru-baru ini dilakukan Tirto dan Jakpat menyatakan, 72,5 persen dari total 1.500 responden (dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara) mendapatkan informasi soal feminisme dari media sosial, disusul dari berita daring dan teman/keluarga.
Baca juga: Feminisme Digital 4.0 dan Balada Feminis Medsos
Media Sosial: Sumber Pengetahuan dan Titik Berangkat Gerakan Feminisme Kini
Karlie, remaja 15 tahun dari Kanada Timur, adalah satu dari banyaknya anak muda yang belajar tentang feminisme dari Twitter. Dalam jurnal berjudul “‘Oh, She’s a Tumblr Feminist’: Exploring the Platform Vernacular of Girls’ Social Media Feminisms” yang ditulis Jessalyn Keller (2019) diceritakan, Karlie telah mengikuti sejumlah akun feminis di Twitter dan Tumblr sejak usia 13 dan bertemu dengan remaja feminis lainnya yang melakukan aktivisme serupa dengannya.
Di berbagai negara termasuk Indonesia, hal ini pun bukanlah sesuatu yang langka. Akun-akun feminisme lokal terus muncul dan berkembang, diekori pertumbuhan anak-anak perempuan dan perempuan dewasa yang sama-sama menyebarkan pesan kesetaraan gender.
Di titik ini, internet, khususnya media sosial, dipandang sebagai medium yang membawa dampak positif bagi perjuangan para feminis. Neqy, penggagas salah satu akun feminis Indonesia @_perEMPUan_ yang berfokus pada isu kekerasan seksual pun juga mengamini hal itu.
“Munculnya orang-orang yang aware dan mau belajar soal feminisme dan mau menyuarakan feminisme adalah awalan yang baik,” kata dia.
Senada dengan Neqy, aktivis perempuan dan pendiri PurpleCode, sebuah kolektif yang berfokus pada aktivisme feminisme di dunia digital Dhyta Caturani mengungkapkan, di permukaan, munculnya orang-orang yang mengklaim diri feminis sebenarnya hal yang positif.
“Kenapa? Karena istilah feminis dan feminisme itu mengalami demonisasi selama berabad-abad. Di Indonesia bahkan sampai saat ini masih begitu. Jadi, semakin banyaknya orang yang mengklaim diri feminis atau terlibat dalam feminisme adalah baik,” jelas Dhyta.
Baca juga: Feminisme 101 dan Rekomendasi Bacaan untuk Belajar
Feminisme di Media Sosial Baik, Tapi…
Kendati fenomena bermunculannya beragam individu, kelompok feminis dan gerakan feminisme di ranah digital adalah perkembangan yang baik, hal ini perlu diamati dan ditanggapi dengan kritis. Dhyta menilai, yang perlu ditelisik secara lebih kritis adalah pesan apa yang mereka sampaikan di dunia digital. Apakah benar pesan-pesan yang disampaikan, pendapat, ekspresi, atau laku di dunia digital mereka benar-benar sesuai dengan nilai feminis.
“Harus diakui, untuk menyatakan diri sebagai feminis, memang ada bare minimum-nya terkait nilai-nilai ini sebagai sebuah common sense bagi kita. Kalau kita mau klaim diri, kita harus mengikuti nilai feminisme yang memayungi semua kelompok secara umum sebagai napas hidup yang kita praktikkan dalam keseharian,” ungkap Dhyta.
Sementara menurut Neqy, hal penting yang harus diingat feminis-feminis digital dalam melakukan gerakan feminisme di media sosial adalah kemauan untuk berdiskusi dengan orang lain, berjejaring, dan melakukan aktivitas, bukan hanya berpendapat, apalagi hanya mengatasnamakan pendapat pribadi.
“Hendaknya aktivisme digitalnya diteruskan supaya enggak cuma berhenti di situ [opini pribadi] dan lebih menyuarakan untuk konteks lebih besar. Tidak hanya membahas opininya sendiri, tapi bagaimana diskusi itu dibawa untuk mendatangkan awareness lebih besar dari masyarakat supaya call to action-nya lebih makro,” kata Neqy.
Tidak ada satu individu pun yang berhak dan pantas menisbatkan dirinya sebagai brand ambassador gerakan apa pun, termasuk feminisme, karena gerakan itu cakupannya luas dan mencakup beragam identitas serta pengalaman.
Ia juga mengkritisi bagaimana sejumlah orang yang mengklaim diri feminis menggunakan media sosial sebagai panggung untuk dirinya sendiri, serta menyoroti soal performative activism yang ditemukan di ranah digital.
“Selain bahwa kita-kita sebagai feminis atau individu yang memberikan edukasi publik tentang pemahaman tertentu, kita seharusnya berperan sebagai messenger sebagai pembuka jalan, dan passing the mic. Jadi, alih-alih menguasai mic-nya dan menyampaikan semua hal lewat diri kita dengan berpikir kitalah brand ambassador gerakan itu, kita harus sadar diri, bahwa kita tidak bisa mewakili semua identitas yang diperjuangkan oleh gerakan feminisme,” papar Neqy.
Ia menekankan, tidak ada satu individu pun yang berhak dan pantas menisbatkan dirinya sebagai brand ambassador gerakan apa pun, termasuk feminisme, karena gerakan itu cakupannya luas dan mencakup beragam identitas serta pengalaman.
“Ini penting jadi catatan karena efek samping dari performative activism justru menciptakan stigma negatif pada gerakan feminisme yang diatasnamakan oleh self-claimed ambassador ini,” imbuhnya.
Baca juga: 8 Aliran Feminisme yang Perlu Kamu Ketahui
Sejalan dengan Neqy, Dhyta pun mengingatkan pentingnya interseksionalitas dalam gerakan feminisme, termasuk di ranah digital.
“Feminisme memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk semua orang. Bukan cuma soal penghentian kekerasan seksual, penindasan perempuan saja, tetapi melihat identitas lain yang lebih luas dan banyak lagi. Misalnya, feminis itu juga harus memperjuangkan hak-hak buruh, pekerja rumah tangga, hak politik rakyat, LGBT, orang dengan disabilitas,” kata Dhyta.
“Kalau ada orang mengklaim sebagai feminis tetapi justru tidak memperjuangkan hak-hak kaum tadi, ini yang kemudian menurutku adalah sesuatu yang negatif dan perlu dikritisi.”
Stigma Feminis Media Sosial
Sebagian orang melabeli feminis di era digital sebagai feminis media sosial dan istilah ini kerap dianggap buruk. Pasalnya, ada anggapan mereka yang bersuara di media sosial hanya lantang di ranah itu dan berpemahaman tidak mendalam.
Neqy melihat, hal ini tidak terlepas dari pengaruh orang-orang yang berbicara soal feminisme secara sempit dalam konteks pendapatnya pribadi aja seperti yang disinggungnya tadi.
Neqy sendiri tidak peduli bila ada orang yang melabeli dirinya feminis media sosial. Selama ini, sebisa mungkin dalam aktivismenya melalui _perEMPUan_, ia tidak mengatasnamakan pendapat pribadi dan hanya membagikan informasi seputar feminisme berbasis fakta dan data yang ada di lapangan maupun dari riset.

Sementara Dhyta melihat, pandangan meremehkan aktivis-aktivis di media sosial sebenarnya sudah lama ada dan tidak hanya ditujukan pada feminis. Ada istilah clicktivism yang sering disematkan pada orang-orang yang bicara lantang di medsos. Menanggapi hal tersebut, Dhyta tidak menilai mereka yang bersuara di ranah digital saja sebagai hal yang otomatis buruk.
“Sekarang ini zaman sudah berubah. Teknologi membuat orang lebih nyaman untuk terlibat dalam aktivitas politik. Karena itulah, tidak terhindarkan, ada perubahan atau perkembangan aktor-aktor aktivisme sosial, termasuk feminisme,” kata Dhyta.
“Ada orang yang memilih perannya untuk berbicara di ranah online karena alasan beragam dan kita harus menerima semua peran ini. Yang harus kita lihat secara jeli, dengan adanya peran-peran baru aktivis di sana, bagaimana kita bisa memikirkan semua peran-peran ini bisa terkoneksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana bisa berkolaborasi, bergerak bersama.”
Ia menyoroti pentingnya upaya menghancurkan dikotomi antara aktivisme online dan offline, terutama yang memberi derajat lebih tinggi terhadap aktivis offline. Berkaca dari berbagai kasus dalam 10 tahun terakhir, banyak gerakan online yang memicu perubahan sosial, yang tidak melulu besar, tetapi lebih kecil atau spesifik.
“Memang harus diakui, gerakan online ini sebisa mungkin bertujuan menggerakkan orang secara offline juga idealnya. Itu sudah terjadi, kok. Tapi kalau ada orang-orang yang sudah ikut aktivisme secara online dan tidak bergerak secara offline juga tidak apa-apa. Peran sekecil atau sebesar apa pun di era seperti sekarang ini harus diakui, diapresiasi, dan harus bersama-sama kita olah sebagai gerakan yang lebih komprehensif.” tutur Dhyta.
Menyikapi Serangan kepada Feminis di Jagat Media Sosial
Seperti halnya aktivis lain, para feminis juga tidak lepas dari serangan pihak lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Di media sosial, hal ini menjadi semakin mudah ditemukan, mulai dari yang menggunakan argumen dan menyampaikannya dengan baik-baik sampai yang menyerang secara personal atau ad hominem.
Apa pun yang kita lakukan, sehalus apa pun cara yang kita gunakan, demonisasi terhadap feminis akan terjadi. Jadi harus dipahami, ini bukan perkara strategi kita. Ini diawali dengan long organized hate against feminism.
Dhyta mengaku akan menanggapi komentar yang disertai argumen jelas, tapi lebih sering diam jika serangannya sangat ofensif atau ad hominem. Yang ia lakukan kemudian adalah membuat narasi balik yang ditujukan kepada publik, bukan spesifik kepada penyerangnya.
“Ini karena serangan yang mereka kirimkan ke publik lewat kanal media sosial akan dibaca juga oleh orang lain, dan itu bisa memengaruhi cara berpikir orang lain juga. Maka itu, perlu buatku untuk membuat counter narrative sebagai penyeimbang bagi orang lain yang membaca serangan tersebut,” ujarnya.
Serangan terhadap feminis sejatinya terjadi sudah lama dan hal ini tidak semata-mata terkait dengan strategi yang dipilih feminis, termasuk memanfaatkan teknologi digital atau tidak.
“Apa pun yang kita lakukan, sehalus apa pun cara yang kita gunakan, demonisasi terhadap feminis akan terjadi. Jadi harus dipahami, ini bukan perkara strategi kita. Ini diawali dengan long organized hate against feminism,” terang Dhyta.
Tidak jarang feminis dicap galak di media sosial, sebagaimana telah terjadi sebelum orang ramai-ramai memakai internet. Menurut Dhyta, ia tidak mempermasalahkan feminis yang memakai cara frontal dan terkesan galak.
“Setelah perempuan mengalami ketidakadilan, penindasan beribu tahun lamanya, masa tidak boleh marah? Kalau kita dituduh galak, sebenarnya itu juga bentuk-bentuk tone policing terhadap feminis yang tidak kita temui pada aktivis-aktivis laki-laki yang memperjuangkan isu-isu keadilan juga,” ungkapnya.
Konflik Antarfeminis, Apa yang Idealnya Dilakukan?
Di media sosial, serangan datang tidak hanya dari orang berperspektif berseberangan. Kadang serangan dilancarkan orang-orang yang sama-sama mengklaim diri feminis.
Menanggapi ini, Neqy berkomentar, “Di sebagian individu atau kelompok feminis masih ada ego-ego sektoral, menganggap feminisme yang satu lebih penting dan perlu diprioritaskan.”
Sementara Dhyta menilai, serangan yang menimbulkan konflik itu memiliki banyak aspek dan tidak ada cara tunggal dalam menghadapinya. Sehingga, penting bagi feminis untuk mengakui adanya perbedaan strategi, ideologi, dan politik yang dimiliki feminis lainnya.
Saat terjadi kritik dari sesama feminis, Dhyta menyarankan agar tidak takut.
“Kritik, saling memahami dari mana kita datang, itu yang membuat kita bisa memperbaiki diri. Kritik harus disampaikan secara tepat, tidak menyerang ad hominem, disampaikan dengan cara beradab, dan dengan intensi kebaikan bersama,” pungkas Dhyta.
Ilustrasi oleh Karina Tungari



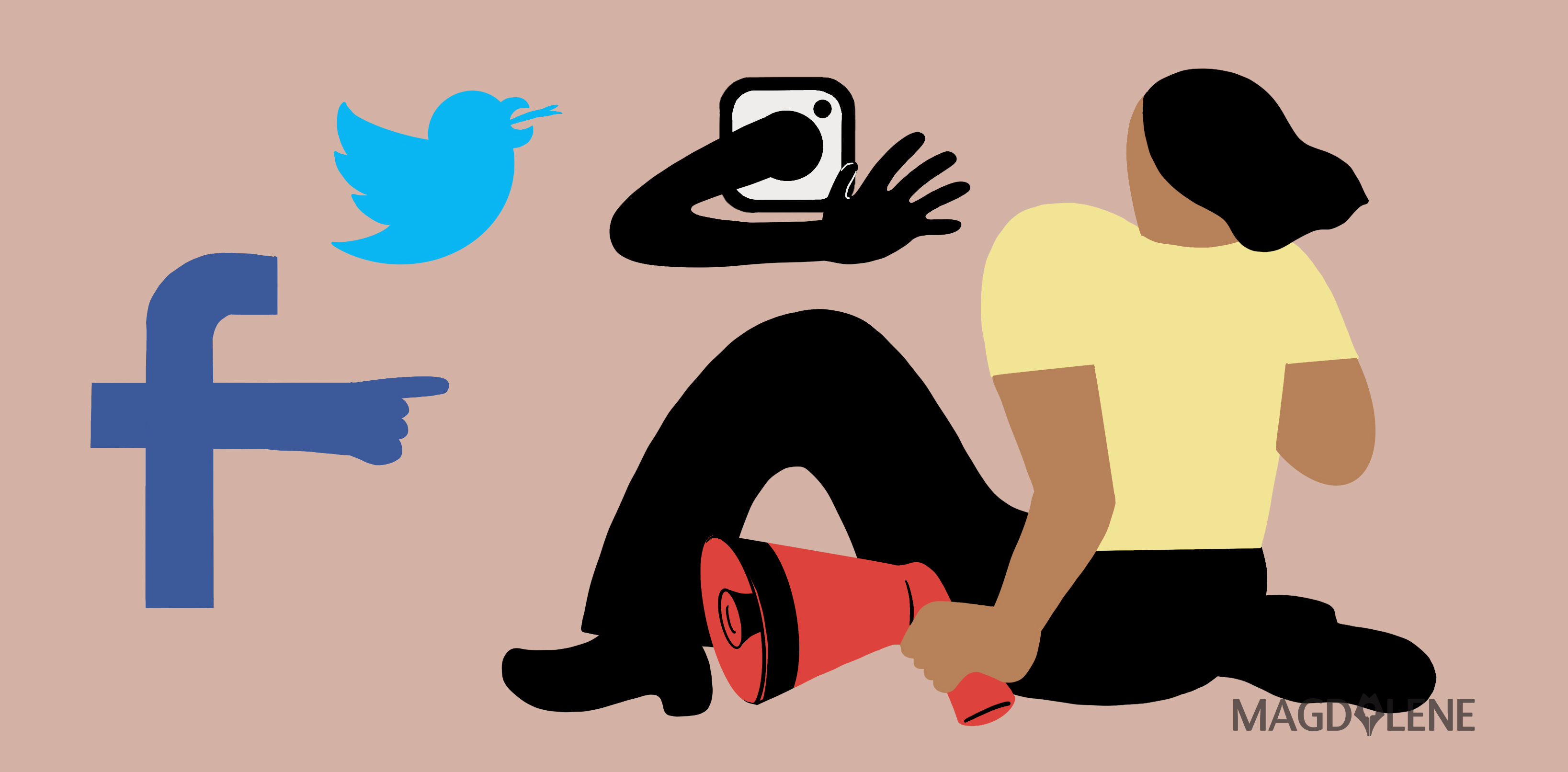




Comments