Kita mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata seperti burnout, coping (with) stress, self-love, dan beragam istilah terkait isu kesehatan mental karena itu semua mudah ditemukan di media sosial. Keterbukaan pada isu kesehatan mental semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Satu dekade belakangan ini, kesadaran tentang kesehatan mental sering dikampanyekan oleh praktisi psikologi, psikiatri, dan kesehatan masyarakat.
Pandemi, selain membuat sebagian besar kita jadi lebih memperhatikan kesehatan fisik, juga membuat kita lebih memperhatikan sisi mental.
Ada beragam cara sering dibagikan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental secara individual, dari meditasi, yoga, afirmasi positif (pernyataan positif bagi diri sendiri maupun orang lain, self-compassion (sikap untuk memberikan kebaikan pada diri dan memahami diri sendiri), hingga terapi dengan bantuan hewan (peliharaan) atau pet therapy.
Namun, benarkah kesehatan mental semata-mata berada pada tataran individu, sehingga cara meningkatkannya adalah lewat terapi individual saja?
Adakah hal-hal lain yang lebih besar pengaruhnya atas individu, hal-hal yang bersifat struktural dan ideologis misalnya?
Bagaimana jika ternyata, cara pikir atau ideologi negara tentang individu (misalnya gagasan tentang warga negara yang baik itu seperti apa) berdampak bagi kesehatan mental warga negara?
Inilah yang saya dan rekan-rekan teliti dalam studi kami pada awal 2020 tentang kesehatan mental remaja dalam konteks pendidikan menengah di Indonesia.
Kami menemukan setidaknya ada tiga konstruksi ideologis kuat pengaruhnya dalam sistem pendidikan kita, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan mental remaja di Indonesia saat ini.
Patriotis, Kapitalis, Moralis
Saya meneliti topik ini bersama rekan peneliti Francesca Salvi dan Paul Gorczynski dari University of Portsmouth, dan Tanya Wells Brown dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Inggris.
Kami menelaah buku-buku mata pelajaran Kewarganegaraan, dokumen-dokumen kebijakan pendidikan, pernyataan-pernyataan tokoh bangsa yang relevan di media, dan berbincang dengan murid-murid sekolah menengah pertama dan guru-guru di Surabaya, Jawa Timur.
Tanpa berniat melakukan generalisasi, studi kualitatif ini mencoba membongkar narasi dominan yang melandasi cara-cara pandang tentang warga negara yang baik dan dampaknya bagi kesehatan mental remaja.
Pertama, analisis data kami menemukan narasi patriotisme yang bernuansa maskulin. Buku-buku pelajaran Kewarganegaraan tingkat pendidikan menengah saat ini masih penuh dengan ide-ide tentang nasionalisme warisan rezim militer Orde Baru.
Alih-alih nilai-nilai demokrasi tentang bagaimana warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara, buku-buku pelajaran ini lebih menitikberatkan pada kewajiban warganegara untuk membela bangsa, mengabdi, dan berkorban bagi negara.
Kisah-kisah heroik pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan dan atlet peraih medali olimpiade menjadi contoh-contoh yang sering dikutip dalam buku-buku ini.
Dalam konteks pendidikan, patriotisme seperti ini diterjemahkan menjadi ketundukan mutlak pada otoritas sekolah dan rasa bangga berjuang mencapai prestasi dalam lomba-lomba.
Gambaran generasi muda ideal di sini adalah mereka yang tangguh, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan siap memenuhi panggilan atau tuntutan sekolah dan bangsa.
Baca juga: Sistem Zonasi Sekolah Hapus Bias Kelas
Citra ini sangat maskulin. Remaja yang berhati lembut dan pandai merefleksikan perasaannya, merawat kebahagiaan diri, dan memperhatikan kesehatan mentalnya tidak sesuai dengan gambaran ideal patriotik maskulin tersebut. Generasi yang lembek dan mudah menyerah – demikian tuduhan yang dilontarkan.
Kedua, data kami menunjukkan bahwa ideologi kapitalisme pasar bebas (atau yang lebih dikenal dengan neoliberalisme) telah merasuki dunia pendidikan Indonesia dan ikut mendefinisikan gambaran ideal remaja Indonesia.
Mantra-mantra kapitalistik tentang daya saing bangsa dan sumber daya manusia yang andal begitu dominan di benak pembuat kebijakan pendidikan; seolah tujuan utama pendidikan hanyalah mencetak tenaga kerja siap pakai.
Tekanan mencapai prestasi akademik sesuai indikator capaian dan tuntutan pasar pun mengemuka dalam praktik pendidikan. Generasi muda ideal digambarkan sebagai mereka yang ambisius, kompetitif, pekerja keras, dan siap menghadapi tuntutan apa pun yang diberikan atasan.
Kesehatan mental tidak mendapat ruang dalam semangat kapitalistik seperti ini. Responden remaja kami mengeluhkan bagaimana kurikulum yang berat dan tuntutan akademik tinggi membuat mereka tidak bahagia. Guru-guru pun mengeluhkan kurangnya waktu dan kesempatan untuk memperhatikan kesehatan mental diri dan siswa.
Yang ketiga adalah moralisme yang diajarkan dalam nuansa agamis dan hubungan ala paternalisme. Narasi-narasi ketaatan pada moral, pada norma masyarakat, dan pada tatanan sosial mewarnai buku-buku pelajaran Kewarganegaraan dan praktik pendidikan kita.
Alih-alih kritis mempertanyakan penindasan dan ketidakadilan sistemik, generasi muda diharapkan patuh dan ikut menjaga tatanan moral yang dibuat otoritas, misalnya melaporkan temannya yang melanggar aturan sekolah.
Retorika agamis pun membungkus ide-ide ini di buku pelajaran Kewarganegaraan; seolah menyiratkan bahwa kepatuhan mutlak pada aturan buatan penguasa adalah kehendak Sang Ilahi.
Situasi ini semakin parah dengan konteks hubungan di dunia pendidikan berdasar paternalisme: guru diposisikan sebagai sosok yang mulia dan otoritatif; siswa hampir tidak memiliki ruang untuk mempertanyakan.
Salah satu contoh yang jelas digambarkan dengan foto di buku pelajaran Kewarganegaraan adalah praktik menunduk dan mencium tangan guru sebagai contoh perilaku remaja yang baik.
Di satu sisi, kami memahami nilai-nilai kearifan agama dan budaya lokal yang dimaksud. Namun, di sisi lain kami mengidentifikasi bagaimana relasi paternalistik dan moralisme membatasi ruang bagi kebebasan individu untuk membuat pilihan sendiri dan penghargaan terhadap konsep diri yang beragam – yang notabene adalah komponen penting bagi kesehatan mental individu.
Memeriksa Lebih Dalam, Lebih Jauh
Dari hasil studi ini kami menyarankan setidaknya tiga hal. Pertama, peneliti dan praktisi kesehatan mental perlu mulai memperhatikan dimensi-dimensi struktural, ideologis, dan kontekstual agar peningkatan kesehatan mental lebih efektif, bukan hanya ujung gunung es pada tataran individu saja.
Baca juga: Naik Kelas tapi Tak Belajar: Mandeknya Capaian Pendidikan Anak-anak Indonesia
Kedua, kami mendorong peneliti dan praktisi kesehatan mental untuk mendefinisikan ulang dan menggali potensi yang dimiliki oleh kearifan agama dan budaya lokal dalam memajukan sekaligus mempertanyakan konsep kesehatan mental.
Harus diakui, konsep dan praktik kesehatan mental modern yang kita kenal saat ini adalah ciptaan Barat yang mengandung narasi-narasi kolonial.
Ketiga, kami mengajak individu-individu terutama generasi muda untuk melihat isu kesehatan mental secara kritis: bahwa orang yang mengalami masalah kesehatan mental bukan saja “pesakitan yang perlu disembuhkan”, tapi korban ketidakadilan struktural dan ideologis.
Tanpa mengecilkan pentingnya yoga, meditasi, dan afirmasi positif, bergerak memperjuangkan transformasi sosial-ideologis bisa jadi adalah proses yang terapeutik.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.




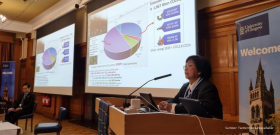
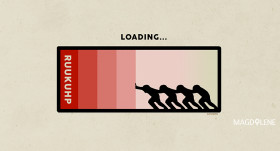

Comments