Ada banyak yang terjadi di malam penganugerahan Oscars 2022, Senin, 28 Maret kemarin. Tapi, momen Will Smith menampar Chris Rock masih belum habis dibahas, setidaknya sampai pekan kemarin hampir selesai.
Kebanyakan orang terbagi jadi dua kubu: satu yang membela Chris dan menganggap kekerasan yang dilakukan Will seharusnya tak pernah terjadi; kubu lain, memperhitungkan candaan ableis Chris sebagai pemicu reaksi Will, dan harusnya orang-orang tidak membahas permasalahan ini sedangkal: kekerasan versus antikekekerasan. Ada isu diskriminasi disabilitas, politik rambut perempuan kulit hitam, dan toxic masculinity ala patriarki dalam momen tak lebih dari 5 menit itu.
Sayangnya, artikel ini tak akan mengupas diskursus momen penamparan itu. Di balik nama Oscars yang terangkat karena kasus Will Smith dan Chris Rock, ada cerita tentang betapa cengap-cengapnya festival film tahunan (konsep festival ini juga sudah digugat sejak lama) di Hollywood tersebut, berusaha mencuri perhatian audiens dunia.
Tahun lalu, perhelatan yang mencap dirinya sebagai ajang sinema paling bergengsi di dunia ini, dapat rating terendah sepanjang eksistensinya. Otomatis, label “paling bergengsi” mulai goyah, dan sebetulnya bukan terjadi baru-baru ini saja.
Beberapa tahun terakhir, The Academy, sebagai penyelenggara, selalu kena protes. Mulai dari #OscarsSoWhite, misoginis karena upah perempuan dan laki-laki yang senjang, dan runtuhnya kekuasaan Harvey Weinstein, bos Hollywood sekaligus predator seksual. Imbasnya Oscars turut kehilangan kuasa, penonton, dan pendukung.
Baca juga: Oscars Needs International Films More Than Ever—Here’s Why
The Academy tentu tidak tinggal diam. Oscars sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pusat perhatian dunia ketika membicarakan sinema. Setidaknya begitu yang dibingkai media. Mereka sudah mengelola “gengsi” tadi jadi industri hiburan dan film dengan putaran ekonomi terbesar di dunia. Kredibilitas yang dipertanyakan tentu saja jadi masalah besar buat anggotanya.
Lalu, apa saja yang coba dilakukan The Academy? Berhasilkah mereka?
Demi Gengsi dan Putaran Duit?
Di usianya yang hampir seabad, Oscars sudah jadi bagian kultur menonton dalam hidup penduduk global, bukan cuma Amerika Serikat. Sejak bisa mengingat dan tertarik pada film, saya selalu gegap gempita menyambut musim Oscars. Ikut senang saat film favorit masuk nominasi, terinspirasi dengan pidato menggugah para pemenang, dan ikut tertawa pada monolog pembukanya tiap tahun. Pengalaman ini bukan cuma dirasakan anak kecil yang punya mimpi jadi sineas suatu saat, tapi juga jadi pengalaman kolektif bagi siapa pun yang terpapar film dan media.
Semula, fungsi Oscars adalah untuk merayakan mereka yang bekerja di industri film Amerika Serikat. Memberikan jatah waktu yang sama buat tiap pemenang kategorinya untuk tampil di podium dan memberikan pidato. Satu-satunya malam yang memberikan lampu sorot dengan porsi adil buat mereka yang bekerja di depan dan belakang layar.
Sebagaimana festival film pada umumnya, Oscars juga jadi tempat sineas unjuk diri dan mempromosikan karsa mereka. Fungsi promosi ini makin kental di Oscar ketika perfilman Hollywood menguasai pasar global. Film-film Amerika Serikat didistribusikan ke bioskop-bioskop negara lain, rating televisi pun mulai dipakai sebagai takaran seberapa besar pengaruh Oscars tiap tahunnya.
Dibandingkan festival film lainnya, pengaruh Oscars memang lebih luas. Pemenang tiap kategorinya bukan cuma dapat gengsi, tapi juga kemungkinan upah naik dan sorotan lebih besar, diikuti kemungkinan dapat projek lebih banyak, dan kesempatan masuk elite Hollywood. Dengan pengaruh sebesar itu, Oscars bukan lagi sekadar festival biasa.
“Hidupku berubah,” kata Gwyneth Paltrow pada Variety, 2019 silam, tentang kemenangannya di Oscars 1998. Wawancara itu menandai 20 tahun kemenangan Oscars pertamanya sebagai Best Actress untuk romcom Shakespeare in Love. “Kayaknya hidupku gak pernah balik ke normal lagi,” tambahnya.
Generasi ibu kita mungkin mengenal Paltrow sebagai artis romcom, tapi kini ia lebih dikenal sebagai Pepper Pots, atau pengusaha dan CEO Goop, perusahaan gaya hidup dan kesehatan multimillion yang saban tahun bikin kontroversi. Bukan cuma upahnya sebagai aktor yang berubah drastis, kesempatan jadi jutawan hingga miliuner.
Sebuah riset dari Colgate University, yang dilansir Forbes, mengatakan kenaikan upah dan status sosial itu nyata bagi para pemenang Oscars. Bagi aktor pria, bahkan persentasenya bisa sampai 81 persen ke atas. Menunjukkan isu kesenjangan upah antara pria dan perempuan masih nyata.
Baca juga: #OscarsSoWhite Still Plagues Hollywood’s Highest Achievement Awards
Bukan cuma para aktor yang kecipratan rejeki ini, para produser dan sutradara juga menjadikan Oscars tempat pertaruhan. Tradisi mempromosikan film mereka agar masuk daftar Oscars sudah lama terjadi. Baik produser independen atau studio besar akan jor-joran pada anggota The Academy demi “gengsi” ini. Penelitian di Journal of Cultural Economics (2005), menyebut jumlah uang yang dikeluarkan untuk mempromosikan sebuah film agar menang Oscars tak main-main.
“Contohnya, Universal Pictures mengeluarkan 15 juta dolar (Amerika Serikat) untuk mempromosikan A Beautiful Mind dengan 5.739 anggota Academy yang memberikan suara. Film ini menang Best Picture 2002,” ungkap riset berjudul For Oscar Glory or Oscar Money? itu.
Pertanyaannya, jika produser dan studio rela mengucurkan duit sebanyak itu untuk masuk Oscars, seberapa banyak uang mereka yang kembali?
IBISWorld yang melakukan riset sejak 2014 menyebut ada kenaikan pemasukan 247,2 persen pada tiap film yang masuk nominasi Oscars. Konon, estimasi terbarunya, para aktor dan kru film yang masuk nominasi dan menang Oscars juga mengalami kenaikan pendapatan kira-kira 20 persen.
Putaran duit itu tentu saja belum diakumulasikan dengan kategori-kategori lain, yang nominalnya bisa lebih bombastis. Apalagi, persaingan mendapatkan Oscars hari ini makin marak dengan terlibatnya perusahaan-perusahaan streaming film raksasa macam HBO, Netflix, dan lainnya.
Dengan hitung-hitungan ini, Oscars jadi sumber duit bagi anggota The Academy yang panen “hadiah” tiap tahun. Sekaligus berpotensi jadi tempat terjadinya nepotisme dan suap. Isu suap ini juga bukan hal baru. Salah satu kasus paling terkenal adalah upaya suap yang dilakukan film Scent of a Woman (1993) yang dibintangi Al Pacino. Dugaan itu diterbitkan dalam sebuah laporan investigasi di The New York Times, 1993.
Masalahnya, suap dan nepotisme bukan satu-satunya masalah yang muncul dari pemusatan Oscars sebagai acuan kesuksesan sebuah film. Berkali-kali, masalah representasi selalu muncul dalam beberapa dekade terakhir karena isi The Academy yang dipenuhi orang-orang kulit putih, dan didominasi laki-laki cis-heteroseksual. Ini berdampak pada film-film yang mereka pilih masuk nominasi dan dimenangkan.
Oscars Harus Terus Diprotes
Belakangan, diskriminasi pada film-film lain yang tidak diproduksi Hollywood juga muncul makin garang. Akademisi Georgia Parr, salah satunya. Di The Conversation, ia menulis kategori Best International/Foreign Film adalah contoh betapa problematisnya Oscars dan The Academy.
“Sejauh ini, yang paling problematis dari area kategori film internasional adalah bagaimana ia memperkokoh gagasan lama bahwa ‘sinema dunia’ berpusat di sinema Euro-America,” kata Parr. Maksudnya, salah satu dosa paling besar yang diciptakan Oscars lewat kategori ini adalah ilusi bahwa film-film yang tidak berbahasa Inggris, dan dibikin oleh orang yang tidak berkulit putih bukanlah film yang “layak” masuk pasar arus utama.
Di titik lebih jauh, kategori “Ini melanggengkan warisan kolonial yang terus menopang (ilmu) kritik, teori, produksi, dan distribusi film (di dunia),” ungkap Parr.
Demi menghindari kritik ini, nominasi Best Picture tahun ini dan Best International Picture diisi dengan deretan terbanyak sepanjang Oscars pernah ada. Setelah rating anjlok di 2021, The Academy merasa perlu banyak berbenah.
Selain itu, mereka juga mengurangi beberapa kategori yang dipilih untuk tidak ditayangkan langsung dan membuat beberapa kategori populer (macam #OscarsFanFavorite dan #OscarsCheerMoment), untuk menggaet lebih banyak penonton. Kategori-kategori yang tidak ditayangkan adalah: Best Original Score, Film Editing, Production Design, Makeup and Hairstyling, Sound, Documentary Short Subject, Live Action Short Film and Animated Short Film.
Keputusan ini kemudian diprotes sejumlah asosiasi pekerja film Hollywood dan beberapa nama raksasa seperti: James Cameron, Kathleen Kennedy, Guillermo del Toro, dan John Williams. Keputusan itu dianggap “membuat penilain berlebihan pada satu disiplin filmmaking di atas disiplin lainnya, sekaligus menurunkan derajat kategori-kategori itu jadi warga kelas dua.”
“Semua ini membuat The Academy jadi kurang relevan. Bukannya malah lebih relevan, seperti tujuan mereka,” kata Scott Bomar, komposer pemenang Emmy, yang pernah terlibat untuk Dolomite is My Name, Hustle & Flow, dan Black Snake Moan. Ia jadi salah satu yang memprotes keputusan The Academy tersebut dan mengkritisi upaya The Academy untuk jadi lebih relevan. “Yang mereka lakukan malah kebalikannya,” tambahnya pada The Washington Post.
Baca juga: Film di Asia Tenggara Belum Inklusif, Minim Representasi Lesbian dan Transpuan
Tak heran, banyak orang yang mengira insiden penamparan yang dilakukan Will Smith pada Chris Rock adalah settingan untuk menaikkan rating Oscars. Meski hal itu tidak terbukti dan mendiskusinya jadi lebih sulit karena isu politis yang membelit peristiwa tersebut.
Namun, yang bisa terus kita bicarakan adalah bagaimana mendorong Oscars untuk terus berevolusi jadi lebih baik. Drama after drama yang muncul tiap tahun dalam penyelenggaraannya memang berhasil menyelamatkan rating Oscars (sebagaimana kenaikan yang dialami tahun ini), tapi tak menyembuhkan industri film dari masalah sebenarnya: whitewashing, rasisme, representasi gender yang timpang, nepotisme, dan serangkaian problem turunannya.





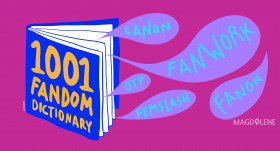


Comments