Bagi kebanyakan orang, punya pasangan yang setia dan hubungan keluarga yang baik itu sangat penting. Tak terhitung banyaknya novel, cerita dongeng, dan juga film yang telah mengangkat cerita romantis sehingga membuat kita jatuh cinta dengan kisah asmara.
Namun, para sosiolog merupakan golongan yang kurang romantis. Dalam hal jatuh cinta, bukan cuma takdir atau kebetulan yang indah yang menyatukan pasangan, faktor-faktor sosial juga penting.
Bagaimana mungkin? Penelitian saya menggambarkan bagaimana sikap kita terhadap sang kekasih dipengaruhi norma sosial.
Meskipun beberapa dari kita masih terlalu muda untuk mengingat hal ini, sekitar tiga dekade yang lalu, prospek perempuan berpendidikan tinggi untuk dapat menikah menjadi tajuk utama dan bahkan menjadi bahasan utama majalah Newsweek pada 1986.
Banyak perempuan dibuat cemas karena pesan-pesan media tersebut. Seperti yang diceritakan dalam film komedi romantis berjudul Sleepless in Seattle, yang salah seorang tokohnya bilang, “Lebih memungkinkan untuk dibunuh oleh teroris dibandingkan menemukan seorang suami setelah berumur 40 tahun.”
Kesimpulan umum saat itu adalah bahwa perempuan berusia di atas 40 tahun yang telah mencapai tingkat profesi (dan pendidikan) yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk menikah.
Baca juga: Melajang Bukan Karena Tak Ketemu Jodoh, Tapi Karena Jodoh Tak Sesuai Harapan
Apa benar? Apakah perempuan yang menghabiskan bertahun-tahun bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik mengorbankan kesempatan mereka untuk menikah?
Sebenarnya, tidak. Penelitian secara konsiten menemukan bahwa perempuan Amerika yang bergelar setidaknya sarjana punya kemungkinan lebih besar untuk menikah dan dan mempertahankan pernikahan mereka dibandingkan perempuan dengan tingkat pendidikan lebih rendah.
Bahkan, hanya beberapa tahun setelah cerita Newsweek tersebut, sosiolog keluarga Andrew Cherlin membantah pesan-pesan yang keliru mengenai prospek menikah perempuan karier.
Kesenjangan pendidikan suami-istri
Di Amerika Serikat, sebelum tahun 1980-an, perempuan tertinggal di belakang laki-laki dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Namun pada 2013, perempuan memperoleh kurang lebih 60 persen gelar sarjana dan gelar master serta setengah dari semua gelar doktor.
Penelitian saya mengambil data dari sensus AS tahun 1980 dan survei komunitas Amerika 2008-2012 untuk meneliti pasangan suami istri, dan mengamati pendidikan dan tingkat pendapatan pasangan yang baru menikah. Saya menemukan di antara tahun 1980 dan 2008-2012, kemungkinan perempuan menikah dengan laki-laki yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dari mereka meningkat.
Jumlah pasangan yang suaminya memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari sang istri menurun hampir 10 persen dari 24 persen pada 1980 menjadi 15 persen di tahun 2008-2012. Pada periode yang sama, pasangan yang istrinya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari sang suami meningkat dari 22 persen menjadi 29 persen.
Jadi, selama 2008-2012 di AS, lebih besar kemungkinan perempuan menjadi pasangan yang memiliki edukasi yang lebih tinggi dalam pernikahan dibandingkan laki-laki.
Karena sejak dulu laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah dan menjadi “kepala” keluarga, saya ingin tahu apakah hal terkait pendidikan pasangan ini mengubah peran mereka?
Apakah pendidikan memberi lebih banyak kuasa dalam perkawinan?
Bersatunya perempuan berpendidikan lebih tinggi dengan laki-laki dengan pendidikan lebih rendah dalam sebuah pernikahan tidak berarti sang istri memiliki kekuasaan yang lebih dalam pernikahan.
Secara umum, perempuan masih menikahi laki-laki yang berpenghasilan lebih besar darinya. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat bahwa perempuan mendapat penghasilan lebih rendah daripada laki-laki dan status pencari nafkah pada suami tetap ada.
Baca juga: Kesenjangan Gender di Dunia Profesional, Mulai dari Upah sampai Penugasan
Penelitian saya menemukan bahwa kecenderungan perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang memiliki penghasilan di atas mereka itu lebih besar dibandingkan kecenderungan perempuan menikah dengan laki-laki yang memiliki pendidikan lebih rendah. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan masih sering bersatu dalam pernikahan ketika status ekonomi perempuan tidak melebihi laki-laki.
Meskipun laki-laki lebih memprioritaskan prospek keuangan dari calon pasangan hidup dari waktu ke waktu, mereka mungkin menilai status perempuan hanya sampai pada titik di mana status pasangan mereka melebihi status mereka sendiri. Dalam hal ini, laki-laki mungkin ragu untuk menikahi perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi dari mereka.
Sementara itu, karena kesetaraan pendapatan telah meningkat secara drastis dalam beberapa dekade terakhir, perempuan mungkin akan rugi lebih banyak apabila mereka menikah dengan pasangan yang kemampuan ekonominya lebih rendah.
‘Perempuan sisa-sisa’ di Cina
Jadi, di AS, laki-laki dan perempuan berpendidikan tinggi lebih cenderung untuk menikah dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Sebaliknya, di Cina, perempuan yang berpendidikan tinggi (tapi bukan laki-laki yang berpendidikan tinggi) mungkin akan kesulitan mencari pasangan hidup.
Para perempuan di Cina telah melampaui para laki-laki dalam jumlah perkuliahan. Penelitian saya sebelumnya mengenai Cina urban kontemporer menemukan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, maka kemungkinan mereka menemukan pasangan hidup semakin menurun, sebaliknya kemungkinan ini meningkat bagi laki-laki.
Media dan publik di Cina menggunakan istilah yang derogatif, “perempuan sisa” untuk mendeskripsikan para perempuan urban yang berpendidikan tinggi ini. Di Cina, prospek rendah untuk menikah bagi perempuan berpendidikan tinggi berkaitan erat dengan peran yang seharusnya dimainkan suami istri dalam keluarga.
Peran pencari nafkah pada suami dan peran ibu rumah tangga pada istri masih sangat kuat di keluarga-keluarga di Cina. Dalam konteks ini, perempuan yang berorientasi pada karier dianggap “egois,” “tidak feminin” dan “tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga,” sedangkan kegagalan suami untuk memenuhi perannya sebagai pemberi nafkah sering kali menjadi sumber utama konflik dalam pernikahan.
Berbeda dengan AS, di mana laki-laki sekarang cenderung menikahi perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dari mereka, praktik tradisional di mana laki-laki menikahi perempuan yang memiliki pendidikan lebih rendah dari mereka bertahan di Cina.
Baca juga: Menikah: Menghidupkan atau Mematikan Diri Perempuan?
Meskipun baik Cina dan AS mengalami berbaliknya kesenjangan gender di tingkat pendidikan tinggi, perbedaan antara AS dan China dalam pola pernikahan mengisyaratkan bahwa faktor struktural, seperti norma gender di masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk prospek pernikahan seseorang.
Laki-laki menikahi perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah dari mereka merupakan sebuah norma sosial yang diterima secara luas. Norma ini bekerja dengan baik pada masa lalu saat pendidikan perguruan tinggi masih jarang dan laki-laki umumnya lebih berpendidikan daripada perempuan. Di AS, evolusi budaya dalam preferensi pasangan sesuai dengan perubahan dalam tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan.
Namun di Cina urban, tidak demikian. Perubahan menuju peran gender yang lebih setara tidak berjalan bersama-sama dengan perubahan sosial yang pesat. Jenis pernikahan tipe laki-laki pencari nafkah sementara perempuan menjadi ibu rumah tangga memberi sedikit keuntungan bagi perempuan Cina yang berpendidikan tinggi. Malah, mereka justru mungkin menunda atau bahkan tidak menikah.
Berbaliknya kesenjangan gender dalam pendidikan terjadi hampir secara global, maka ada baiknya mendapatkan informasi lebih agar kita dapat memahami bagaimana meningkatnya pendidikan perempuan berdampak pada pernikahan dan kehidupan berkeluarga.
Dalam hal pernikahan, bukan hanya takdir dan cinta yang menyatukan pasangan. Faktor-faktor sosial seperti pendidikan dan aturan-aturan gender yang berlaku juga memainkan peran penting.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.



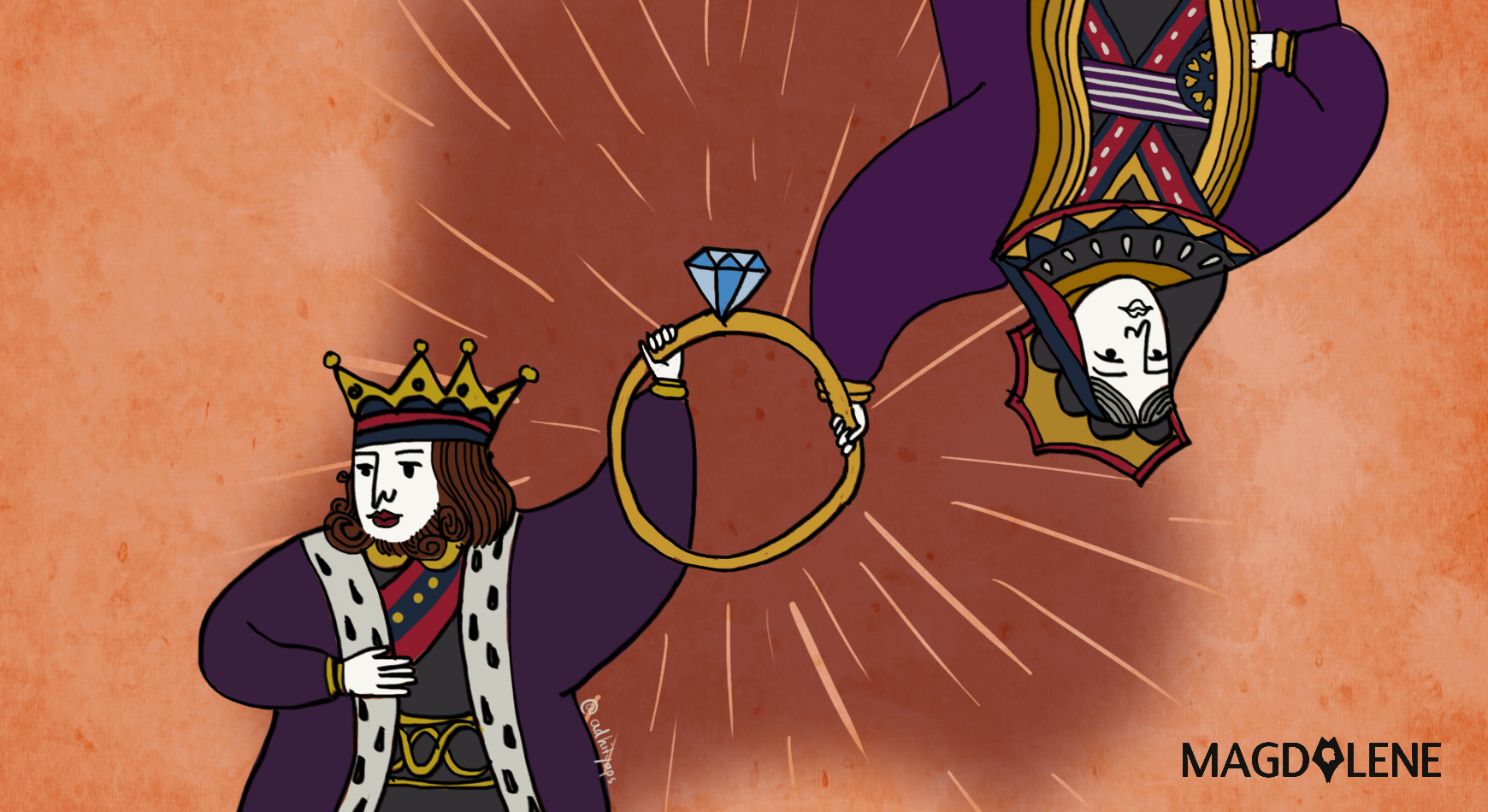



Comments