Sejak lahir kedirian perempuan kerap disebut milik dan tanggung jawab ayah atau kerabat laki-lakinya. Setelah perempuan menikah, kedirian dan tanggung jawab itu menjadi milik suaminya.
Contohnya, istri yang memilih childfree dinilai menentang kodratnya sebagai pemilik rahim. Pun, perempuan dihakimi habis-habisan jika melepas jilbabnya, demikian juga mereka yang memilih berjilbab panjang dan mengenakan cadar. Tak hanya itu, ada juga hadis yang menyebutkan istri akan dilaknat malaikat sampai subuh jika menolak berhubungan seksual dengan suaminya.
Karenanya, eksistensi tubuh perempuan tidak sepenuhnya berada dalam genggaman sendiri. Peneliti kajian gender dan feminisme Islam Masthuriyah Sa’dan berargumen otoritas tubuh muslimah selalu dimiliki oleh dirinya sendiri, bukan keluarga maupun suaminya.
Pasalnya, dalam Islam ada konsep al-harakah, al’ ‘adalah dan al-musawarah atau keadilan serta kesetaraan, Masthuriyah mengatakan, diajarkan menggunakan penafsiran hadis dengan pendekatan harga diri manusia. Adapun penafsirannya berupa wacana yang manusiawi dan menghormati manusia
“Pengalihan wewenang tubuh perempuan atas dalih agama, sosial, dan budaya merupakan pelanggaran hak karena Islam mengenal konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Islam juga mengenal konsep keadilan dan kesetaraan,” ujarnya dalam sesi webinar “Tubuh Muslimah Milik Siapa” oleh Magdalene Learning Club, Awal April lalu.
Ia melanjutkan, penegasan tubuh perempuan sebagai miliknya sendiri ada dalam hadis yang diriwayatkan Abu Buraidah. Bahwasanya ada perempuan yang akan dinikahkan dengan kerabatnya untuk mengangkat derajat sosial dan ekonomi keluarga. Namun, sebelum menikah perempuan itu menemui Rasulullah dan mengatakan, dia rela dinikahkan dengan kerabatnya tersebut.
Rasulullah lalu memberikan keputusan terakhir di tangan perempuan dan perempuan itu mengatakan rela dinikahkan dengan kerabatnya tersebut. Akan tetapi, dia ingin menegaskan kepada perempuan lain bahwa ayah tidak memiliki hak untuk mengurusi perihal pernikahan.
“Orang tua tidak memiliki hak soal keputusan pernikahan perempuan. Yang memiliki hak adalah perempuan itu sendiri dan hal ini bisa juga dikaitkan dengan konteks childfree. Itu hak perempuan karena tahu tubuhnya sendiri bukan orang lain. Bukan keluarganya apalagi pemuka agama,” jelas penulis buku Santri Waria tersebut.
Baca juga: Perempuan Bukan Sumber Fitnah, Pentingnya Pahami ‘Mubadalah’
Mengapa Muncul Paham Tubuh Perempuan Bukan Miliknya?
Masthuriyah mengatakan, Islam menjunjung keadilan, kesetaraan, dan otoritas tubuh perempuan. Karenanya, dalam penafsiran ayat keagamaan diperlukan pendekatan human dignity untuk menjawab pertanyaan kemanusiaan. Pasalnya, pemikiran Islam kontemporer tidak memposisikan teks keagamaan berdiri sendiri sebab pemahamannya bergantung pada sosok yang menafsirkan teks keagamaan itu.
Dengan demikian, kajian teks keagamaan kontekstual yang progresif mengaitkan ayat dengan konteks kehidupan perempuan. Meski demikian, konsep yang menjunjung HAM tersebut tidak nyaring terdengar. Karenanya banyak yang menilai Islam tidak melindungi dan melakukan pemaksaan terhadap perempuan. Mengutip Amina Wadud, ungkap Masthuriyah, penyebabnya berupa penafsiran ayat Al-quran yang bias gender.
Kajian poligami, ujarya, cendekiawan muslim membenarkan laki-laki melakukan poligami dua sampai empat kali karena disebutkan dalam ayat ketiga surah an-nisa. Namun, ayat tersebut tidak dimaknai seutuhnya dan melupakan bagian ayat yang menyebutkan jika ada kekhawatiran tidak berlaku adil, maka menikah dengan satu saja. Atau dengan hamba sahaya yang dimiliki, dengan demikian lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.
Akan tetapi, melihat situasi di Indonesia khususnya tentang poligami, tokoh agama menggunakan teks keagamaan untuk kepentingan pribadi, bukan Islam secara komprehensif. Ada bias penafsiran, sehingga membenarkan poligami sementara ada hal yang harus dijadikan pertimbangan, seperti berperilaku adil. Namun, itu tidak terdapat dalam penafsiran yang bias pada perempuan.
“Ini yang tidak disebutkan ulama klasik, ustad, dan kyai bahwa yang dinikahi adalah janda. Kalau ustad sekarang menikah dengan gadis yang berusia muda. Beda jauh dengan yang diajarkan Nabi dan tidak secara utuh diikuti pemuka agama,” ujarnya.
Baca juga: Buku Sejarah Melenyapkan Perempuan dalam Islam
Selain itu, Masthuriyah mengutip Fetima Mernissi, feminis dan seorang cendikiawan muslim, penyebab lainnya ialah teks keagamaan yang dipahami secara misoginis. Mengambil contoh sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Bakar bahwa tidak beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Fetima mengkritisi hadis tersebut sebagai misoginis sebab secara kontekstual sejarah dan budaya hadis itu diriwayatkan pada masa konflik Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ali.
“Sebelum itu hadis ini tidak pernah disebut sama sekali. Jadi hadis misoginis tidak bisa dijadikan dalil atau argumentasi. Anehnya, ketika ada perempuan mau menjadi pemimpin, hadis ini digoreng untuk menundukkan calon perempuan agar tidak mencalonkan,” jelasnya.
Penyebab ketiga berupa budaya patriarki yang mengakar dan memengaruhi budaya dan cara memahami teks keagamaan. Selain itu, tokoh atau pengajar agama yang belum memahami isu gender, sehingga menormalisasi kekerasan hingga pemerkosaan dalam pernikahan, seperti dalam kitab kuning di pesantren dianggap sebagai hal biasa.
“Ketidaktahuan ini membuat proses kekerasan terus berjalan dan menjadi kewajaran. Kalau pesantren membuka ruang dan wacana dalam gender serta feminisme mungkin kitab ini akan dicabut,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang melihat persoalan kemanusian dalam konteks hak asasi manusia. Jangan sampai saat kita menjalani sunnah kita melanggar hak perempuan,”
Baca juga: Bagi Kelompok Anti-Feminisme, Ketertindasan Perempuan adalah Ilusi
Konstruksi Masyarakat Sebabkan Pembedaan Laki-laki Perempuan
Masthuriyah menyatakan, ada hadis yang menyebutkan semua orang, laki-laki, perempuan, dan kelompok minoritas gender maupun seksualitas, terlahir dengan keadaan suci atau fitrah. Hal yang kemudian menentukan anak tersebut harus feminin, maskulin, atau memeluk agama tertentu ialah konstruksi sosial dari orang tua dan kondisi lingkungannya.
Konstruksi tersebut membedakan dan memarginalisasikan anak-anak tersebut sejak lahir. Anak laki-laki, misalnya, dalam proses akikahnya harus menyembelih dua ekor kambing, sementara satu untuk anak perempuan. Proses akikah itu sendiri merupakan ajaran budaya Arab yang terakulturasi dalam ajaran agama dan menjadi kewajiban syariat Islam dan diatur dalam hukum fikih, ujarnya.
Pembedaan itu berlanjut ke ranah pendidikan, di mana anak laki-laki lebih didahulukan untuk mengemban pendidikan tinggi karena konstruksi laki-laki ialah imam dan perempuan adalah makmum. Lalu saat menikah perempuan tidak bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri, berbeda dengan laki-laki yang bisa menjadi wali untuk dirinya.
“Ada juga perempuan kerja di domestik yang dianggap sebagai kodrat, tetapi konstruksi sosial budaya. Tidak apa-apa perempuan kerja di publik dan menjadi pemimpin. Begitu pun laki-laki jadi bapak rumah tangga,” kata Masthuriyah.
Karenanya, untuk meyakinkan muslimah bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri memang butuh proses kesedaran gender yang tidak berjalan cepat. Namun, proses itu juga perlu dilakukan laki-laki yang harus sadar tentang agama berkeadilan gender dan tubuh perempuan adalah milik perempuan itu sendiri.
“Apa yang saya (perempuan) mau, itu yang saya perjuangkan dan orang lain tidak boleh membatasi keinginan saya. Kalau dibatasi itu melanggar hak. (Namun) bicara seperti ini tidak mudah dan harus ada proses kesadaran gender dulu,” tandasnya.





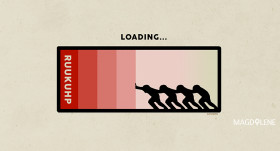


Comments