Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menarik perhatian publik kembali setelah video wawancaranya dalam channel Daniel Tetangga Kamu milik presenter dan aktor Daniel Mananta diunggah di YouTube pada 2 Juli lalu. Salah satu topik perbincangan mereka menyinggung rumah tangga BTP, atau dulu akrab dipanggil Ahok, dengan mantan istrinya, Veronica Tan, yang berakhir pada 2018 lalu ketika Ahok masih dipenjara dengan tuduhan penistaan agama.
Dalam tayangan bertajuk “Usaha BTP untuk Menyelamatkan Rumah Tangganya” yang disukai oleh 14 ribu akun YouTube, BTP membicarakan soal perselingkuhan Veronica serta kelakuan teman dekat Veronica saat BTP memintanya untuk tidak lagi dekat dengan sang mantan istri.
“Harga diri saya diinjak-injak. Sebagai laki-laki, sebagai gubernur, dan saya lebih berkuasa dan saya lebih kuat posisinya, dan dia salah gitu kan. Tapi saya kan tidak mau mempermalukan istri saya waktu itu. Ini kan tetap mamanya anak-anak. Saya juga pengen menutup aib ini, kan saya juga pengen keluarga saya balik. Makanya saya tutup, saya nasihatin. Tapi apa yang saya dapet? Makin berani…” demikian petikan pernyataan BTP dalam video tersebut.
Sebelum BTP menceritakan soal rumah tangganya yang dulu, hal serupa pun dilakukan pesinetron Galih Ginanjar dalam sebuah video di channel YouTube Rey Utami dan Benua pada 20019 lalu. Di sana, Galih menceritakan berbagai keburukan mantan istrinya, Fairuz A. Rafiq, termasuk menyebut vulva mantan istrinya berbau seperti ikan asin. Setelah saya telusuri, ternyata perselisihan kedua orang tersebut telah berlangsung sejak mereka bercerai dan keburukan satu sama lain pun pernah tersebut di media-media.
Setali tiga uang dengan dua public figure ini, mantan istri Reza SMASH, Fabiola Elizabeth Agnes pun pernah membeberkan keburukan laki-laki tersebut pada Juni lalu. Dilansir Tempo, setelah terpicu oleh komentar ibu Reza dalam sebuah artikel, Fabiola pun menuliskan di Instagram Story-nya bahwa Reza adalah tukang mabuk, berselingkuh, dan memakai narkoba.
Fabiola juga memaparkan perjanjian antara dirinya dan Reza yang dibuat setelah mereka berpisah. Namun, menurut Fabiola, Reza mengingkari janjinya untuk tidak mengulang bad habit seperti main perempuan, mabuk, dan memakai narkoba dengan membawa pulang seorang perempuan lain beberapa hari setelah Reza berjanji.
Shaming dan balas dendam
Di era media sosial seperti sekarang, banyak orang yang merasa bahwa pernyataan di Instagram, Twitter, Facebook, atau Youtube adalah senjata yang ampuh untuk membalas perlakuan buruk mantan pasangan. Meski kekuatan tindakan ini tidak sebesar hukuman penjara atau denda, shaming mantan tetap populer juga karena bisa memberi kepuasan tersendiri bagi seseorang, terlebih saat ia melihat mantannya dicap buruk pula oleh orang lain. Sederhananya, mencari massa banyak-banyak untuk menjadikan mantan sebagai public enemy.
Baca juga: Cara ‘Move On’ dari Mantan ala Harley Quinn dalam ‘Birds of Prey’
Membalas memang merupakan reaksi yang normal muncul begitu seseorang tersakiti. Namun yang menarik bagi saya adalah ternyata, membalas dengan melibatkan penonton digemari oleh banyak orang. Jika melihat sejarah, hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak lama sekali. Lihat bagaimana orang berkumpul menyaksikan orang meregang nyawa berkat tebasan guillotine atau hukuman gantung. Ingat juga bagaimana orang bersorak ketika ada dua orang bergulat saling hajar dan pihak yang menang meraup dua kesenangan sekaligus: Mengalahkan lawan dan dipandang sebagai jagoan. Membalas dengan shaming seperti sekarang melanggengkan kebiasaan macam itu.
Tidak hanya sebagai balasan atas tindakan tak menyenangkan dari mantan, shaming pun bisa menjadi suatu alat untuk mendongkrak citra diri dan simpati publik. Tidak sedikit juga yang menempatkan diri sebagai korban dalam suatu relasi dengan harapan audiensnya memberi dukungan dan melihatnya sebagai protagonis selepas kandas hubungannya dan sang mantan.
Sangat lumrah sebenarnya bila ia merasa sangat marah, kecewa, kesal, juga sedih atas akhir yang buruk dari relasinya serta saat mengingat tindakan-tindakan mantan yang menyakitinya. Namun, shaming sebagai perwujudan emosi-emosi tersebut merupakan hal yang seburuk-buruknya pilihan menurut saya.
Alih-alih berkonsentrasi membalas dendam, kita bisa mengalihkan perhatian pada hal lain. Saya tidak bilang salah satunya adalah memaafkan dan menerima keadaan dengan segera loh, ya. Atau cepat-cepat berpikir positif dan “mengambil hikmah” dari tiap kejadian yang kita hadapi.
Kita bisa, misalnya, mulai kembali memperhatikan diri sepenuhnya, mengidentifikasi di mana bocel-bocel diri kita yang sempat muncul ketika berelasi dengan mantan dan memikirkan bagaimana memperbaiki atau memulihkannya. Bisa juga kita menjajal hal baru yang konstruktif yang membuat kita menjadi versi terbaik diri kita, yang pada akhirnya mengalihkan perhatian dan kemarahan kita terhadap mantan. Tidakkah tepat kata Kunto Aji dalam “Sulung”, “yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri”?
Berkeluh kesah vs umbar aib
Setelah relasinya kandas dengan tidak baik-baik, sangat wajar bagi seseorang untuk menumpahkan emosi dan menceritakan pengalamannya ke satu dua orang terdekat dan tepercaya. Sebagai salah satu cara pemulihan diri, curhat ke teman atau keluarga bisa menjadi outlet yang baik, terlebih bila mereka yang dicurhati itu mau mendengarkan—bukan mendengar saja, memahami dan berempati alih-alih menghakimi atau mengutuki si mantan.
Garis bawahi kata “terdekat dan tepercaya”. Bukan kepada banyak orang, bukan lewat media sosial yang bisa diakses siapa pun termasuk orang yang tidak dikenal, bukan juga menyebut mantan dengan label-label tertentu. Ketimbang mendukung pemulihan patah hati, bercerita ke banyak orang dengan mengungkit keburukan mantan di masa lalu malah bisa menambah masalah baru, entah buat diri sendiri ataupun mantan.
Baca juga: Patah Hati Akibat ‘Ghosting’ Sungguh Melelahkan
Kenapa? Pertama, bayangkan bila audiens kita adalah teman sang mantan juga, lantas pernah pula dicurhati soal pengalaman hubungan kita dari versi si mantan. Bisa jadi kita atau mantan malah tidak dipercaya karena ada pernyataan yang berlainan.
Kedua, cap “drama queen” yang bisa disematkan orang lain kepada kita karena mereka tidak tahu sebenar-benarnya pengalaman yang sedang kita jalani. Mereka menganggap kita terlalu berlebihan meski kenyataannya, pengalaman putus tiap orang beserta cara dan kemampuan masing-masing orang menghadapinya itu berbeda.
Ketiga, menceritakan keburukan mantan secara publik tak pelak memantik pertengkaran baru dengan mantan. Kalau memang tujuan seseorang adalah menabuh genderang perang dan memang doyan ribut, ya lain cerita. Tetapi kalau ia justru mau hidup lebih tenang, lega, tak menghadapi masalah baru yang tidak seharusnya muncul, ya jauhilah keinginan buat memublikasikan permasalahan relasi yang lalu.
Belum lagi kalau si mantan terpikirkan untuk menempuh jalur hukum lantaran pernyataan kita dianggap mencemarkan nama baik. Di negara yang punya regulasi karet soal hal ini, alih-alih mendapat dukungan, kita malah bisa menerima bumerang plus hujatan sebagian orang lain.
Kesal dengan kelakuan mantan yang dulu sih oke-oke saja. “Memperingatkan” orang lain atau calon pasangan baru mantan juga sebenarnya jamak dilakukan orang setelah putus. Tetapi, jamak belum tentu sepenuhnya tepat. Mengapa? Bisa saja si mantan yang ditemui calon pasangan barunya adalah sosok yang berbeda sekali dari sosok yang kita kenal dulu. Potensial menipu? Iya, bisa jadi, tetapi barangkali juga benar kata penulis Oscar Wilde, “every saint has a past, and every sinner has a future”. Orang berubah, situasi berubah.
Terbukalah untuk menerima itu alih-alih sepanjang hidup mengecap seseorang selamanya buruk. Bukankah tidak ada yang seratus persen hitam dan putih di dunia ini?
Kalaupun mantan pernah melakukan tindakan sangat menyakitkan dan melanggar hukum, katakanlah seorang pelaku KDRT atau kekerasan dalam pacaran, atau masih mengintimidasi pasca-pisah, yang lebih baik kita lakukan adalah mengadu ke profesional psikologi, lembaga bantuan hukum, atau polisi. Orientasinya adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan membatasi perilaku mantan, bukan untuk mempermalukan atau mematikan karakternya sebagai bentuk balas dendam saja.
Pengalaman pahit pasti pernah dirasakan tiap orang yang patah hati. Saya kira, supaya ia tak terasa lebih getir, lebih baik bila kita menyimpannya sendiri, atau setidak-tidaknya hanya membagikan kepada segelintir orang untuk meringankan beban. Tidakkah diam itu lebih tepat dibanding membuka mulut dan menusuk orang dengan lidah kita?



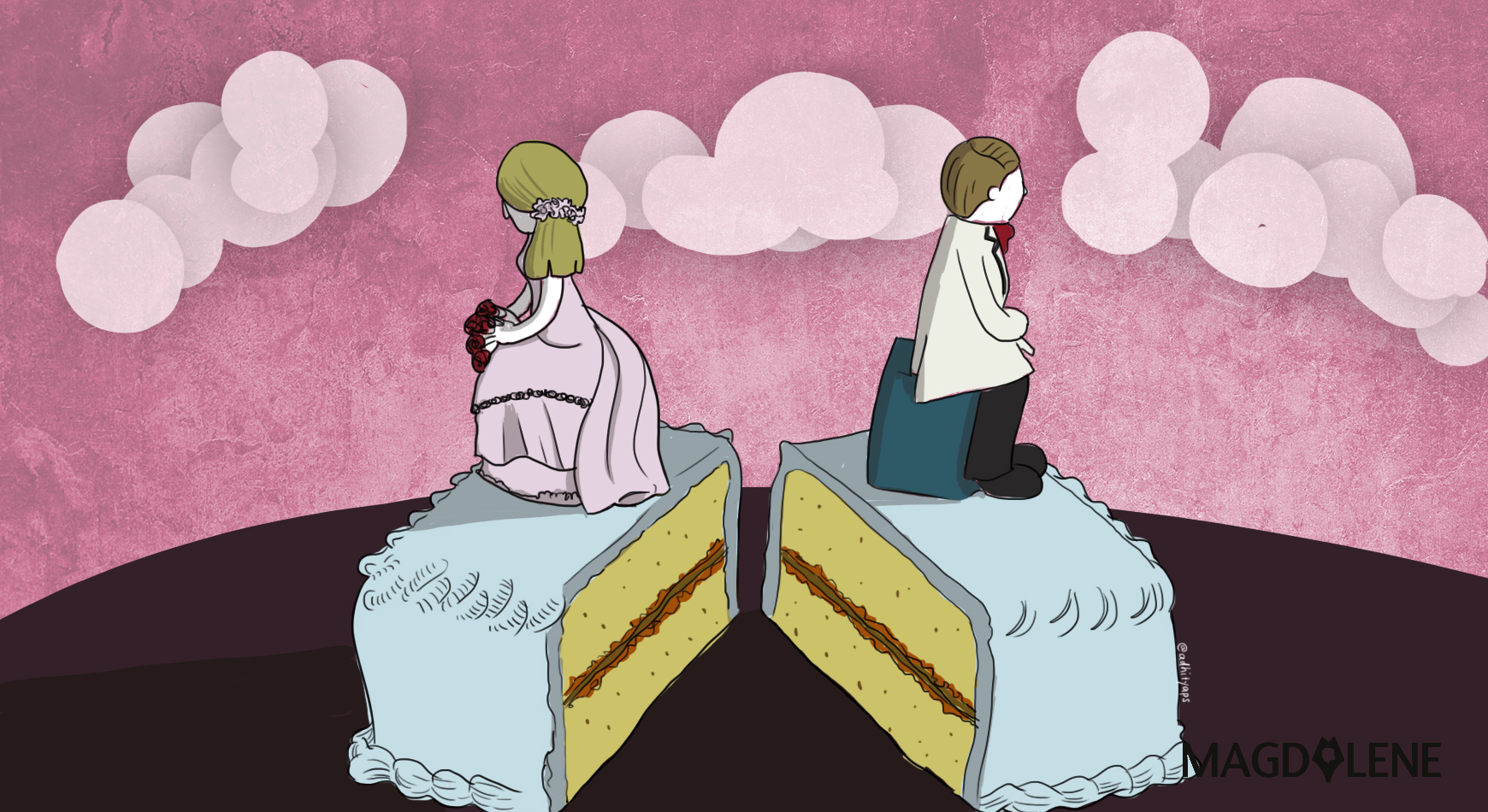




Comments