Kalau gigi saya bolong, rasanya enggak begitu susah mencari dokter untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan datang ke dokter yang bukan langganan dan di tempat yang sama sekali baru pun bukan soal. Waktu saya harus operasi caesar pun, saya enggak pakai milih-milih dulu ahli anestesi mana yang bakal menangani saya karena siapa pun yang memang sudah tersertifikasi, pasti mampu mengurus masalah itu.
Namun, beda cerita waktu berurusan dengan masalah mental.
Pengalaman pertama saya datang ke psikolog dimulai pada 2015. Waktu itu, saya sedang punya masalah relasi yang berat sampai mengganggu aktivitas harian dan kesehatan tubuh saya. Lantas, saya meminta rekomendasi psikolog ke salah seorang kawan yang kala itu masih jadi dokter residen psikiatri. Dia menyebut satu nama, “Mbak Kesya” dan saya langsung percaya Mbak Kesya pasti bisa memberi solusi manjur, padahal belum browsing apa pun soal dia. Namanya masih awam tentang kesehatan mental, saya langsung percaya, masalah bisa cepat tuntas layaknya berobat fisik ke dokter.
Saya datang ke tempat praktik Mbak Kesya, yang di depannya terdapat plang dengan nama dia. Satu jam lebih 15 menit saya bercerita, dia sempat menyebut saya ada gejala gangguan kecemasan dan depresi pada pertemuan pertama itu. Di penghujung sesi, dia bertanya kapan saya akan konseling lagi dan dengan gampang saya jawab minggu depan. Baru ketika saya hendak membayar biaya konseling di meja resepsionis, saya kontan berubah pikiran. Di tagihan, tertera Rp1,5 juta. Hari itu menjadi kali pertama dan terakhir saya menginjakkan kaki ke kantor Mbak Kesya.
Dua tahun berselang, berbagai hal terjadi dalam hidup dan makin membuat saya tidak stabil. Saya akhirnya memutuskan mendaftar konseling ke salah satu lembaga psikologi di Jakarta Selatan setelah mengetahui biaya per sesinya jauh lebih ramah kantong, sekitar Rp200 ribuan. Dari 2017 itulah saya bertemu dengan “Mbak Hanum” dan perjalanan konseling saya dengannya pun lanjut sampai 2019 awal.
Baca juga: Dukung dan Dengar Pasangan itu Baik, tapi Kita Bukan Terapisnya
Sebenarnya, saya cukup nyaman dengan Mbak Hanum. Namun entah kenapa, saat saya mau datang kepadanya lagi pada tahun ini, sulit sekali mendapat respons apalagi jadwal dari lembaga psikologi tempatnya terafiliasi itu. Berbulan-bulan setelah saya WhatsApp hendak membuat appointment, tak ada balasan apa-apa dari mereka. Barangkali, sejak pandemi memang banyak klien yang mesti dilayani, sehingga saya mesti ekstra-sabar menunggu jawaban.
Di tengah penantian tak berujung itu--sementara masalah mental saya kian mengganggu dan rajin kambuh--saya sempat sekali konseling daring dengan psikolog lain. Setelah konseling dengannya, entah kenapa saya merasa ada yang kurang dari respons-responsnya. Namun, psikolog setelah dia lah yang paling “meninggalkan kesan” bagi saya, sebut saja “Mbak Karin”.
Jadi, sebelum sampai ke Mbak Karin, saya sempat ke psikiater juga karena gejala-gejala fisik sudah muncul, plus ada pemikiran bunuh diri. Saya pikir intervensi obat sudah mulai diperlukan saat itu. Setelah beberapa kali ke konseling dengannya dan sempat intensif seminggu sekali (dan ini lumayan menguras kocek juga karena saya enggak pakai BPJS), psikiater ini mendiagnosis saya dengan hal baru: Borderline personality disorder (BPD).
Lantaran konseling dengan psikiater jelas tak bisa selama dengan psikolog, dan saya sadar selain obat, saya butuh psikoterapi lebih panjang, saya pun mulai mencari psikolog lagi. Berbekal rekomendasi teman, saya mendapat nama Mbak Karin ini. Saya sempat cek namanya di Google dan memang dia sudah menulis beberapa karya akademik terkait BPD. Saya pun percaya, “she’s the one”, sampai akhirnya saya mendapati realitas yang memupuskan kepercayaan itu.
Baca juga: ‘Plot Twist’ Kasus Dedy Susanto dan Tips Sebelum Terapi Psikologis
Awal konseling daring, dia sudah getol menanamkan nilai-nilai normatif, padahal saya bilang saya tak percaya dengan nilai-nilai macam itu. Karena saya cerita saya punya banyak masalah dari macam-macam aspek, Mbak Karin langsung dengan tegas bilang yang harus diselesaikan pertama adalah masalah relasi. Padahal, menurut saya ada masalah lain yang lebih urgen bagi saya untuk diurai lebih dulu dari itu. Setiap saya mengutarakan sesuatu, dia akan balik lagi ke persoalan relasi itu. Saya merasa dia mendengar, tetapi tidak mendengarkan.
Yang paling red flag bagi saya adalah saat Mbak Karin bilang, “Laki-laki adalah pemimpin, kepala, dan perempuan mengikuti” atau “Enggak papa perempuan cari penghasilan, tapi jangan melebihi laki-laki, nanti dia enggak pede”. Atau, saat dia cerita bagaimana semestinya perempuan menuruti kata suami meski itu berkaitan dengan ekspresi dirinya sendiri yang membuatnya nyaman. Dalam hati saya langsung bereaksi, ok, bye. Sebuah pengeluaran ratusan ribu yang sia-sia, saya pikir.
Lelah Mengulang Cerita
Sebuah meme di Instagram sempat membuat saya cekikikan sendiri. Di sana, ada twit seseorang berisi, “Bagian terburuk dari datang ke terapis baru adalah memberi tahu masalah saya dari awal, jadi saya buat Powerpoint untuk membantu”, yang diikuti gambar slide Powerpoint berjudul “Trauma saya dari tahun 1997-sekarang”.
Meme itu sangat relatable buat saya dan mungkin sebagian orang yang sedang berobat mental lainnya. Dari cerita saya tadi saja, sudah terbayang, berapa kali saya harus mengulang cerita? Sebab ini bukan sembarang cerita melainkan cerita-cerita yang mengandung trauma, tentu saja hal itu melelahkan, baik secara fisik maupun emosional.
Memang, ada orang-orang yang setelah datang ke psikolog merasa lebih plong. Namun, dari pengalaman saya sendiri, butuh waktu untuk menstabilkan emosi setelah konseling. Hampir tiap kali saya konseling dengan Mbak Hanum saya menangis. Mencoba mengingat dan menyampaikan kembali pengalaman menyedihkan atau berbagai kecemasan yang selama ini enggak pernah tersampaikan selalu berhasil mengosongkan baterai stamina saya.
Maka, saat saya “kehilangan” Mbak Hanum, saya sempat merasa kesal dan agak malas mencari psikolog baru. Misalnya saya cerita tentang suatu masalah yang sekarang sedang saya hadapi, Mbak Hanum tentu sudah punya catatan tentang pengalaman saya sebelumnya dan mungkin bisa mengaitkan hal itu dengan masalah sekarang. Lain cerita dengan psikolog baru, yang harus saya jelaskan satu per satu dulu, mulai dari aspek relasi yang sekarang, relasi yang dulu, keluarga dan masa kecil, pekerjaan, dan sebagainya. Namun, yang namanya sudah emergency sampai gagal berfungsi sehari-hari, ya saya mau enggak mau bercerita dari awal lagi.
Masalah Kepercayaan
Teman-teman saya yang lain ada yang sampai empat hingga tujuh kali berganti ahli psikologi dengan bermacam-macam alasan. Ada yang karena masalah jarak, biaya, hingga kecocokan, persis seperti yang saya alami dengan Mbak Karin tadi.
Tak saya mungkiri, pengalaman dengan Mbak Karin sempat menciutkan niat memulihkan mental lewat konseling lagi dan memudarkan kepercayaan ke ahli psikologi. Memang, saya sudah sempat berganti-ganti psikolog sebelumnya dan toh tetap datang lagi ke mereka. Namun entah bagaimana, konseling dengan Mbak Karin itu begitu membekas buruk dan membuat saya berpikir, “Yang saya kira ahli di isu saya dan bisa menolong saya aja ternyata enggak sesuai harapan. Bagaimana kalau psikolog berikutnya sama saja?”
Saya teringat pengalaman satu kawan, penyintas pemerkosaan, yang juga pernah punya pengalaman buruk dengan salah seorang psikolog. Setelah menceritakan tragedinya itu, ia malah diminta banyak berdoa dan sang psikolog bilang, “Tuhan enggak akan ngasi cobaan melebihi kemampuan umat-Nya.”
Saya sempat cerita soal pengalaman buruk dengan Mbak Karin tadi di Instagram. Tak dinyana, dua teman yang sama-sama anak Psikologi merespons dan hendak membantu saya mencarikan psikolog yang memang punya expertise di isu saya atau metode yang ingin saya coba. Saya jelas berterima kasih atas inisiatif mereka itu, tetapi masih saja ada pesimisme menyembul di hati saya. Apakah yang punya expertise di isu saya pasti bikin saya nyaman dengan caranya berkomunikasi? Apakah dia enggak akan judgy? Apakah psikolog yang menurut teman saya bagus dan cocok buatnya akan cocok buat saya juga?
Seperti jodoh, kita enggak pernah tahu kapan akan dapat psikolog atau psikiater yang tepat. Ada yang “hoki” bisa dapat yang cocok sekali cari, ada juga yang macam saya. Enggak heran kalau biaya pemulihan mental itu mahal. Enggak cuma ada biaya per sesi konselingnya aja, tetapi ada juga biaya-biaya yang sering luput diperhatikan kayak gonta-ganti psikolog sampai dapat yang cocok (begitu satu enggak cocok, ratusan ribu melayang), dan biaya energi serta waktu yang terkuras saat harus cerita dari awal.
Sekarang, saya baru bertemu psikolog lain yang menurut saya cukup ideal dari segi biaya, metode, dan cara komunikasi. Saya harap, teman-teman yang juga sempat kelimpungan dan kapok karena bertemu psikolog yang kurang tepat, masih mau mencoba lagi walau capek. Bagaimana pun, layaknya sakit fisik macam patah tulang atau sakit paru-paru, masalah mental juga perlu dipulihkan, apalagi kalau sudah parah dan mengganggu.





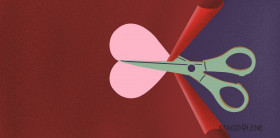


Comments