Tok! Terdengar suara palu yang diketokkan di atas bantalan kayu meja pengadilan agama. Seketika rasa sejuk menjalariku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaikan siraman mata air setelah perjalanan panjang di gurun pasir yang tandus.
Hari itu adalah tonggak bersejarah bagi saya kembali menjadi diri sendiri. Kembali bisa merasakan bahwa badan ini punya kepala untuk berpikir, kaki untuk melangkah, dan tangan untuk memilih yang saya inginkan. Setelah bertahun-tahun bergumul dengan pernikahan toksik yang menghabiskan seluruh energi baik pribadi maupun keluarga, terutama orang tua, bahkan sampai harus kehilangan salah satu dari mereka karena tak mampu menyaksikan anak satu-satunya harus merasakan beban yang sedemikian besar.
Ketidakberesan dalam perkawinan saya sebetulnya sudah terasa sejak awal. Karakter yang keras dan mendominasi dari pasangan bisa saya maklumi. Saat itu saya berpendapat laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin memiliki kekuasaan semi-absolut demi kemaslahatan negara kecil yang bernama keluarga. Surga adalah hal mudah bagi perempuan karena surat sakti yang berstempel rida ada di tangan suami.
Pemakluman itu berakhir saat kebohongan demi kebohongan terungkap. Sosok surgawi yang saya kenal hanyalah sebatas pendongeng pengantar mimpi. Mimpi tentang dongeng kitab suci yang tak lagi menyejukkan tapi memuakkan, penuh kemunafikan. Lisan tak sejalan dengan tindakan. Kata-kata serta perlakuan kasar menjadi makanan sehari-hari untuk hal yang kecil sekalipun.
Baca juga: Sanksi Sosial Membuat Perempuan Korban KDRT Enggan Bercerai
Saat semua aset pribadi dipindah tangan, kemudian saya menjadi pesakitan akibat berbagai penipuan yang terjadi dengan pihak-pihak lain tanpa pernah tahu asal usulnya, lepas sudah semua komitmen janji suci. Tak mau lagi keloro-loro hidup bersama seorang gold digger yang naik level menjadi gold robber, saya dengan tekad bulat memilih: Cerai!
Kisah “sukses” ini menginspirasi beberapa teman untuk hijrah diri, istilah yang lebih saya sukai daripada kata cerai. Di sisi lain, yang mencibir dan menganggap keputusan saya egois dan sembrono pun tak kalah banyaknya.
Seorang kawan, “Sigit” mengaku terinspirasi untuk memberi semangat sang kakak agar keluar dari perkawinan yang penuh dengan kekerasan. “Deni”, seorang kawan di media sosial memutuskan untuk menyerah dengan pernikahannya yang sudah berjalan sembilan tahun karena pasangannya memiliki mantan yang belum bisa move on dari masa remaja. Ada lagi “Rindang” (nama samaran) yang akhirnya berani hijrah dari suami 3 P: Pemalas, penuntut, dan penipu.
Baca juga: Cintai Perempuan dengan Membebaskannya
Tantangan pertama dalam proses hijrah diri ini biasanya justru datang dari keluarga. Keluarga dekat alih-alih menasihati sering kali berperan sebagai pahlawan kesiangan yang justru memperkeruh keadaan. Walaupun ada juga orang tua yang punya pandangan lebih terbuka, sehingga mendukung keputusan si anak untuk berpisah. Pilihan menjadi sendiri kembali dianggap tidak lazim dan yang dianggap wajar adalah mempertahankan perkawinan. Tak ayal, saat menghadiri acara keluarga atau bahkan saat belanja di tukang sayur, keluarga akan disibukkan dengan pertanyaan semacam: Si A kenapa harus cerai, sih? Ada orang ketiga, ya? Kok enggak kasihan sama anak, sih!
Kalimat terakhir tentang anak, jika sudah memilikinya, adalah pertimbangan terberat kedua sebelum memutuskan untuk berhijrah diri. Tak bisa dipungkiri, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa anak hampir dipastikan akan jadi korban. Mereka akan dilabeli sebagai anak broken home. Produk rumah gagal itu akan menghasilkan anak-anak madesu (masa depan suram) yang bahkan dipercaya tidak punya masa depan. Wow!
Kenapa saya tempatkan anak sebagai pertimbangan berat kedua? Yang pertama apa? Memangnya anak enggak penting? Sebentar. Bukankah anak itu hadir karena ada kita? Dalam arti sebagai salah satu penyebab mereka lahir ke dunia. Ini bukan seperti pertanyaan: Mana yang duluan, telur atau ayam? Orang tua adalah dewasa pertama sekaligus pelaku yang pertama merasakan hantaman psikologis sebelum si anak. Sehingga pertimbangan terberat pertama yang harus disiapkan amunisi jiwa adalah diri kita sendiri, orang tua.
Baca juga: Menikah Itu Tidak Indah
Menjadi istri seorang perwira menjadikan kakak perempuan Sigit tak kurang apa pun. Status sebagai priayi. Rumah berada di kawasan bergengsi di ibu kota. Kendaraan tak lagi sekadar keluaran Asia Timur Raya. Tapi sang istri harus berdarah-darah bertahan dengan penyiksaan lahir batin. Lahirnya anak-anak tak mampu meredam tabiat sang suami. Tubuh yang kurus kering didera bermacam sakit menjadikan suami semakin menjauh. Ia berdalih bertahan demi masa depan anak-anaknya. Apakah menurutnya definisi bahagia adalah orang tua yang berkorban demi anak-anaknya? Entahlah.
Rindang beda lagi. Anak yang ia khawatirkan akan terganggu jiwanya saat hijrah diri justru semakin ceria. Rindang mengaku saat keputusan itu dibuat, seluruh keluarga turun tangan. Mereka mengambil alih tugas pengasuhan si anak sementara Rindang harus mencari nafkah.
“Alhamdulillah, anakku sekarang mondok di pesantren. Dia sendiri yang mutusin loh! Padahal dulu waktu ayahnya masih di sini dia justru anaknya cengeng dan penakut,” ujarnya.
Sementara Deni, sadar bahwa pemakluman yang ia berikan kepada mantan istri dulu adalah tindakan yang salah. Anak yang menjadi alasan ia bertahan, justru lebih menurut dan memilih tinggal bersama nenek yang selalu ada ketika dibutuhkan. Sedangkan sang mantan melenggang tanpa pesan selama bertahun-tahun.
Saya sendiri berkata pada seorang sahabat, “Aku harus jadi ‘pohon’ untuk anakku.”
Dia hanya tersenyum dan berkata, “Tidak, kamu hanya butuh jadi manusia.”
Ilustrasi oleh Karina Tungari.



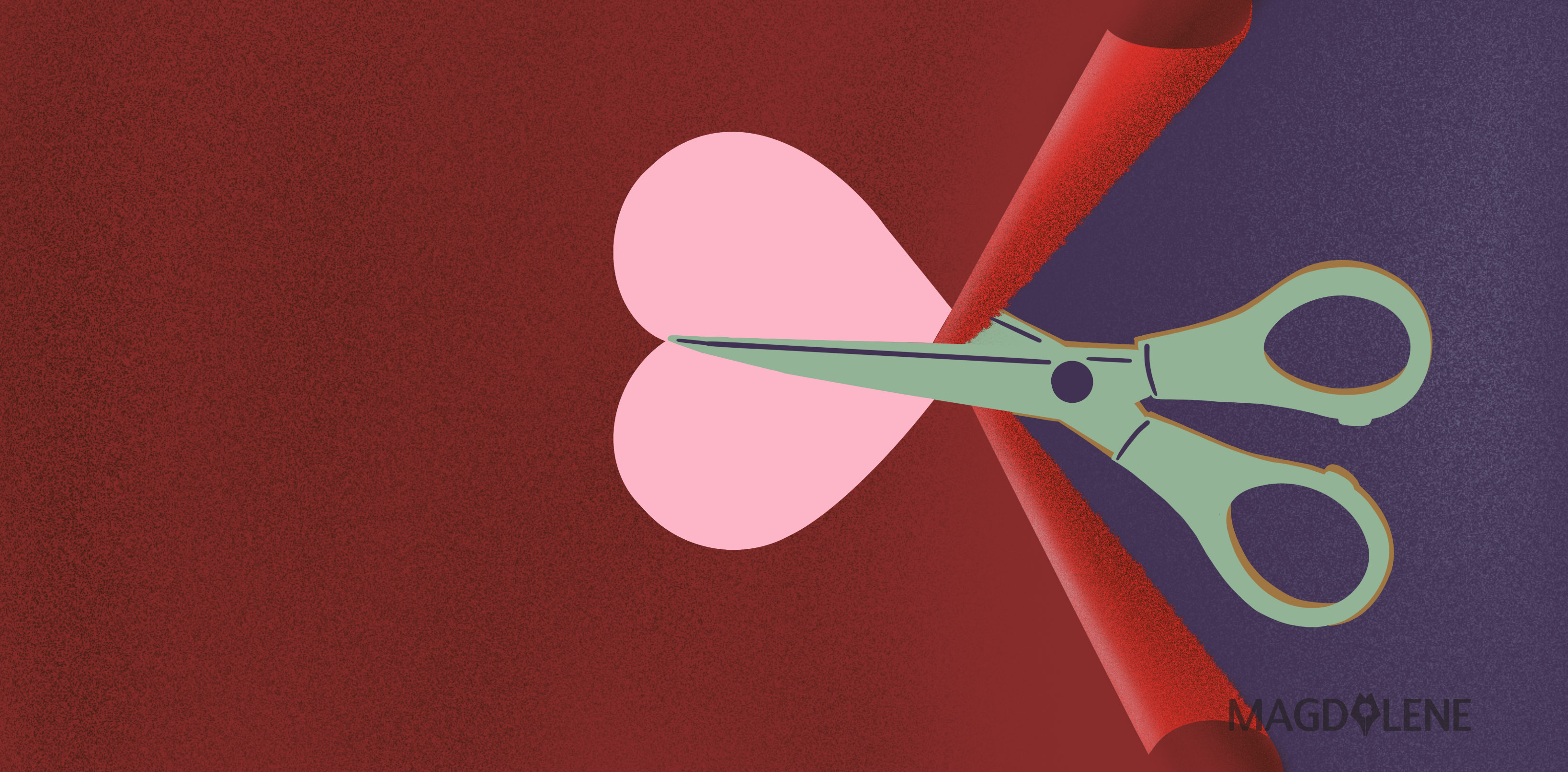



Comments