Sejak berseragam putih abu-abu, ada dua hal yang “senang” saya besar-besarkan: Minta izin ibu bapak sebelum bepergian, dan mengutarakan keinginan yang menyangkut masa depan. Ini saya lakukan mengingat mereka sangat protektif dengan anaknya. Maklum, sudah semata wayang, perempuan pula.
Awalnya, kebiasaan ini saya anggap wajar, apalagi saya masih menumpang ibu dan bapak. Sampai Senin pagi, meme yang diunggah seorang psikolog, melintas di beranda Instagram.
Katanya, anak perempuan Asia yang belum menikah masih harus minta izin orang tua untuk keluar rumah meski sudah berusia 22 tahun. Pernyataan paling akurat, relevan, dan seketika bikin saya overthinking. Tentu bukan konten yang diharapkan untuk menyambut awal pekan, tapi isi kolom komentar cukup bikin bernapas lega, karena saya enggak “menderita” sendirian.
Konten itu menjadi awal pertemuan virtual saya dengan Sai, wiraswasta asal Kabupaten Semarang, yang juga berada dalam lingkaran yang sama. Belakangan ini, ia berencana mendaftar pekerjaan di Jakarta. Namun, keinginannya terpaksa diurungkan.
“Orang tuaku keberatan, mereka cuma kasih aku izin kerja di Semarang atau Yogyakarta,” ceritanya pada Magdalene, (20/4).
Ditambah pertimbangan lain yang enggan disebutkan, Sai menuruti permintaan ibu dan ayahnya yang mengutamakan keamanan. Lantaran tinggal di desa, orang tuanya memiliki stigma tertentu tentang ibu kota, termasuk angka kriminalitasnya. Alhasil ia tidak diperbolehkan tinggal sendiri di Jakarta, melainkan di bawah atap yang sama.
“Mereka pengen kalau aku kerja di Jakarta, aku udah harus bersuami,” terangnya.
Momen itu bukan kali pertama bagi Sai. Perempuan 26 tahun itu mengaku, hampir semua keputusan besar yang akan diambil dan bersifat pribadi, dibicarakan dengan orang tuanya. Kebiasaan itu menjadi pola komunikasi yang sudah dilakukan sejak kecil.
Meskipun tergolong positif dan dapat menjaga hubungan dengan orang tua—seperti dijelaskan dalam MensLine Australia—di sisi lain, ia justru merasa ruang geraknya semakin sempit.
“Sebenarnya mereka enggak pernah memaksa atau melarang secara langsung, cuma keberatan. Pengennya aku tinggal yang deket-deket aja,” terangnya.
Padahal sewaktu SMP dan SMA, Sai hidup berasrama di Indramayu, dan ngekos di Yogyakarta saat berstatus mahasiswa. Semua berubah ketika ia pulang ke rumah. Orang tuanya punya kekhawatiran berlebih hingga membatasi dengan sejumlah aturan, membuatnya membandingkan diri dengan teman-temannya yang lebih fleksibel. Termasuk dalam pengambilan keputusan.
Terlepas dari alasan keamanan dan anggapan anak adalah tanggung jawabnya, apa yang membuat orang tua sebisa mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan, yang akan dipilih anaknya?
Baca Juga: 'Silent Treatment', Perilaku Alternatif Orang Tua
Nilai Keluarga dan Overprotektif
Sebenarnya saya setuju, keterlibatan orang tua dalam hidup anak, enggak selamanya salah. Masalahnya, sejauh mana mereka terlibat, adalah pembahasan lain yang perlu digarisbawahi. Terutama ketika usia anak tergolong dewasa, dan sudah berpenghasilan sendiri.
Pasalnya, setiap anak berhak dilihat sebagai individu secara utuh, satu hal yang kerap terlupakan oleh sebagian orang tua. Sering kali mereka memaksakan keinginannya, dalam menanggapi situasi yang dihadapi sang anak.
Psikolog klinis dewasa Anggita Panjaitan mengatakan, hal ini dipengaruhi nilai-nilai dalam keluarga, terutama yang datang dari keluarga konvensional.
“Ada beberapa pendekatan agama dan budaya yang percaya, anak itu tanggung jawab orang tua sampai dia menikah,” ujarnya. Hal itu membuat orang tua memegang erat ajaran tersebut secara kaku. Terlebih di sejumlah daerah yang memosisikan perempuan sebagai warga kelas dua.
“Jadi kalau udah ‘diambil’ cowok lain, orang tua baru bisa melepaskan tanggung jawabnya,” jelas Anggita.
Selain pernikahan, keyakinan untuk berbakti terhadap orang tua dengan gantian merawat mereka, juga menjadi budaya yang masih dilanggengkan sampai detik ini. Kalau enggak dilakukan, katanya nanti durhaka, seperti Malin Kundang.
Situasi tersebut yang menjebak Sai, karena sebenarnya ia menyanggupi untuk tinggal dan menghidupi dirinya sendiri, baik di Semarang maupun Yogyakarta. Sayangnya, ia terbebani pertimbangan moral, terlebih saat ini adiknya bekerja di luar kota.
“Apa yang terbentuk di masyarakat, jadi budaya, dan dianggap baik dan benar kan seperti itu. Ada saatnya anak merawat orang tua,” katanya. “Jadi keadaan ini yang memaksaku tinggal dengan mereka, seenggaknya untuk sementara waktu.”
Kondisi ini bertolak belakang dengan pola asuh di Barat. Mereka cenderung membiarkan anak mengekspresikan pikiran dan perasaan secara terbuka, dan mengajarkan sikap mandiri sejak dini. Bahkan membiarkan anak menentukan pilihannya sendiri.
Pola asuh itu diterapkan mulai dengan sleep training. Selain waktu istirahat lebih panjang bagi orang tua, metode tersebut dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian anak, seperti dijelaskan dalam Parent-child bed-sharing: the good, the bad, and the burden of evidence (2016) oleh peneliti Viara Mileva-Seitz, dkk. dari Leiden University, Belanda. Lebih dari itu, mereka juga menekankan agar anaknya keluar dari rumah, setelah berusia 18 tahun.
Namun, faktor ini tidak hanya didorong oleh budaya. Terdapat beberapa hal lain yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut, yakni terbiasa dengan peran sebagai orang tua.
Terbiasa mengontrol dan mengarahkan anak sejak kecil, tanpa disadari mendorong mereka terus melakukan hal ini hingga anak-anaknya dewasa. Terutama yang memiliki parenting style otoriter dan overprotektif.
“Mereka meyakini anak enggak bisa tanpa mereka. Lalu khawatir anaknya akan membuat kesalahan, bahkan dilukai dunia,” paparnya. “Makanya mereka merasa perlu terlibat segitu besarnya dalam kehidupan anak-anak.”
Faktor terakhir juga bisa datang dari cara anak membina relasi dengan orang tua. Mereka yang cenderung bergantung dan tidak menunjukkan sisi kemandirian, otomatis membuat orang tua khawatir akan masa depan anaknya.
Sayangnya, apabila ketiga hal di atas terus terjadi, aspek kedewasaan dalam diri anak akan terusik. Seperti anak menjadi kurang mampu menghargai diri dan muncul keraguan, setiap harus mengambil keputusan sendiri.
“Otomatis skill hidupnya terbatas, anak selalu cemas karena takut apa pun pilihannya dikritisi,” ujar Anggita.
Baca Juga: Hormati Orang Tuamu Tapi Bela Dirimu Sendiri
Benarkah Menikah Solusinya?
Mungkin kamu pernah mendengar, bagaimana orang tua mendeskripsikan pernikahan, layaknya sebuah akses untuk terbebas dari jeratan yang “mengikat” anak-anaknya di rumah. Tak jarang, anak pun beranggapan pernikahan menjadi satu-satunya jalan untuk berdaya.
Pernyataan itu diyakini “Ambar”, 23 yang berharap bisa menjadi diri sendiri, ketika tanggung jawab atas dirinya “pindah tangan” dari orang tua ke pasangannya kelak.
“Harapannya aku bisa lebih lega kalau melakukan hal--hal yang diinginkan. Merasa nyaman, bisa mengambil keputusan bareng, dan bertumbuh dalam partnership yang sehat,” harapnya.
Sayangnya, pernikahan bukanlah solusi yang tepat untuk keluar dari lingkaran ini. Menurut Anggita, pilihan tersebut justru menciptakan permasalahan baru, karena keduanya adalah hal berbeda.
“Kita beranggapan dengan menikah, ortu akan sama sekali tidak terlibat. Tapi apakah ada jaminan demikian?”
Kondisi itu pernah dialami “Sitta”, seorang wiraswasta yang menetap di rumah orang tuanya, bahkan setelah menikah di usianya yang saat itu menginjak 26 tahun. Awalnya, ia mengira pernikahan akan memberikannya keleluasaan untuk mandiri, karena tanggung jawab sudah berpindah ke suami.
Kenyataannya, orang tuanya justru ikut mengatur suaminya, dengan alasan menantu dianggap sama dengan anak kandung.
“Bahkan hal-hal sepele semacam mengatur posisi kasur dalam kamar tidur kami saja harus nurut ortu. Kalau enggak, bikin perang besar berkepanjangan,” tulis perempuan 34 tahun itu, menanggapi meme yang diunggah seorang psikolog.
Tak hanya itu, pernikahan juga tidak menjamin, apabila pasangan tidak menganut nilai-nilai serupa dengan orang tua. Apa jadinya kalau ia juga tidak mengizinkan pasangannya untuk taat, dan bersikap overprotektif?
Baca Juga: Dear Orang Tua, Bebaskan Anak dari Enam Hal Ini
“Sebaiknya fokus membangun keberdayaan diri aja, untuk membuktikan kita adalah orang dewasa yang cukup matang,” ungkap Anggita. “Berdaya secara finansial, karakter, dan konflik,” sambungnya.
Dalam memberdayakan diri, anak bisa menunjukkan perilakunya yang mencerminkan kedewasaan. Misalnya lebih bertanggung jawab, mandiri, memahami dan percaya terhadap value yang diinginkan, mampu menghadapi perbedaan dengan tenang dan dewasa, serta mampu berkomunikasi secara asertif.
Alih-alih menggunakan kata ‘izin’ misalnya, anak dapat bercerita layaknya hubungan itu setara, dan tidak ada hierarki dalam keluarga.
Hal itu telah dilakukan Syifa, jurnalis sebuah media yang berdomisili di Jakarta. Sewaktu duduk di bangku SMA dan mulai memahami keinginannya, ia menjelaskan ke orang tuanya terkait ketertarikannya dengan literasi.
“Aku bilang suka nulis dan baca. Agak berat sih untuk mereka dukung pilihanku, karena berharapnya aku berkarier di bidang kesehatan,” tuturnya.
Meskipun akhirnya menekuni jurnalisme, bukan berarti ayah ibunya menerima pilihan tersebut. Sewaktu memulai pekerjaan, mereka sempat mempertanyakan apakah Syifa yakin dengan keputusannya.
Akhirnya, perempuan 25 tahun itu berusaha memahami orang tuanya, dan menjelaskan tentang pekerjaannya. Mulai dari cara kerja, keuntungan, hingga gaji yang enggak seberapa, jika dibandingkan profesi dambaan mereka.
“Sebagai anak memang kita harus sabar ya, namanya juga sama orang tua. Mungkin juga banyak pekerjaan baru yang muncul dan berbeda dengan zaman mereka,” katanya. “Kita nggak bisa minta mereka paham, kalau kita aja enggak mau menjelaskan.”
Dari situ, tidak hanya orang tuanya yang lebih mengerti pekerjaan Syifa, relasi mereka juga semakin membaik. Kini ia hanya melibatkan orang tua dalam diskusi untuk mengambil pilihan-pilihan krusial, seperti keinginan menikah dan membeli rumah suatu saat nanti.
Namun, peran orang tua seharusnya hanya sebatas memberikan pertimbangan dari sudut pandang yang bijaksana. Oleh karena itu, Anggita memberikan saran terakhirnya.
“Jadikan saran orang tua sebagai pertimbangan aja, tapi keputusannya tetap di kita, karena kan ini hidup kita,” tegasnya.



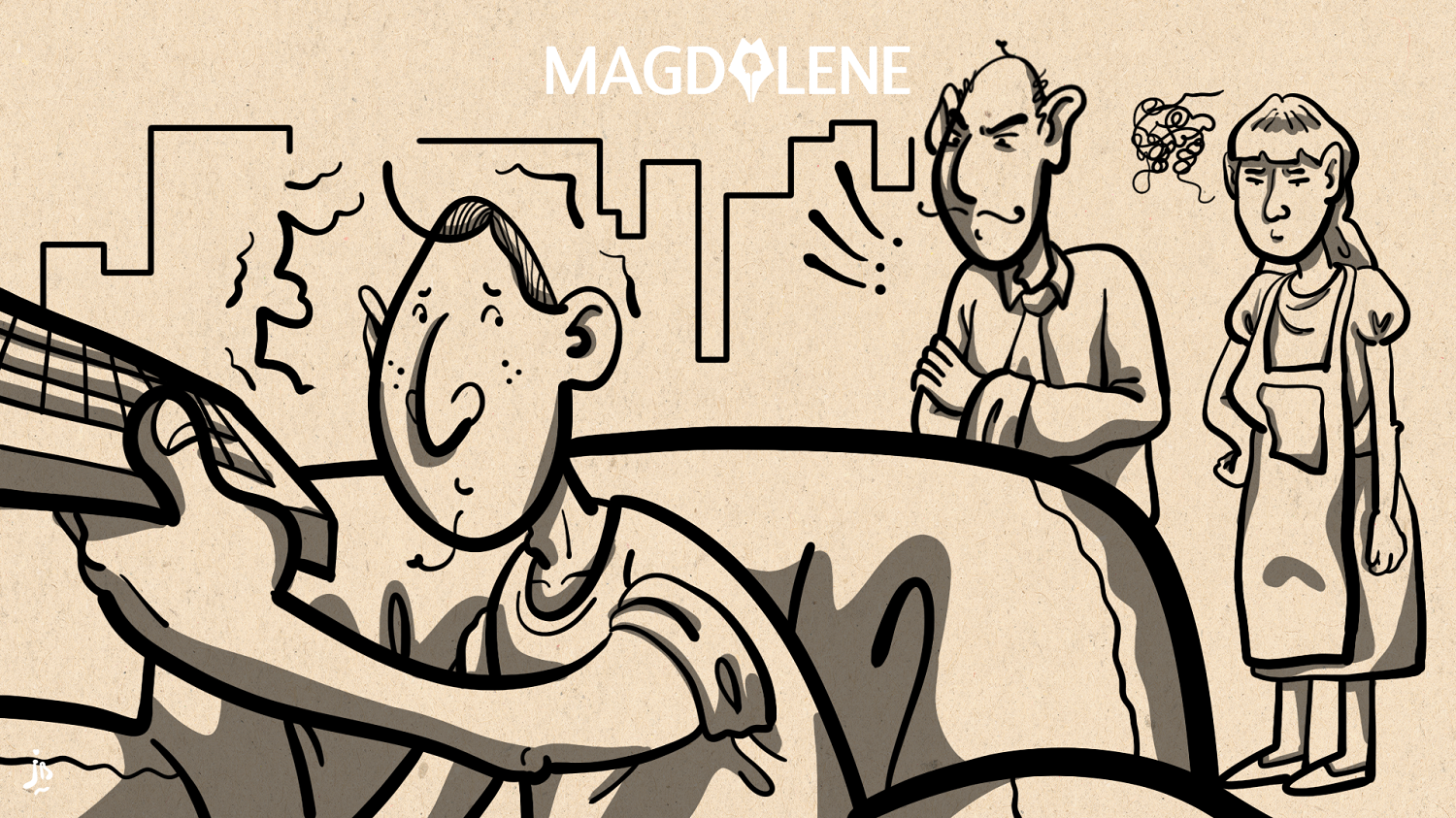




Comments