Beberapa waktu lalu, Balairung Press, media daring pers mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan kasus pemerkosaan yang dialami Agni, oleh sesama mahasiswa saat mengikuti kuliah kerja nyata. Artikel tersebut memicu kemarahan publik atas ketidakmampuan institusi pendidikan menangani kasus kekerasan seksual. Dukungan terhadap Agni pun mengalir di media sosial. Publik beramai-ramai mengecam HS, pelaku pemerkosaan. Beberapa di antaranya bahkan mempublikasikan identitas serta akun media sosial HS di Twitter.
Di tengah-tengah dukungan publik yang masif, muncul respons negatif terhadap artikel Balairung Press sekaligus terhadap respon publik yang mengecam HS. Menurut beberapa pihak, apa yang dilakukan Balairung Press dan publik melanggar salah satu asas hukum yang paling esensial: asas praduga tidak bersalah. Alasannya, kejahatan tersebut belum pernah terbukti di pengadilan. Berdasarkan asas ini, HS harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan sebaliknya -- Innocent until proven guilty.
Asas praduga tidak bersalah acap kali menjadi problem yang dihadapi jurnalis, media maupun penyintas yang mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual yang belum pernah terbukti di pengadilan. Persoalan ini pun semakin mengemuka sejak munculnya gerakan #MeToo. Gerakan ini sering kali dianggap mencederai asas praduga tidak bersalah karena mendorong penyintas untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang pernah dialaminya serta pelaku kekerasan di media sosial. Istilah trial by Twitter pun muncul karena #MeToo dianggap menjadikan media sosial sebagai “pengadilan” dan publiklah “hakimnya'. Benarkah demikian?
Bila hendak berbicara tentang asas praduga tidak bersalah, maka kita harus kembali pada sifat peradilan pidana, yakni negara versus warga negara. Sifat peradilan pidana tidaklah imbang karena negara memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada warga negaranya. Dalam proses peradilan pidana, negara berhak untuk mengurangi dan merampas hak-hak warga negara. Ketika seseorang terbukti melakukan kejahatan, maka negara berhak merampas hak atas kebebasannya melalui pidana penjara.
Karena sifat peradilan pidana yang cenderung mengurangi dan merampas hak-hak warga negara, maka prosedurnya harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dipidana dan dirampas hak-haknya. Di sinilah muncul asas praduga tidak bersalah. Dengan kata lain, asas praduga tidak bersalah adalah asas prosedural dalam peradilan pidana, bukan di luar peradilan pidana, yang tujuannya menghindari dihukumnya orang yang tidak bersalah. Asas ini salah satunya diwujudkan melalui kewajiban aparat penegak hukum membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa (beban pembuktian ada pada penegak hukum, bukan pada tersangka atau terdakwa).
Miskonsepsi lain terhadap asas praduga tidak bersalah adalah asas ini dianggap mewajibkan penegak hukum mengasumsikan bahwa tersangka/terdakwa secara faktual tidak bersalah. Hal ini tentu saja tidak relevan apabila tersangka/terdakwa tertangkap tangan melakukan kejahatan. Sekali lagi, asas praduga tidak bersalah adalah asas prosedural, bagaimana aparat penegak hukum harus bertindak hati-hati dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang.
Dalam liputan-liputan media dan pengungkapan kasus kekerasan seksual oleh penyintas di media sosial, pelaku tidak dihadapkan pada negara. Hak-haknya tidak mungkin dikurangi atau dirampas. Oleh karena itu, secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran asas praduga tidak bersalah.
Percaya pada korban
Di berbagai belahan dunia, gerakan “Believe the Victim” mendapatkan kritik dan kecaman karena dianggap memaksa publik berhenti berpikir kritis terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Media dikritik karena dianggap mengesampingkan keakuratan fakta. Pihak yang kontra seringkali mengungkapkan bahwa sebelum terbukti berdasarkan putusan pengadilan, maka selalu terdapat kemungkinan bahwa tuduhan korban tidak benar. Tapi, seberapa besar kemungkinannya?
Dalam artikel yang berjudul "What kind of person makes false rape accussation?" oleh Sandra Newman, data menunjukan bahwa laporan perkosaan yang terbukti palsu sangat jarang terjadi. Sejak tahun 1989 di Amerika Serikat hanya terdapat 52 kasus dimana pelaku akhirnya dibebaskan karena laporan terbukti palsu, dibandingkan dengan 790 kasus pembunuhan pada periode yang sama. Namun, kasus-kasus tersebut pun seringkali dianggap palsu karena inkonsistensi definisi hukum perkosaan dan pemahaman aparat penegak hukum yang rendah terhadap perkosaan.
Selain itu, di tengah-tengah kultur masyarakat kita yang patriarkal, di mana penyintas sering kali disalahkan karena dianggap memprovokasi pelaku atau ikut “berkontribusi” atas kekerasan yang dialami, mengungkap kekerasan seksual yang dialami merupakan tindakan yang penuh risiko. Oleh karena itu, percaya pada korban bukan berarti meredam kemampuan berpikir publik. Percaya pada korban juga bukan berarti menciptakan liputan media yang serampangan. Percaya pada korban adalah tentang besarnya kemungkinan bahwa korban menyatakan yang sebenarnya.
Terakhir, ada hal yang mungkin patut kita renungkan. Jika saat ini publik lebih memilih media sosial untuk “mengadili” pelaku kekerasan, saya rasa alasannya satu: karena selama ini sistem peradilan pidana kita tidak bisa memberikan keadilan bagi korban sebagaimana mestinya.
Carla Nathania adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



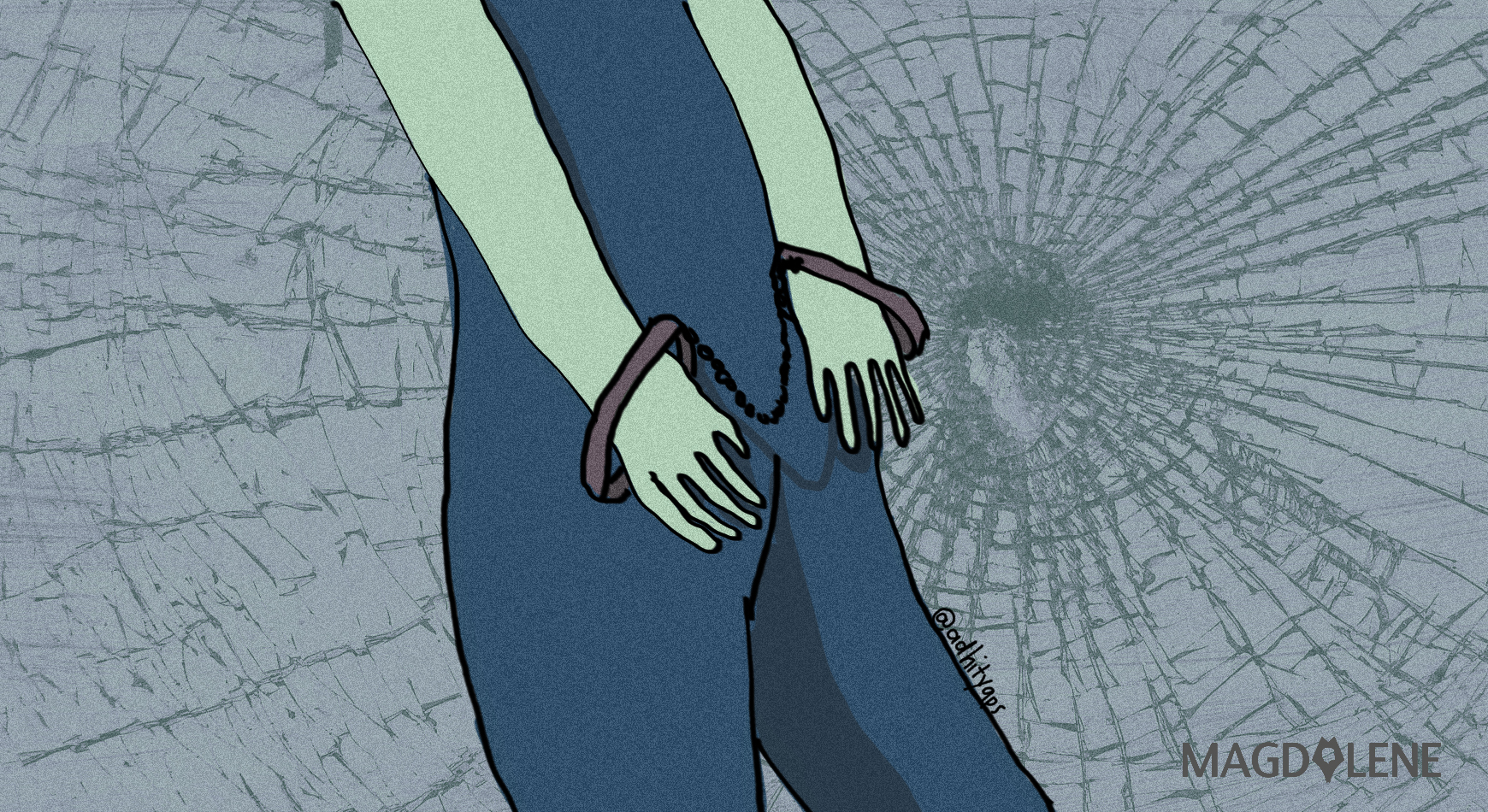

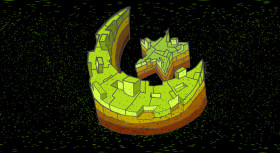


Comments