Konferensi Iklim di Bonn, Jerman, yang berakhir pada pertengahan Juni masih menemui jalan buntu terkait pendanaan iklim negara maju ke negara miskin dan berkembang.
Negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa, ogah membayar kompensasi kerugian dan kerusakan parah yang dialami negara berkembang karena krisis iklim. Mereka berdalih pembiayaan itu membutuhkan dana jumbo dengan jangka waktu puluhan tahun.
Penolakan ini mesti disikapi serius. Pasalnya, upaya meredam kerusakan bumi oleh negara miskin dan berkembang membutuhkan dana yang tak sedikit. Seiring waktu, kerusakan tersebut berdampak kian parah dan semakin meluas. Ini didukung laporan Panel Antar-pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) terbaru yang menjelaskan bahwa penduduk paling rentan berada di wilayah Afrika barat, tengah, dan timur, Asia Tenggara, Amerika tengah dan selatan, negara-negara pulau kecil berkembang, dan kutub utara.
Negara-negara di kawasan ini, termasuk Indonesia, juga masih kewalahan melakukan langkah adaptasi di tengah iklim yang berubah.
Baca juga: Gerakan Aksi Iklim Indonesia Meningkat, Tapi Belum Pengaruhi Kebijakan
Dana yang Kurang dan Timpang
Negara-negara kaya AS, Kanada, Eropa, Jepang, Rusia, dan Australia, dituntut untuk lebih bertanggung jawab menangani persoalan perubahan iklim. Pasalnya, sejak puluhan tahun silam, mereka menghasilkan emisi yang jauh lebih banyak dibandingkan negara miskin dan berkembang.
 Porsi emisi global selama 1850-1969 menunjukkan negara-negara kaya bertanggung jawab atas kerusakan bumi sejak lebih dari seabad silam. (Jason Hickel/Lancet)
Porsi emisi global selama 1850-1969 menunjukkan negara-negara kaya bertanggung jawab atas kerusakan bumi sejak lebih dari seabad silam. (Jason Hickel/Lancet)
Ini sebenarnya sudah disadari sejumlah negara maju. Pada 2009, mereka berkomitmen mengucurkan pendanaan senilai US$100 miliar per tahun mulai 2020. Sialnya, janji ini tak kunjung terpenuhi.
Apakah nilai bantuan US$100 miliar per tahun cukup untuk membantu negara miskin? Tentu tidak. Organisasi nirlaba Climate Policy Initiative, menaksir dunia membutuhkan pendanaan iklim US$ 4,5-5 triliun (Rp66.791- 74.212 triliun) per tahun pada tahun 2030.
Kelompok negara kaya juga mendapat kritik atas penyaluran dana yang tidak proporsional dibandingkan kekuatan ekonomi mereka.
Berdasarkan perhitungan organisasi nirlaba World Resources Institute, guna mencapai target U$100 miliar per tahun, 23 negara kaya membutuhkan alokasi dana sedikitnya 0,22 persen dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) masing-masing.
Sayangnya, data kompilasi komitmen pendanaan iklim versi Pemerintah Inggris menunjukkan komitmen pendanaan sebagian besar negara kaya masih di bawah batas minimum 0,22 persen dari PNB.
Sebagai contoh, AS mengalokasikan pendanaan sebesar US$11,4 miliar per tahun hingga 2024. Jumlah ini hanya 0,05 persen dari PNB AS tahun 2020.
Selain tak proporsional, pendanaan juga masih berat sebelah ke upaya-upaya mitigasi (pengurangan emisi untuk meredam risiko perubahan iklim). Pembiayaan untuk mengatasi dampak iklim (adaptasi) di negara berkembang masih loyo. Porsinya pada 2019 hanya 25 persen dari total pendanaan iklim.
Pembiayaan adaptasi amat diperlukan negara miskin dan berkembang. Sebab, dampak krisis iklim justru menambah beban perkara yang sudah ada di negara tersebut. Misalnya persoalan kemiskinan, minimnya akses kebutuhan dasar, literasi yang rendah, konflik, dan buruknya tata kelola pemerintahan.
Beban berganda (bahkan lebih) tersebut akhirnya menghambat laju pembangunan di negara miskin dan berkembang. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenaikan ketimpangan antara negara kaya dan miskin.
Baca juga: Bencana hingga Kematian di Depan Mata, Kenapa Kita Masih Cuek pada Krisis Iklim?
Apa Dampaknya Bagi Indonesia?
Mandeknya pendanaan negara kaya mengakibatkan upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia tak optimal. Misalnya, dalam komitmen iklimnya, pemerintah telah mematok upaya pengurangan emisi bisa mencapai 41 persen pada 2030 dengan bantuan internasional. Sementara, jika berbasiskan kemampuan sendiri, Indonesia hanya mampu mengurangi 29 persen emisinya.
Per 2019, pemerintah melaporkan pengurangan emisi Indonesia baru mencapai 9,63 persen.
Dana adaptasi yang diterima Indonesia pun masih relatif sedikit. Berdasarkan data Adaptation Fund, lembaga nirlaba dengan fokus isu pembiayaan iklim, Indonesia mendapatkan lima proyek adaptasi dengan total hibah sebesar 9,7 juta dolar Amerika Serikat (AS).
Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dana yang diterima Kepulauan Solomon yaitu sebesar 9,9 juta dolar AS.
Padahal, apabila dilihat dari jumlah populasi dan luas wilayah, dampak yang dialami Indonesia akibat krisis iklim jauh lebih besar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kerugian ekonomi yang dialami Indonesia adalah sebesar Rp544 triliun untuk periode 2020-2024 atau rata-rata Rp 108 triliun per tahun.
Baca juga: Lawan Krisis Iklim: Tokoh Fiksi Ramah Lingkungan Perlu Diperbanyak
Langkah Strategis Terkait Pendanaan Iklim
Indonesia perlu terus mendesak negara kaya untuk membayar ‘utang iklimnya’ ke negara miskin dan berkembang. Ada empat langkah yang bisa dilakukan.
Pertama, Indonesia perlu konsisten melaksanakan prinsip ‘to lead by example’ (memimpin dengan memberi contoh) yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada KTT Perubahan Iklim di AS tahun lalu.
Pemerintah pun perlu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya meminta bantuan tapi juga berkomitmen mengucurkannya bantuan.
Hal ini penting untuk meningkatkan posisi tawar negara, sekaligus menunjukkan itikad baik penanganan krisis iklim melalui aksi kolektif, tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada negara kaya.
Indonesia sudah memulai aksi positif dengan berkomitmen untuk membantu peningkatan kapasitas Negara-negara Kepulauan Pasifik pada KTT Adaptasi Iklim 2021. Langkah ini tepat dan perlu dilanjutkan dengan aksi nyata.
Kedua, memperkuat koalisi negara berkembang dengan melibatkan aktor non-negara (organisasi nirlaba, pengusaha, filantropis, dan akademisi). Koalisi ini berguna untuk menggaungkan peningkatan ambisi pendanaan iklim negara kaya, serta memasukan kerugian dan kerusakan sebagai pilar ketiga selain mitigasi dan adaptasi.
Ketiga, dalam negosiasi iklim selanjutnya, Indonesia perlu menyuarakan distribusi pendanaan untuk aksi adaptasi yang lebih proporsional. Kucuran dana mesti memperhitungkan dampak yang sudah dialami suatu negara, maupun potensinya di masa depan.
Keempat, Indonesia sedang memegang Presidensi G20 (Group of 20). Posisi ini strategis untuk menjembatani dialog negara maju dengan negara berkembang terkait pendanaan iklim. Selain itu, forum ini dapat digunakan untuk menagih janji sembilan anggota G20 yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, Uni Eropa, dan Spanyol (sebagai tamu tetap), yang telah mengikat janji pendanaan US$100 miliar untuk pendanaan iklim.![]()
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.



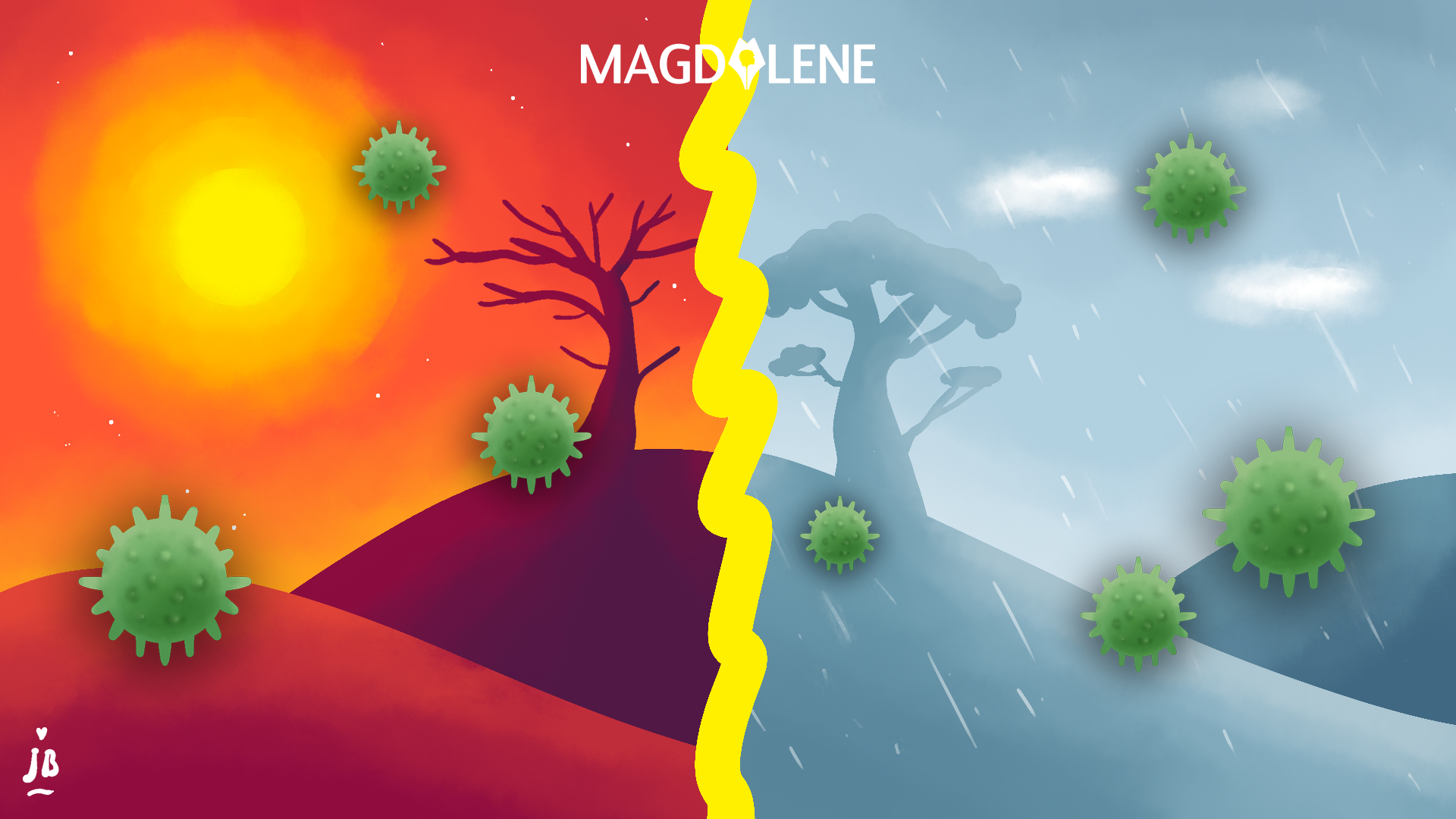



Comments