Sebetulnya untuk diriku sendiri, proses untuk menjadi seorang feminis memakan waktu yang cukup lama. Dulu, sama seperti banyak orang, aku merasa feminis itu lebay. Perempuan saja yang tidak bisa menjaga diri sehingga diperlakukan buruk, pikirku. Buktinya, waktu aku masih duduk di bangku sekolah, hampir semua temanku laki-laki, dan sedikit pun aku tidak pernah dilecehkan atau diperlakukan buruk. Padahal aku ini perempuan loh.
Argumenku itu sama sekali tidak valid. Dulu sebelum lulus SMA, rambutku dipotong cepak, dadaku rata, dan aku tidak suka pakai rok. Aku jijik memakai beha dan aku benci saat datang bulan. Aku benci menjadi perempuan. Perempuan yang lemah, perempuan yang genit. Aku ingin sekali menjadi laki-laki, seperti kakakku. Sebisa mungkin aku berperilaku seperti laki-laki. Itu semua terjadi karena masyarakat mendikteku kalau kuat itu keren, berani itu baik, lembut itu banci, cantik itu genit. Kuat dan berani itu laki-laki, lembut dan cantik itu perempuan. Aku tidak pernah digoda atau diperlakukan buruk karena aku menyerupai laki-laki alias kadang mereka lupa kalau aku perempuan.
Tapi di sekolah, aku juga tidak luput dari perisakan. Alasannya, aku tidak berpakaian sesuai genderku. Jadinya ya tetap saja jadi bahan ejekan, walaupun tidak separah teman laki-laki yang feminin. Mereka dibilang banci, sementara aku dipanggil tombol. Tombol terdengar lebih keren daripada banci. Banci itu lemah, genit, dan suka bingung seperti perempuan. Tomboi itu kuat, perkasa, dan tegas, seperti laki-laki. Seumur hidup aku tinggal di dunia yang menekankan bahwa laki-laki harus seperti ini, sedangkan perempuan harus seperti itu.
Sampai pada suatu hari, ketika aku sudah kuliah, aku magang di Women’s Crisis Center milik Rifka Annisa, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta yang bergerak melawan kekerasan terhadap perempuan. Aku magang untuk sekedar mengisi waktu liburan. Kebetulan dosen di kampus mengatakan kalau mau magang tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, di Yogya juga ada.
Aku magang di situ dengan anggapan, aku ini pro perempuan. Dengan perspektif genderku yang masih buruk, aku malah diberi kesempatan untuk menjadi pengamat korban kekerasan. Aku masuk ke ruang konseling bersama konselor dan mencatat cerita-cerita korban. Cukup mendengarkan dan mengamati, tidak berbicara.
Cerita-cerita yang kudengar membuatku kewalahan. Aku tercenung, dan setiap selesai mendengar cerita, kepalaku sakit. “Biasa kalau awal-awal memang seperti itu,” kata seorang konselor menenangkanku. Selama ini aku selalu berpikir kejahatan itu ada, tapi sesuatu yang jauh dariku. Sesuatu yang kubaca di koran atau kulihat di televisi. Sedangkan di Rifka Annisa, aku berhadapan langsung dengan para korban kejahatan.
Ada seorang Ibu yang dipukul suaminya hingga tulang rusuknya retak. Ada seorang anak perempuan yang masih di TK diperkosa anak SMP. Ada seorang janda diperkosa tukang sayur. Ada seorang Istri dimadu dua kali. Ada anak perempuan diperkosa kakeknya sendiri. Ada seorang janda dilecehkan oleh tetangganya.
Sebut saja jenis kejahatan itu, hampir semua ada. Namun, bahkan dengan mendengarkan semua cerita itu, pemahamanku tentang gender masih buruk.
Masih ada saja pikiran-pikiran seperti, “Aduh sayang sekali ibu itu tidak bekerja, seharusnya perempuan itu bekerja supaya tidak diperlakukan semena-mena.”
“Aduh, kenapa sih harus menikah umur segitu, kan mending bekerja dan menjadi perempuan karier.” Nilai-nilai patriarki ternyata masih mengakar dalam diriku.
Suatu hari ketika para konselor sedang asyik membicarakan penyanyi Fatin Shidqia Lubis, aku nyeletuk, “Aduh aku enggak suka Fatin!” Lalu Mbak Indi, Manajer Konselor bertanya, “Kenapa? Aku suka loh suaranya.” Aku menjawab, “Aku tidak suka karena dia suka menangis, tidak feminis.” Dan tentu saja Mbak Indi langsung menukas, “Memang menjadi feminis tidak boleh menangis?”
Pada saat itu aku merasa kalau Mbak Indi orangnya tidak santai. Tapi setelah dipikir lagi, aku yang sekarang akan menanyakan pertanyaan yang sama pada aku yang dulu. Memangnya kalau menjadi feminis tidak boleh menangis? Aku sadar, pada saat itu aku masih mengidealisasikan sifat ”maskulin”. Bahwa yang baik itu adalah sifat-sifat yang dipandang masyarakat sebagai sifat laki-laki. Perempuan feminis adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang tidak menangis, yang tegas, yang tidak plinplan. Lah, memangnya perempuan selalu plinplan dan menangis? Lalu laki-laki tidak boleh menangis dan plinplan? Aku belajar dengan perlahan tapi pasti. Aku mulai mencintai diriku sendiri, sebagai seorang perempuan cis-gender.
Suatu hari aku membaca mengenai teori hukum feminis. Pada intinya, dulu, orang-orang memperdebatkan bagaimana hukum yang baik mampu mengakomodasi perempuan agar tercapai kesetaraan gender. Ada sebuah konsep yang memandang apabila kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan adanya perlakuan setara (equal treatment). Konsep perlakuan setara memandang bahwa perempuan harus diperlakukan sama persis seperti laki-laki. Tidak ada cuti hamil, tidak ada cuti haid, hal-hal seperti itu harus dianalogikan sebagai penyakit prostat atau penyakit lain. Jadi boleh cuti kalau haid atau hamil, tapi cuti sakit, supaya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Seharusnya kita mengintegrasikan nilai-nilai dunia publik, yang ditata sedemikian rupa sehingga hanya cocok untuk laki-laki, dan rumah tangga. Pengakuan terhadap sektor privat sebagai sesuatu yang setara dan saling berkoneksi, bukan secara dikotomis dan hierarkis, akan dapat sedikit demi sedikit mengatasi persoalan hierarki gender.
Seiring dengan perkembangan jaman, muncullah konsep baru yakni kesetaraan gender dapat dicapai dengan perlakuan istimewa (affirmative action) atau kesetaraan substantif. Perempuan memiliki sifat-sifat biologis yang berbeda dengan laki-laki, dan hal tersebut harus dimaklumi.
Dua konsep ini kemudian menjadi perdebatan. Manakah yang seharusnya diikuti? Perempuan ingin diperlakukan setara dalam hal gaji, perlindungan hukum, suara di pemerintahan, akses politik, pendidikan, dan kesempatan-kesempatan bisnis, namun perempuan juga ingin diperlakukan istimewa karena karakteristik biologisnya yang berbeda dengan laki-laki.
Sampai pada suatu hari, ahli hukum Lucinda M. Finley dari Amerika Serikat mengatakan bahwa argumen kesetaraan gender maupun perlakuan setara tidak akan menyelesaikan masalah hierarki gender. Loh kenapa?
Katanya, baik perlakuan setara maupun perlakuan istimewa masih menganggap perempuan sebagai “yang lain”, anomali, ancaman, seseorang yang lebih rendah statusnya, dan yang bermasalah, sehingga agar diterima, perempuan harus diasimilasikan pada norma-norma patriarki. Menurut Finley, untuk mengatasi adanya hierarki gender, kita perlu memahami adanya kekeliruan dikotomi publik-privat. Seharusnya kita mengintegrasikan nilai-nilai dunia publik dan rumah tangga. Sekarang ini, sektor publik (tempat kerja) telah ditata sedemikian rupa sehingga hanya cocok untuk laki-laki, padahal tidak mungkin sektor publik bisa hadir tanpa kehadiran sektor privat (rumah tangga). Dengan demikian, pengakuan terhadap sektor privat sebagai sesuatu yang setara dan saling berkoneksi, bukan secara dikotomis dan hierarkis, akan dapat sedikit demi sedikit mengatasi persoalan hierarki gender.
Di situ titik balik dalam hidupku. Pertanyaanku terjawab dengan penelitian hukum 50 tahun yang lalu! Ketinggalan zaman banget ya.
Akhirnya aku sampai pada kesimpulan yang sangat sederhana. Kita harus saling menghargai. Kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan seksual, atau kekerasan tidak akan terjadi kalau manusia saling menghargai. Mereka yang bekerja di kantor seharusnya menghargai mereka yang bekerja di rumah. Mereka yang memiliki cita-cita menjadi menteri harus bisa menghargai cita-cita menjadi ibu rumah tangga. Mereka yang kuat menghargai yang lemah. Mereka yang berkuasa menghargai yang tidak berkuasa.
Loh, kalau begitu, perempuan juga harus menghargai laki-laki dengan cara menjaga pakaiannya, dong, biar tidak diperkosa? Waduh, itu mah beda konteks. Memakai baju mini itu bukan kejahatan, pemerkosaan itu kejahatan. Apa pun yang terjadi, pemerkosaan, pelecehan, kekerasan, itu tidak boleh. Mau pakai baju mini kek, mau enggak pake baju kek, pemerkosaan tetap tidak boleh dilakukan.
Temanku pernah bercerita tentang sebuah artikel yang sangat bagus, intinya mengatakan, ketika ada seorang perempuan berjalan telanjang di depan publik, dia tetap tidak boleh diperkosa. Yang dia lakukan itu juga salah, karena melanggar norma dan hukum, dan dia mungkin akan dikenai hukuman karena perbuatannya, tetapi bukan pemerkosaan. Selain itu, ada banyak kasus perkosaan terjadi bukan karena pakaiannya. Perempuan berjilbab, anak umur 6 tahun, atau tuna grahita, ada yang menjadi korban pemerkosaan.
Kesimpulan saling menghargai memang terdengar gampang, tapi sebetulnya sulit. Kita sudah hidup dalam label. Dalam dunia yang hitam dan putih. Benar dan salah. Laki-laki dan perempuan. Padahal dunia itu lebih dari itu. Untuk saling menghargai, kita harus mengakui bahwa dunia itu tidak hanya hitam dan putih, tetapi juga abu-abu, merah, kuning, hijau, jingga. Tidak hanya benar dan salah, tapi eh bener juga enggak tapi salah juga enggak, eh gimana ya. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, atau cis-gender, ada juga non-binary, ada non-conforming, ada transgender, ada a-gender, queer dan lain-lain. Dunia ini begitu besar dan banyak kemungkinan, dan kita harus menghargai kemungkinan-kemungkinan itu.
Begitulah perjalananku menjadi feminis di usia 21 tahun. Masih ada tahun-tahun berikutnya lagi untuk berkembang. Tapi kalau sekarang aku ditanya, kamu feminis? Iya aku feminis, aku anti kekerasan, dan menghargai perbedaan. Titik.
Clianta de Santo adalah relawan konselor hukum Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta.



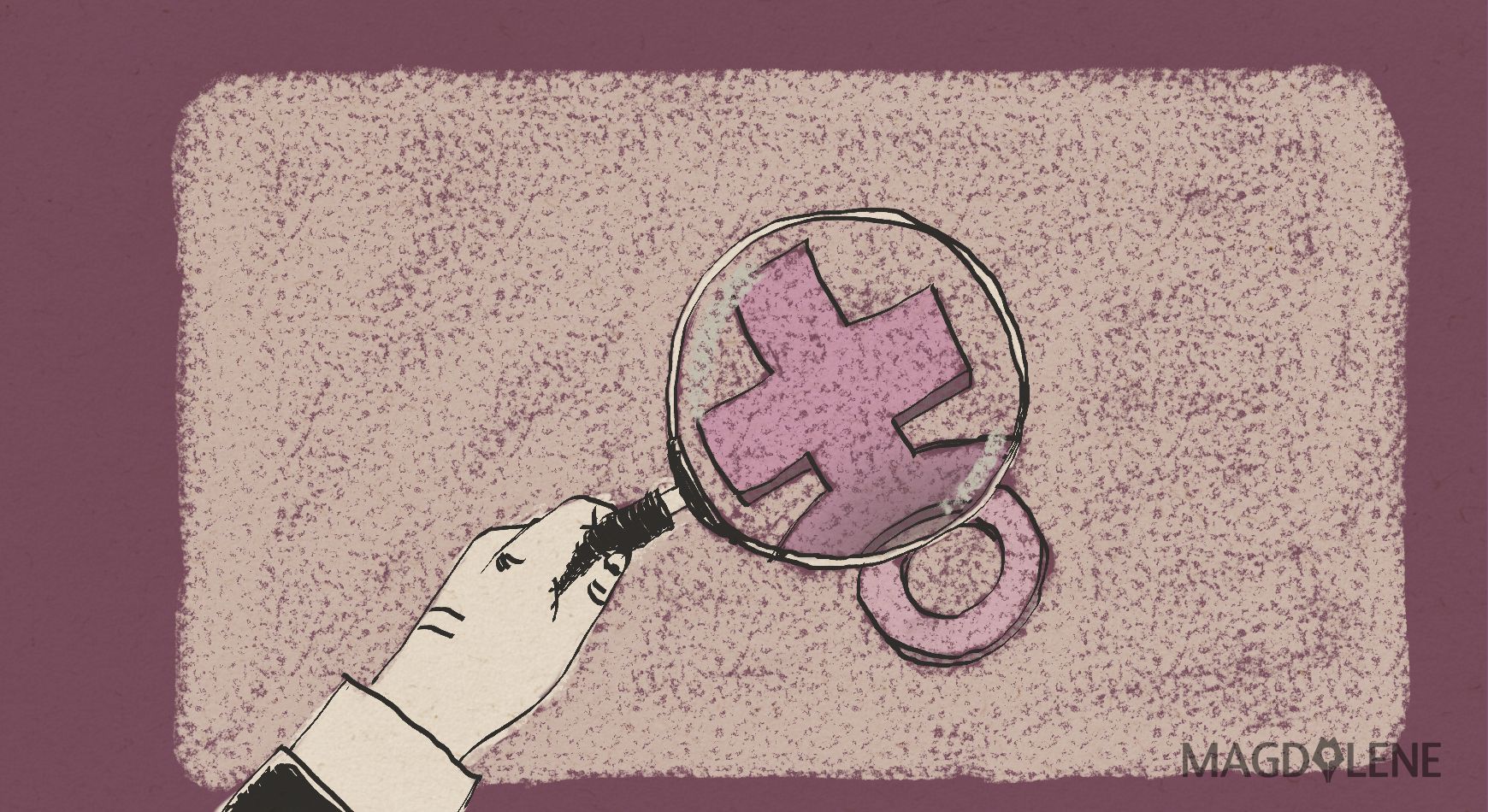




Comments