Suatu pagi di penghujung Desember, foto sepasang istri-suami menghiasi lini masa Instagram saya. Mereka adalah sepasang kekasih yang baru saja meresmikan hubungan, Polly Alexandria Robinson dan Nur Khamid mendapat ucapan selamat dari warganet. Dari ribuan ucapan selamat itu, sebagian dari mereka mengatakan betapa beruntungnya Nur bisa menikahi Polly yang berkulit putih.
Saya pikir ada hal lain yang disoroti masyarakat dari pasangan ini selain perbedaan budaya, ras, dan agama yang akhirnya bisa disatukan. Ternyata saya tidak menemukan hal lain. Komentar-komentar di Instagram Polly pun lebih banyak diisi dengan harapan warganet yang berpikir jodoh mereka mungkin sedang berada di luar Indonesia. Kendati bernada humor, komentar-komentar ini menjadi catatan saya bahwa masih banyak orang yang berpikir menikah dengan orang kulit putih adalah berkah. Bagi saya, ini bentuk inferioritas yang sengaja dilanggengkan.
Tentu inferioritas ini tidak tumbuh dari pola pikir individu saja. Supaya makin viral, media ikut andil mereproduksi kisah mereka dalam berbagai kemasan. Masih dengan pola yang sama, judul-judul provokatif tanpa pembaruan sudut pandang dipajang. Seolah-olah, hanya ada dua hal yang bisa dibahas dari pernikahan kedua sejoli ini: keberuntungan Nur dan kecantikan Polly.
Sebagai perempuan yang sedang belajar jurnalistik, bentuk eksploitasi ini membuat saya geram.
Polly bukan perempuan kulit putih pertama yang menjadi fenomena. Sebelum perempuan Inggris ini dieluk-elukan sebagai jodoh idaman, Jennifer Brocklehurst, Bianco Monte, Ermina Fransisca, dan Kathleen Mijo Kovarbasic pun mengalami hal yang sama. Seperti Nur, para lelaki yang menikahi mereka dianggap lebih beruntung. Tanpa sadar masyarakat mendegradasi nilai lelaki kulit berwarna sekaligus mengobjektifikasi perempuan kulit putih.
Padahal, dalam hubungan yang sehat dan seimbang, kedua pihak tentu sama-sama merasa beruntung bisa saling menemukan. Sayangnya, kualitas hubungan ini dibingkai media berdasarkan penilaian fisik semata. Saya bayangkan seandainya Polly seorang kulit berwarna, sorotan yang didapatkannya mungkin tak semasif sekarang. Seandainya Polly keturunan Afrika, dia mungkin tak memenuhi standar cantik mayoritas masyarakat Indonesia dan mungkin pula tak akan diundang stasiun televisi mana pun. Miris mengingat diskriminasi ini masih banyak terjadi di era di mana kesetaraan sebagai manusia dan bangsa didengungkan.
Baca juga: Butuh Belasan Tahun untuk Akhirnya Mencintai Kulit Gelapku
Sebelum kisah cinta Polly dan Nur viral, standar kecantikan warisan kolonial sebenarnya sudah lama merisaukan saya. Terlahir dengan kulit terang, saya tidak jarang mendapatkan pujian saudara dan orang terdekat. Sejujurnya, saya tidak pernah merasa istimewa hanya karena kulit saya yang di mata sebagian orang tampak lebih indah. Kerisauan ini tumbuh pada suatu sore ketika saya duduk di samping rumah dan seorang anak tetangga mendatangi saya untuk minta uang (sejak masih bayi, dia memang sudah terbiasa main di rumah orang tua saya). Sambil merengek, dia bilang ingin membeli losion seperti yang diiklankan di televisi. Saya tanya iklan losion mana yang dia maksud, dia bilang iklan itu dibintangi sekelompok penyanyi perempuan yang sebagian anggotanya keturunan Tionghoa.
Setelah mengetahui iklan yang dia maksud, saya menolak memberi uang padanya. Saya nasihati dia dengan mengatakan dia sudah cantik dengan kulit sawo matangnya. Dia merengut, tapi tidak putus asa. Dia bilang ibunya mengejeknya jelek karena berkulit sawo matang. Sampai di sini saya terdiam. Tetangga saya memang tidak berpendidikan tinggi, namun saya tak menyangka dia akan mengeluarkan ejekan rasialis itu pada anaknya yang baru berusia tujuh tahun.
Beberapa hari kemudian, bocah tersebut bertengkar lagi dengan ibunya. Sambil lari-lari, dia mengatai ibunya bodoh. Setelah puas mengatai ibunya, dia duduk di teras rumah saya. Tetangga saya menyusul sambil berseru meminta saya menasihati anaknya untuk tidak membantah omongan orang tua. Anak tetangga saya, dengan wajah masih jengkel, berkata dia marah karena ibunya mengingkari janji untuk pergi ke salon dan meluruskan rambutnya. Selain berkulit sawo matang, dia memang berambut ikal. Rambut ikal ini menjadi sumber rasa tidak percaya dirinya yang lain dan membuat saya kaget. Saya tidak habis pikir bagaimana pemikiran untuk menolak diri sendiri ditanamkan dalam usia semuda itu.
Tetangga saya gemar menonton sinetron. Dia tipikal orang yang bisa betah berjam-jam menghabiskan waktunya untuk mengonsumsi tayangan-tayangan dengan kualitas rendah. Saya paham kemiskinan tak memberinya banyak pilihan, dan sekalipun dia punya pilihan itu, saya yakin dia tak mampu memilih tayangan yang baik untuk anak-anaknya.
Anaknya sering bercerita tentang sinetron yang dia tonton bersama ibunya. Kadang-kadang dia mengungkapkan kekagumannya pada beberapa artis blasteran karena kulit putih dan wajah cantik mereka. Tak sekali dua kali pula dia mengusap kulit saya dan bertanya bagaimana cara saya mendapatkan warna seterang itu. Saya sedih melihatnya tumbuh menjadi gadis yang tidak percaya diri. Setelah saya melahirkan, dia tetap menunjukkan kekagumannya pada kulit anak saya.
Baca juga: Kami Perempuan Melanesia, Kami Ada, dan Kami Cantik!
Yang membuat saya sedih, dia kemudian melakukan hal yang dulu dilakukan ibunya. Saat anak saya mulai bisa bermain di luar rumah, dia berkata, “Hah, kulit Adek enggak putih kayak Mama Ika!” Ucapan ini terasa menyakitkan bagi saya. Menyakitkan karena saya tidak bisa memutus pola pikir rasialis, seksis, dan diskriminatif yang terjadi di depan saya. Ingin rasanya saya menegur tetangga saya agar lebih berhati-hati saat bicara dengan anak-anaknya namun itu akan percuma. Memaksakan diri berdiskusi dengan orang yang tak memiliki pemahaman untuk mengubah keadaan hanya akan membuat saya tampak buruk. Di mata tetangga saya, saya mungkin orang sok pintar yang hanya bisa ngomong berdasarkan buku.
Kesedihan dan kejengkelan ini semakin terakumulasi saat saya bekerja di media. Semakin saya mencoba kritis, semakin mudah pula saya dibuat marah oleh banyak hal. Saya marah melihat produsen kosmetik tetap gencar mempromosikan bagaimana mendapatkan kulit putih ketimbang kulit sehat. Media melanggengkan rasialisme dan supremasi ini dengan memudahkan mereka yang bertampang bule untuk masuk industri hiburan meski tidak jarang minim talenta. Seolah-olah, sudah sewajarnya masyarakat mendapatkan tontonan berkualitas rendah. Asalkan modelnya cantik dan tampan, peringkat akan terangkat. Seolah-olah karena sudah gratis, masyarakat yang cukup kritis tak seharusnya mengkritik.
Saya bukannya sinis pada orang-orang Kaukasian atau orang-orang keturunan Kaukasian yang memilih berkarier di Indonesia. Saya percaya sebagian dari mereka punya talenta nyata, yang sayangnya tak diimbangi dengan keberuntungan yang besar. Mereka mungkin tahu begitu sulit bagi orang-orang kulit berwarna menghilangkan rasa rendah diri akibat penindasan di masa lalu. Saya tak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena di sinilah sistem besar bernama kapitalisme turut berperan.
Kelak jika anak saya tumbuh dengan kulit tak seterang kulit saya, saya ingin dia bisa belajar mencintai diri sendiri. Saya ingin dia mengerti bahwa kualitas manusia tak seharusnya dinilai dari fisik semata. Saya ingin dia mengerti bahwa menikah dengan orang dari warna kulit apa pun tak akan membuatnya lebih rendah atau lebih tinggi. Saya ingin dia mengerti bahwa beruntung dalam pernikahan tak melulu soal mendapat wajah yang rupawan, tapi juga bisa saling menjadi teman hidup yang menyenangkan. Dan pada akhirnya, jika dia dewasa nanti, saya ingin dia menjadi perempuan yang mandiri, penuh kasih, percaya diri, dan tahu artinya menghargai.



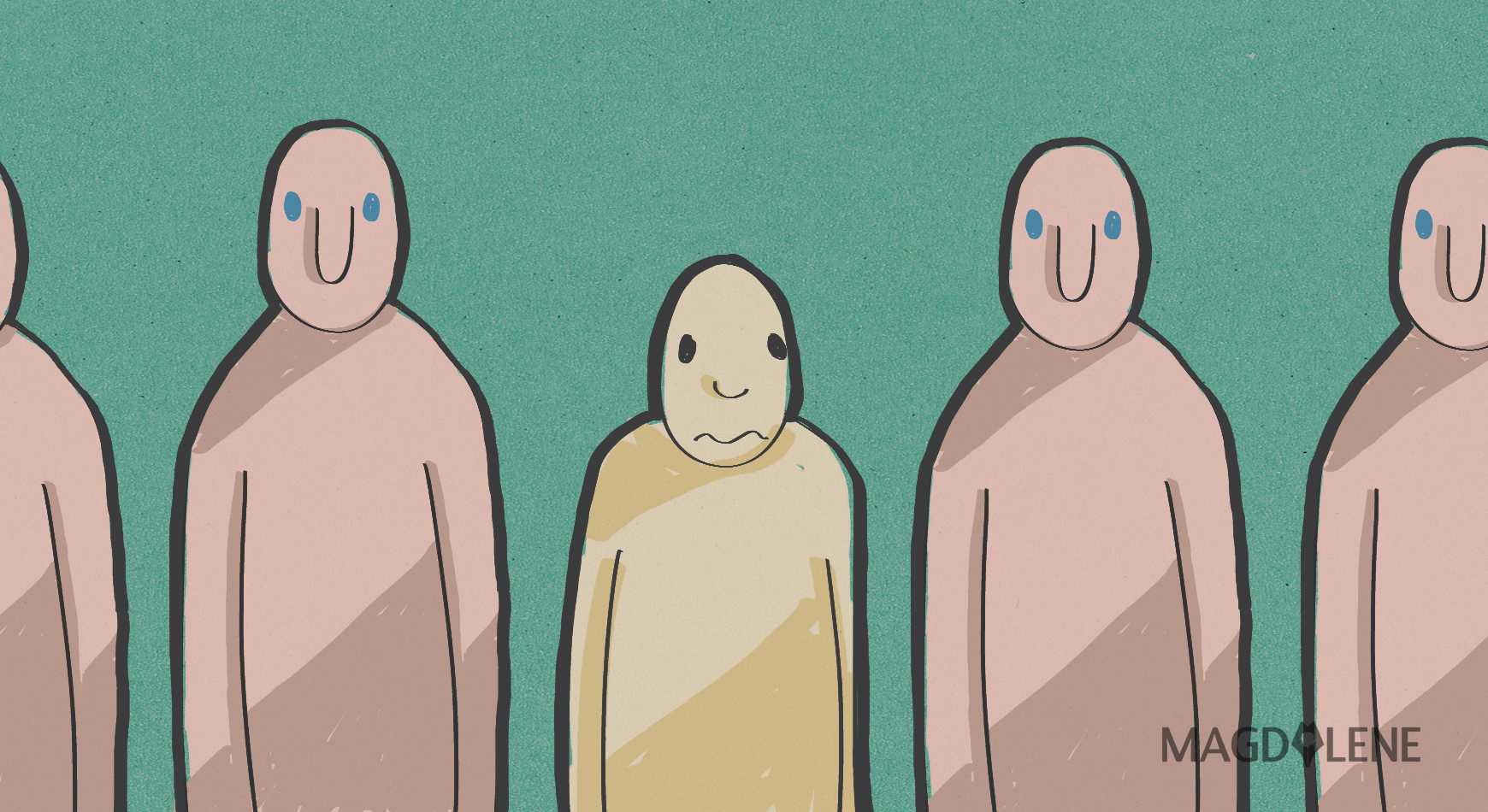



Comments