Pemerintah didorong untuk menacanangkan peraturan yang tegas terkait pengajuan dispensasi untuk menikah, karena hal ini telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkawinan anak.
Pernikahan anak masih marak di negara ini, dengan satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Artinya 22,91 persen perempuan di Indonesia melakukan praktik perkawinan anak, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Hal ini membuat Indonesia menduduki peringkat kedua di wilayah Asia Tenggara dan peringkat ketujuh di dunia dengan angka perkawinan anak terbesar.
Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah di Kementerian Agama, Muhammad Adib Machrus, mengatakan bahwa dispensasi nikah menjadi faktor utama yang melanggengkan praktik pernikahan anak.
“Jika mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, dan kekal. Dengan demikian, praktik perkawinan anak yang memperburuk kondisi anak dan mencabut hak-hak mereka adalah praktik yang ilegal. Memberi dispensasi nikah pada anak berarti melegalkan praktik ilegal,” jelas Adib dalam Dialog Publik Pencegahan Perkawinan Anak, Selasa lalu (18/12).
Di Indramayu dispensasi kawin tahun 2015 sebanyak 456 berkas, dan pada tahun 2016 mencapai 350 berkas.
Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa penaikan usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun tidak akan membawa perubahan apa-apa jika syarat dispensasi nikah masih longgar.
KPAI mencatat bahwa di Indramayu, Jawa Barat, saja ada 456 pasangan yang menikah lewat dispensasi umur pada 2015, dan pada 2016 mencapai 350 pasangan.
Retno mengatakan bahwa alasan pengajuan dispensasi nikah ini berbeda-beda tergantung kemampuan ekonomi masyarakat. Pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, kemiskinan mendasari kurangnya pendidikan orangtua tentang dampak-dampak perkawinan anak serta pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Di sisi lain, alasan masyarakat kelas atas melakukan pernikahan anak adalah agar menghindarkan anak dari perbuatan zina atau dosa.
“Yang terjadi pada masyarakat kelas menengah tergolong fenomena baru seiring dengan isu konservatisme agama di Indonesia,” ungkap Retno.
Ia menambahkan bahwa seharusnya anak tidak dibebankan akibat dari kelalaian orang tua dalam membimbing dan mendidik mereka.
“Anak-anak itu bisa salah, boleh salah, dan harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menikahkan anak bukan upaya perbaikan, tapi justru akan menghancurkan masa depan mereka. Dalam hal ini, pihak-pihak yang lebih dewasa, termasuk orang tua, masyarakat, dan negara bertanggung jawab mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi anak-anak kita,” kata Retno.
“Lagi pula, pernikahan tidak semestinya dimaknai hanya sebatas upaya menyelamatkan citra keluarga karena tidak sebanding dengan dampak buruk yang akan terjadi pada anak dalam jangka panjang,” tambahnya.
Retno juga menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak, termasuk hak pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, serta membatasi status dan peran anak.
Ia menyebutkan anak-anak yang menikah berpotensi tinggi berhenti bersekolah sehingga akses terhadap penghidupan layak otomatis tertutup. Selain itu, organ reproduksi anak perempuan yang belum berfungsi sempurna juga menyebabkan tingginya risiko kematian ibu dan bayi.
Akses pendidikan seksual terbatas
Budi Wahyuni, Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), mengatakan bahwa sistem pendidikan seksual harus diperbaiki agar anak mengenali tubuh mereka dan terhindar dari risiko melakukan aktivitas seksual, serta membebaskan anak dari stigma dan diskriminasi di lingkungan sosial mereka.
“Upaya penghapusan perkawinan anak tanpa perbaikan pendidikan kesehatan reproduksi itu omong kosong. Kita perlu ingat bahwa anak-anak terus berkembang secara biologis. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan seksual,” jelasnya.
Saat ini di Indonesia, ujarnya, pendidikan kesehatan reproduksi masih dianggap sebagai hal tabu sehingga anak-anak sulit mengakses informasi yang proporsional.
“Anak-anak harus mulai mengenali tubuh mereka sendiri dan itu tidak harus berujung pada seks pranikah atau kehamilan tak direncanakan. Pakar kesehatan reproduksi tentu menyebut masturbasi ketika remaja memiliki kebutuhan seksual. Masalah pencegahan kehamilan dan penularan penyakit kelamin—pakar kesehatan akan lantang menjawab: kondom,” ujar Budi.
Perkawinan anak meningkatkan kerentanan anak terhadap infeksi dan penyakit kelamin dari mulai Human Papillomavirus, kanker mulut rahim, hingga HIV/AIDS, ujar Budi. Ia menambahkan bahwa lubrikasi vagina juga belum berfungsi sempurna pada usia anak sehingga berisiko tinggi terjadi iritasi ketika dilakukan penetrasi.
“Sedangkan pengetahuan orang sekitar justru mengukuhkan bahwa, semakin sulit penetrasi, maka itu berarti vagina masih bagus, rapat dan sebagainya—padahal tidak demikian,” jelas Budi.
Budi juga menyebutkan kurangnya pendidikan terkait akses kesehatan dan kebutuhan reproduksi.
“Di Indonesia, hampir tidak mungkin anak-anak membicarakan seksualitas mereka dengan orang dewasa, seperti orang tua atau guru BK [Bimbingan Konseling]. Lalu siapa yang bisa mereka ajak? Ya, teman-temannya, pacarnya—yang sama-sama tidak memahami isu kesehatan reproduksi,” tambahnya.
Anak-anak yang telah menikah juga direnggut haknya atas perlindungan anak, ujar Budi.
“Anak yang menikah tiba-tiba mengalami loncatan status. Mereka langsung dianggap orang dewasa hanya karena secarik kertas nikah. Mereka langsung kehilangan hak perlindungan anak,” jelasnya.
Survei ini menunjukkan bahwa 81 persen perempuan pekerja mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.





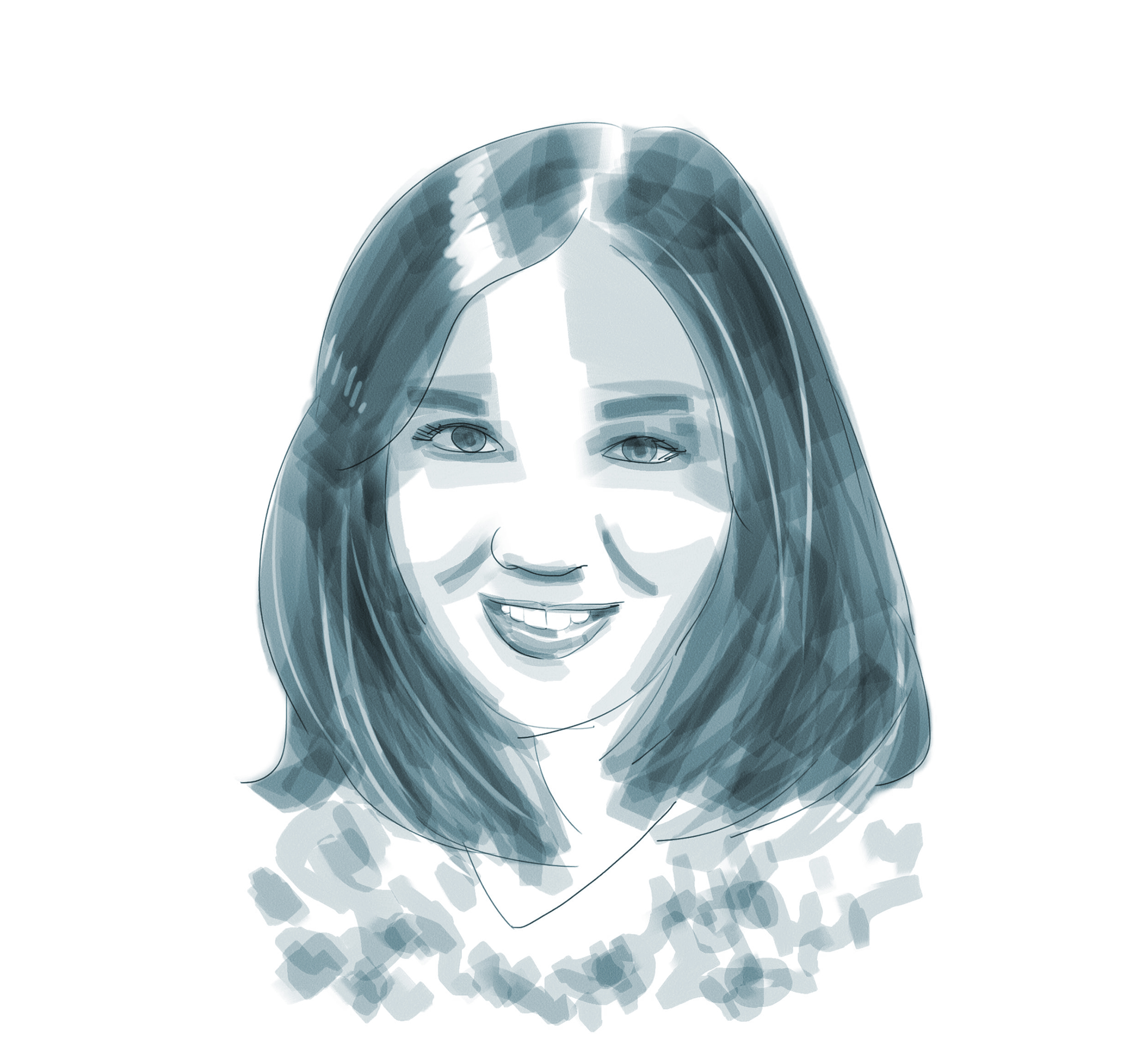



Comments