Sebagai remaja dari generasi 90-an akhir yang terpapar internet, saya mengenali kata dan konsep feminisme pertama kali melalui BuzzFeed. Yang saya tangkap dari informasi saat itu adalah bahwa perempuan mengalami opresi (saya belum paham maksudnya waktu itu) dan saya sebagai perempuan harus ikut melawan.
Pada lain waktu, saya melihat Beyonce memajang tulisan “FEMINIST” besar-besar di layar LED MTV VMA 2014. Lalu, Emma Watson juga muncul dengan pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyinggung soal feminisme. Selain itu, ada Taylor Swift, Lady Gaga, Benedict Cumberbatch, dan banyak sekali selebritas keren yang juga vokal soal isu gender dan feminisme. Kalau begitu, sebagai orang yang juga ingin menjadi keren, saya harus menjadi feminis juga!
Kata mereka (atau kata Chimamanda Ngozi Adichie melalui narasinya di video klip Beyonce), feminis adalah orang yang percaya pada kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Saya belum betul-betul mengerti ketika mendengarnya, tetapi saya yakin terhadap hal itu. Kenapa manusia harus dapat hal yang berbeda hanya karena jenis kelaminnya?
Mengenal feminisme membuat saya merasa menjadi secret cool girl dan mulai mengais-ngais informasi mengenai masalah perempuan hingga jadilah saya yang seperti ini.
Bila bermain hitung-hitungan, saya ini termasuk perempuan beruntung meskipun saya, seperti hampir semua perempuan tentu pernah digoda orang di jalan, pernah dikomentari bagian tubuhnya tanpa saya minta. Hanya saja, saya tidak merasa punya trauma seksual.
Diskriminasi berdasarkan gender pun tidak saya alami, paling tidak yang saya sadari. Malah, saya cenderung mendapat keuntungan dari gender saya ini karena saya selalu diajari orang tua untuk bisa menjadi ratu dan mengejar apa pun yang saya mau dengan penuh lemah lembut. Kalau lahir sebagai laki-laki, mungkin orang tua saya justru akan lebih keras. Intinya, saya tidak punya struggle berarti sebagai perempuan.
Baca juga: Feminisme dan Budaya Pop: Jangan Hanya Mengganti Saluran
Tentu saya mengerti kalau perjuangan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama perempuan. Namun namanya juga manusia, sering kali saya merasa tertinggal dalam perbincangan karena kurangnya reliabilitas. Maklum, saya mayoritas ganda: Cisgender dan heteroseksual, golongan kelas menengah dengan orang tua sebagai jaring pengaman, serta pemeluk agama mayoritas.
Privilese jadi tidak feminis?
Dengan privilese yang sudah saya punya itu, bisa saja saya memilih menjadi feminis jalur akademis. Tetapi saya sadar, kemampuan saya tidak begitu mumpuni. Bidang keilmuan yang saya geluti tidak memungkinkan saya untuk mempelajari permasalahan perempuan secara mendalam dan tempat saya berkuliah belum memiliki ruang berarti untuk mendiskusikan mengenai gender.
Saya akan cenderung “memaksa” kalau saya berusaha menyerap sebanyak-banyaknya dan sesegera mungkin pengetahuan soal feminisme hanya untuk bisa diterima dan diakui sebagai feminis. Sampai detik ini saja, saya masih belum membaca The Second Sex-nya Simone de Beauvoir yang menjadi salah satu “kitab suci” di kalangan teman-teman saya yang feminis.
Kalau sedang senggang, saya suka berpikir sendiri, apakah ketiadaan pergulatan dalam menjadi perempuan dan kurangnya pengetahuan teoretis membuat saya kurang feminis?
Pertanyaan itu menguat mengingat feminisme yang saya pahami dan ikuti diawali hanya dengan ikut-ikutan selebritas dan penyedia konten hiburan, yang kalau dilihat lagi selalu membuat saya mengernyitkan dahi sambil menghina diri semasa SMP. Kemudian saya juga mengetahui bahwa ternyata, selebritas dan beberapa tokoh feminis yang saya kagumi dikritik berbagai pihak karena dirasa tidak inklusif, terlalu putih, dan sebagainya.
Baca juga: Kalau Kamu Begini, Kamu Bukan Feminis: 7 Pandangan Saklek Soal Menjadi Feminis
Sudah kurang pengalaman, kurang belajar, salah panutan pula. Ini mungkin namanya sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu menabrak tembok (saya menulis ini masih dalam kondisi kecewa setelah mengetahui kalau Adichie ternyata seorang TERF).
Menjadi feminis yang tak sempurna
Walau di satu sisi saya masih terpikirkan untuk diterima dan diakui sebagai feminis, di lain sisi saya sadar bahwa label feminis sendiri masih sering dimaknai sebagai peyorasi. Perempuan yang memasang dan mengekspresikan label ini dianggap mau menang sendiri, banyak mau, cuma mau enaknya saja, dan hal lain yang tidak ada bagus-bagusnya.
Tak hanya itu, saya juga mengamati ada kesan eksklusif dalam kelompok feminis tertentu, seolah saat seseorang dalam kelompok itu berbuat salah, “kartu anggota” feminisnya dapat langsung dicabut. Feminis yang terkesan eksklusif, dengan rekam jejak aktivisme yang panjang dan gelar akademik tinggi menterengnya, membuat saya terintimidasi sekalipun saya perlahan melahap banyak buku feminisme dan mencari asal-usul penulisnya.
Jangan lupakan ekspektasi sebagian feminis yang bagi orang-orang tertentu berarti mengurangi kesenangan hidupnya karena dianggap bertentangan dengan nilai feminisme. Saya lantas berpikir, apakah kalau menjadi feminis, saya tidak bisa lagi mendengarkan lagu-lagu berlirik nyeleneh dan bertindak sesuai dengan standar heteronormatif? Saya masih sangat sering mendengarkan lagu-lagu yang liriknya pasti akan di-cancel habis-habisan oleh feminis di tahun 2020, memilih untuk diam dan cenderung pasif apabila merasa tidak nyaman, berdandan untuk mencari validasi orang lain, dan ingin masuk ke dalam standar kecantikan. Apa tindakan saya yang tidak mengikuti standar feminis yang beredar luas ini akan mencederai gerakan tersebut?
Baca juga: Melirik Keberagaman Fokus Perjuangan Aliran-aliran Feminisme
Semakin saya belajar, semakin lenyap kepercayaan diri saya untuk mengklaim sebagai agen perubahan setelah mengetahui kalau apa yang selama ini saya ketahui ternyata belum ada apa-apanya dibanding yang lain dan hanya secuil dari banyaknya referensi feminisme. Kalau begitu, mengapa tidak menyebut diri saya dengan “peduli dengan isu perempuan” dibanding dengan melabeli diri sebagai feminis? Mungkin dengan ketiadaan label tersebut malah akan memudahkan saya untuk mengikuti prinsip feminisme.
Walau begitu, saya ini hanya manusia biasa yang masih suka menjelek-jelekkan diri, ikut-ikutan, dan melabeli diri sendiri demi mencari identitas yang entah akan diketemukan atau tidak. Layaknya anak TK yang diberi bintang oleh gurunya dan setelah itu betul-betul bertindak seperti malaikat, saya juga ingin memberi stempel tulisan feminis di punggung tangan sebagai pengingat dan motivasi saya untuk menghidupkan label tersebut.
Pasti feminisme yang saya coba terapkan tidak akan sempurna. Seandainya saya seorang selebritas, mungkin saya sudah kena cancel sejak jauh-jauh hari dan dikritik habis-habisan mengingat pilihan-pilihan dalam keseharian saya tadi. Kemudian, saya disebut poser yang hanya mendompleng gerakan feminisme demi hal selain kesetaraan gender yang nyata.
Kendati tak sempurna pun, saya akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berusaha untuk selalu bertanggung jawab. Tidak seluruh pikiran, perilaku, dan kegiatan saya akan masuk ke dalam standar feminisme. Tapi paling tidak, saya jadi berpikir ulang apakah yang gagasan saya atau yang saya lakukan adalah sesuatu hal yang baik dan benar.
Saya yakin bahwa feminisme mempunyai banyak bentuk. Saya punya cara sendiri, Anda punya cara sendiri. Mungkin tidak ada salah atau betul karena kehidupan sendiri adalah spektrum abu-abu tanpa ujung. Selama masih ada keyakinan bahwa perempuan dan kelompok gender minoritas lainnya masih memiliki masalah akibat gendernya dan perlu diperjuangkan, maka saya merasa, selama itu pula orang tersebut adalah feminis.



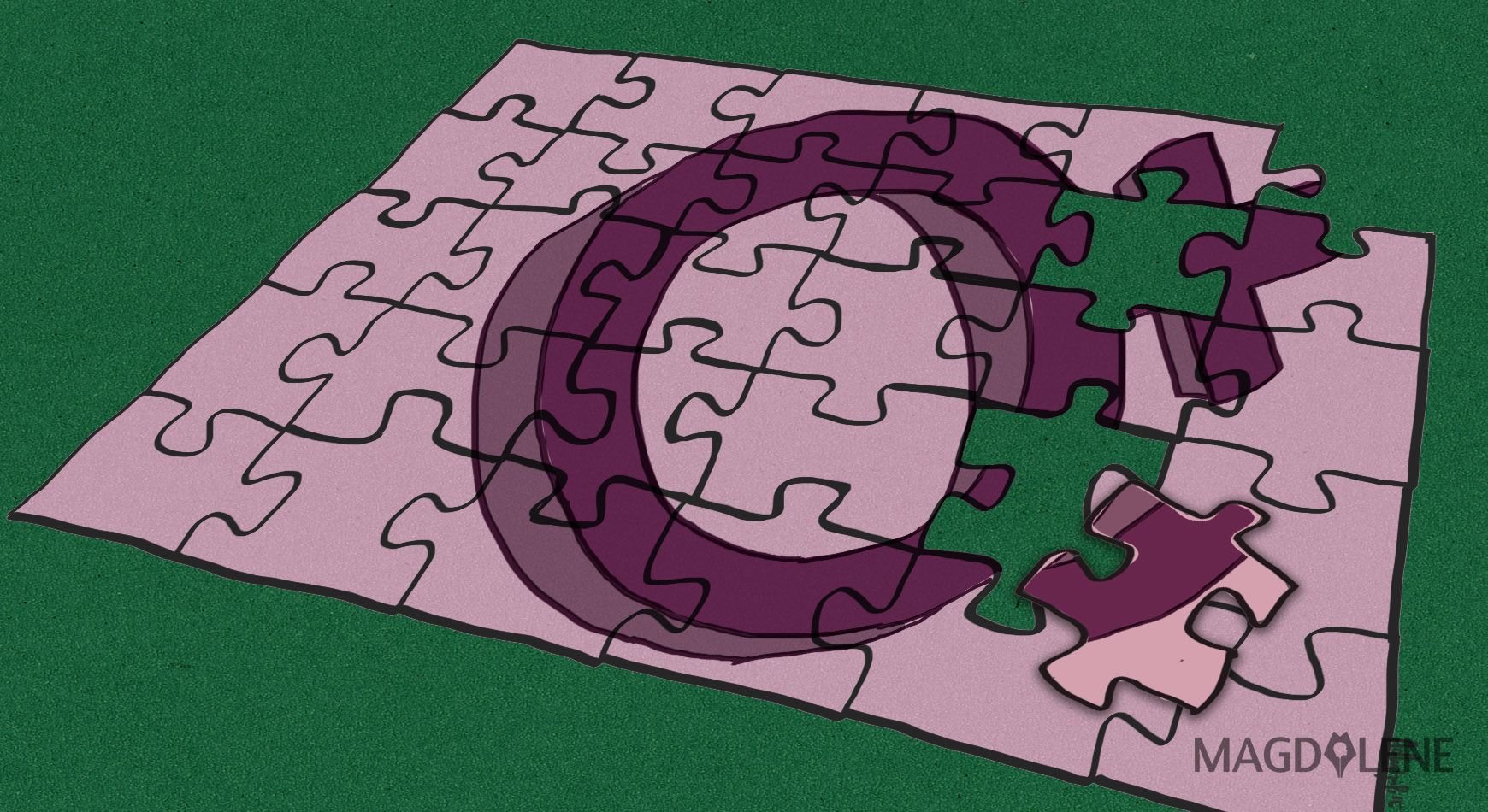



Comments