Akhirnya ada satu hari libur yang berhasil kami sepakati sebagai hari bertemu. Sudah sepuluh tahun berlalu sejak terakhir kali kami berjumpa. Aku dan Tia bersahabat sejak SMA dan sama-sama mengikuti klub renang. Maka, untuk merayakan pertemuan ini, berenang adalah pilihan terbaik.
Jam tangan menunjukkan pukul satu kurang lima belas menit. Aku datang seperempat jam lebih awal dari waktu janjian. Setelah satu jam menunggu di halaman parkir kendaraan, aku tidak melihat tanda-tanda kehadirannya. Dulu, ia biasanya datang tepat waktu, bahkan selalu terlihat telah hadir di lokasi janjian beberapa menit lebih awal. Dengan suara lantang, wajah ceria, dan tubuh lincahnya, ia akan memanggil dari jarak bermeter-meter. Tapi kali ini belum juga tampak.
Lantas aku turun dari sadel sekuter dan mencoba menengok ke area kolam renang. Ramai tidak, ya? Datang atau tidaknya dia, aku akan tetap berenang. Sudah lama juga aku tidak berenang. Kurasa karena ini hari libur, kolam renang jadi sangat ramai. Banyak orang tua yang membawa anak-anaknya. Ada juga segerombolan anak tanpa orang tua menemani.
Baiklah, ramai juga tak masalah.
Aku kembali ke halaman parkir sambil menerka-nerka bagaimana penampilan terkini sahabatku itu. Pantatku belum juga menyentuh sadel saat seseorang dari bawah pohon ketapang sana memanggil namaku. Itu dia! Suara lantang itu langsung kusambut dengan lambaian tangan. Kami berpelukan dan saling bertatapan. Kantung matanya menebal dari yang kuingat terakhir kali, tapi senyumnya tetap manis dan nada suaranya tetap ceria.
Setelah menemukan sebuah meja tempat menaruh tas dan alas kaki, kami berganti pakaian dan langsung melompat ke kolam renang. Kurasa karena awan-awan gelap datang, kolam yang tadinya ramai mendadak sepi perlahan. Kami berenang-renang kegirangan seperti siswa sekolah dasar yang merasakan libur sekolah untuk pertama kali.
“Yun, aku ingin cerai.”
Pernyataan yang tiba-tiba ini membuatku harus segera menggali referensi tentang kabar terbarunya dalam otak. Kutatap ia lekat-lekat. Nada bicaranya yang tenang membuatku bertanya-tanya apa yang telah terjadi selama sepuluh tahun.
Ia tersenyum, “Aku lelah.”
“Tapi tak nampak?”
Pertanyaanku dijawab dengan gelak tawa darinya. Terbahak-bahak. Diajaknya aku ke tepi dan mengambil minuman yang baru saja diantarkan oleh petugas kolam. Kapan ia memesan minuman, aku tak ambil pusing.
“Menyesal aku kenal dia. Andai saja dari dulu bisa berpikir seperti ini, tak akan kudekati dia.”
Aku masih menatapnya lekat.
“Iya. Kau ingatlah betapa gegabahnya aku dulu.”
Segera kenangan tentang perjalanan cinta masa SMA muncul satu-satu di kepalaku. “Apa maksudmu?”
“Iya. Aku lupa bagaimana kami dulu bisa jadi sepasang kekasih. Padahal kalau diingat-ingat, tak pernah ia menyatakan perasaan dan memintaku untuk jadi kekasihnya. Lagi pula, sebelum bersamanya, aku sedang menyukai seseorang. Kau tahu orangnya siapa? Kau pasti mengenalnya.”
“Hmm? siapa?”
Dia tertawa terpingkal-pingkal. Gelas di tangannya sampai miring dan minuman di dalamnya hampir tumpah. “Irwansyah! Tak ingatkah kau pada Irwansyah?”
“Kau serius? Dia? Aku ingat banyak yang suka padanya.”
“Iya, aku salah satunya. Dulu ia sering membelikanku minuman dingin usai pelajaran olahraga. Itu suka, kan? Itu tanda ia menyukaiku, kan? Tapi aku tak yakin. Malu!”
Matanya terlihat berbinar-binar mengingat Irwansyah. Tanpa niat merespon, kuanggukkan kepala tanda siap menyimak lanjutan cerita.
Baca juga: Ibu Sudah Melawan
“Kau tentu ingat masa-masa lulus SMA kita. Banyak teman yang pergi berkuliah ke luar negeri. Kau salah satunya. Dia juga salah satunya. Kau tahu, ia menuliskan alamat asrama tempatnya tinggal dan memintaku ikut berjanji bahwa kami akan saling berkirim surat. Tapi, begitu mengetahui kabar pernikahanku, ia tak lagi membalas suratku!”
Tubuhku diguncang-guncangnya. Minuman di tanganku terombang-ambing dan sedikit tumpah airnya dari gelas. Segera ia meminta maaf dan melanjutkan cerita.
“Kau tahu, Irwansyah menikah seminggu yang lalu. Kabar ini kudapat dari salah seorang kawan yang kini bekerja bersamanya. Aku sedih. Seandainya dulu aku menyatakan cinta. Seandainya dulu aku tak silau pada kegagahan orang dewasa dan bersikap polos.”
“Suamimu kenapa?”
“Oh! Mungkin sedari awal ia tak mencintaku.” Tia beranjak dan menarikku ke tepi kolam. Kami tinggalkan minuman di atas meja. “Dingin. Mari masuk ke dalam kolam. Aku berharap hujan turun.”
Aku melongo. Dingin memang. Kudongakkan kepala dan mendapati awan-awan semakin mendung.
“Sepertinya benar-benar akan hujan. Burung-burung terbang gelisah.”
“Benar, kan, hujan akan turun? Aku suka berenang di kala hujan. Dadaku jadi beku. Renyuh rasanya.”
“Ceritakan tentang suamimu.”
“Oh, kau tahu, aku sering sakit hati sendiri. Merasa kesal sendiri. Berulang-ulang. Aku bingung bagaimana bisa dulu aku begitu mencintainya. Kekesalanku pun tak pernah ditanggapi olehnya dan akhirnya aku jadi terbiasa,” ia tertawa terbahak-bahak.
“Aku rasa ia sering punya selingkuhan. Itu salah satu kekesalanku. Tapi sekarang jika kupergoki ia tersenyum membaca sebuah surat, itu tak lagi membuatku pusing. Aku sudah tahu kenapa.”
“Kenapa?”
“Yun, itu pasti dari murid-muridnya. Aku dulu pernah memeriksa surat-surat itu. Tanpa alamat. Kertas buku tulis biasa. Isinya penuh ujaran kekaguman dan ungkapan cinta! Kau tahu suamiku itu gemar menulis sajak meski tak pernah sekali pun ada sajak yang ditujukan untukku. Tapi untuk murid-muridnya itu ia menulis begitu banyak sajak! Aku merasa sudah menikahi seorang guru cabul!”
Suaminya adalah seorang guru prakarya di sebuah SMA. Aku sendiri belum pernah jumpa. Pernikahan mereka diadakan saat aku sedang berkuliah di Belanda.
“Kau tahu, aku pernah bertanya maksud dari isi surat-surat itu. Ia marah. Ia menyebutku sebagai istri yang tak patuh karena melanggar privasinya. Apa kau pikir aku demikian? Ia suamiku. Apa gunanya privasi?”
“Aku belum menikah, Tia.”
“Ya, aku ingin sepertimu.” Dipeluknya aku dari samping. Kurangkul pundaknya seraya bertanya tentang anaknya.
“Tentu aku mencintai anakku. Keputusan bercerai ini pun kusadari akan menyakitinya. Tapi aku tidak bisa hidup dalam lingkaran setan ini lagi.”
“Kekesalan apa lagi yang kau hadapi selain perselingkuhannya?”
“Ia bukan rekan rumah tangga yang baik. Kau tahu, saat piket jaga pagi, aku selalu berangkat ke rumah sakit pukul delapan pagi dengan meninggalkan setumpuk piring kotor sisa sarapan di dapur. Sampai aku pulang pukul sepuluh malam, piring-piring itu masih tetap di sana! Ditambah lagi tiba-tiba ada kain perca, balok kayu kecil, dan lem sisa hasil prakarya buatannya. Dan entah apa lagi, itu semua berserakan di mana-mana. Ya Tuhan!
“Keadaan itu membuatku merasa seperti pembantu. Aku lelah seharian bekerja dan ia masih mengharapkanku membereskan segala kekacauan di rumah, padahal ia selalu berangkat pukul sembilan dan pulang lebih awal dariku. Bukankah seharusnya ia bisa membantu? Aku ingin lelaki yang lebih terbuka!”
Ia mencelupkan kepala ke air. Aku hanya bisa mengehela nafas menatap tubuhnya mengambang di permukaan kolam. Sebagai dokter, waktunya sudah banyak tersita oleh orang-orang di rumah sakit. Seharusnya ia mendapatkan suami yang bisa mengerti.
Baca juga: Antara BH, Drakor, dan Jemuran Kos
Awan di atas semakin gelap. Ia mengganti posisi tubuh dan kembali bersandar di tepi kolam. “Kau tahu, ini bukan kali pertama aku mengajukan cerai. Setahun yang lalu aku meminta obrolan serius dan mengajukan itu kepadanya. Ia hanya diam lalu memelukku. Tanpa ucapan maaf, Yuyun. Tanpa ucapan maaf. Esoknya, ada yang berubah. Ia jadi mulai lebih perhatian kepadaku dan mau membantu pekerjaan rumah. Tapi itu hanya bertahan beberapa minggu. selanjutnya, ia kembali acuh tak acuh!” ia tertawa sambil menyiramkan air kolam ke wajahnya sendiri.
“Kau tahu, sebelum aku berangkat tadi ia sempat bertanya aku hendak ke mana. Kujawab pergi berenang bersamamu, ia cemberut lalu menyindirku. Disebutnya aku sebagai ibu yang gemar keluyuran tanpa memikirkan suami dan anak. Padahal, kau tahu, anakku jadi membenciku karena sering dibisiki yang tidak-tidak olehnya. Oh, sedihnya aku.”
“Kau ceritakan tentangku padanya?”
“Tentu!”
“Mungkin ia curiga kau akan membocorkan dapur rumah tangga kalian.”
“Oh, semoga! Aku muak. Pernah suatu hari aku pulang dari piket jaga malam dan mendapati ia sedang menulis surat. Kuintip dari belakang, langsung saja ia mendampratku! ‘Sana cuci piring! pakaian kering belum lagi digosok!’ ujarnya. Betapa aku kecewa dan semakin kehilangan tenaga. Bukan kasih sayang yang kuterima, malah umpatan dan perintah.”
“Saat kalian menikah, kau sudah berkuliah di fakultas kedokteran. Bukankah, idealnya, ia paham jam kerja seorang dokter?”
“Idealnya, iya. Kenyataannya, tidak.”
Lantas ia terkenang akan raut wajah ayahnya saat menjadi wali pernikahan. Jauh lebih mendung dari awan di atas kepala kami sekarang, ujarnya. “Tatapan nanarnya terhadap pesta sederhana itu lebih mirip seperti tatapan upacara melepas anak gadis sebagai tumbal. Aku benar-benar merasa bersalah.”
Setelah menikah, Tia tetap melanjutkan kuliah dengan biaya dari ayahnya dan sampai di sinilah ujung ingatanku tentangnya. Setelah itu kami absen berkirim surat.
“Tapi untungnya ibu mertuaku tak ikut campur. Sikapnya itu cukup membantuku. Kau tahu, kan, kami tinggal bersama orang tua suamiku? Kami masih di sana. Ayah mertuaku jarang di rumah. Suamiku pun tak disukai oleh ibu tirinya. Oh, baru pula kusadari ini!” ia mengangguk-angguk sendiri.
“Ibu tiri?”
“Iya. Ibu kandung suamiku meninggal saat kau masih di Belanda, aku tak sempat mengirimu surat. Lalu ayahnya menikah lagi dengan seorang janda. Suamiku jadi punya dua saudari tiri. Ia baik luar biasa kepada mereka, tapi aku heran mengapa ia tak bisa baik kepadaku.”
“Kepribadian ganda?”
“Bukan, itu bukan kepribadian ganda. Aku tahu ia melakukannya dengan sengaja. Yang semakin membuatku heran, Yun, jika ia tak menyukaiku, mengapa permintaan ceraiku tak ditanggapi serius?”
Ia terlihat masih akan bersuara ketika gerimis datang. Sontak ia mendongak dan, bagai menerima berkah dari Yang Kuasa, senyumnya merekah bersamaan dengan jatuhnya hujan lain dari ekor mata. Aku tahu itu air mata, bukan gerimis yang menimpa wajahnya.



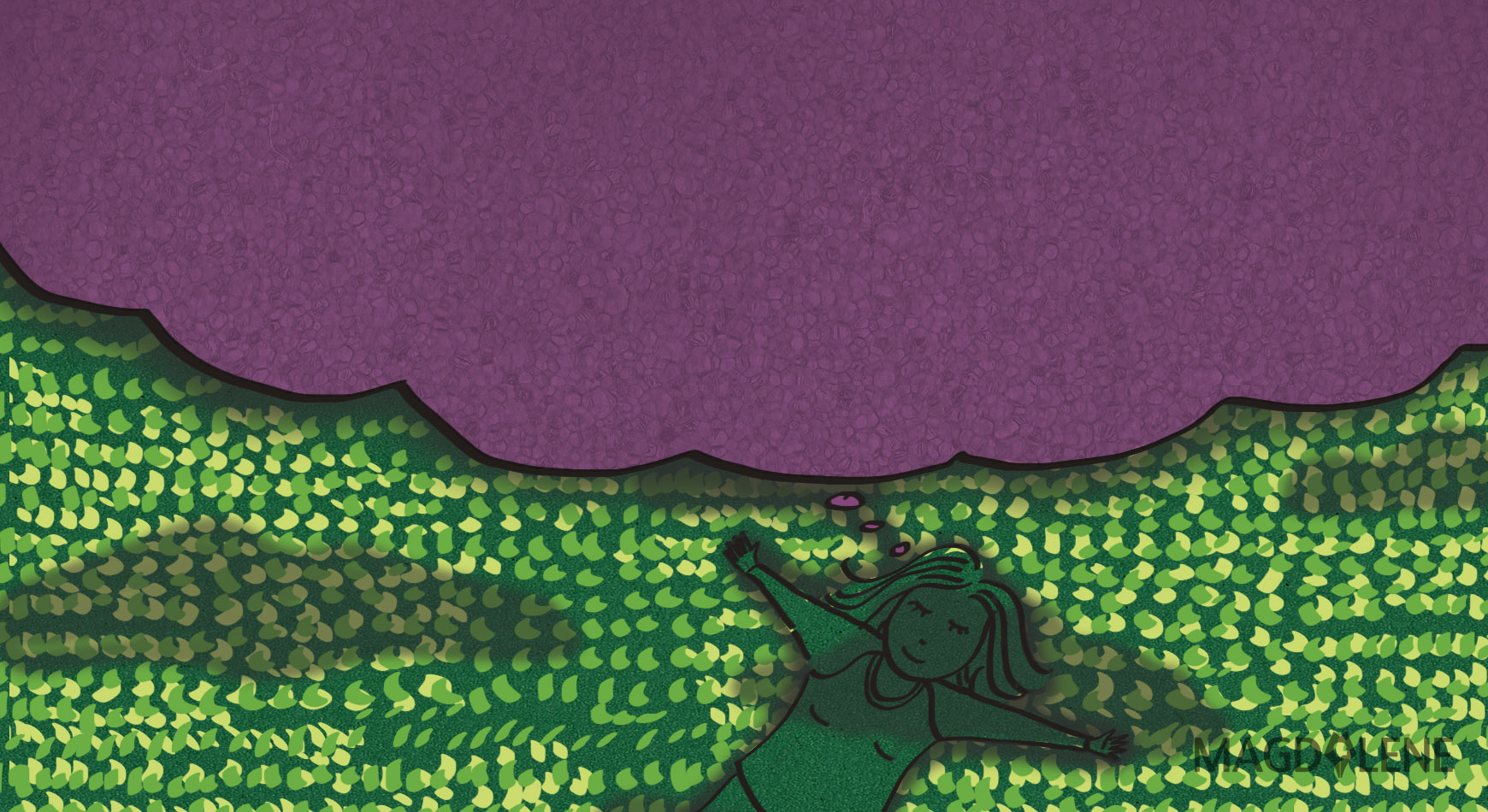



Comments