Aku ingat pertemuan terakhir kita di warung kopi. Kamu duduk bersandar pada bangku sofa, menatap layar kaca, dan membuang muka. Kamu tak menatap, dan sepertinya lebih pilih menggumam ketimbang bicara denganku.
Beberapa tahun lalu, kita memutuskan untuk melingkarkan benang merah di kelingking, menghiasnya dengan lonceng warna-warni. Mengalirinya dengan kata-kata manis. Membiarkannya dekat dengan nadi, berharap itu abadi.
Namun, lembar-lembar kalender yang kadaluarsa tak lagi bisa menyembunyikan luka. Sudah beberapa purnama berlalu sejak kita memutuskan untuk mengulur benang merah. Benang itu melilit meja, kursi, tempat tidur, lemari, pohon, tiang, batu, dan segala tempat di mana kami pernah berlalu. Mungkin karena mengulurnya terlalu jauh, benang itu tergores tajam dan melapuk. Sejak itu pula kita hanya bicara sepatah dua patah kata, seperti saat ini.
“Hei,” kataku singkat.
Sudah tak ada lagi panggilan mesra dalam percakapan kita. Kata-kata seperti nasi basi yang tak mungkin dipanaskan kembali.
Kamu tak menoleh. Matamu masih terpaku pada layar kaca meskipun pemilik warung kopi mematikan saluran televisi. Namun kamu masih mengangguk-angguk, terkadang mengangkat bahu keheranan seolah seluruh berita itu singgah di matamu.
Aku memanggil lagi, tapi kamu tak bergeming. Aku memutuskan untuk beranjak dari tempat duduk dan berdiri tepat di hadapanmu. Kamu tak melihatku.
Baca juga: Air Mata untuk Arcana
Pikiranmu melayang jauh. Aku bisa melihat warna, gambar, dan teks berjalan pada bola matamu yang hitam, serta genangan sepi yang menunggu ruah. Aku bisa mendengarkan kamu tertawa, tersenyum, dan terkejut. Aku bisa tenggelam dalam kesedihanmu.
Aku ingin menyerah, tapi masih menyuratimu dengan kata-kata. Kutiupkan ke matamu yang dulu kutatap dengan cinta. Kamu masih tak berkedip. Matamu terpaku pada kekosongan, kebimbangan, dan ketidakingintahuan. Sejenak, aku meyakini bahwa kamu telah mati.
Aku menutup mata dan membayangkan saat-saat kita bisa duduk berdua dan bercanda. Aku bisa membayangkan bibirmu membentuk sabit indah di antara kepulan asap rokok saat aku menggoda manja. Kamu berusaha mengalihkan tatap malu-malu ke jendela. Kala itu dunia seperti dihiasi bunga-bunga kenikir berwarna oranye, rumput-rumput pelangi, dan embun yang menguap menjadi awan serupa gula-gula kapas.
Aku menghembuskan napas panjang.
Kamu sudah tidak ada di sini.
Aku membuka mata dan melingkarkan tangan, berusaha memelukmu erat dengan tenaga yang bahkan sudah tidak ada lagi. Kamu tak memelukku kembali.
Kamu sudah tidak ada lagi di sini.
Tahun demi tahun berlalu. Semakin lama tahun berjalan, semakin panjang benang merah itu kita biarkan merentang. Kata-kata sudah habis. Dalam setiap perdebatan, umpatan, tamparan, makian, kemarahan, kekecewaan, dan tangisan yang kita kubur dalam diam, benang merah yang dulunya tersambung dalam genggam tangan kian berkelindan.
Baca juga: Cerita Cermin Mutiara
Aku masih mencari cinta, dalam hitungan tahun, bulan, hari, menit, waktu dan detik.
Sudah selama ini,
bukannya kamu dan aku, adalah takdir?
Aku masih berharap pada waktu yang membiarkan kita bersama. Setiap perayaan adalah bunga yang mekar dalam tiga hari lalu berakhir di tempat sampah. Kehadiranmu tidak lagi kucari, namun tidak dapat kuhindari. Aku berusaha lari berkali-kali, kamu tahu. Namun seluruh dunia mendorong paksa untuk kembali terperosok pada sosokmu. Dunia menggelapkan langitnya, mendung memuntahkan hujannya, dan pohon-pohon merontokkan daunnya. Semata untuk satu kata yang tidak pernah lepas dari kita berdua:
Takdir.
Kini benang merah itu mengikat kaki, tangan, mata, telinga, bahkan leher kita. Ikatannya begitu kencang sehingga tidak jarang kita tersedak hampir kehilangan nafas. Semakin lama dan semakin tahun berlalu, benang merah itu semakin kusut masai. Kita tidak dapat mengulur benang tersebut. Setiap kali mencoba memutus benang merah, keengganan muncul seperti belati mencoba menghakimi.
Sudah begitu lama dia bersamamu, kan?
Kalian sudah ditakdirkan bersama.
Selamanya.
Pikiranku kalut.
Bagaimana jika dia adalah satu-satunya takdirku?
Bagaimana kalau tidak ada lagi yang menginginkanku?
Sejuta bagaimana lainnya...
Semakin lama tahun berlalu, kejemuan justru mendatangiku dengan hebat. Hari-hari yang kami lewatkan tanpa perayaan justru membuatku semakin tercekik. Apakah benar cinta adalah takdir? Bukan lebam dan luka-luka sewarna api yang menghanguskan diri?
Kamu dapat melihat bagaimana benang yang mengikat kami sudah pula mengikat tubuhnya, mencekik leher dan nadi, menekan paru, dan melilit jantungnya. Benang-benang merah itu merasuk dalam darah, daging, dan tulangnya. Kami mengulur benang itu terlalu jauh dan ia mengikat benang itu terlalu kencang. Maka tugasku kali ini adalah membantumu menyusuri benang merah itu dan melepaskannya dari tubuhmu.
Mataku menyusuri setiap inci tubuhmu dan menemukan jawab. Kamu masih mengikatkan benang merah itu ke jari kelingkingmu. Benang itu diikat pita, dan disimpul sedemikian indahnya, meskipun kamu tahu hal itu mulai sibuk mengunyah jiwamu. Hari ini, aku akan melepaskan simpulnya.
Aku benar-benar mencoba melepaskan simpul dari kelingkingmu, dengan hati-hati, atau dengan paksa. Sudah kucoba segala cara, sungguh. Dengan gigi, gunting, pisau, api, bahkan gergaji. Aku tak bisa mengingat sudah berapa lama simpul itu bertahan, dan benang-benang itu telah berubah menjadi benang-benang kaca yang menggores tubuhmu sedemikian dalam, membusuk seperti koreng.
Aku menyusuri benang yang tersambung dalam tulang, terbelit dalam daging, dan tersangkut di darahmu. Kadang aku tak sengaja melukaimu karena kurang hati-hati. Tapi kamu tak menoleh. Kamu tak bicara, bahkan kamu tidak jua merasa.
Baca juga: Sabuk di Kamar 1032
Aku mengurai benang yang melilit tubuhmu selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nyatanya, untaian benang ini tak pernah habis, ini tak pernah usai. Maka pada suatu ketika, aku memanggil namamu lirih, sembari bersimpuh di kakimu. Menangis. Meraung. Memaki. Meronta. Kamu masih tidak menoleh. Kamu tidak bicara. Kamu tidak berkedip.
Aku berharap semua ini akan segera berakhir.
Dalam tahun-tahun selanjutnya yang terasa asing, aku berhenti berusaha dengan sisa harap dan tenaga. Benangku juga telah berubah menjadi benang kaca yang menggurat tubuhku sendiri. Pembicaraanku denganmu hanyalah lewat mimpi-mimpi malam hariku. Mimpi yang kutunggu-tunggu adalah mimpi saat aku menemuimu, atau kupikir demikian.
Dalam mimpiku yang terakhir, kamu tiba dengan pakaian terbaik, dan wangi yang sungguh lama sudah terlalu kurindu. Hanya dalam mimpiku, kamu menoleh, mengusap kepalaku, menyempatkan mengecup pipi dan keningku. Dalam pertemuan terakhir kita dalam mimpi, sebelum pergi, kamu sempatkan berpamitan sambil mengecup punggung tanganku dan berbisik “Kamu yang tak pernah melepaskan ujung benangku dari jari kelingkingmu, Sayang.”



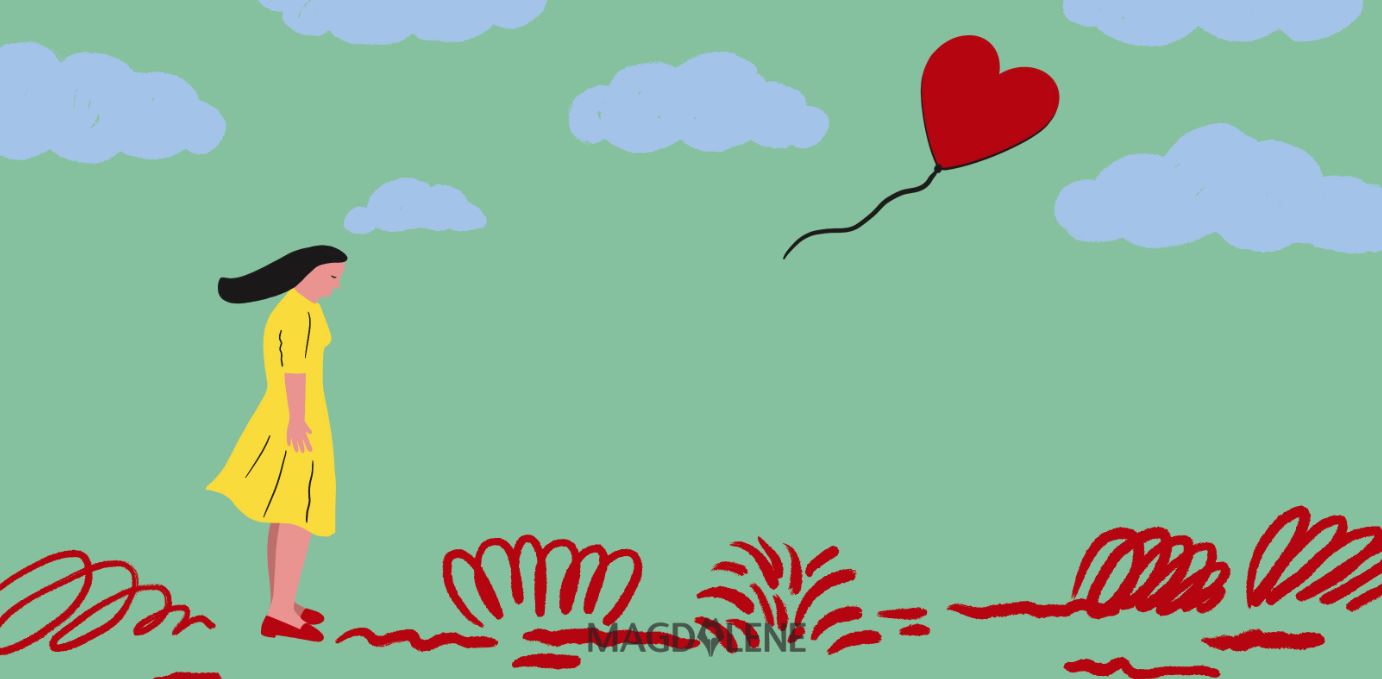



Comments