Wabah virus corona (COVID-19) adalah alarm kencang bagi seluruh manusia di bumi untuk menyadai bahwa kita sedang berada di ambang krisis—krisis lingkungan, ekonomi, politik, dan kepedulian (care). Kehadiran wabah dalam dunia yang global dan persebarannya yang cepat menambah beban permasalahan umat manusia yang belum selesai, seperti kerusakan lingkungan, seksisme dan kesenjangan sosial.
Wabah ini membuat permasalahan yang sudah ada sebelumnya menjadi semakin disadari oleh masyarakat luas. Dari peristiwa kepanikan massal kita melihat bagaimana masyarakat menengah ke atas bisa berlomba-lomba membeli dan menimbun barang primer, sementara kelas bawah cuma mampu menyambung hidup belanja harian. Pejabat daerah bisa mengamuk menolak melakukan tes karena tidak mau terkena stigma penyakit. Di sisi lain, bantuan dana untuk penanganan wabah berencana digunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengetes seluruh anggotanya, sementara dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak memiliki alat pelindung diri yang memadai.
Baru-baru ini artis-artis pop internasional seperti Britney Spears dan Cardi B menyerukan agar pemerintah-pemerintah berlaku tegas dan melakukan tes massal. Mereka juga menyerukan pemerataan kekayaan karena di tengah wabah, orang-orang kelas bawah akan semakin susah tanpa pemasukan harian dan tidak bisa mengakses tes COVID-19 yang berbayar. Alih-alih bernyanyi di rumah mewah untuk menghilangkan kebosanan, panggilan kesadaran politik adalah perlawanan untuk meraih hari esok. Karena jika memang wabah Covid-19 ini akan berhasil ditaklukkan, dunia tidak akan pernah sama lagi.
Baca juga: Feminisme Interseksional Setelah Perjuangan Kemerdekaan
Wabah Covid-19: tantangan melawan neoliberalisme
Awal 2020 menjadi penanda kuat dari krisis lingkungan yang sudah menunjukkan tanda-tandanya dari sepuluh tahun terakhir: Kenaikan suhu bumi, lapisan ozon yang menipis, peningkatan keasaman air laut, menurunnya cadangan air tawar, dan berkurangnya persediaan minyak mentah. Krisis lingkungan ini mengganggu keseimbangan ekologi dan menyebabkan wabah seperti cepat menyebar.
Sejarah Indonesia mencatat pertalian antara wabah, kerusakan lingkungan, dan krisis politik. Pada 1910-1911, di Batavia terjadi wabah kolera/disentri yang membunuh sekitar 6.000 orang. Satu tahun sebelum wabah terjadi, banjir besar menenggelamkan Batavia sampai-sampai surat kabar De Locomotief membuat judul “Batavia Onder Water” atau Batavia di Atas Air. Banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi tapi khususnya akibat kegagalan pemerintah kolonial Belanda mengonservasi air. Alih-alih menggunakan kearifan lokal yang dilakukan kerajaan Tarumanegara (419 M) dalam mengelola air, pemerintah kolonial malah menerapkan pembangunan kanal-kanal seperti yang dilakukan di negeri Belanda, dan hal tersebut terbukti gagal.
Sayangnya, sejarah dunia memenangkan negara-negara yang melakukan dan memperkenalkan praktik imperialisme dan kapitalisme ke seluruh negara modern. Indonesia, sebagai negara bekas dijajah lebih mengadaptasi sistem penajajah dengan menjadikan negara seperti Kolonial Belanda. Pemerintahan berlaku seperti perusahaan yang bertujuan mengeruk keuntungan terus menerus. Lihat saja bagaimana pemerintah dan antek-anteknya memaksa untuk mengesahkan RUU Omnibus Law.
Feminisme di Indonesia kencang di media sosial tapi belum berhasil mengubah atau menghasilkan undang-undang yang pro-perempuan atau menerapkan perspektif gender.
Isu COVID-19 menampar keras sistem ekonomi neoliberalisme negara-negara di seluruh dunia, khususnya dalam akses sistem kesehatan dan antisipasi penanganan wabah. Indonesia yang sudah babak belur dalam sistem kesehatan, semakin terpuruk dalam kesenjangan sosial yang terpampang nyata dalam akses kesehatan yang mahal dan terbatas.
Ahmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk wabah COVID-19 pada awal Maret masih menyampaikan bahwa rumah sakit swasta menolak menangani pasien COVID-19 sebab khawatir pasien lain tidak mau datang. "It's business," katanya.
Keserakahan adalah landasan utama kapitalisme, dan sistem ekonomi penumpukan laba ini adalah penyakit negara-negara modern. Semua itu terlihat jelas dalam wabah COVID-19. Prinsip neoliberalisme, yang menyatakan bahwa pengerukan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pembukaan pasar bebas dan persaingan global akan memberikan kesejahteraan bagi kelompok terbawah, terbukti omong kosong. Kehadiran wabah menampar kita semua bahwa neoliberalisme tidak mampu menjadi jawaban dari peradaban manusia.
Lihat bagaimana harga-harga barang pokok dan bawang bombai melambung tinggi di tengah pandemi. Dan bagaimana mungkin di tengah krisis wabah masih ada orang yang melakukan penimbunan alat-alat kesehatan seperti masker dan alcohol swab yang diperjualbelikan secara bebas dengan harga tinggi? Rumah tangga tidak hanya diserang karena anggotanya mungkin mengidap atau menjadi pembawa virus Covid-19, tapi juga terancam secara ekonomi karena harus mengambil cuti tidak dibayar bahkan tidak bisa lagi membeli beras.
Kapitalisme sudah cukup menyengsarakan penduduk bumi. Dalam Feminism for 99 Percent: A Manifesto yang ditulis oleh Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser (Verso, 2019), kapitalisme dinyatakan tidak hanya sebagai sistem ekonomi tapi sesuatu yang lebih besar: Institusionalisasi keajekan sosial yang mengatur hubungan-hubungan non-ekonomi guna mendukung kelancaran praktik sistem ekonomi yang berlangsung. Kegagapan pemerintah Indonesia pada hari ini dalam menangani wabah Covid-19 adalah akumulasi dari obsesi pertumbuhan ekonomi yang selama ini diagung-agungkan pemerintahan Joko Widodo. Obsesi pertumbuhan ekonomi telah merusakan lingkungan, mengorbankan masyarakat adat, meminggirkan perempuan, dan menyingkirkan minoritas seksual. Itu semua harus disudahi.
Baca juga: Ekofeminisme: Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
Mempertanyakan keberhasilan feminisme liberal
Di tengah-tengah krisis global politik, lingkungan, dan kesehatan, gerakan perempuan sedang tumbuh. Gelombang besar gerakan feminis internasional hidup kembali pada Oktober 2016 di Polandia. Demonstrasi besar dilakukan oleh 100.000 perempuan yang turun ke jalan dan melawan kriminalisasi aborsi.
Pada akhir bulan, gerakan ini menjalar ke Argentina, dengan tuntutan keadilan kasus femicide Lucía Pérez. "Ni una menos" menyebar ke Itali, Spanyol, Brazil, Turki dan puncaknya Amerika Serikat dalam inagurasi presiden seksis, Donald Trump. Di Indonesia, gelombang Women's March diadakan pertama kali pada 2017 dan berlangsung setiap tahun. Gelombang demonstrasi feminis ini setidaknya dihadiri 2.000-5.000 orang setiap tahunnya.

Women's March 2020. Foto oleh Wulan Kusuma Wardhani

Women's March 2020. Foto oleh Wulan Kusuma Wardhani
Kebangkitan gerakan feminisme di seluruh dunia, termasuk di Indonesia adalah harapan di tengah-tengah krisis. Kita percaya bahwa hanya manusia yang dapat menentukan nasibnya untuk terus hidup di bumi ini. Namun gerakan feminisme seperti apa yang mampu menyelamatkan bumi berikut isinya?
Feminisme yang tumbuh di Indonesia butuh diberikan arahan yang jelas, bahwa feminisme pada hari ini adalah feminisme yang juga bertujuan untuk melawan seksisme, heteronormativitas, kerusakan alam, dan rasialisme yang disebabkan oleh kapitalisme. Feminisme di Indonesia kencang di media sosial tapi belum berhasil mengubah atau menghasilkan undang-undang yang pro-perempuan atau menerapkan perspektif gender.
Di sisi lain, feminisme harus berani mengakui kebobrokan dan evaluasi dalam gerakannya. Dalam konteks Indonesia, terpilihnya perempuan-perempuan seperti Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani (Partai Keadilan Sejahtera) dan Endang Maria Astuti (Golkar) telah ikut mendorong adanya RUU Ketahanan Keluarga (RUU HALU). RUU ini seksis, klasis, patriarkal dan misoginis dan hendak mendorong mundur emansipasi perempuan. Tiga perempuan tersebut menampar gerakan feminis Indonesia dan memberikan peringatan bagi gerakan feminis Indonesia untuk mengevaluasi diri.
Tiga perempuan anggota DPR tersebut mungkin memang tidak akan mengaku dirinya feminis, tapi mereka bisa dipilih dan naik ke tampuk legislatif atas perjuangan gerakan feminis sebelumnya. Gerakan feminis yang membela kekuasaan perempuan dan sekedar mendobrak glass ceiling adalah feminisme liberal. Feminis liberal menghasilkan perempuan-perempuan pengisi kekuasaan—melihat mereka sebagai sekadar individu tanpa menekankan feminisme sebagai ideologi untuk mengubah sistem. Sehingga representasi perempuan menjadi tokenisme, perempuan tersebut menjadi bagian dari sistem yang mengopresi rakyat dan kelompok minoritas.
Baca juga: Siapakah yang Pantas Disebut Feminis?
Karenanya, kita harus mengakui bahwa feminisme liberal sudah gagal dan mengevaluasi ulang gerakan kita. Feminis liberal yang mengutamakan kepentingan individualisme dan solusi individual tanpa menyertakan analisis kelas dan ekonomi hanya akan berkontribusi pada sistem ekonomi dan krisis yang sudah menjalar. Politik perempuan di Indonesia di bawah sistem neoliberalisme menghasilkan dua kubu: Neoliberal progresif atau Islamis populis reaksioner. Kedua-duanya saling melawan tanpa ada agenda perubahan sistem keseluruhan. Gerakan feminisme tidak boleh terjebak pada dua kubu ini. Kita harus menancapkan fondasi yang inklusif, kokoh, dan disiplin pada prinsip feminisme.
Sosok-sosok neoliberal progresif seperti Sri Mulyani atau Susi Pudjiastuti, yang selalu dielu-elukan karena memberikan representasi perempuan dalam pemerintahan, bekerja seperti totem-totem yang dipuja sebagai feminis tapi nyatanya tidak memberikan kebijakan yang signifikan. Kekuasaan perempuan-perempuan tersebut tidak berdampak kepada nasib masyarakat adat yang melawan tambang, pengakuan terhadap minoritas seksual, kekerasan di Papua apalagi akses kesehatan.
Kita terlalu terpaku pada sosok perempuan neoliberal progresif yang dipuja sebagai feminis dan diharapkan membawa perubahan sementara isu-isu feminis liberal sendiri mandek. Hingga pertengahan 2020 ini, feminis liberal di Indonesia bahkan tidak pernah berhasil dalam isunya memberikan akses hak seksual reproduksi dan hak aborsi aman kepada perempuan.
Feminisme harus menolak kerangka persaingan dari bentuk paling dasar seperti membanding-bandingkan—perempuan berjilbab vs berkebaya, menikah vs tidak menikah, punya anak vs tidak mau punya anak—seakan-akan hanya ada dua pilihan.
Kerangka persaingan, ketamakan, dan akumulasi modal harus dibuang jauh-jauh dalam gerakan feminisme yang sedang tumbuh di Indonesia dan di seluruh dunia. Feminisme tidak bekerja dalam kerangka persaingan melainkan kerja sama atau kooperasi. Untuk itu, feminisme menolak sistem ekonomi kapitalisme, bukan membenci wiraswasta seperti yang diasumsikan para think tank Libertarian. Kita melawan sistem dan ketamakan manusia yang merupakan konstruksi sosial dari sistem ekonomi neoliberal.
Feminisme harus menolak kerangka persaingan dari bentuk paling dasar seperti membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan perempuan berjilbab vs berkebaya, menikah vs tidak menikah, punya anak vs tidak mau punya anak. Kita harus menolak semua kategori yang seakan-akan hanya ada dua pilihan.
Hal yang ditawarkan feminisme hari ini adalah merombak total narasi persaingan dan perlombaan individual baik pencapaian, rasa sakit, patah hati, dan penderitaan. Sebaliknya, menyediakan akses dasar bagi seluruh manusia adalah keutamaan dalam gerakan feminis hari ini. Pemenuhan hak dasar seperti hak hidup, rasa aman, tempat tinggal, air, sumber daya, pangan dan sebagainya harus diperjuangkan bersama-sama dalam bentuk dukungan solidaritas internasional.
Jika feminisme Indonesia hanya berkutat pada isu pilihan dan solusi individual terus menerus tanpa menyerang permasalahan sistem dan pemerintahan, feminisme Indonesia akan menjadi gerakan reaksioner yang jalan di tempat. Setelah wabah Covid-19 berlalu, gerakan feminis yang sudah besar dan internasional harus sama-sama mengevaluasi dan memikirkan kegagalan sepuluh tahun terakhir dan mengambil kesempatan untuk bangkit kembali. Masa depan Indonesia, ada di tangan para feminis yang berusaha mengubah hari ini.




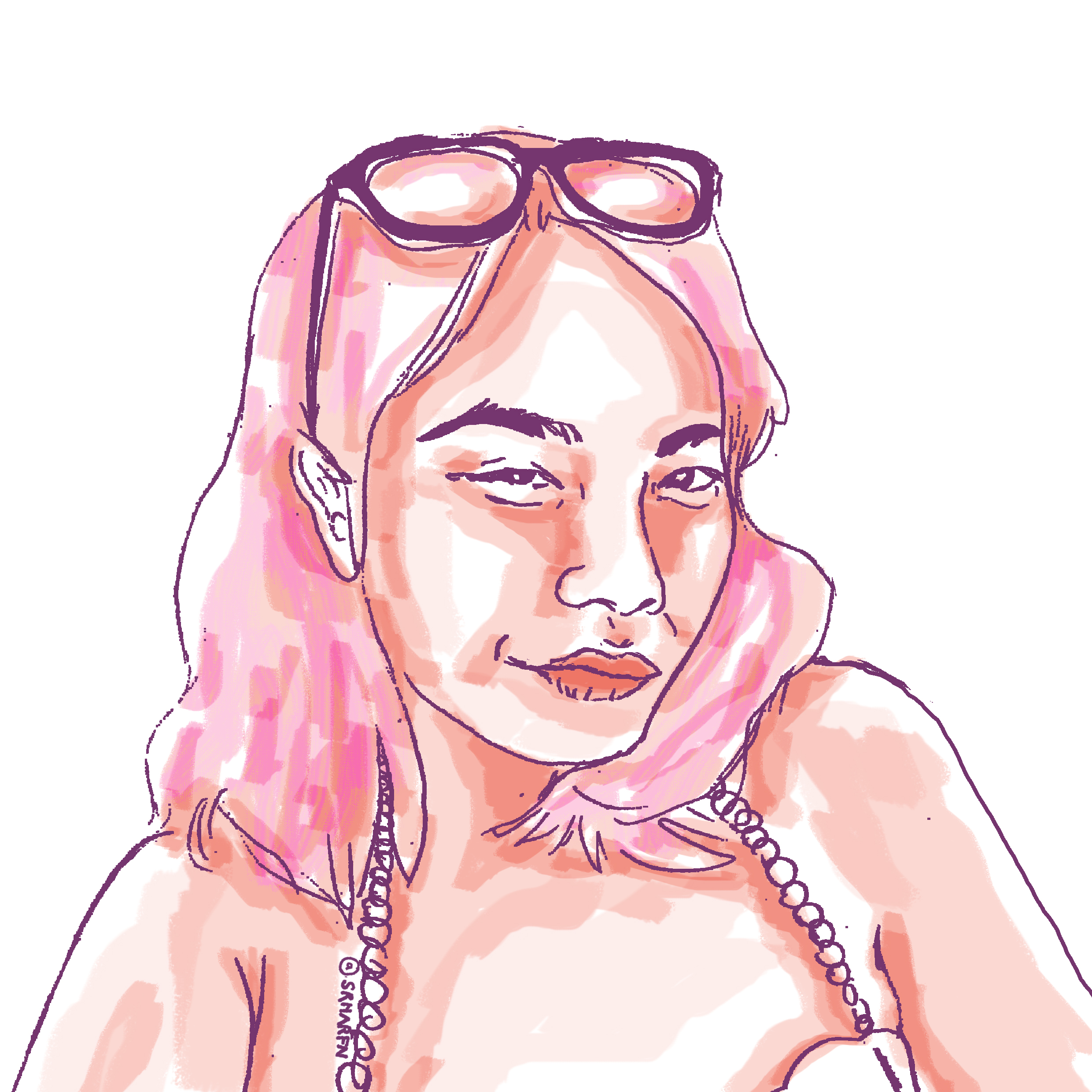



Comments