awanDi komunitas akademik global, ada pandangan bahwa ilmuwan Indonesia cenderung mengikuti tren belaka. Menyerap perkembangan sains karena sedang ramai dibahas di luar Indonesia.
Ini terlihat dalam ilmu sosial dan humaniora. Perkembangan teori di lingkup global kerap jadi acuan akademisi Indonesia dalam pengajaran, penelitian, dan bahkan sebagai bahan obrolan antara sesama akademisi.
Pada periode 1990-an, misalnya, semua ilmuwan tergelitik untuk bicara postmodernism (sikap kritis dan skeptis terhadap wawasan ilmu modern). Sementara pada dekade 2000-an, perspektif cultural studies (membedah politik dan sejarah dari beragam budaya yang ada saat ini) menjadi juara setelah menurunnya popularitas teori sosial lainnya.
Ajakan untuk lepas dari tradisi “ikut-ikutan” ini sebenarnya sudah muncul sejak puluhan tahun yang lalu.
Pada 1986, ilmuwan politik Muhammad Rusli Karim via Harian Kompas menjelaskan pentingnya ilmuwan Indonesia mencari teorinya sendiri. Sastrawan dan sosiolog Ignas Kleden pun berupaya memperkenalkan wacana “indigenisasi” (pembumian wawasan adat di Indonesia) terhadap ilmu sosial.
Ide-ide tersebut sayangnya hanya terdengar sayup di tengah dominasi ilmu sosial global yang pro-pembangunan.
Baca juga: Akademisi Perempuan: Dibombardir Sanksi Dunia, Serangan Putin Jalan Terus
Dewasa ini, ada momentum baru bagi komunitas akademik Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan teori asing, yakni melalui gerakan “dekolonisasi sains” (dekolonisasi pengetahuan).
Meski belum banyak diadopsi oleh ilmuwan Indonesia, dekolonisasi sains menawarkan pijakan penting supaya dunia pendidikan tinggi dan dan sains di Indonesia bisa menemukan suaranya sendiri.
Memerdekakan Sains dari Watak Kolonialis
Dekolonisasi sains adalah ajakan keluar dari dominasi produksi pengetahuan yang berkiblat pada negara kolonial – lebih khususnya dunia Barat (eurosentrisme) – agar muncul lebih banyak ruang ilmiah bagi akademisi di penjuru dunia lain.
Dalam pandangan dekolonisasi, ilmu pengetahuan kini terpusat di peradaban Barat, sementara pelaku sains dari wilayah yang mereka jajah selalu hanya jadi objek pengetahuan.
Dengan demikian, “kita”, para ilmuwan negara non-Barat, tidak memiliki otoritas untuk menyelediki diri sendiri, apalagi mengangkat derajat pengetahuan yang barangkali sudah tersedia dari berbagai abad terdahulu di komunitas yang kita kenal.
Bahkan, pandangan sains yang berwatak kolonialis ini seringkali bersifat rasis – seperti menggambarkan orang “kulit berwarna” atau masyarakat negara Selatan sebagai pihak yang tidak cerdas atau abnormal.
Upaya untuk lepas dari dominasi ini, khususnya di pendidikan tinggi, sudah dimulai sejak munculnya gerakan dekolonisasi pada dekade 1960 di Afrika Timur.
Dekolonisasi sains pada era saat ini merupakan bagian dari gerakan emansipatif (pembebasan) yang lebih luas. Misalnya, ini juga didorong oleh gerakan sosial lain di luar universitas yang menyuarakan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial – dari Black Lives Matter hingga #Metoo.
Tapi, hal yang paling penting dari dekolonisasi sains adalah upaya untuk keluar dari kemutlakan sains yang lahir dari proses penjajahan.
Setidaknya, ini adalah tujuan besar para ilmuwan yang mendorong wacana dekolonisasi. Sebagian besar dari penulis tersebut berasal dari Amerika Latin, Asia Selatan, dan juga Afrika.
Baca juga: Masalah Besar dinSTEM: Representasi Perempuan dan Produk yang Bias
Dekolonisasi Sains di Indonesia
Sayangnya, hampir tidak ada ilmuwan sosial dari Indonesia yang turut meramaikan diskursus tersebut.
Hal ini cukup ironis. Ilmuwan sosial Walter Mignolo, misalnya, menekankan bagaimana Indonesia pernah punya peran besar dalam dekolonisasi politik global, yakni melalui Konferensi Asia Afrika.
Indonesia senantiasa mendukung upaya memerdekakan negara terjajah, tapi tidak banyak ilmuwan sosial kita melakukannya dalam ranah teori sosial.
Alasan atas kelangkaan ini terkait erat dengan pemberangusan literatur kiri atau Marxisme yang terjadi sejak 1965. Kekuasaan Orde Baru ini menjadi alasan besar mengapa pemikiran pascakolonial, dekolonial, atau bahkan Marxisme tidak memiliki pijakan yang kuat dalam ilmu sosial-humaniora Indonesia.
Padahal, kita bisa melihat jejak-jejak lensa kolonial dalam sains di Indonesia – tidak hanya pada ilmu sosial tapi juga ilmu alam.
Ilmu eksakta seperti biologi dan kedokteran perlu membuka diri dengan pertama-tama mempertanyakan asal-usul seluruh fondasi ilmiahnya, terutama yang relevan dengan konteks Indonesia.
Peneliti biologi Sabhrina Gita Aninta, misalnya, menjelaskan bias perspektif Barat yang seakan “kaget” saat meneliti biodiversitas di wilayah ekuator yang begitu kaya. Bahkan, beberapa akademisi juga mempertanyakan penamaan fauna seperti orang utan yang prosesnya sarat dengan politik imperialis dan menyingkirkan wawasan Suku Dayak Iban di Kalimantan.
Indonesia masih menjadi rumah bagi untaian wawasan lokal yang belum kita kenali dan beri nama. Beda halnya dengan para rekan sejawat di Amerika Latin, yang berhasil melunturkan ketergantungan pada pengetahuan Barat sembari merayakan pengetahuan lokal yang mereka miliki.
Gagasan soal “pluriverse”, yakni kumpulan wawasan yang berupaya menantang narasi pembangunan global yang sarat kepentingan bisnis dan greenwashing (klaim ramah lingkungan yang menyesatkan), misalnya, adalah contoh pengetahuan tandingan yang mulai populer dan diterima komunitas ilmiah global.
Upaya seperti ini bisa jadi inspirasi bagi ilmuwan Indonesia untuk mencoba berpikir dengan semangat dekolonisasi.
Baca juga: Pendidikan Perempuan dan Hal-hal yang Belum Selesai
Meraih Derajat yang Sama
Selama ini, ada kejemuan di antara ilmuwan Indonesia terhadap dominasi teori yang ada. Ini kemudian mendorong mereka untuk mengikuti tren revolusi keilmuan – seringkali yang berkiblat pada dunia Barat.
Tapi, bisa jadi kecenderungan tersebut bersumber dari rasa inferioritas ilmuwan Indonesia yang sulit memaparkan gagasannya tanpa ditopang teori yang mereka rasa cukup “keren”.
Faktor ini justru semakin memperkuat dominasi pengetahuan Barat.
Dalam artikelnya, sosiolog Leon Moosavi mengingatkan para akademisi agar tidak sekedar “anut grubyuk” (ikut-ikutan), dan harus segera menunggangi gerbong dekolonisasi karena sedang ramai dinaiki oleh semua orang.
Persoalannya di Indonesia justru terbalik karena gerbong tersebut sepi senyap, meski kereta sudah menunggu lama untuk meluncur.
Catatan penting lainnya adalah bahwa dekolonisasi sains bukan hanya soal kebijakan. Sudah terlalu banyak persoalan dalam ranah sains di Indonesia yang semuanya ingin dijawab dengan “kebijakan”. Tidak demikian halnya dengan dekolonisasi sains – ini adalah persoalan tradisi akademik.
Dekolonisasi sains berangkat dari kemauan untuk melihat ke dalam disiplin ilmu masing-masing dan bertanya soal ada tidaknya kemungkinan untuk melakukan pencarian kebenaran tanpa harus bergantung pada pemikiran ilmuwan Barat.
Salah satu pemikir dekolonisasi, Gurminder Bhambra, mengingatkan bahwa dekolonisasi bukan berarti menolak teori Barat – tujuannya tidak pernah demikian.
Yang lebih tepat adalah perlunya menempatkan teori atau wawasan ilmiah dari dunia Selatan dalam derajat yang sama dan setara dalam produksi pengetahuan global. Hal ini yang pada akhirnya secara perlahan harus menjadi tujuan ilmuwan Indonesia.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.




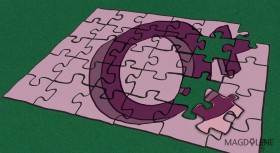


Comments