Perasaan cemas, kesal, dan jengkel terdengar dari nada bicara Firdha, 25, ketika menceritakan kembali pengalamannya berulang kali mendapat teror dan pelecehan seksual dari orang-orang asing beberapa bulan lalu.
“Ini terjadi berbulan-bulan, aku bisa dapat chat enggak jelas dari nomor beda-beda. Mereka yang chat ke aku bisa lebih dari empat orang. Semuanya itu nomornya sama sekali enggak aku kenal. Selain chat dan telepon, mereka juga ngajakin video call,” ujar ibu satu anak ini kepada Magdalene.
Konten-konten bermuatan pornografi pun sering kali Firdha terima dari mereka. Parahnya lagi, foto-fotonya di Facebook diambil tanpa izin dan dikirimkan kepadanya, seolah sengaja ingin membuatnya takut. Melihat pola teror yang terjadi padanya, Firdha yakin jika pelaku yang menerornya itu merupakan para laki-laki cabul dari satu grup Facebook yang mengambil foto dari akunnya, kemudian dibagikan dengan kata-kata yang menggambarkan ia sedang menjajakan jasa video call sex (VCS).
“Puncaknya yang paling parah itu, mereka menyebar foto-foto aku di grup, user name-nya diganti jadi nama samaran, terus nawar-nawarin jasa perempuan binal dengan nyebarin nomorku. Aku enggak ngerti mereka dapat dari mana nomorku itu. Pokoknya aku was-was banget, sempet mikir apa nomor aku disadap sama orang atau gimana,” ujar Firdha penuh emosi.
Ia mengatakan dirinya merasa trauma untuk kembali berselancar di akun Facebook miliknya. Ia pun mengubah pengaturan akunnya menjadi privat dan mengganti foto profilnya dengan foto suaminya, dengan harapan pelaku lebih takut untuk menerornya lagi.
“Aku blokir semua yang chat-chat aneh itu, tapi selang sebulan atau dua bulan, pasti ada lagi [yang meneror]. Parah sih emang. Maunya dilaporin, tapi enggak tahu harus lapor kemana, akhinya diblokir dan report aja lewat Whatsapp,” tambah Firdha.
Baca juga: Jika Konten Intim Tersebar, Ini yang Bisa Dilakukan
Pengalaman serupa dirasakan pula oleh Santika Patma, 26, yang juga mendapat teror nomor-nomor tidak dikenal beberapa bulan lalu. Lebih parah lagi, nomor-nomor tidak dikenal itu meneleponnya tengah malam, atau jam tiga dini hari saat ia tengah terlelap tidur, sehingga makin membuatnya ketakutan.
“Awalnya WhatsApp, ya gitu basa-basi, enggak aku bales. Besoknya ngirim foto-foto aku yang diambil dari Facebook, aku panik banget. Habis itu, ada banyak nomor yang nelepon tiap malem, barengan gitu. Mereka maksa minta diangkat dengan kata-kata ‘sange (sedang birahi) nih’, ‘lagi pengen, nih’,” ujar Santika kepada Magdalene.
Santika pun kini memutuskan untuk menghapus foto-fotonya di media sosial serta mengganti nama akun Facebook-nya agar pelaku tidak mengambil fotonya tanpa izin. Ia mengatakan sempat melihat foto profil pelaku yang mengibarkan bendera putih, biru tua, dan biru muda, bendera yang berafiliasi dengan geng motor XTC.
“Aku ketakutan banget, bahkan untuk nomor HP inginnya ganti karena takut disadap, cuma belum aja. Semoga dia menghilang. Aku berharap kejadian itu yang terakhir,” tambah Santika.
Perempuan dan anak paling rentan
Menjamurnya grup-grup pelaku kekerasan gender berbasis online (KBGO) di media sosial seperti yang dialami Firdha dan Santika sebetulnya bukan fenomena baru terjadi. Era digital yang makin membebaskan orang untuk berinteraksi dan memungkinkan untuk mengambil data pribadi dengan mudah, menjadikan kejahatan seksual seolah diberi lahan empuk untuk beraksi.
Dalam artikel The Conversations yang bertajuk Domestic violence and Facebook: harassment takes new forms in the social media age, disebutkan bahwa Facebook telah menjadi media kuat bagi pelaku kekerasan seksual untuk mengorganisasi dan menargetkan para korban lewat akun-akun Facebook miliknya. Para pelaku ini bergerak semakin bebas di bawah anonimitas dengan membentuk grup-grup bermotif kejahatan seksual yang sama.
 Artikel The Unsafety Net: How Social Media Turned Against Women di The Atlantic juga menggaribawahi hal serupa. Tidak hanya Facebook, akun media sosial lain seperti Twitter dan YouTube pun menjadi sarang pelaku kekerasan seksual. Dalam artikel tersebut, terdapat kritik bagi para pembuat kebijakan perusahaan terknologi yang dianggap tidak melihat itu sebagai permasalahan besar dan harus segera ditangani. Perusahaan-perusahaan tersebut malah kerap memakai dalih freedom of speech pengguna.
Artikel The Unsafety Net: How Social Media Turned Against Women di The Atlantic juga menggaribawahi hal serupa. Tidak hanya Facebook, akun media sosial lain seperti Twitter dan YouTube pun menjadi sarang pelaku kekerasan seksual. Dalam artikel tersebut, terdapat kritik bagi para pembuat kebijakan perusahaan terknologi yang dianggap tidak melihat itu sebagai permasalahan besar dan harus segera ditangani. Perusahaan-perusahaan tersebut malah kerap memakai dalih freedom of speech pengguna.
Kriminolog Universitas Budi Luhur, Chazizah Gusnita mengatakan, adanya grup-grup pelaku kekerasan seksual di media sosial merupakan implikasi negatif dari internet. Hal ini menjadi lahan seksi untuk transaksi bisnis kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Para pelaku cenderung berkelompok untuk menjustifikasi tindakan mereka sebagai suatu tindakan kejahatan yang sama-sama memberi keuntungan, dalam hal ini keuntungan yang didapat adalah rasa takut korban yang mereka nikmati.
“Kejadian teror itu bisa dikategorikan bisnis kejahatan karena ada keuntungan di dalamnya. Sebetulnya, entah itu prostitusi online, revenge porn, atau ancaman lain adalah konsekuensi dari kebebasan informasi di internet. Tentu modus dan jenisnya banyak,” kata Chazizah kepada Magdalene.
“Coba, siapa sih, yang enggak main internet sekarang? Kita enggak bisa bilang semua pengguna internet itu adalah smart people, secara psikologis orang beda-beda. Si peneror punya cara-cara atau modus dengan korbannya melalui media sosial atau grup media sosial,” imbuhnya.
Selain memanfaatkan kebebasan di media sosial, menurut Chazizah, para pelaku kejahatan seksual juga beraksi dengan mencari celah korban dari kelompok yang secara sistematis dianggap lebih rentan dan tidak berdaya di masyarakat, yaitu perempuan dan anak. Karena itu, grup predator seksual yang menyasar anak-anak banyak berseliweran di media sosial.
“Perempuan rentan karena ada stereotip sebagai sosok yang santun, feminin, dan tidak berani melawan. Sementara anak-anak, mereka enggak sadar kalau orang tuh ada niat jahat. Selain itu, para pelaku juga melihat celah kelengahan pengawasan [orang tua],” papar Chazizah.
Baca juga: Survei: Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Pindah ke Dunia Maya di Tengah Pandemi
Pada 2017, Indonesia sempat dibuat geger dengan grup Facebook bernama Official Loly Candy's Groups 18+. Grup tersebut diketahui mempromosikan berbagai konten bermuatan pelecehan dan pencabulan anak dengan anggota sekitar 7.497 orang. Setelah ditelusuri dan para pelakunya ditangkap oleh pihak berwajib, ternyata grup tersebut terhubung dengan 11 grup lain yang terlibat kejahatan terhadap anak di beberapa negara.
Meski sekarang ini kebijakan di media sosial terus dikencangkan, tak berarti para pelaku kejahatan seksual semakin berkurang, kata Chazizah. Bahkan sekarang ini, game online yang digandrungi anak-anak juga sudah menjadi sasaran.
“Ada penelitian mahasiswa saya yang menunjukkan kalau game online sekarang ini justru jadi tempat buat pelaku pencabulan anak, ya. Kan ada istilah mabar (main bareng), mereka bikin akun palsu, pura-pura usia 10 atau 12 tahun, padahal usianya sudah dewasa. Melalui itu, mereka mulai pendekatan, sampai akhirnya punya grup sendiri, mereka punya WhatsApp sendiri, terus disusupi konten-konten porno,” ujar Chazizah.
Telegram sarang distributor konten porno
Selain grup Facebook, Telegram sebagai aplikasi pengirim pesan sekarang ini juga mulai disalahgunakan sebagai pusat distribusi konten-konten porno oleh para pelaku. Aplikasi ini memiliki kelebihan yakni layanan penyimpanan cloud, dan daya tampung anggota yang besar hingga mencapai ribuan orang sehingga dimanfaatkan para predator seksual untuk berkomunikasi dan bertransaksi.
Jika mempunyai akun Telegram, seseorang bisa dengan mudahnya menemukan grup-grup penyebar konten-konten non-konsensual itu hanya dengan mengetik suatu kata di mesin pencari. Layaknya sistem di YouTube, ia bisa melihat berapa banyak subscriber di grup tersebut. Permintaan akses untuk bergabung menjadi anggota grup predator seksual pun relatif mudah: Cukup mengeklik dan membaca ketentuan pembuka dari administrator, seseorang sudah bisa terhubung dan mengakses banyak konten.
Perempuan rentan akibat stereotip sebagai sosok yang santun, feminin, dan tidak berani melawan. Sementara anak-anak belum sadar akan niat jahat orang dan pelaku juga melihat celah kelengahan pengawasan orang tua.
Di dalam grup semacam itu pula, banyak ditemukan penjual paket konten-konten pornografi dalam skala besar. Konten-konten tersebut bukan lagi dihitung berdasarkan jumlahnya, melainkan kapasitas penyimpanan, misalnya 100 GB atau sampai 1 TB. Bahkan, ada transaksi di grup-grup predator seksual yang dilakukan dengan dolar dan bitcoin. Ini mengindikasikan bahwa mereka terhubung dengan orang-orang dari berbagai negara.
Dalam kasus video intim mirip Gisella Anastasia dan Anya Geraldine yang baru-baru ini ramai dibicarakan, sebelum menyebar di media sosial lain, video tersebut berasal dari Telegram.
Pada Maret lalu, Korea Selatan menjadi pemberitaan dunia karena munculnya skandal NTH Room. NTH Room merupakan grup chat konten seksual di Telegram yang beranggotakan 260.000 orang.
Laki-laki berusia 25 tahun bernama Cho Joo Bin adalah otak di balik sindikat kejahatan tersebut. Ia membagi grup ke dalam beberapa kelas dengan tarif berbeda-beda, ada yang setara Rp2,6 juta sampai dengan Rp19,5 juta. Cho Joo Bin mendapatkan konten-konten seksual non-konsensual dari 74 korban yang merupakan perempuan dan anak-anak di bawah umur. Mereka diancam dan diteror agar mau melakukan segala keinginannya.
Perlu regulasi holistik
Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi Digital At-Risks Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengatakan bahwa pada dasarnya, semua platform digital yang dapat menyimpan atau mengirimkan data dapat disalahgunakan menjadi alat untuk penyebaran konten intim non-konsensual, namun yang membedakannya adalah seberapa privat atau publiknya platform tersebut.
“Tentu saja platform digital memiliki tanggung jawab agar ruang yang ia sediakan adalah ruang aman bagi penggunanya. Pertanyaannya, pengguna yang mana yang dipilih platform digital tersebut untuk dilindungi? Apakah warga pada umumnya, atau justru pelaku-pelaku kekerasan seksual seperti yang sedang dibahas ini?” ujar Ellen kepada Magdalene.
Baca juga: Penyebaran Konten Intim dan Jalan Panjang Korban Dapatkan Keadilan
Menurut Ellen, penting untuk melihat kembali secara lebih dalam bagaimana regulasi platform digital, baik yang dibuat oleh mereka sendiri sebagai penyedia layanan atau melalui regulasi dari pemerintah di mana para pengguna platform tersebut berada. Sudah saatnya berbagai pihak membuat regulasi holistik, yang menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan dampaknya terhadap korban-korban kekerasan seksual.
“Terutama terkait penyebaran konten intim juga. Ini sering kali dipinggirkan atau tidak diindahkan sebagai situasi yang membahayakan atau mengancam jiwa korban, padahal tidak demikian. Dampak pada kondisi mental korban bisa berujung pada tendensi bunuh diri,” kata Ellen.
“Di Indonesia sendiri, dengan mindset patriarki, korban bisa jadi menghadapi stigma yang luar biasa dari keluarga atau masyarakat yang membahayakan dirinya. Atau bahkan dengan adanya pasal karet Undang-Undang (UU) ITE atau UU Pornografi, korban bisa menghadapi kekerasan dalam bentuk kriminalisasi,” tambahnya.
Sementara menurut Chazizah, selain menguatkan regulasi dan UU yang bisa menjerat pelaku, perlu ada perubahan menyeluruh dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang cenderung mengutamakan proses hukum pada tindak kejahatan yang berdampak secara fisik. Jika dampaknya “hanya” terlihat secara psikologis, kejahatan tersebut masih sering dianggap sepele dan diabaikan.
“Di berbagai pasal UU kita mungkin mengatur kekerasan psikis seperti yang dialami korban kejahatan seksual di dunia maya. Cuma kalau lapor, mungkin kita akan berhadapan dengan logika aparat yang akan bilang, ya penjara aja udah penuh sama kasus-kasus yang sifatnya merugikan materi dan fisik, ini harus ngurus [kasus yang berdampak] psikologis yang enggak kelihatan. Kalau ngurus kasus KDRT saja kadang harus ada babak belur atau pembunuhan dulu baru dilihat sebagai kasus serius,” ujar Chazizah.




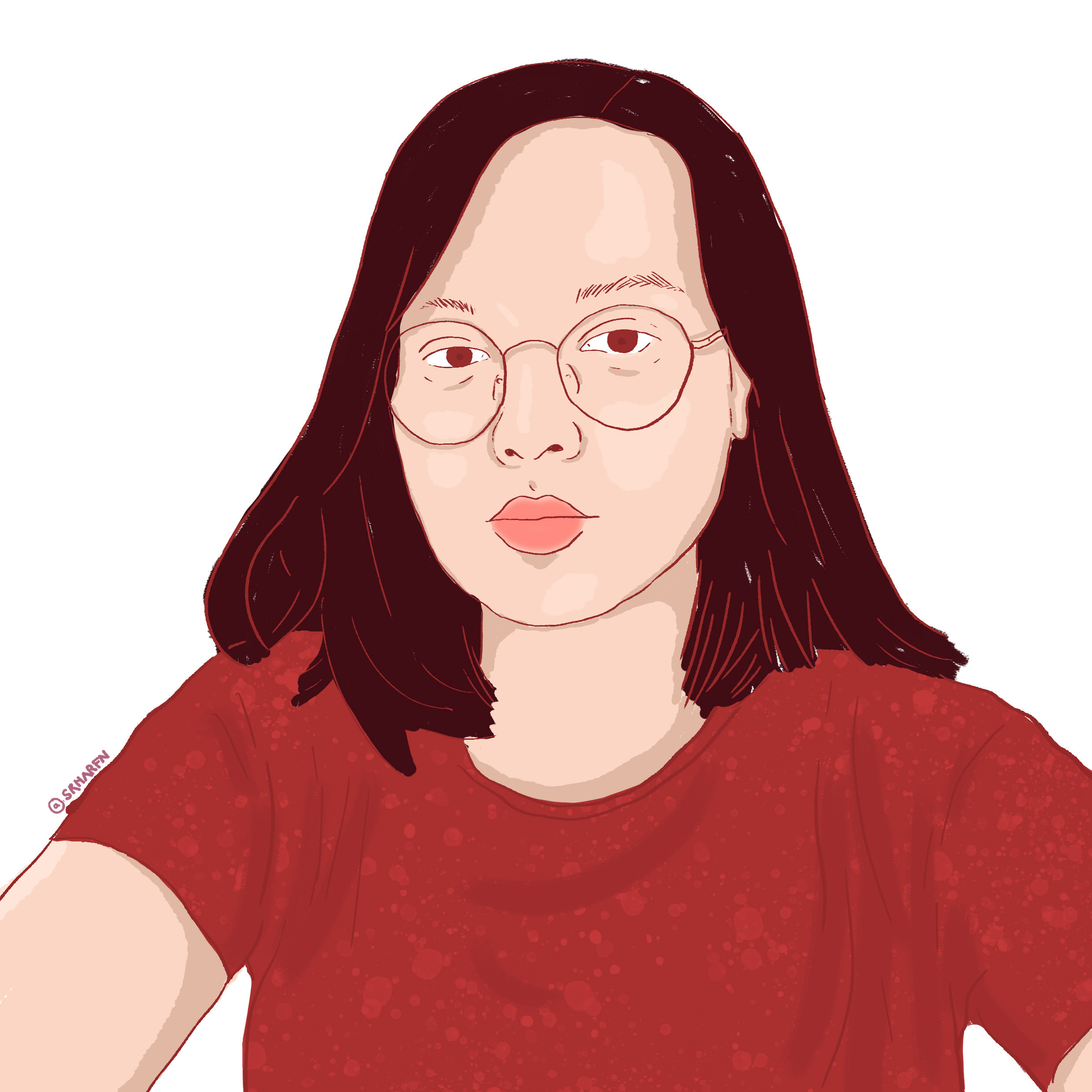



Comments