Buat saya, mencari indekos yang nyaman dan pas itu sama sulitnya dengan mencari pacar yang cocok. Saat pertama kali pindah ke Bandung untuk berkuliah pada 2017, ada saja masalahnya saat hunting indekos, dari mulai harga, fasilitas, jarak, sampai kebersihan.
Tapi yang paling bikin jleb adalah saat ingin mencari tempat baru yang lebih dekat kampus. Di sebuah rumah, belum sampai lima langkah memasuki gerbang, langkah saya dan teman saya dihentikan oleh penjaga. Setelah menanyakan maksud kami sambil melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, bapak penjaga itu mengatakan dengan ketus, “Ini kos khusus muslimah.”
Kami langsung bertukar pandang dengan bingung, karena per definisi, kami berdua adalah muslimah. Hanya saja memang tidak mengenakan jilbab.
Pengalaman serupa, tapi agak lebih ekstrem, pernah dialami Basa Nova Siregar, saat menjadi mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi negeri di Bogor. Karena biaya penelitian yang tinggi, Basa harus mencari kamar kos baru yang lebih murah. Saat menemukan tempat yang sesuai, perjanjian sewa Basa dibatalkan sepihak oleh sang pemilik indekos.
“Aku sudah bikin janji untuk bertemu dan membayar uang muka kos. Tapi sehari sebelum bertemu, ibu kos menelepon kalau (perjanjian kos) batal. Katanya baru tahu kalau agamaku Katolik. Dia bilang, ‘Demi kenyamanan bersama, lebih baik penghuni kosnya Muslim semua.’ Padahal kos itu enggak dilabeli khusus muslimah,” kata Basa.
Ia kemudian masih mencoba bernegosiasi, sampai datang langsung ke tempat kos tersebut tapi ibu kos tidak bergeming. Peristiwa itu menimbulkan luka yang membekas di hati Basa bahkan sampai bertahun lamanya.
“Aku sedih banget. Merasa luka batin. Aku enggak mau menutup-nutupi agamaku demi dapat kos yang ideal,” kata Basa, yang saat ini sedang menjadi pengajar di sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, di bawah Yayasan Indonesia Mengajar.
Nyaman dengan yang sama
Pengalaman saya, teman saya, dan Basa bukan kasus yang terisolasi. Saya mendapatkan banyak sekali cerita dari mereka yang pernah mengalami hal serupa. Alasan penolakannya seragam, yaitu karena pemilik indekos tidak mau menerima penghuni yang tidak beragama sama.
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, hal ini disebabkan oleh menguatnya konservatisme agama di Indonesia, yang dimulai pada tahun-tahun terakhir rezim Orde Baru, saat kelompok-kelompok Islam di Indonesia mulai diberi ruang untuk berekspresi lewat syiar agama.
“Konservatisme itu umumnya muncul di kalangan urban, khususnya di tempat-tempat yang terdapat banyak perguruan tinggi. Makanya ada kos-kosan yang diberi label khusus untuk orang-orang dari kelompok agama tertentu, khususnya agama Islam,” ujarnya kepada Magdalene.
“Sekarang labelnya sudah dicopot. Tapi dalam praktiknya masih saja berlangsung. Dasarnya adalah kecenderungan memandang orang yang berbeda keyakinan itu lebih buruk dari dirinya,” kata Bonar.
Ia menambahkan bahwa keberadaan indekos khusus agama tertentu akan menimbulkan segregasi dalam kehidupan sosial yang menyebabkan seseorang hanya bisa berinteraksi dengan orang yang berasal dari golongan yang sama. Hal ini juga akan menimbulkan prasangka sebagai cikal bakal perilaku intoleran.
Menurut Bonar, permasalahan menjadi kian kompleks ketika stigma dan prasangka ini memasuki aspek bisnis.
Sebagian besar masyarakat Indonesia merasa lebih nyaman bila hidup bersama orang-orang yang berasal dari ras dan etnis yang sama dengan dirinya dan keluarga.
“Kos sudah jadi bagian dari aktivitas ekonomi publik yang dikenakan pajak oleh pemerintah. Sehingga seharusnya terbuka untuk semua golongan masyarakat,” katanya.
Tapi diskriminasi berbasis agama bukan satu-satunya persoalan di Indonesia. Faktanya, masyarakat Indonesia juga belum menerima keberagaman etnis dan ras sebagai bagian dari kehidupan sosial dalam konteks yang positif.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan tim Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas meluncurkan “Survei Penilaian Masyarakat terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi” pada 2018. Hasilnya, sebagian besar masyarakat Indonesia merasa lebih nyaman bila hidup bersama orang-orang yang berasal dari ras dan etnis yang sama dengan dirinya dan keluarga.
Baca juga: 22 Tahun Pasca-Kerusuhan Mei 1998, Prasangka dan Trauma Masih Ada
Sebanyak 82,7 persen responden mengaku lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama, sementara 83,1 persen mengaku lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama. Bahkan lebih dari setengah responden mengaku tidak akan merespons langsung bila ada pihak yang mendiskriminasi kelompok etnis dan ras tertentu. Sisanya, 35 persen memilih untuk melaporkan ke pihak berwenang, dan 26 persen memilih untuk sekadar bersimpati. Survei ini dilakukan terhadap 1.207 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Orang Indonesia juga punya masalah rasialisme
Orang tua Sekar Ayu Nugraheni adalah pemilik sebuah indekos di daerah Bandung yang dilabeli khusus untuk perempuan yang beragama Islam. Menurut Sekar, orang tuanya berpendapat perempuan yang baik hanyalah mereka yang muslimah dan berjilbab. Tapi, ia menambahkan, itu bukan satu-satunya permasalahan. Orang tuanya juga menaruh stigma buruk terhadap penghuni kos yang berasal dari kelompok ras lain.
“Pernah ada anak kos keturunan Tionghoa yang kurang menjaga kebersihan. Orang tuaku langsung menyerangnya dengan bawa identitas ras. Katanya, ‘Orang Cina tuh gitu, ya. Jorok kalau pakai kamar mandi’,” kata mahasiswi sebuah universitas negeri di Bandung itu.
“Aku menegur mereka dan mengatakan kalau menilai seseorang dengan membawa identitas suku, ras, atau agamanya itu tidak benar, karena perilaku seseorang sepenuhnya bergantung pada individunya, bukan rasnya,” ujarnya.
Baca juga: Konservatisme Agama di Sekolah dan Kampus Negeri Picu Intoleransi
Prasangka terhadap keturunan Cina di Indonesia memiliki akar yang mendalam. Menurut Adam Tyson dalam tulisan 'Realities of Discrimination in Indonesia: The Case of The Civil Service' yang dimuat di Jurnal Administrasi Publik, Universitas Parahyangan (2003), rasialisme terhadap ras Tionghoa di Indonesia telah terinstitusionalisasi. Sebagian besar hal itu merupakan warisan kolonialisme Belanda dan pemerintahan rezim Orde Baru yang memisahkan etnis Tionghoa dari berbagai fasilitas yang bisa didapatkan orang Indonesia lainnya. Perlakuan diskriminatif juga banyak dilakukan di keseharian, dimulai dari yang menyerang aspek psikologis sampai di ranah kebijakan.
Selain keturunan Tionghoa, banyak orang Indonesia yang memiliki prasangka buruk terhadap orang-orang dari Papua. Banyak kejadian tidak menyenangkan yang menimpa orang-orang Papua yang tinggal di Pulau Jawa, termasuk ketika mereka mencari tempat tinggal.
“Walter”, pemuda Papua yang pernah tinggal di Yogyakarta untuk menempuh pendidikan, mengalaminya saat mencari indekos.
“Saat saya menelepon pemilik kos untuk menanyakan kamar kosong, dia menanyakan asal SMA dan daerah saya. Begitu saya jawab bahwa saya dari Papua, dia langsung bilang bahwa kosnya sudah penuh. Padahal saya lihat sendiri kalau baru ada satu kamar yang terisi,” katanya kepada Magdalene.
Bonar mengatakan, masyarakat Indonesia pada umumnya masih memiliki stereotip rasial tertentu terhadap orang-orang Papua.
“Mereka dianggap terbelakang, kasar, jorok, dan suka minum minuman keras. Karena mahasiswa Papua yang tinggal di Pulau Jawa ini sulit mendapatkan kos, makanya hampir di setiap daerah yang ada perguruan tinggi negerinya ada asrama khusus orang-orang Papua,” kata Bonar.
“Meskipun masyarakat pasti menyangkalnya. Katanya, ‘Ah, enggak. Kita ‘kan satu bangsa dan negara’,” tambahnya.
Papua vs BLM
Elizabeth Brundige dkk. dalam laporan yang berjudul Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control tahun 2004, menulis bahwa perlakuan diskriminatif orang Indonesia terhadap orang Papua merupakan sebuah bentuk diskriminasi rasial. Hal itu didukung bahwa ras orang-orang Papua, yaitu Melanesia, merupakan kelompok ras yang berbeda dengan orang-orang Jawa sebagai kelompok dengan populasi yang mayoritas ada di Indonesia.
Di berbagai media massa dan platform media sosial, diskursus kembali mengemuka bahwa diskriminasi rasial yang dilakukan orang Indonesia terhadap orang Papua, memiliki kesamaan dengan diskriminasi rasial yang dilakukan orang kulit putih Amerika Serikat terhadap orang kulit hitam. Bonar membenarkan adanya kesamaan itu, meskipun orang Papua di Indonesia dan orang kulit hitam di Amerika Serikat memiliki latar belakang historis yang berbeda.
Pemberitaan media massa yang kebanyakan justru melanggengkan stereotip dan prasangka terhadap orang Papua.
Pemantiknya adalah penganiayaan oleh polisi kulit putih terhadap George Floyd, seorang warga kulit hitam AS. Masyarakat AS beramai-ramai melaksanakan protes di jalan. Mereka mengkampanyekan Black Lives Matter (BLM) yang mendorong agar semua pihak menghargai hak hidup dan hak asasi manusia para orang kulit hitam.
Kasus yang menimpa Floyd mengingatkan kita akan penganiayaan yang dialami mahasiswa Papua, Obby Kogoya, di Yogyakarta pada 2016, sebagai buntut dari pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh personil gabungan polisi, tentara, dan sejumlah organisasi massa. Obby yang saat itu hendak memasuki asrama setelah berbelanja di pasar, ditangkap dan dianiaya petugas karena dituduh membawa senjata tajam. Tuduhan itu tidak terbukti.
“Selama sekolah di Jawa, kitorang yang dari Papua sering dianggap setengah binatang. Itu saya rasakan dari teman-teman yang kuliah di Solo. Jadi mereka bukan dari masyarakat yang tidak berpendidikan saja, tapi juga dari kalangan berpendidikan. Sering kali orang Papua dikata-katai, ‘Monyet! Ketek!’ Begitu,” kata Filep Karma, aktivis Papua, dalam bukunya Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua (2014).
Baca juga: Kami Perempuan Melanesia, Kami Ada, dan Kami Cantik!
Meike Lusye Karolus, dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, menilai bahwa rasialisme ini turut dipengaruhi oleh peran pemberitaan media massa yang kebanyakan justru melanggengkan stereotip dan prasangka terhadap orang Papua.
“Media telah merepresentasikan orang Papua dengan cara pandang yang kolonialis, rasialis, dan tidak adil. Perlu dilihat lebih jeli apakah representasi orang Papua yang dimunculkan ini mewakili orang Papua sebagai dirinya sendiri atau untuk tunduk pada wacana dominan yang sengaja dibentuk untuk menaklukkan mereka?” ujarnya kepada Magdalene.
“Tapi media bisa digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif yang bisa mendekonstruksi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap kelompok tertentu sehingga pengetahuan kita terbangun dengan lebih adil.”
Perlakuan buruk sebagai cerminan stigma buruk itu bahkan pernah Meike alami. Oleh karena itu, sebagai perempuan Melanesia, Meike berkeinginan untuk bisa berjalan dan berjuang bersama perempuan Melanesia lain untuk memperbaiki anggapan dan nasib mereka di masa mendatang.
“Di jalan yang sunyi itu, sebaiknya kita tidak berjalan sendirian. Ada masa ketika saya dihina karena dilihat mirip monyet. Ada masa ketika saya ditolak karena agama saya. Semua pengalaman itu membuat kepekaan saya untuk melihat penindasan terasah. Kita harus bangkit dan berbuat sesuatu agar anak-anak kita kelak tidak mengalami luka yang sama dengan para orang tuanya,” kata Meike.




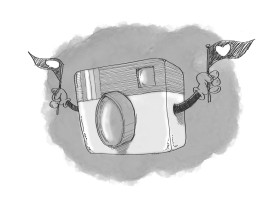
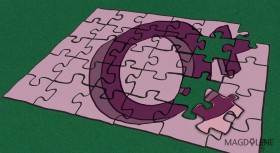

Comments