Kasus pemerkosaan yang dilakukan warga Indonesia di Inggris, Reynhard Sinaga, menunjukkan adanya ketimpangan yang besar dalam etika pemberitaan di dua negara. Reynhard, yang dijatuhi hukuman seumur hidup setelah terbukti memperkosa hampir 200 orang, telah ditangkap sejak 2017. Namun media di Inggris baru memberitakan kasusnya setelah vonis dijatuhkan akhir Desember 2019. Selain itu, cara pemberitaannya pun beretika dan tidak “salah fokus”.
Sementara itu di Indonesia, alih-alih membuat berita yang informatif, kritis, dan mencerahkan seperti BBC dan The Guardian, banyak media yang melihat persoalan ini sebagai suatu sensasi. Ketik saja kata kunci Reynhard Sinaga di mesin pencari internet, maka artikel-artikel yang keluar dari media Indonesia sebagian besar bersifat clickbait yang mengeksplorasi hal-hal di luar konteks kasus ini, dari mulai “selfie ganteng”, gawai yang dia miliki, hingga orientasi seksualnya.
Peneliti Firman Imanuddin dari Remotivi, sebuah lembaga pengawas media di Indonesia, mengatakan, ketika kasus Reynhard ini viral, ia sudah menyangka akan terjadi marking, atau kondisi di mana dalam sebuah informasi atau suatu identitas tertentu itu ditonjolkan dan dikaitkan dengan perilaku tertentu padahal secara kontekstual itu tidak relevan.
Misalnya, kita tentu sering membaca berita sensasional yang menyebut kekerasan seksual dilakukan oleh homoseksual, tapi ketika yang melakukannya adalah heteroseksual, jarang ada embel-embel orientasi seksual yang dicantumkan, ujarnya.
Baca juga: Reynhard Sinaga dan Pemerkosaan terhadap Laki-laki
“Saya pernah lihat ada berita dulu ibu-ibu bermata sipit memarahi petugas. Nah itu ada marking ras di sana, yang menonjolkan bahwa dia adalah orang Cina. Sedangkan jarang ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa ibu-ibu Jawa, atau ibu-ibu Sunda. Jadi marking ini adalah perilaku yang selalu menyasar kelompok marginal,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Minggu (12/1).
Erwin Dariyanto, Managing Editor/Section Head Timeless Content Detik.com, mengakui medianya suka mencari-cari hal lain untuk dieksplorasi meski kadang tidak relevan.
“Karena kasus ini kan kasus kekerasan seksual, tapi karena segmen yang lain tidak kebagian, jadinya dicari-cari dan dibikin-bikin. Contohnya jadi bahas gadget yang dimiliki Reynhard. Tapi kalau sudah keterlaluan, artikelnya ‘sampah’ biasanya juga ditegur netizen dan kita biasanya bikni klarifikasi, atau jadi bahan masukan buat redaksi,” ujarnya dalam diskusi yang sama.
Rochimawati, editor di Vivanews.com, mengatakan tuntutan menjaring banyak klik membuat berita-berita yang tidak kurang etis pun lolos di medianya.
“Iya, saya juga kadang merasa malu ketika di repost sama Magdalene karena artikelnya clickbait dan mengeksploitasi korban padahal yang menulis juga perempuan,” ujarnya, mengacu pada kampanye #WTFMedia di akun Instagram @magdaleneid yang mengkritik pemberitaan media yang seksis dan misoginis.
“Tapi ya kadang yang begitu-begitu lolos karena tuntutan banyaknya tulisan setiap harinya. Dan saya juga enggak bisa ngatur semua editor, paling bisa ngasih tahu,” tambahnya.
Baca juga: Pro dan Kontra Pemberitaan Kekerasan Seksual
Perspektif pasar
Jurnalis senior Luviana dari konde.co, yang berfokus pada isu gender, mengatakan media yang menjual konten sensasional ini biasanya tidak memiliki regulasi yang memungkinkan untuk membuat konten dari perspektif kritis.
Ia memaparkan empat perspektif media dalam menggambarkan korban kekerasan seksual. Pertama, perspektif normatif yang menganggap tubuh perempuan memang layak diperjualbelikan, perempuan harus menjadi ibu yang baik, dan bahwa korban merupakan perempuan genit.
Kedua, perspektif konsumtif, di mana informasi semata-mata dianggap barang konsumsi. Ketiga, perspektif pasar yang sensasional dan menciptakan stigma dan diskriminasi (“Payudara Nikita Mirzani Tumpah”, “5 Artis yang Pindah Agama”).
“Keempat adalah perspektif kritis, yang menulis dalam perspektif korban. Misalnya bagaimana hakim memojokkan korban, dll. Nah, perspektif kritis ini masih sangat jarang, yang paling banyak tetap perspektif pasar dan sensasionalisme,” ujar Luviana.
“Padahal masyarakat sipil sebetulnya punya stand point yang jelas. Kita sama-sama menolak adanya kekerasan seksual,” tambahnya.
Pemilihan konten yang hanya mengedepankan unsur sensasionalitas ini terjadinya karena banyak peliputan itu tidak berdasarkan lingkaran di sekitarnya, kata Luviana. Misalnya ketika terjadi kebakaran, secara etika jurnalistik orang pertama yang harus kita wawancarai adalah korban, kedua saksi korban, dan yang ketiga adalah orang-orang yang tahu soal kebakaran itu dan dia juga pengamat.
Tapi ada beberapa media, yang mewawancarai artis-artis atau pemuka agama yang jelas-jelas tidak menguasai kasus itu, akibatnya banyak pembelotan isu yang justru mengarah pada diskriminasi komunitas LGBT, tambahnya.
Baca juga: Media Jangan Perburuk Masalah Kekerasan Seksual
Firman mengatakan pers kini tidak lagi berfungsi sebagai gatekeeper, yang mengontrol akses publik terhadap informasi. Dalam era internet seperti sekarang, saat informasi bisa didapatkan di mana saja, bukan publik lagi yang mengikuti agenda pers, tapi pers yang mengikuti agenda publik, ujarnya. Jadi ketika ada sesuatu yang viral di media sosial, itu dijadikan berita.
“Karenanya, penting untuk media punya angle. Tapi kebanyakan media tidak punya itu; angle yang dipakai hanya SEO saja, kira-kira apa ya konten yang paling menarik untuk diklik, tapi mereka enggak punya analisis apa pun,” ujarnya.
Dalam situasi media yang semakin menonjolkan sisi sensasionalnya, peran media alternatif cukup penting, karena berperan sebagai wadah untuk memberi suara para kaum marginal yang menjadi korban kejamnya konten sensasional media arus utama, kata Luviana.
“Saya melihat peran media alternatif yang penting untuk memberikan ruang demokratisasi, melakukan counter culture, dari suara warganet di sosial media itu mempengaruhi ruang redaksi. Suara publik tersebut ternyata sekarang berpengaruh padahal dulu tidak seberpengaruh sekarang,” ujarnya.
Meskipun industri media sekarang ini semakin berpacu pada konten-konten clickbait, Erwin selaku editor mengaku tetap optimis untuk kemajuan pemberitaan di media yang lebih berimbang ke depannya, mengingat sekarang ini publik juga sudah mulai cerdas dalam mengontrol pemberitaan. Jika memang berita yang dimuat itu tidak layak, atau terlalu mendiskriminasi korban maka biasanya akan menuai banyak kritik dari warganet, ujarnya.
“Kita banyak belajar dari media luar dalam memberitakan kasus kekerasan seksual, ketika pihak kepolisian Inggris melarang adanya pemberitaan kasus ini sebelum sidang selesai, mereka mematuhi. Hal yang berbeda mungkin terjadi di Indonesia,” katanya.




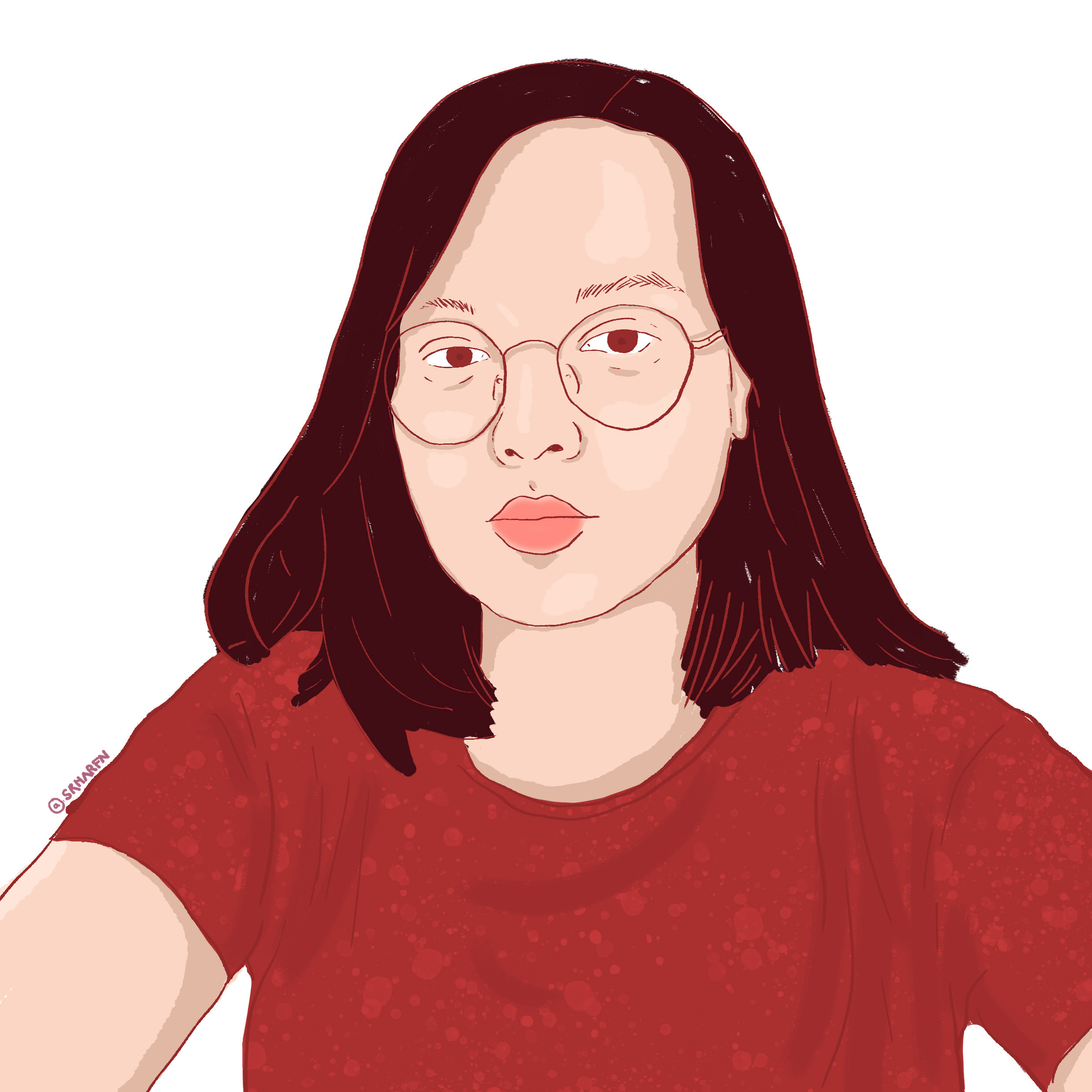
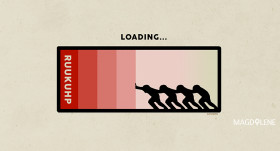


Comments