Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat – Pahrurozzi, khatib berusia 24 tahun dari desa Labuhan Lombok di Lombok Timur, lahir dan besar dalam keluarga Muslim konservatif. Sejak kecil ia telah diajarkan untuk tidak menyukai orang-orang non-Muslim.
“Sejak kecil, saya telah diindoktrinasi oleh keluarga saya bahwa orang-orang yang bukan Muslim itu jahat, dan ajaran selain ajaran Islam itu tidak benar,” katanya saat berbincang dengan Magdalene dan beberapa media lain dalam kunjungan ke Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kunjungan tersebut diorganisir oleh lembaga swadaya masyarakat Oxfam Indonesia sebagai bagian dari proyeknya “I am One, I am Many” (Saya Satu, Saya Banyak). Bermitra dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) NTB dan LSM Circle of Imagine Society (CIS) Timor, proyek ini berfokus pada perdamaian dan keragaman, melawan diskriminasi, dan mengembangkan kepemimpinan anak muda. Ketika saya bertemu dengan Ozi (foto, kiri), nama panggilannya, dia tampak canggung dengan penampilannya. Saya sempat memergokinya beberapa kali saat bertanya kepada teman-temannya, apakah dia tampak baik-baik saja atau aneh. Waktu itu dia mengenakan pakaian normal, dengan kemeja biru, celana jins hitam, dan sepatu kets biru.
Ketika saya bertemu dengan Ozi (foto, kiri), nama panggilannya, dia tampak canggung dengan penampilannya. Saya sempat memergokinya beberapa kali saat bertanya kepada teman-temannya, apakah dia tampak baik-baik saja atau aneh. Waktu itu dia mengenakan pakaian normal, dengan kemeja biru, celana jins hitam, dan sepatu kets biru.
Saat wawancara, dia mengungkapkan bahwa dia biasa mengenakan pakaian Islami – gamis, sarung, dan peci – hampir sepanjang hidupnya. Baru dalam dua bulan terakhir dia mulai mengganti pakaiannya.
“Saya masih merasa tidak nyaman mengenakan pakaian seperti ini,” katanya.
Ozi memiliki gelar Quran dan Hadits dari Jurusan Dakwah Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Hamzanwadi Nadhatul Wathan (IAIH NW), Lombok Timur. Dia kemudian mulai menyampaikan khotbah salat Jumat di salah satu masjid di desanya.
Meski masih muda, dia tidak pernah menghindar dari isu kontroversial. Suatu kali, Ozi berkhotbah tentang kasus penghujatan yang mengakibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara. Khotbah tersebut membuat banyak di antara jemaah yang mendengarnya mendatangi Ozi untuk menanyakan kebenaran kasus tersebut.
Masri Asril, 24, dari desa Ubung, Lombok Tengah, juga berbagi cerita serupa. Tumbuh dalam keluarga miskin, aksesnya terhadap informasi sangat minim saat ia masih anak-anak dan remaja.
“Saya baru punya handphone waktu kuliah,” kata Masri.
Di universitas itu pula dia pertama kali berkenalan dengan organisasi kampus Islam fundamentalis.
“Karena saya tidak memiliki akses terhadap informasi saat masih muda, saya memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Ketika saya menemukan organisasi ini, saya merasa rasa ingin tahu saya akhirnya terpuaskan,” ujarnya.
"Sebenarnya pada saat itu saya juga sedang patah hati,” katanya tersipu malu. “Itu juga salah satu alasan mengapa saya bergabung dengan organisasi ini. Seperti pelarian untukku,” tambahnya.
 Selama dua tahun di organisasi kampus yang diklaimnya memiliki hubungan dengan lembaga asing, gaya hidupnya berubah 180 derajat. Ada aturan-aturan ketat, termasuk larangan untuk bertatapan langsung dengan perempuan.
Selama dua tahun di organisasi kampus yang diklaimnya memiliki hubungan dengan lembaga asing, gaya hidupnya berubah 180 derajat. Ada aturan-aturan ketat, termasuk larangan untuk bertatapan langsung dengan perempuan.Dia bahkan tidak diizinkan berada di dekat perempuan: “Saya akan bilang: stop, jangan terlalu dekat.” Dia juga tidak diperbolehkan berjabat tangan dengan saudara perempuan, seperti bibi atau sepupu, ketika dia mengunjungi rumah mereka untuk halal bihalal atau acara lainnya.
“Suatu hari, Ibu pernah minta saya mengantarkan bibi saya pulang setelah berkunjung ke rumah kami. Saya langsung menolaknya. Dalam organisasi ini, saya diajarkan untuk tidak berinteraksi dengan perempuan yang bukan muhrim, kecuali ibu dan saudara perempuan saya,” tambah Masri (foto, kanan).
Menonton televisi juga dilarang, demikian pula mengenakan celana jins. Dia hanya diperbolehkan memakai celana ngatung di atas pergelangan kaki. Dia tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai agama, dan dia diminta untuk menegur temannya yang berpacaran. Pada dasarnya, Masri menjalani kehidupan yang tertutup dari dunia luar.
“Ada begitu banyak batasan. Saat saya bergabung dengan organisasi itu, saya menjadi sangat eksklusif dan terbatas,” katanya.
Transformasi besar
Sekarang ini Ozi dan Masri telah menjadi “agen-agen perdamaian” bersama 28 anak muda lainnya di NTB yang tergabung dalam Aliansi Kerukunan Pemuda Lintas Agama (AKAPELA), dengan misi untuk menyebarkan perdamaian dan keragaman melalui seni di seluruh provinsi ini. Didukung oleh LBH Apik NTB dan Oxfam Indonesia, AKAPELA juga mempromosikan isu-isu penting lainnya seperti kesetaraan gender, memerangi radikalisme dan diskriminasi, dan perkawinan anak. Program ini juga ada di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Ini adalah tahun kedua proyek ini,” kata Marcellina Kristi Praptiwi, Manajer Proyek Oxfam Indonesia. “Pertama, kami melakukan assessment. Kami memetakan dan memilih daerah mana yang memiliki tingkat keragaman tinggi, bukan daerah yang homogen. Dan kami mengidentifikasi tiga wilayah yang memiliki banyak kasus diskriminasi: Mataram, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.”
Setelah pemetaan, Oxfam Indonesia dan LBH Apik NTB meluncurkan proyek percontohan.
“Berdasarkan survei baseline terhadap 300 responden di NTB dan NTT, kami menemukan bahwa bentuk diskriminasi yang paling umum adalah larangan kegiatan ibadah atau pembangunan tempat ibadah sebesar 39,1 persen, dan pengucilan terhadap kelompok minoritas di masyarakat 31,6 persen,” jelasnya. “Dan konflik yang paling potensial adalah di kalangan anak muda yaitu sebesar 36,2 persen.”
Surya Jaya, Koordinator Program Keragaman LBH Apik NTB, mengatakan bahwa sejak dimulainya proyek pada 2017, mereka telah melakukan pendekatan terhadap 500 anak muda di desa, sekolah, organisasi dan berbagai forum pemuda dan masyarakat di provinsi tersebut untuk mengundang mereka menghadiri dialog besar. Tema diskusi beragam, dari pembahasan tentang gender, diskriminasi, radikalisme, kekerasan terhadap perempuan, hingga keragaman.
“Itu sebabnya kami melibatkan anak muda. Karena kami percaya bahwa anak muda memiliki potensi besar yang positif. Dan mereka bisa menyebarkannya ke teman-teman mereka dan juga masyarakat,” kata Surya.
Setelah diskusi, Surya memilih 30 anak muda. Dari masing-masing lima cluster atau gugus desa, enam pemuda yang memenuhi kriteria dan/atau direkomendasikan oleh desa mereka akan dipilih untuk bergabung dengan AKAPELA, dan mengambil bagian dalam semua aktivitas dan pengembangan kapasitas AKAPELA. Mereka dilatih untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menjadi fasilitator untuk menyebarkan nilai keragaman melalui diskusi.
Ozi tidak pernah berpikir dia akan berubah dari seorang fundamentalis menjadi seorang pluralis yang menyebarkan informasi tentang kesetaraan gender hanya dengan menghadiri beberapa diskusi. Ketika ditanya bagaimana pergantian drastis terjadi, dia memuji Surya karena telah mengajarkannya tentang karakter dan identitas.
“Titik balik saya adalah saat Mas Surya menjelaskan tentang perbedaan antara karakter dan identitas,” kata Ozi.
“Dia mengatakan kepada saya bahwa identitas adalah agama atau kepercayaan Anda: Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara tentang agama, kita harus ingat bahwa setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik dan memiliki titik temu yang sama, yaitu untuk menjadi orang yang baik,” ujarnya.
“Beda dengan karakter. Karakter melekat dan dimiliki oleh setiap orang, dan setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Jadi ketika berbicara tentang agama, bukan agama (identitas) yang keras. Yang keras itu adalah karakter orang tersebut.”

Melihat kembali khotbah-khotbah Ozi dulu – seperti kasus Ahok – dia menyadari bahwa dia adalah bagian dari masalah.
“Saya menyadari bahwa saya adalah orang pertama di sekitar sini yang menyebarkan informasi tentang kasus Ahok. Sayalah yang memicu kebencian," kenang Ozi.
Marah dengan transformasi Ozi, teman-temannya protes atau bahkan menghina dia, tapi Ozi akan menanggapi dengan mengutip ayat al-Quran: “Allah jameel wahibbul jameel.”
“Artinya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan,” katanya.
Sekarang ini, Ozi berkhotbah tentang kesetaraan gender di mimbar Jumat. Dia ingin menjadi “khatib gender”, katanya. Ozi mulai menafsirkan beberapa hadits (ucapan, tindakan dan kebiasaan yang dicatat dari Nabi Muhammad) yang berhubungan dengan perempuan. Misalnya, surat an-Nisa dalam Quran yang berisi ayat-ayat khusus tentang perempuan.
“Ada hadits yang mengatakan: Almar'atu 'imadul bilad, yang artinya perempuan merupakan tiang negara. Menurut penafsiran saya, pemimpin tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Selama mereka memenuhi karakteristik seorang pemimpin yang menurut perintah Allah. Yaitu pemimpin harus berbuat baik, adil, dan bisa mengajarkan kebaikan kepada masyarakat,” jelas Ozi.
Tidak seperti Ozi, Masri telah keluar dari organisasi ekstremis sebelum bergabung dengan AKAPELA karena orang tuanya mengkhawatirkan tingkah lakunya yang menutup diri dan berubah drastis.
“Saya akhirnya meninggalkan organisasi itu, dan saya sangat bersyukur,” kata Masri, yang saat ini kuliah di Universitas Mataram, jurusan Sastra Inggris.
Pada pertengahan 2016, dia diundang oleh Baiq Nila Fatimasari, yang telah berkontribusi dalam proyek percontohan tersebut, dan juga anggota AKAPELA, untuk menghadiri dialog besar.
“Masri direkomendasikan oleh desanya, kemudian saya datangi Masri di Ubung, dan saya melihat bahwa dia benar-benar melakukan sesuatu untuk masyarakat desanya,” kata Nila. Bersama dengan teman masa kecilnya Widiya Suci, Masri telah mendirikan komunitas Insan for Humanity (INSANITY), dengan mengajar bahasa Inggris dan pemberdayaan lingkungan kepada anak-anak sekolah dasar. Keduanya sekarang sudah menjadi anggota AKAPELA.
Kristi, Manajer Proyek Oxfam Indonesia, mengungkapkan harapannya agar proyek tersebut dapat mendorong lebih banyak anak muda untuk lebih sadar akan berbagai aspek di masyarakat dan untuk merayakan keragaman.
“Anak muda memainkan peran penting untuk membuat perbedaan,” tambahnya.
*Tonton kampanye video AKAPELA untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan di sini.
**Artikel asli dalam bahasa Inggris bisa dibaca di sini.





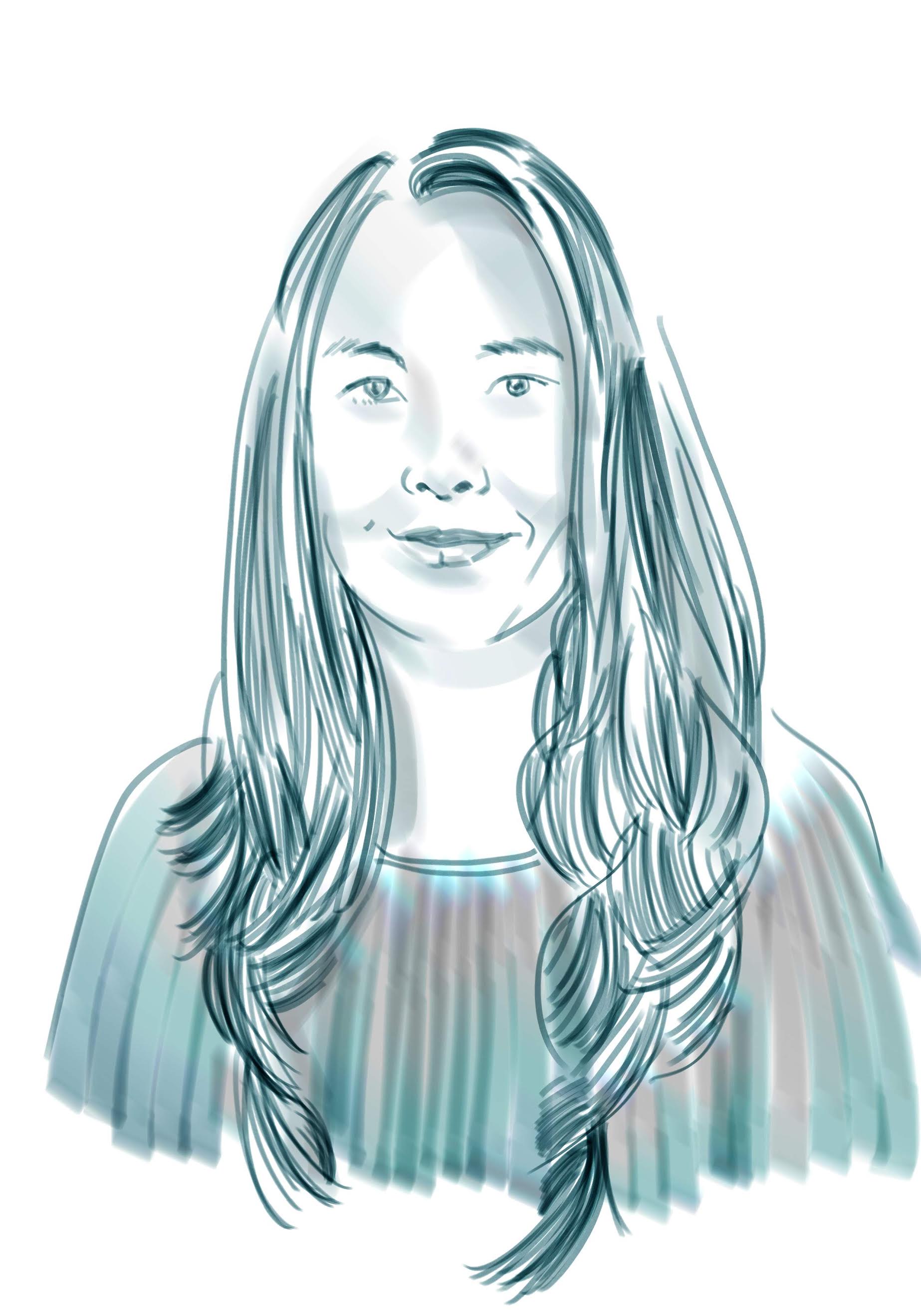



Comments