Tidak bisa dipungkiri memang, menemukan pasangan sebagai seorang gay itu ibarat mencari semanggi berdaun empat. Meskipun daunnya empat, mereka masih sulit dicari karena berada di spektrum warna yang serupa dengan semanggi berdaun tiga.
Sebagai komunitas minor di tengah arus heteronormativitas, terkesan mustahil bagi seorang gay untuk secara terbuka menunjukkan rasa ketertarikannya kepada laki-laki secara acak, atau secara tiba-tiba didekati oleh laki-laki asing dan berlanjut pada kisah cinta seperti di film. Hal tersebut mungkin saja sih terjadi, tetapi satu dibanding jutaan kemungkinan. Laki-laki gay cenderung bersembunyi di balik heteroseksualitas ketika berada di ruang publik. Maka dari itu, sebagai seorang gay yang sedang mencari pasangan, dibutuhkan suatu platform yang mengumpulkan individu gay lain di satu medium, salah satunya adalah aplikasi kencan khusus gay.
Platform pencarian jodoh/kencan berbasis komputer sudah eksis sejak tahun 1960an yang dimulai dengan St. James Computer Dating Service (Com-Pat) di Inggris, serta Operation Match di AS, yaitu sebuah layanan pencarian jodoh berbasis komputer besutan sekelompok mahasiswa Universitas Harvard. Lalu pada tahun 90an, beriringan dengan perkembangan internet dan gawai mulai bermunculanlah situs-situs pencarian jodoh dengan model iklan online hingga chat room, seperti Prodigy, Match.com, Craiglist dan lainnya.
Memasuki abad ke-21, barulah bermunculan aplikasi kencan yang tentunya lebih mudah digunakan, karena kita hanya perlu menggeser jari kita ke kanan jika kita menyukai apa yang kita lihat dan ke kiri jika kita tidak menyukainya. Ya, Tinder. Tinder tidak hanya dapat digunakan oleh pengguna heteroseksual berkat fitur yang dapat memilih gender apa yang ingin ditampilkan. Tinder menjadi aplikasi kencan daring yang versatile karena dapat digunakan oleh pengguna homoseksual.
Baca juga: Budaya Kencan Gay: Rumit dan Diskriminatif
Sebenarnya aplikasi kencan khusus gay sudah ada sebelum Tinder, misalnya Grindr yang diluncurkan pada 2009. Namun entah mengapa, bahkan saya sendiri lebih nyaman menggunakan Tinder dibandingkan dengan aplikasi kencan khusus gay. Mungkin karena lebih to the point? Untuk itu di sini akan lebih difokuskan pada pengalaman saya di aplikasi kencan tersebut.
Kelompok gay di Indonesia memiliki julukan sendiri untuk tiga aplikasi kencan yang paling banyak diminati yaitu “kitab merah” untuk Tinder, “kitab biru” untuk Blued, dan “kitab kuning” untuk Grindr. Saya mulai menggunakan Tinder ketika saya merasa jenuh dengan “ketidakjelasan” yang sering saya temui di dua kitab lainnya. Banyak pengguna yang kesannya tidak yakin dengan apa yang mereka cari dan hanya berjalan mengikuti ke mana arus membawa mereka di aplikasi tersebut. Bagi saya pribadi hal itu cukup menyebalkan karena saya bisa-bisa terjebak dengan orang yang ternyata pada akhirnya hanya akan membuang waktu dan kesempatan saya di aplikasi tersebut.
Berdasarkan rekomendasi beberapa teman gay, saya mulai mencoba “kitab merah” yang menurut mereka tidak perlu banyak bertele-tele dalam mencari pasangan. Ternyata memang benar, saya hanya perlu mengisi data profil, memasang foto dan biodata menarik, serta menentukan gender mana yang menjadi preferensi pencarian saya. Sisanya, seperti yang sudah diketahui bersama, saya hanya perlu menggeser ke kanan pada profil yang menarik perhatian saya dan menggeser ke kiri jika saya tidak tertarik. Setelah itu saya hanya perlu menunggu apakah profil yang saya suka juga menggeser ke kanan untuk foto saya, atau mungkin sudah lebih dahulu menggeser ke kanan pada profil saya. Kedua kemungkinan tersebutlah yang akan menentukan apakah saya dan orang tersebut matched atau tidak, jika matched maka barulah saya dan orang tersebut dapat mengakses fitur chat.
Bagi seorang gay, yang berpotensi besar untuk putus relasi dengan keluarga, seakan ada tekanan untuk menemukan relasi baru sebagai tempat “pulang”.
Impresi pertama saya, aplikasi kencan ini terkesan serba instan dan penuh kepastian, sangat sesuai dengan kepribadian saya yang tidak mau terlalu banyak membuang waktu, karena saya dapat memilih orang seperti apa yang saya ingin kencani dan dapat dengan pasti mengetahui apakah orang tersebut juga berpikir serupa terhadap saya.
Setelah sekian bulan menjadi pengguna Tinder, saya mulai merasakan sesuatu yang “mengonsumsi” saya dari dalam, yaitu ketidakpercayaan diri yang luar biasa. Ternyata proses “serba instan dan pasti” yang ditawarkan tersebut memiliki efek samping yang tidak saya duga sebelumnya.
Banyak faktor yang menimbulkan pemikiran bahwa saya ini kurang menarik, kurang menjual, kurang layak, tidak disukai, dan sebagainya. Faktor tersebut timbul dari jumlah match yang bisa dihitung jari, belum lagi hal kecil seperti match yang kurang minat berinteraksi atau bahkan tidak mau berinteraksi sama sekali. Ditambah profil orang lain dengan berbagai foto yang sangat menarik didukung dengan biodata apik yang seakan menegaskan posisi mereka dalam lingkup sosial. Tak jarang pula ada match yang melontarkan ungkapan kebencian lalu melakukan unmatched. Seolah-olah saya ini barang yang tidak akan pernah laku di etalase.
Tingkat ketidak percayaan diri saya semakin menurun sampai pada titik di mana saya sama sekali merasa tidak mau dan mampu untuk bertemu dengan orang baru. Saya sempat merasa depresi untuk beberapa minggu, merasa tidak pantas berada di lingkaran sosial mana pun, dan bahkan merasa kurang berharga sebagai manusia. Depresi yang semakin menjadi membuat saya memutuskan untuk menghapus aplikasi tersebut dan mencoba untuk berefleksi tentang apa sebenarnya yang saya inginkan sebagai seorang gay, dan di mana posisi saya di alam semesta ini sebagai seorang gay. Beban terasa lebih ringan setelah saya bisa terlepas dari aplikasi kencan tersebut. Saya mulai memperoleh kembali rasa percaya diri setelahnya.
Baca juga: Seks Anal dan Otoritas Tubuh
Hampir setiap orang mendambakan pasangan, mengingat kita adalah makhluk sosial yang rentan jika hidup hanya sendirian saja. Hampir setiap orang ingin menjalani dan berbagi hidup dengan orang-orang yang disayangi dan memperoleh kembali perasaan yang serupa dengan sukarela. Bagi seorang gay, yang memiliki potensi cukup besar untuk putus relasi dengan keluarga suatu saat, seakan ada tekanan untuk menemukan relasi baru yang bisa dipercaya sebagai tempat untuk “kembali pulang” sesegera mungkin. Namun menurut saya, kondisi diri kita khususnya mental tidak dapat dikorbankan demi mencapai tujuan tersebut.
Menyayangi diri sendiri itu merupakan hal paling utama, sisanya akan mengikuti.
Kejadian seperti yang saya alami tidak berarti hanya dapat terjadi di salah satu “kitab”. Saya rasa “kitab-kitab” yang lain juga berpotensi menuai “racun” bagi penggunanya. Kembali lagi ke cara masing-masing individu dalam memaknai dan menggunakannya. Masalah suatu hal “beracun” atau tidak merupakan sudut pandang individual, sehingga pengalaman orang yang satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Tapi jika sudah terdeteksi ada “racun”, tetap ingat untuk beristirahat. Jangan sampai pengalaman mencari pasangan dan menjalin relasi dengan orang baru menjadi menakutkan atau bahkan traumatis.






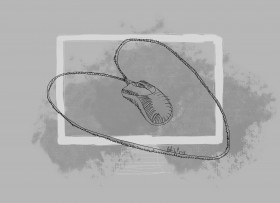
Comments